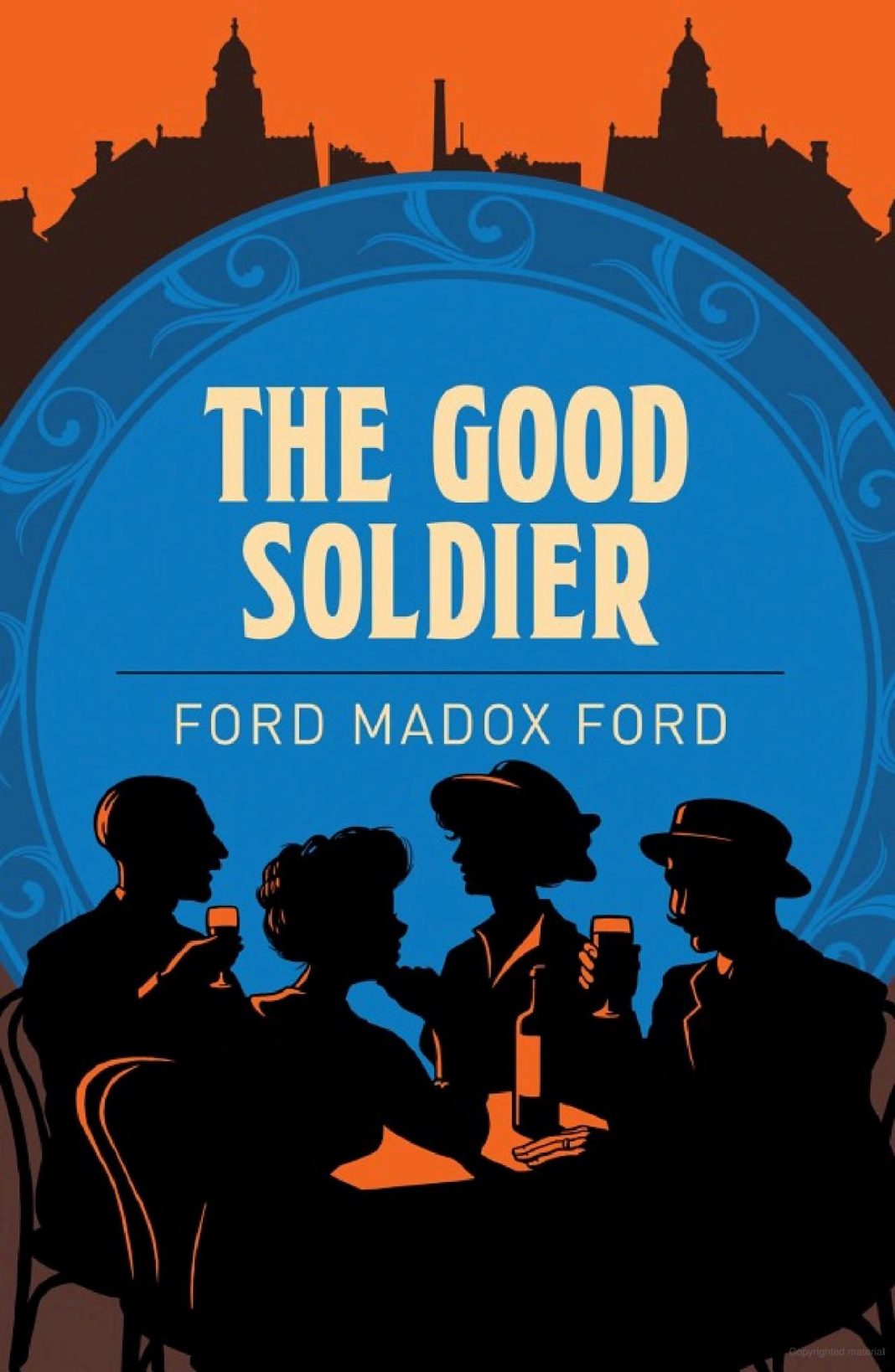The Good Soldier (1915) adalah buku yang unik dan mungkin tak tertandingi karena merupakan mahakarya, yang selalu memberikan kejutan baru bahkan bagi pembaca yang sudah pernah membacanya. Ford Madox Ford sendiri, sepuluh tahun setelah novel ini terbit, mengaku takjub dengan kepiawaiannya sendiri dalam merangkai cerita dan menjalin referensi silang yang rumit. Meskipun Ford telah menulis novel lain yang hebat, seperti tetralogi Parade’s End, ia menyebut The Good Soldier sebagai “telur auk”-nya—sebuah karya tunggal yang memuat segalanya tentang kisah ini, tak hanya semua yang ingin ia sampaikan, tetapi juga semua yang perlu disampaikan.
Sekilas, ceritanya tampak sederhana. Dua pria Inggris bertemu di Jerman dan menghabiskan beberapa tahun di Amerika, menjalin persahabatan erat hingga terungkap bahwa istri salah satu pria dan suami wanita yang lain telah berselingkuh. Sang istri mengetahui perselingkuhan tersebut, tetapi suaminya tidak. Setelah kematian sang istri, semakin banyak fakta terkuak tentang perilaku dan makna emosional di balik perselingkuhan itu.
Kisah ini dikisahkan oleh suami yang tidak mengetahui perselingkuhan tersebut. Dengan demikian, novel ini memiliki elemen cerita detektif, meskipun sang narator bukanlah seorang detektif. Ia justru mendapatkan fakta-fakta secara tak sengaja, meskipun sebenarnya ia lebih suka tidak mengetahuinya. Ketegangan cerita tidak terletak pada apa yang terjadi, meskipun dramatis, melainkan pada interpretasi narator terhadap emosi yang bergejolak, yang terwujud dalam gerakan kecil atau ucapan singkat.
Taruhan terbesar Ford adalah kenaifan narator (Dowell), seorang pria kaya yang menganggur tetapi bermaksud baik dari keluarga tua Philadelphia yang siap menerima pernikahan tanpa seks dengan seorang wanita (Florence) yang kehidupan emosionalnya adalah rahasia dan tipuan. Florence meyakinkan Dowell pada awal bulan madu mereka bahwa hubungan perkawinan mungkin sangat membebani hatinya yang lemah sehingga dia mengubah Dowell menjadi pelayan yang mengurus setiap kebutuhannya, sementara juga memberinya banyak waktu luang untuk melanjutkan hubungan dengan setidaknya dua kekasih pilihannya.
Cara berpikir dan ungkapan Dowell adalah khas Amerika, dan wawasan Ford tentang Amerika mungkin sedikit meleset, tetapi Amerika bukanlah subjeknya, Inggris-lah yang menjadi fokus, dan karakter Dowell cukup meyakinkan. Kebajikannya yang sebenarnya adalah dia apa adanya, dan dia tidak berpura-pura dapat diandalkan. Dia dengan bebas mengungkapkan keraguan diri tentang kompetensinya, baik sebagai aktor dalam drama maupun sebagai penerjemah, dan dia berhasil untuk tidak tampak tidak jujur atau egois. Dia melukis empat potret—Edward Ashburnham, pemilik tanah yang luas di Inggris; istrinya, Leonora, putri bangsawan Irlandia yang miskin; Florence, pewaris kekayaan New England; dan Nancy Rufford, anak asuh Leonora, yang telah tinggal bersama Edward dan Leonora sejak usia tiga belas tahun.
Edward dan Leonora tampak seperti pasangan yang sempurna, anggun, bermartabat, dan terhormat. Edward, meskipun memiliki riwayat sakit jantung, adalah sosok yang mengagumkan. Ia pernah bertugas di militer di India dan menjadi tuan tanah sekaligus hakim di Inggris. Namun, di balik kesempurnaan tersebut, Edward memiliki kelemahan fatal: ia tidak mampu memahami dirinya sendiri. Meskipun ia seorang yang bermoral—jujur, murah hati, dan bertanggung jawab—ia terlalu sentimental.
Ia mudah terpengaruh oleh orang-orang yang tampak menderita atau lemah, dan hal ini membuatnya tidak peka terhadap istrinya sendiri, Leonora (yang dinikahkan dengannya melalui perjodohan). Leonora adalah wanita yang kuat dan pendiam, sering dianggap “dingin” oleh Dowell. Namun, “kedinginan” Leonora sebenarnya hanyalah kehangatan yang terpendam. Ia sebenarnya mendambakan keintiman, misalnya, ia menginginkan anak dari Edward, yang sayangnya tak kunjung hadir. Fakta mengejutkan yang terungkap adalah bahwa Edward dan Leonora tidak pernah berbicara dari hati ke hati selama tiga belas tahun pernikahan mereka, meskipun mereka selalu tampak akrab di depan umum.
Seiring berjalannya cerita, terlihat jelas bahwa Edward dan Leonora tidak hanya tidak mengenal keintiman, tetapi juga tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Pertama, mereka tidak membaca novel. Kedua, Leonora berkonsultasi dengan pendeta dan biarawati untuk mendapatkan nasihat pernikahan, dan yang mereka tawarkan hanyalah klise usang seperti “pria memang begitu”. Edward tidak berkonsultasi dengan siapa pun, dan tampaknya tidak ada ruang dalam hidupnya untuk konsultasi semacam itu.
Pria lain dari kelas sosialnya menceritakan kisah-kisah vulgar, mungkin sebagai bentuk berbagi informasi, tetapi hal ini membuat Edward tidak nyaman. Jadi, ketika Edward mulai merasa tidak selaras dengan Leonora sekitar tiga atau empat tahun dalam pernikahan mereka, ia mudah dieksploitasi. Ia akhirnya menjalin hubungan yang merugikan dan kehilangan sekitar 40 persen dari nilai aset tanahnya. Selama sepuluh tahun berikutnya, Leonora mengambil alih pengelolaan aset tersebut dan mengembalikannya ke nilai semula. Namun, keseimbangan hubungan mereka rusak parah akibat kendali Leonora dan ketidakpercayaan Edward.
Baik Dowell, si pria Amerika, maupun Edward, si bangsawan Inggris, sama-sama mengalami “pengebirian” dalam pernikahan mereka. Meskipun Dowell menyalahkan Leonora dan Florence atas ketidakbahagiaannya, Ford, sang penulis, justru menggambarkan para suami dengan lebih mendalam. Mereka sebenarnya ikut berperan dalam “pengebirian” diri mereka sendiri karena tidak tahu bagaimana menjadi pria sejati. Dowell, misalnya, berbeda dari kebanyakan pria Amerika karena tidak tertarik menghasilkan uang. Sedangkan Edward, ia tidak pernah diajarkan bagaimana menjadi seorang pria, selain menjalankan tugas dan formalitas. Ia juga digambarkan agak bodoh.
Berbeda dengan Dowell yang pasrah dengan keadaannya, Edward mendambakan persahabatan dan dukungan yang ia cari dari wanita-wanita lain, sementara Leonora diam-diam menerima perselingkuhannya. Leonora berharap Edward akan kembali padanya setelah masalah keuangan mereka teratasi. Namun, harapannya pupus ketika Florence, dengan sikap dingin dan manipulatif, menjerat Edward.
Dowell berpendapat bahwa Florence adalah wanita yang dangkal. Ia hanya mementingkan penampilan, ingin terlihat cantik, berpakaian bagus, terlihat pintar, dan dilayani. Ia adalah seorang pemanjat sosial. Sebelum Florence datang, Leonora bisa menerima hubungan Edward dengan wanita lain karena ia menganggapnya sebagai hal yang wajar. Namun, ketika Edward berhubungan dengan Florence yang dibenci Leonora, ia kehilangan rasa hormat dan simpati pada Edward, meskipun ia masih mencintai dan menginginkannya.
Novel ini menarik karena Ford banyak menggunakan paradoks, yaitu pernyataan yang tampak bertentangan tetapi sebenarnya mengandung kebenaran. Misalnya, saat menceritakan riwayat militer Edward, Ford menulis, “Akan sangat baik baginya untuk terbunuh.” Kalimat ini terkesan kejam, tetapi dapat dimengerti karena muncul di akhir novel, ketika kita tahu bahwa hidup Edward berakhir tragis dan menyedihkan. Beberapa orang menganggap The Good Soldier sebagai salah satu novel dengan gaya bahasa terbaik. Ford sangat ahli dalam merangkai cerita dan menjalin berbagai elemen sehingga makna yang kompleks dan terkadang bertentangan dalam setiap kalimat menjadi mudah dipahami. Ia berhasil menggambarkan situasi, karakter, dan peristiwa dengan sangat jelas.
Ford awalnya memberi judul novel ini The Saddest Story. Namun, editornya menggantinya menjadi The Good Soldier karena Perang Dunia I baru saja pecah. Ford tidak menyukai judul baru ini, tetapi editornya benar. Judul The Good Soldier justru lebih tepat karena mengarahkan pembaca pada isu sosial yang lebih luas. Leonora, Edward, Dowell, dan Florence berjuang melawan ketidaktahuan dan kegagalan moral. Mereka adalah korban dari sistem yang menjebak dan menghancurkan mereka. Novel ini menggambarkan keruntuhan tatanan sosial dan budaya Eropa pada masa Perang Dunia I, seperti yang juga digambarkan oleh Charles Dickens dan William Thackeray dalam karya-karya mereka. Ford dengan cerdas menunjukkan bahwa kehancuran tersebut tak terelakkan, dan menyisakan kesedihan yang mendalam.