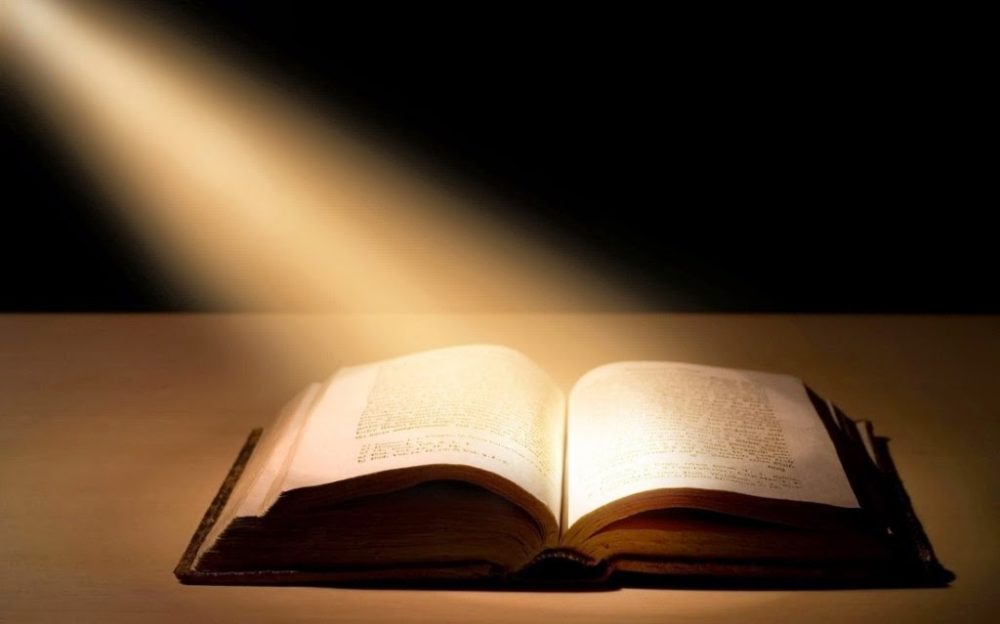Kegagalan kita dalam beragama adalah tidak teliti dalam membaca nash–baik itu perintah maupun larangan. Budaya taqlid kiranya memang mengelayuti konteks beragama di Indonesia. Beragama karena trend bukan beragama karena content.
Hal inilah yang membuat kita kehilangan link utama mempertemukan diskursus publik yang rahmatan lil alamin. Disebebabkan kesibukaan kita melihat itu sebagai trend, alih-alih mendapati kedalaman beragama kita justru sibuk mengulik kehebohan yang dapat ditimbulkan dengan kita beragama.
Artis pindah agama, komersialisasi dan rekomendasi produk halal, panggung hijrah dari preman menuju ustad, cocokologi ayat dan seruan berjihad sebagai tameng dan pengkaburan retorikal kerap jadi isu yang membuat agama seakan jadi uforia belaka.
Apalagi dengan bumbu-bumbu gosip infotainment di media mainstrem, begitu pun dengan media sosial yang tak habis-habisnya dipenuhi girangnya berita gado-gado. Netizen dari berbagai kalangan, mulai dari radius kritis, oportunis sampai apatis menjadi agen-agen yang meramaikan dunia virtual.
Keagamaan kita riuh di permukaan namun dangkal di dasarnya. Gejala taqlid hari-hari ini tidak lagi dipahami sebagai istilah akademis, akan tetapi menjamur menjadi popularisme publik. Bukan saja dalam wilayah fiqh semata, akan tetapi dalam kehidupan beragama secara luas meliputi, sosial, politik, dan budaya.
Trend taqlid ini tentu bersumber dari motif keagamaan da’i yang secara diam-diam justru memplitir ikhlas menjadi impas. Impas berarti ada kontrak yang dijalin dan terdapat kesepakatan, meskipun kontrak ini berjalan mengendap-endap tak sejelas kontrak di bidang ekonomi. Kontrak ini berjalan sambil lalu, dengan alasan-alasan normatif keagamaan, sehingga bius itu akhirnya berhasil mematikan nalar kritis sasarannya.
Apa sebenarnya yang dimainkan para da’i—atau dalam bahasa yang lebih pas mungkin kami sebut sebagai tokoh agawan—ini? Apakah ada orientasi-orientasi duniawi yang secara tak sadar—mungkin barangkali sadar?—diejawantahkan sebagai misi-misi pribadi dibalik kesucian agamanya. Husnudzon penulis semoga itu jauh pada tokoh-tokoh pemuka agama di bumi pertiwi ini.
Dalil dan Sitiran keras
Dalam Islam, Alquran dan Sunnah menjadi fondamen utama ajaran agamanya. Mengulik fenomena tersebut, Alquran menyindir keras kejahatan tersebung itu. Disebutkan dalam QS. Ali Imran [3]: 79 menerangkan:
“Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah,” tetapi (dia berkata), “Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya!”
Ungkapan, “Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah“, menjadi sindiran bagi basyar (manusia-manusia) diluar predikasi-Nya. Ayat ini memberikan kemutlakan pada albasyar (manusia tertentu) pilihan-Nya yaitu, nabi dan rasul yang tak akan menyimpang dengan menyeru untuk mengkultuskan dirinya sendiri. Utusan-Nya tidak pernah menjadi jemawa sebab menjadi orang pilihan-Nya, melainkan penuh kerelaan dan ketundukan kepada-Nya.
Pasca wafatnya Nabi Muhammad, selaku utusan-Nya yang terakhir—khatamun nabiyya—tugas dakwah tidak lantas berhenti. Maka rasul mewariskan dua pusaka Alquran dan Sunnah sebagai hikmah yang harus diajarkan kepada generasi setelahnya. Tugas kenabian kemudian berpindah kepada tangan-tangan pengajar (ulama) yang menjembatani Alquran dan Sunnah kepada umat. Hingga ditegaskan oleh Rasul dalam sabdanya, “al-Ulama warasatun Anbiya“.
Polemik Ulama Kontemporer
Ulama secara etimologi merupakan bentuk jam’ak (plural) dari kata ‘aalim yang berarti orang-orang yang berpengetahuan. Maka secara umum orang-orang yang berilmulah yang mewarisi peran kenabian pasca wafatnya nabi.
Menurut penulis hal itu benar adanya, sebab dalam dakwahnya, Nabi Muhammad didukung oleh orang-orang yang berilmu. Bukan saja paham pada esensi ajaran agama Islam, akan tetapi melingkupi keahlian-keahlian dalam kehidupan di dunia.
Penguasaan-penguasaan pada sektor ekonomi, pendidikan dan politik menjadi modal yang besar dalam tumbuh kembangnya Islam. Kesemuanya saling bahu membahu dalam mengembangkan ajaran Islam agar dapat diterima oleh masyarakat luas.
Berbanding terbalik dengan era kontemporer saat ini, dimana keilmuan terkapling pada wilayah-wilayah sektoral. Apalagi dengan gejala sekularisme dan liberalisme di paruh awal abad 20-an, agama dan ilmu pengetahuan membuat gap yang lebar.
Ulama dan ilmuan kemudian mengambil jarak yang cukup ekstrim hingga akhirnya saling membeda-bedakan peran. Bahkan simplifikasi ini berujung pada pembunuhan peran masing-masing pihak. Hingga akhirnya ulama dimonopoli oleh para ahli yang mengaku pelindung syari’at.
Bahkan ulama sering dikoar-koarkan sebagai wacana politis, sikap memonopoli peran ulama ini memperpanjang kegaduhan atas perdebatan ulama sebagai pihak yang tersudut. Membela orang yang katanya “ulama” menjadi semacam pembelaan herois. Padahal sikapnya justru jauh sekali dari gambaran-gambaran keulamaan yang membersamai rasul dalam mendakwahkan Islam dulu.
Hingga akhirnya, istilah ‘ulama’ semakin keruh dipakai dengan sombong oleh-oleh orang-orang yang menamai dirinya dengan istilah tersebut sebagai sikap pengakuan. Bahkan banyak orang yang terpengaruh oleh sikap apologis, tanpa berfikir kritis.
“Al-Islamu mahjubun bil al-muslim—ulama)”, sitir Muhammad Abduh menilai Islam yang telah kehilangan pengaruh dan kekayaan spiritualitasnya, hanya karena tingkah penganutnya yang bertolak belakang dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
Problematika taqlid dengan mengelu-elukan ulama atas pamor retoris dan framing media-media imitatif-lah yang membuat keagamaan seakan jadi panggung olok-olok. Merasa menjadi ulama apalagi dengan berkeyakinan penuh, tanpa merasa dosa menganggap dirinya berada disisi yang paling benar membuat “ulama” sekali lagi terpeleset menjadi istilah yang memilukan.