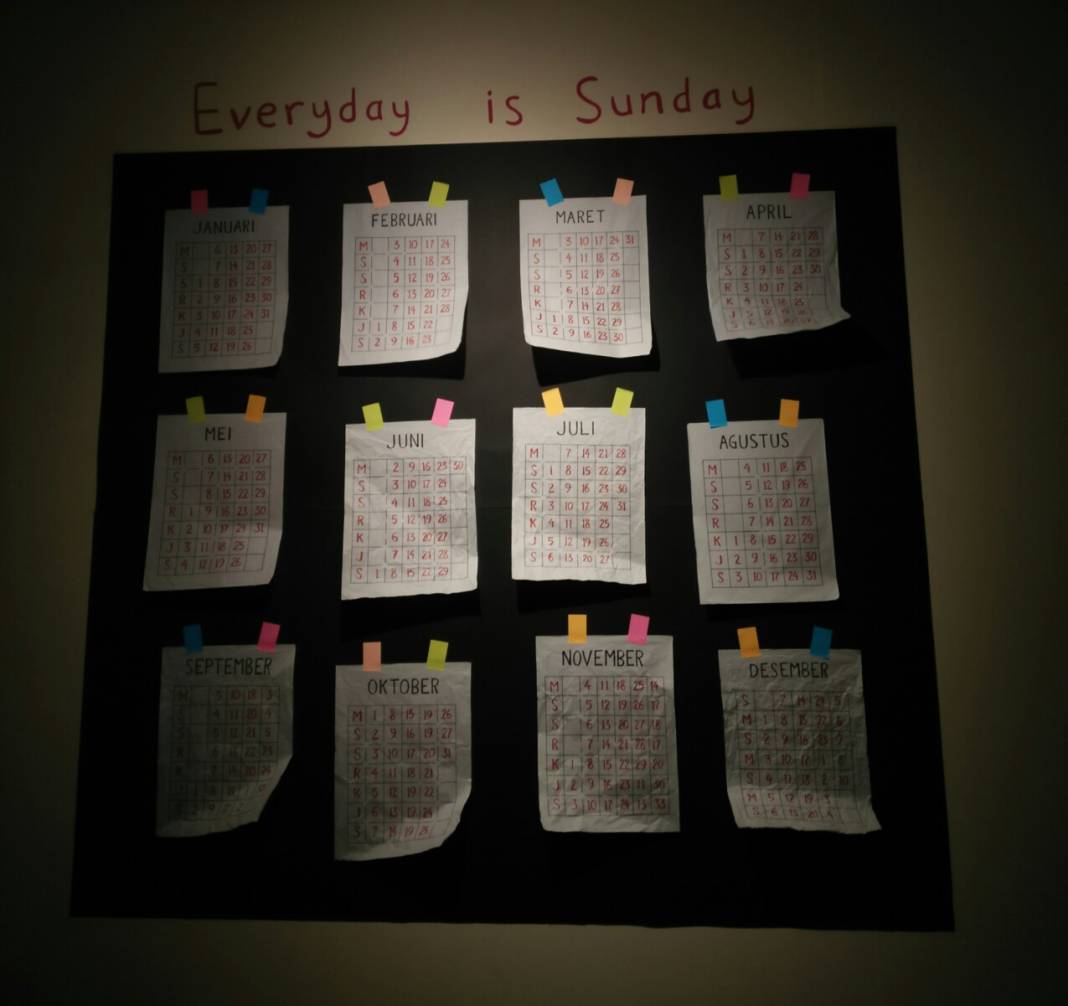Sekolah dan/atau kampus sejatinya ialah sebentuk upaya manusia demi pencapaian diri kemanusiaanya yang hakiki. Kendati tak sedikit cela terhadap unsur-unsur pendidikan yang sejatinya pun tak bisa dianggap baik-baik saja, sekolah serupa lautan bagi manusia-manusia merentangkan pelampung pikirannya. Begitulah pembacaan saya atas esai Bunga Hening Maulidina (Solopos edisi 21 Maret 2017).
“Sakit”, seperti yang dikatakan Bunga dalam tulisannya, kendati hanya diderita sebagian siswa, kiranya menyebar di institusi-institusi pendidikan di penjuru daerah manapun. Tak usah jauh-jauh. Perkara ini memulangkan ingatanku pada sekuntum pagi kala jendela kelasku ditusuk kemilau matahari.
Saat itu dosen menjelaskan tentang kelainan-kelainan yang mungkin dialami siswa di sekolah. Maka penjelasan menyasar kepada perilaku-perilaku siswa yang dianggap “menyimpang” dari budaya dan/atau konsensus umum.
Siswa yang gemar menyendiri dan cenderung pendiam misalnya, tak mendapat pemakluman atas dirinya. Sebab menyendiri dan pendiam ialah salah satu jenis kelainan dalam pembelajaran di kelas. Guru musti tahu alasan apa dibalik tingkah laku siswa yang demikian. Lantas muncul hipotesa-hipotesa. Barangkali pengaruh didikan orang tua, barangkali ia bermasalah dengan teman-teman sekelasnya, barangkali…
Para calon guru yang saat itu masih berstatus mahasiswa dibekali kemampuan mendiagnosa dan/atau melabelkan kata “sakit” pada siswa yang berlainan pribadinya dengan kebanyakan siswa.
Sementara di dunia pendidikan yang sudah ada, kebanyakan guru barangkali tak sampai jeli memahami kesakitan siswa-siswanya. Benarkah siswa A sakit yang disebabkan oleh hipotesa-hipotesa yang biasa muncul atawa justru disebabkan hal-hal lain yang selama ini kurang mendapat sorotan dari para guru. Misalnya, siswa B sakit sebab terlalu banyak membaca buku.
Kesakitan Ilmiah
Buku-buku diktat keilmuan di institusi pendidikan ialah akar-akar kebahagiaan para siswa dan guru-guru. Membaptis diri pada buku-buku diktat dengan bahasanya yang ilmiah ialah modal utama kesuksesan capaian pendidikan. Bila capaian itu hendak diwakili dengan angka-angka.
Beriman kepada buku-buku diktat, bahasa-bahasa ilmiah, yang muaranya pada penyerahan diri terhadap sistem pendidikan yang ada masih banyak diyakini sebagai kebijakan paling arif. Predikat pintar dan baik yang diperoleh siswa ialah kala siswa itu tunduk terhadap aturan-aturan yang ada, atawa istilahnya tak banyak melakukan perlawanan terhadap tatanan kehidupan pendidikan yang sudah ada.
Sebaliknya, siswa “sakit” ialah para siswa yang membelot, menyeberangi sungai ilmiah. Yang barangkali lebih senang berlama-lama membaca buku-buku nondiktat –untuk menyebut buku-buku fiksi semacam novel dan puisi, serta buku-buku non fiksi misalnya esai.
Bila buku-buku diktat menyajikan jawaban-jawaban atas pertanyaan, maka buku-buku nondiktat lebih kerap mempertanyakan jawaban-jawaban yang selama ini ada dan diyakini kebenarannya dalam kehidupan. Barangkali di situlah letak kenikmatan kesakitan yang dialami para siswa “sakit”. Tentang gaya bahasanya, ketakterdugaan-ketakterdugaan yang sembunyi di bilik-bilik lembarnya.
Ihwal bahasa ilmiah dan kaitannya dengan buku-buku diktat, perkataan seorang dosen mengendap dalam benak saya. Perlu menjadi perhatian bagi mahasiwa, supaya tidak menulis skripsi dengan bahasa yang tidak ilmiah.
Sebab identitas keagungan seorang akademis ialah kemampuannya berbahasa ilmiah terutama dalam karya-karya tulisnya. Maka mahasiswa musti merunduk-runduk pada tata kebahasaan yang demikian berjarak dengan mata manusiawi kita.
Sejauh perjalanan pendidikan yang saya alami di perguruan tinggi, para dosen atawa bahkan lebih jauh lagi—sistem pendidikan—belum memiliki iktikad memaklumi eksperimen berbahasa para mahasiswanya. Sehingga bahasa-bahasa dalam skripsi dan beragam penelitian di kampus ibarat pusaran angin puting beliung. Kaku dan itu-itu melulu. Sementara dalam pikiran dan perasaan siswa “sakit” yang disebabkan pembacaan mereka terhadap beragam buku nondiktat timbul riak kecamuk yang mahadahsyat. Tsah!