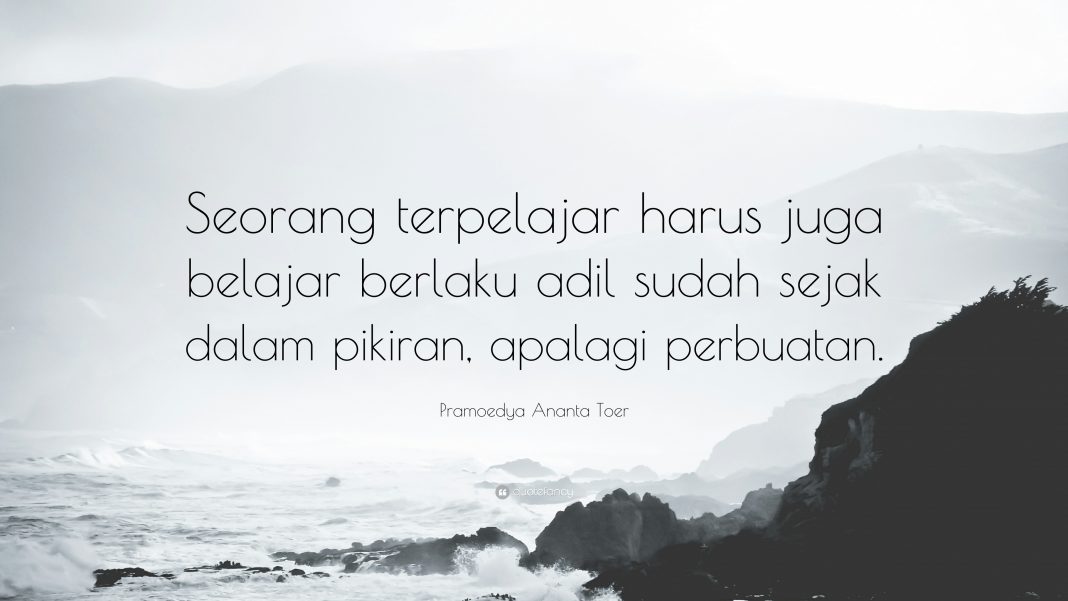Penulis: M. Dudi Hari Saputra, MA. (Peneliti di Indonesia Development Institute, Jakarta).
‘Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan’.
(Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia, 1975.)
Ungkapan ini selalu berseringai di kepala, menginspirasi namun sekaligus menampar sanubari. Bagaimana tidak, ketidakadilan intelektual lebih sering dipertontonkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya kaum terpelajar.
Fenomena fallacy (kekeliruan berfikir) bahwa saya professor maka saya lebih baik dari yang doktor, atau yang doktor maka saya lebih baik dari yang master, atau yang master maka saya lebih baik dari yang sarjana, atau yang sarjana maka saya lebih baik dari yang tidak memiliki gelar kesarjanaan apa-apa.
Gradasi intelektual yang dimaknai sebagai hirarki kebenaran yang menyesakkan, belum lagi fenomena bahwa saya lulusan dari sini maka lebih baik dari lulusan dari sana, dsb.
Bagaimana ukuran-ukuran prestasi pribadi menjadi kriteria kebenaran?. Seperti nada sindir dari Bambang Sugiharto: Bisa jadi anda benar, tapi karena anda bukan siapa-siapa, maka anda dianggap ngawur. Sedangkan bisa jadi ucapan yang ngawur tapi karena keluar dari mulut professor, maka ungkapan itu “dianggap” benar dan logis.
Berkelibat teringat ungkapan Sayidina Ali bin abi thalib kwjh.: Perhatikan apa ucapannya, bukan siapa yang mengucapkan.
Kalimat sederhana ini memiliki dasar pijakan epistemologi dan objektifitas yang kuat: Bahwa ukuran kebenaran bukan karena siapa penyampainya, tapi bagaimana rasionalitas dan korelasi dengan fakta dari apa yang diucapkan, yakni apakah mampu menjelaskan atau sesuai dengan kenyataan.
Tidak jarang, dalam perjalanan intelektual pribadi, saya lebih sering menemukan orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu dan wawasan yang luas karena belajar dari proses-proses informal. “Ketidakbertitelan” malah membuat mereka menjadi lebih tawadhu sehingga mampu menyelami realitas yang sebenarnya terjadi.
Ibarat kata: Teori-teori yang terlalu banyak, malah menjadi penghalang diri dengan realitas yang sebenarnya terjadi (ilmu sebagai hijab/penghalang).
Saya teringat ketika bertanya kepada Ferizal Ramli tentang bagaimana kualitas pendidikan di Jerman, universitas mana yang sebaiknya dimasuki. Dia menjawab bahwa semua universitas di Jerman memiliki kualitas yang setara.
Lantas bagaimana dengan Indonesia ?, disadari atau tidak, fenomena ego intelektual masih ada, bahwa saya dari alumni universitas sini, tentu lebih dari anda yang alumni universitas sana.
Namun fenomena ini bukan sekedar mindset atau citra, namun benar-benar terjadi. Adanya disparitas kualitas universitas di Indonesia turut memberikan andil tidak meratanya kualitas SDM di seantro nusantara tercinta.
Bagaimana bisa terjadi pemerataan pembangunan dan pendidikan, jika dosen-dosen terbaik hanya berkutat pada alumni nya?, atau di kota-kota besar di mana fasilitas begitu lengkap?.
Lantas, bagaimana kita bisa adil dalam berfikir, terlebih dalam bersikap?, jika kita terus menjaga mekanisme sistem yang membuat orang-orang pintar berkumpul pada satu tempat, tanpa ada usaha untuk menyebarkan kesetiap pelosok negeri?.
Apa alasan bahwa orang Papua tidak berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama baiknya seperti di Surabaya, Bandung, Jogja atau Jakarta?.