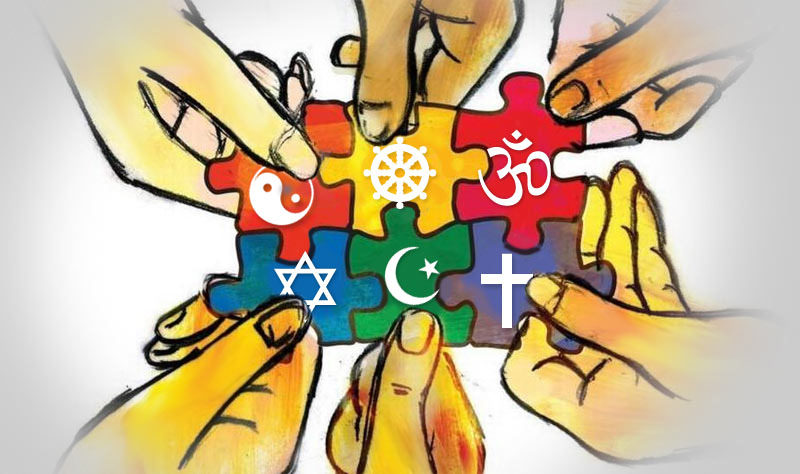Adanya penyerangan di Gereja Lidwina oleh seorang pemuda belum lama ini di Yogyakarta menyampaikan pesan berharga kepada kita: toleransi masih dangkal. Karena itu, mendesak untuk segera kembali membiakkan toleransi.
Menanamkan toleransi kepada anak muda sesungguhnya tidak bisa cukup dengan pengajaran. Pemahaman akan perbedaan harus dialami dan dirasakan ibarat belajar berenang, kita tak bisa menjadi atlet renang kalau hanya mengandalkan buku-buku teori.
Kita harus tercebur langsung ke dalam kolam, merasakan tekanan airnya, mengukur kedalamannya, lalu menyeimbangkan air dengan tubuh supaya tidak tenggelam. Bagi perenang, air adalah hidup. Air bukan untuk dihindari, tetapi untuk dirasakan. Tanpa air, seseorang tak pernah menjadi atlet renang. Alih-alih menghanyutkan, air justru menjadi wadah agar tubuh tidak terbenam ke dasar kolam. Begitulah kiranya dengan toleransi. Kita tak akan pernah benar-benar toleran kalau hidup di lingkungan sendiri.
Menjadi pribadi toleran berarti harus menceburkan diri ke kolam kehidupan, merasakan geliatnya, mengukur kedalamannya, lalu mencari keseimbangan agar tidak tersesat antara cinta dan benci yang buta. Menjadi toleran tak bisa hanya dengan mengkaji buku, memahami teori Pancasila, apalagi hanya membaca kitab suci. Menjadi toleran harus membersamai setiap orang. Arti membersamai pun tak bisa semata membersamai orang sekitar yang kebetulan dipersatukan oleh sebuah identitas.
Psikolog Amerika Muzafir Sherif pada tahun 1950-an menyebutkan bahwa konflik dan kebencian terjadi justru karena interaksi sesama kelompok, bukan pada pribadi lepas pribadi. Interaksi inilah yang kemudian menimbulkan fanatisme dan kebencian. Toleransi adalah kesadaran. Namun, kesadaran hanya akan terjadi kalau kita terjun dan tercebur ke kolam kehidupan. Kesadaran itu adalah bahwa kita harus paham, negeri ini menjadi majemuk secara alami. Ya, benar-benar alami.
Seperti kata Sindhunata, kita benar-benar tidak tahu mengapa di Indonesia ini ada beragam hayati, meski dengan sentuhan sinar matahari yang sama. Begitulah kenakeragaman hayati, benar-benar alami. Timbul begitu saja. Dan, di sanalah keindahannya.
Ibarat taman, tentu sangat menjemukan jika taman itu hanya ditumbuhi mawar saja. Mata kita akan lelah, bahkan stres melihatnya. Karena itu, taman harus ditumbuhi berbagai bebungaan. Bebungaan itu tumbuh bersama dengan keragamannya, meski dengan sarapan matahari yang sama. Sangat alami.
Kitalah bunga-bunga itu. Kita adalah bunga di taman Tuhan, ujar John James Osborne dalam buku puisinya, Flowers In God’s Garden. Kita beragam dengan caranya yang sangat alami. Tak ada yang mengusahakannya demikian. Bukankah Pancasila adalah hasil galian bangsa dan sama sekali bukan temuan?
Pancasilan itu adalah lambang kealamian. Pancasila adalah sesuatu yang natural. Sekali lagi, seperti kata Sindhunata, bahwa kita sama sekali tidak tahu, mengapa ada keragaman hayati di zamrud khatulistiwa ini.
Semestinya kita juga harus sadar bahwa kita tidak tahu mengapa terlahir berbeda dan beragam. Karena itu, tak semestinya kita mengutuk, apalagi mengasingkan sesuatu yang berbeda di luar kaum kita. Sebab, seperti kata Spengler, bahwa kultur tumbuh begitu saja, tak bisa ditentukan dan seakan tanpa tujuan, persis seperti bunga-bunga yang tumbuh di ladang-ladang. Di taman itu, kita tak bisa mencerabut bunga melati yang tumbuh bersisian dengan bunga anggrek meski keduanya beda spesies (kultur).
Selain taman menjadi menjemukan, akar anggrek bisa tercerabut, lalu layu sebelum pada akhirnya mati. Demikian juga dengan kultur. Kita tak bisa mencerabut seseorang dari kulturnya hanya karena dia berbeda dengan kita. Tentu saja perbedaan manusia tidak bisa disamakan dengan perbedaan anggrek dan melati. Anggrek dan melati beda spesies, sementara manusia hanya sekadar beda kultur.
Intinya, kita tak bisa mencerabut akar kultur orang yang berbeda dengan kita. Selain jadi homogen, tanpa kita tahu, akar kultur kita juga bisa tercerabut, kamudiaan layu, lalu mati secara perlahan.
Karena itu, kultur orang lain yang bersisian dengan kita harus dijaga, bukan ditenggelamkan. Sesungguhnaylah kita ini adalah makhluk sosial. Kita lahir untuk bersisian dan bersama orang lain. Begitulah syarat negeri bahagia, demikian kalau boleh memelintir kata Kurnia JR. Negeri bahagia adalah tempat kita kembali, tempat berlindung di masa tua.
Di negeri bahagia itu, kita mengenang segala kelakuan kita sebelum akhirnya benar-benar pergi. Ke mana kita kembali kalau bukan ke tempat asal kita yang benar-benar beragam itu? Nah, dalam pada itulah, rasanya menjadi mendesak bagi kita untuk kembali membersamai orang lain. Apalagi pada masa kontemporer ini, banyak oknum yang ingin mencerabut kultur yang tumbuh bersisian dengan kita. Mereka ingin kita berdiri sendiri. Bahkan, tak sedikit dari kita yang ingin berdiri sendiri.
Berbagai survei, misalnya, menyebutkan bahwa banyak siswa kita yang menolak Pancasila. Dalam studi Endang Turmudi (2016), peneliti senior LIPI, menyebutkan angka yang gawat: 84,8 persen siswa sepakat agar Pancasila ditukar. Padahal, Pancasila adalah sesuatu yang alami. Ini terjadi karena guru kita juga banyak yang ingin menukar Pancasila, sebesar 76,2 persen. Senada dengan itu, Wahid Institute (2016) juga menyebutkan bahwa ada 37 persen anak muda yang mendukung praktik radikalisme.
Harus Dialami
Angka-angka di atas adalah bentuk hidup dari keinginan kita untuk menolak sesuatu yang natural. Ini terjadi karena kita tidak menceburkan diri ke kolam kehidupan. Kita ingin menjadi atlet renang, tetapi alergi air.
Lebih dari itu, kita ingin mengasingkan diri dari orang lain. Kita ingin berdiri sendiri. Padahal, berdiri sendiri sama halnya dengan kesepian. Kita tak sadar bahwa seperti kata Chairil Anwar, jika menyendiri, kita akan mampus dikoyak-koyak sepi. Karena itu, sangat menyejukkan apa yang dilakukan Sabang-Merauke (Seribu Anak Bangsa Merantau untuk Kembali).
Sabang-Merauke melakukan pertukaran siswa antardaerah dengan memilih keluarga angkat yang agamanya berbeda. Kegiatan ini menjadi sebuah kesadaran bahwa bersama itu harus menceburkan diri; bahwa bersama itu harus dialami-dirasakan, bukan dipelajari.
Kita yakin, adanya kebencian bukan karena hakikat kita membenci. Menurut Erich From dalam The Anatomy of Human Destructiviness (1973), sesungguhnya tak ada manusia yang terlahir membenci, seperti agresif dan merusak. Kita hanya kurang komunikasi satu sama lain.
Inilah yang dialami Apipa (muslim), siswa yang ikut program Sabang-Merauke. “Pertama kali jumpa mereka (keluarga angkat dari Kristen), saya takut, karena saya takut orang dari agama-agama lain.”
Namun, setelah tercebur ke kolam kehidupan, alih-alih membenci, Apipa bahagia, bahkan semakin tercerahkan. Toleransi memang harus dialami secara langsung. Setidaknya, begitulah hasil studi Pettigrew dan Tropp (2006). Pada penelitian itu, mereka melakukan metaanalisis terhadap lebih lima ratus studi yang meneliti efek kontak antarkelompok.
Dari penelitian itu, mereka kemudian menemukan bahwa setelah kontak, sikap terhadap kelompok menjadi lebih positif dari waktu ke waktu. Mereka mampu melihat bahwa orang lain berbeda adalah sebuah anugerah dan keniscayaan. Mereka akan melihat ke titik universal (persamaan), bukan ke titik privat (perbedaan).
Dengan kata lain, jika individu dalam kelompok yang berbeda sudah melihat diri mereka sebagai anggota dari entitas sosial yang tunggal, kontak positif akan meningkat dan bias antarkelompok akan berkurang (Baron & Byrne, 2000). Singkatnya, toleransi itu harus dialami, tak cukup hanya diajarkan!
Kolom terkait:
Catatan dari Notre Dame: Belajar Menghargai Perbedaan Keyakinan
Keragaman Agama Itu Sunnatullah
Kebhinekaan Itu Sunnatullah, Hentikan Politisasi Pluralisme!