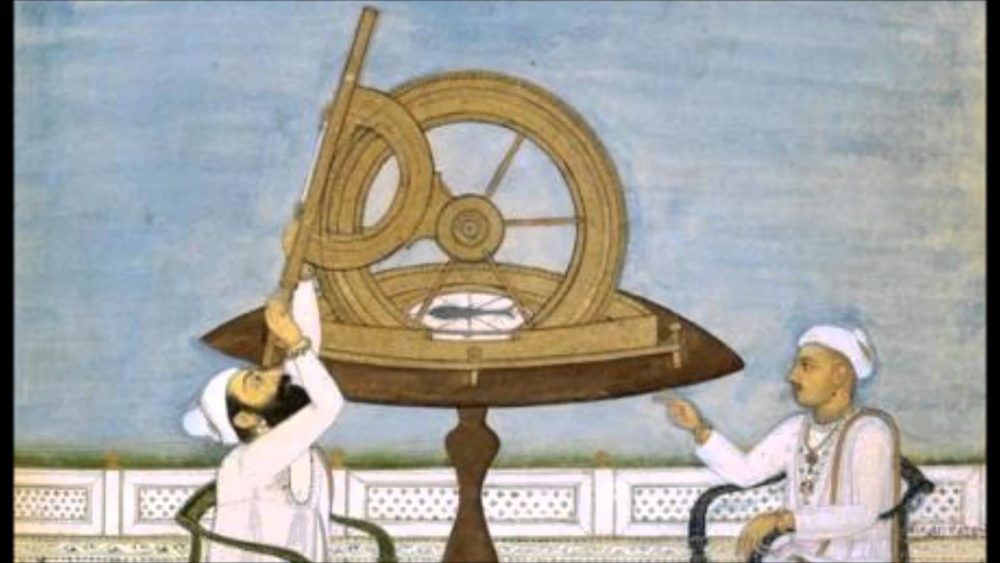Pada 1988, sarjana Jerman Reinhard Schulze menghebohkan jagad intelektual, terutama di kalangan mereka yang menggandrungi Islam modern. Dalam kongres kaum orientalis di Cologne, Jerman, ia melancarkan kritik terhadap kesarjanaan yang melihat reformasi Islam semata karena interaksinya dengan, atau pengaruh dari, Barat.
Tak ada keraguan, Islam mengalami periode stagnan yang cukup lama. Sebuah masa yang biasanya dikenal dengan sebutan “taklid”. Kreativitas dan inovasi pemikiran yang menandai kecemerlangan masa keemasan Islam (golden age) telah ditenggelamkan oleh kejumudan dan fanatisme. Diktum yang dikenal luas dalam periode stagnasi tersebut, bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Pertanyaannya, kapan dinamika pemikiran Islam mulai menggeliat kembali?
Historiografi yang dominan di kalangan sarjana ialah modernitas di dunia Muslim merupakan impor dari Barat. Kaum Muslim tertidur lelap dan mulai tersadarkan setelah dikejutkan oleh invasi Barat dan berkenalan dengan ide-ide progresif yang muncul di Barat.
Schulze datang dan melacak jejak-jejak reformasi dalam Islam pada abad ke-18 sebelum terjadinya pertautan dunia Muslim dengan Barat. Bukan hanya itu. Yang menyulut kontroversi ialah klaimnya bahwa seperti halnya Eropa yang mengalami Pencerahan (Enlightenment) pada abad ke-18, demikian juga yang terjadi dengan dunia Islam. Ia bahkan menyebut apa yang terjadi di dunia Islam abad ke-18 sebagai sebuah “islamische Aufklärung” (Islamic Enlightenment). Reaksi terhadap hipotesis Schulze sangat beragam, bahkan bisa dikatakan heboh.
Terlebih ketika Schulze mempublikasikan ceramahnya, beragam respons muncul dari sarjana-sarjana beken seperti Albrecht Hofheinz, Rudolf Peters, Tilman Nagel, Bernd Radtke, dan lain-lain. Sebelum bicara lebih jauh signifikansi pandangan Schulze bagi proyek kontekstualisasi Islam, ada baiknya kita diskusikan model kesarjanaan yang lebih fashionable sebelumnya.
Pengaruh Barat
Di mata banyak orientalis, reaksi kaum Muslim terhadap (kolonialisme) Barat tidak semata dilihat dalam konteks perlawanan dan resistensi. Di balik resistensi tersebut ada semacam kekaguman tentang kemajuan yang diraih oleh negara-negara Barat. Tema yang cukup favorit di kalangan Muslim saat itu ialah kenapa dunia Islam terbelakang, sementara Barat mengalami kemajuan.
Mereka merancang berbagai macam proyek reformasi atau pembaharuan Islam dengan cara menganjurkan perombakan tatanan masyarakat. Struktur yang mereka warisi dari masa silam terbukti tak mampu bersaing dengan pencapaian Barat. Secara diam-diam mereka ingin mereformasi masyarakat Muslim dengan meniru hal-hal yang mereka anggap baik dari Barat.
Konstruksi pembaharuan Islam model ini, menurut sejumlah orientalis, merupakan pengaruh dari interaksi kaum Muslim dengan ide dan konsep Barat. Hal ini tergambar, misalnya, dari karya Albert Hourani yang sekarang sudah menjadi klasik, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (1962). Seperti tampak dari judulnya, masa liberal dalam pemikiran Arab berawal dari tahun 1798. Kenapa? Itulah tahun ketika Napoleon Bonaparte dan pasukan Prancis mendarat di Mesir.
Artinya, benih-benih pemikiran liberal di kalangan kaum Muslim bermula dari interaksi dan perkenalan mereka dengan Barat. Menarik dicatat, Hourani memulai bukunya yang dibaca luas ini dengan mendiskusikan pemikir-pemikir Arab yang terkesima dengan ide dan budaya Barat, dari Rifa’at al-Tahtawi, Khairuddin al-Tunisi hingga Muhammad Abduh.
Tahtawi pernah tinggal beberapa lama di Prancis. Dia diutus oleh Muhammad Ali Pasha untuk menjadi imam di Paris. Dia begitu mengagumi budaya orang-orang Prancis. Bukan hanya menjadi imam, ia juga belajar bahasa Prancis dan membaca buku dan literatur negara itu. Sepulangnya ke Mesir ia menulis buku mengekspresikan kekaguman itu, berjudul Talbis al-ibris fi talkhis baris (Pemurnian Emas dalam Ikhtisar gambaran Paris).
Dari judulnya saja kita sudah bisa menerka isinya. Betapa kekagumannya pada Paris begitu mendalam. Dia suka jalan-jalan Paris yang bersih, budaya saling menghargai, bahkan cara mereka menyiapkan hidangan makanan di atas meja.
Khairuddin al-Tunisi juga mengekspresikan kekagumannya pada Barat. Sebagai politisi yang sukses di wilayah Ottoman Suriah, ia menulis buku yang menyarankan agar pemerintahan Ottoman menerapkan sistem politik ala Barat. Dalam bukunya, Aqwam al-Maslaik fi Ma’rifat Ahwal al-Mamalik (Jalan Lurus tentang Situasi Pemerintahan), ia mengadvokasi sistem parlementer yang konstitusional dan modernisasi pendidikan.
Kekaguman Abduh terhadap Barat sudah menjadi pengetahuan umum. Dia dikenal dengan pernyataannya “Saya melihat Islam di Barat tapi tanpa Muslim, dan melihat kaum Muslim di dunia Islam tapi tak ada Islam.”
“Pencerahan Islam”
Schulze tidak mempersoalkan kekaguman tokoh-tokoh Muslim terhadap Barat seperti ditulis Hourani. Yang dia persoalkan adalah kecenderungan sarjana-sarjana Barat untuk mengabaikan dinamika internal dalam tradisi Islam sendiri. Karenanya, ia melacak benih-benih reformasi Islam bukan pada kedatangan Napoleon di Mesir, melainkan jauh sebelumnya sejak paruh pertama abad ke-18.
Di Barat, abad ke-18 dikenal sebagai awal modernitas dalam pengertian yang sesungguhnya. Pencerahan, revolusi industri di Inggris, dan revolusi politik di Amerika dan Prancis menjadi simbol perkembangan. Dengan kata lain, abad ke-18 acapkali dipersepsikan sebagai tahapan baru dalam kehidupan Barat ketika akal dan ide-ide kemajuan mendapat perhatian utama.
Schulze mengidentifikasi ciri khas Aufklärung atau Pencerahan Eropa yang sebenarnya dapat ditemukan dalam Islam. Sebagaimana dirumuskan oleh Immanuel Kant dalam “What is Enlightenment?”, manusia yang tercerahkan mengakui kemampuan dirinya dan tidak tergantung pada faktor eksternal.
Selain soal “subjectivity” ini, Pencerahan juga ditandai oleh pergeseran dari pandangan teosentrik menuju antroposentrik. Ide-ide lama tidak lagi dianggap paling otentik. Sebaliknya, kebaruan dan ide tentang kemajuan (the idea of progress) ditekankan. Pencerahan juga mengasumsikan emansipasi sosial dan ekonomi.
Bagi Schulze, semua ciri-ciri Enlightenment itu dapat ditemukan dalam Islam abad ke-18. Seruan untuk tidak tergantung pada pendapat-pendapat ulama terdahulu mulai terdengar dan pintu ijtihad dibuka kembali karena sesungguhnya tidak ada yang menutupnya.
Yang luput dari perhatian Schulze adalah bahwa seruan untuk menghidupkan kembali ijtihad atau munculnya sikap kritis terhadap pandangan ulama terdahulu bukankah tipikal abad ke-18. Kata “ijtihad” sendiri bukan istilah baru. Pembaharuan Islam merupakan rekonseptualisasi berkelanjutan yang tak pernah henti-hentinya disuarakan oleh sejumlah ulama Muslim sebagai tugas keagamaan. Mereka menyitir hadits Nabi, bahwa di setiap abad akan selalu muncul seseorang yang bertekad memperbaharui agamanya.
Dengan kata lain, proyek kontekstualisasi Islam merupakan bagian dari dinamika internal Muslim yang berkesinambungan dari konsep-konsep lama seperti ijtihad (penalaran personal), tajdid (pembaharuan), islah (reformasi) atau ihya (penyegaran kembali). Dinamika internal tersebut tak lepas dari pengaruh semangat zaman dan konteks tertentu sehingga nuansa dan keragaman menjadi ciri khas yang utama.
Karena itu, walaupun Pencerahan Islam merupakan refleksi dinamika internal seperti dikatakan Schulze, pertautan dengan ide-ide Barat menjadi pemicu atau daya pendorong (impetus) bagi intensitas proyek kontekstualisasi Islam yang sudah diperkenalkan para pembaru Muslim terdahulu. Penjelasan ini bukan “teori ketiga” atau alternatif di antara Schulze dan Hourani, tapi semata untuk menunjukkan kompleksitas lahirnya Islam modern.
Saat ini gagasan Schulze sudah diterima luas. Tak lagi heboh. Sebab, kita memang tidak mungkin mengabaikan dinamika dan subyektivitas yang mengitari dan mengiringi sejarah Islam. Namun demikian, kita juga tak mungkin mengabaikan bahwa interaksi dengan Barat, setidaknya pada level gagasan, telah memperkaya berbagai dimensi kontekstualisasi Islam.
Baca juga: