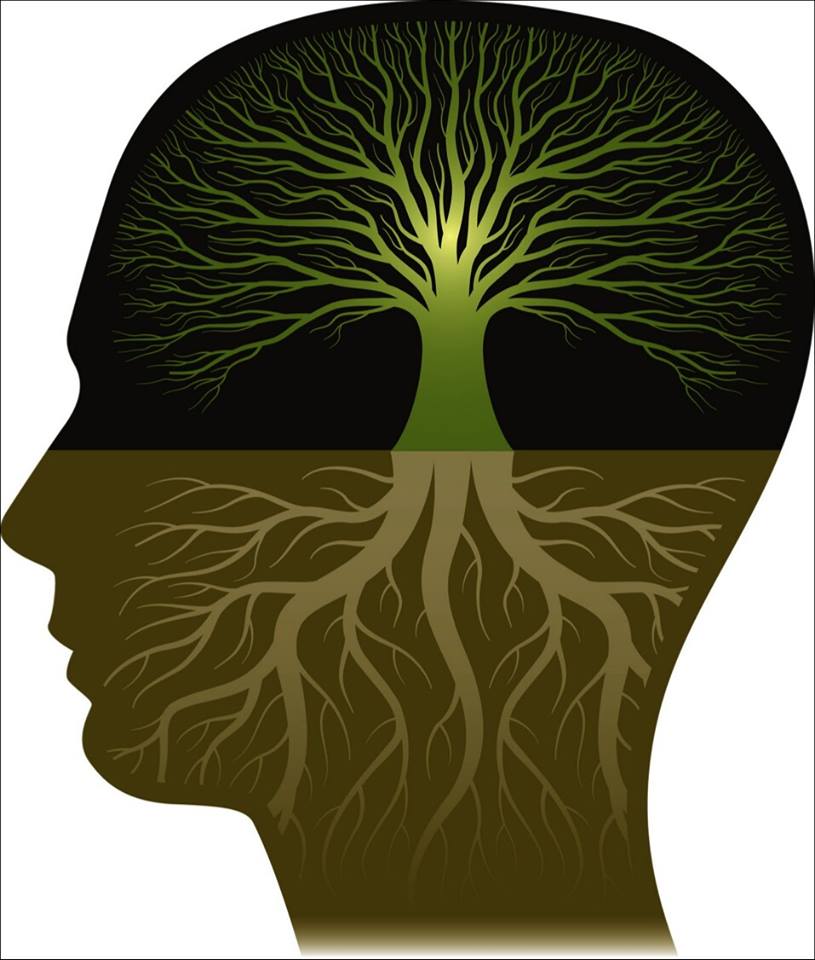Perkembangan kecerdasan buatan menandai fase baru dalam sejarah pengetahuan manusia. Jika modernitas ditandai oleh dominasi rasionalisme dan empirisme, maka era AI ditandai oleh kemampuan mesin untuk memproses data dalam skala masif, mengenali pola, serta menghasilkan simulasi realitas. Dalam konteks ini, hubungan antara agama dan sains kembali menjadi perdebatan penting. Islam, yang sering dianggap sebagai tradisi religius klasik, justru memperlihatkan relevansinya yang semakin kuat ketika ditinjau melalui lensa perkembangan teknologi mutakhir.
Dari sudut pandang ilmiah, salah satu titik temu yang paling signifikan antara Islam dan sains modern adalah persoalan biometrik, khususnya sidik jari. Ilmu forensik kontemporer membuktikan bahwa sidik jari setiap manusia bersifat unik dan tidak dapat direplikasi secara alami. Keunikan ini menjadi dasar bagi sistem identifikasi berbasis biometrik yang digunakan dalam keamanan digital, kriminalistik, dan autentikasi personal. Menariknya, Al Quran telah menyinggung detail tentang ujung jari manusia dalam Surah Al Qiyamah ayat empat. Secara teologis, ayat ini berbicara tentang kebangkitan di akhirat, namun secara epistemologis ia juga dapat dibaca sebagai pengakuan wahyu terhadap kompleksitas biologis manusia.
Dalam kerangka filsafat ilmu, hal ini menunjukkan adanya korespondensi antara wahyu dan realitas empiris. Wahyu tidak bertentangan dengan sains, tetapi justru mendahuluinya dalam mengafirmasi keunikan manusia pada tingkat mikrobiologis. Di era AI, keunikan sidik jari diproses sebagai data, dianalisis melalui algoritma pembelajaran mesin, dan digunakan untuk menentukan identitas individu dengan presisi tinggi. Semakin canggih teknologi ini, semakin terlihat bahwa apa yang dahulu dipahami secara teologis kini menemukan pembenaran ilmiah. Keajaiban Islam dalam konteks ini bersifat presains, yaitu wahyu yang selaras dengan temuan ilmiah jauh sebelum instrumen ilmiah tersedia.
Namun, keajaiban Islam di era AI tidak hanya terletak pada kesesuaian dengan sains, tetapi juga pada cara Islam menetapkan batas epistemologis terhadap representasi realitas. AI bekerja dalam paradigma representasional, yakni menganggap sesuatu dapat dipahami sejauh ia dapat direduksi menjadi data, pola, dan visualisasi. Teknologi pengenalan wajah, rekonstruksi gambar, dan model generatif menunjukkan ambisi manusia untuk memvisualisasikan hampir semua aspek realitas. Akan tetapi, dalam teologi Islam, wajah Allah tidak dapat divisualisasikan, dan penggambaran wajah Rasulullah SAW dihindari dalam tradisi arus utama.
Secara filosofis, larangan ini berkaitan dengan prinsip tanzih, yaitu penegasan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk-Nya. AI beroperasi dalam batas kategori empiris, sementara Tuhan berada di luar ruang, waktu, dan bentuk visual. Oleh karena itu, ketidakmampuan AI untuk menggambarkan Allah bukanlah kegagalan teknologi, melainkan konfirmasi bahwa realitas ilahi melampaui horizon pengetahuan manusia dan mesin. Islam dengan demikian berfungsi sebagai pengingat epistemologis bahwa tidak semua kebenaran dapat direduksi menjadi data.
Dalam kasus Rasulullah SAW sebagai panutan umat islam seluruh dunia, ketiadaan representasi visual autentik memiliki implikasi etis yang mendalam. Islam mewariskan kehadiran Nabi melalui riwayat, akhlak, dan ajaran, bukan melalui citra visual. Dalam era deepfake dan manipulasi gambar berbasis AI, pendekatan ini menjadi semakin relevan, karena ia melindungi integritas historis dan spiritual figur kenabian dari distorsi digital. Secara akademis, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk etika representasi dalam tradisi Islam.
Lebih jauh lagi, kecerdasan buatan juga membuka ruang baru untuk kajian ilmiah terhadap Al Quran. Dengan metode linguistik komputasional, para peneliti mulai menganalisis struktur kebahasaan, pola tematik, dan simetri naratif dalam teks suci. Meskipun pendekatan ini masih berkembang, temuan awal menunjukkan tingkat kompleksitas yang sulit direplikasi oleh manusia maupun mesin tanpa sumber transenden. Pada saat yang sama, AI tetap bergantung pada hukum logika dan keteraturan alam, yang dalam Islam disebut sebagai sunnatullah.
Dari perspektif integrasi ilmu, keajaiban Islam di era AI dapat dipahami dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi empiris, yaitu keselarasan wahyu dengan temuan ilmiah modern seperti biometrik. Kedua, dimensi epistemologis, yaitu pengakuan Islam terhadap rasionalitas tanpa mereduksi kebenaran menjadi data semata. Ketiga, dimensi metafisik dan etis, yaitu penjagaan batas representasi di tengah budaya visual berbasis teknologi.
Dengan demikian, Islam tidak sekadar bertahan di era AI, tetapi justru menawarkan kerangka intelektual yang lebih komprehensif. Wahyu membimbing akal, teknologi dimanfaatkan dengan etika, dan sains dihargai tanpa mengabaikan transendensi. Di sinilah letak keajaiban Islam yang sesungguhnya, bukan sebagai agama yang sekadar cocok dengan sains, tetapi sebagai tradisi yang mampu berdialog kritis dengan masa depan.