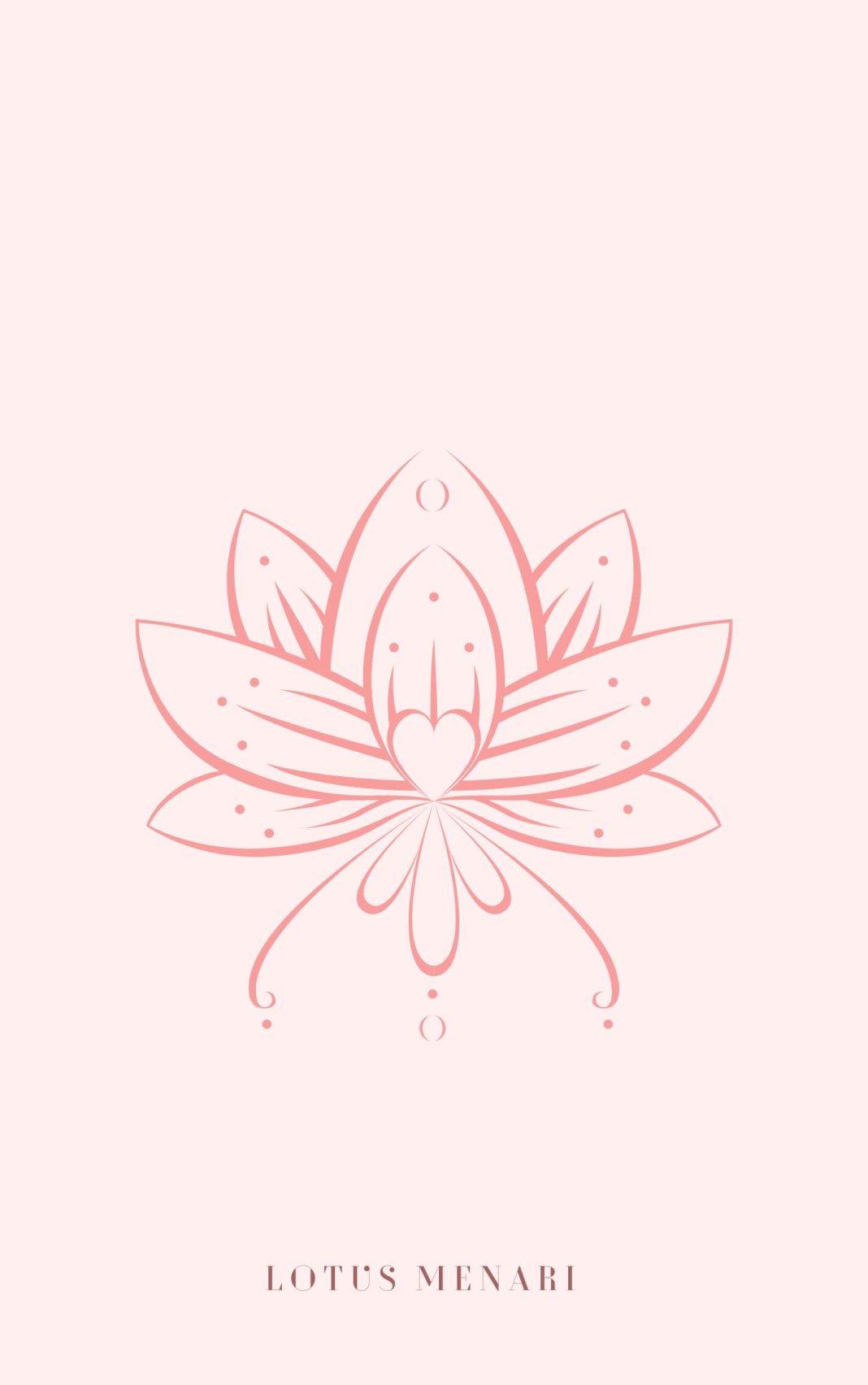Pagi tiba seperti biasa. Dari jendela kecil kamar kos, cahaya tipis menyelinap, menghapus sisa gelap malam seperti gula larut di dalam teh panas. Di meja kayu sederhana, secangkir kopi hitam mengepulkan uap. Aromanya bukan sekadar penanda hari dimulai, melainkan pengingat bahwa hidup—betapapun pahit—masih bisa dinikmati, seteguk demi seteguk.
Di balik tirai yang setengah terbuka, pertanyaan itu kembali muncul: apakah hari ini akan ada pertolongan? Apakah rezeki akan mampir tanpa diduga? Hidup dalam ketidakpastian finansial membuat setiap pagi terasa seperti doa yang dipanjatkan dalam diam. Dapur hanya menyisakan nasi dan telur. Saldo rekening hampir habis. Namun entah bagaimana tubuh ini tetap bangkit, bibir ini tetap menemukan alasan untuk tersenyum, seolah Tuhan meninggalkan secercah alasan untuk tetap bersyukur.
Ritual Kecil, Harapan Besar
Menyambut matahari pagi telah menjadi ritual yang saya cintai. Kehangatannya berbisik lembut: dunia belum sepenuhnya meninggalkanmu. Ada sesuatu yang nyaris sakral dalam cahaya itu—ia datang dengan setia, bahkan ketika hal-hal lain runtuh satu per satu. Dari situ, saya belajar satu hal sederhana tapi mendalam: konsistensi adalah harapan itu sendiri.
Dalam getirnya hidup, kopi dan sinar mentari menjadi sahabat. Kopi menghangatkan tubuh letih; matahari menenangkan hati yang gamang. Bersama-sama mereka mengingatkan bahwa, betapapun goyah langkah saya, hidup tetap layak dijalani.
Saya sering membayangkan, betapa rapuhnya hidup jika tidak ada ritual kecil semacam ini. Barangkali kita semua membutuhkan sesuatu yang sederhana, secangkir kopi, seberkas cahaya untuk tetap merasa manusiawi.
Universitas Kehidupan
Saya tahu saya tidak sendirian. Jutaan orang lain di dunia bangun dengan kenyataan serupa: merentangkan apa yang tersisa, menunggu sesuatu yang mungkin tak pernah datang. Ada yang kehilangan pekerjaan, terjerat utang, ada pula yang bahkan tidak punya rumah untuk kembali. Insecure finansial adalah benang halus yang mengikat kita dalam kecemasan bersama.
Namun ada hal lain yang juga universal: keberanian untuk bangkit lagi. Untuk menuang secangkir kopi. Membuka jendela. Menyapa hari dengan kalimat lirih: hari ini, aku akan mencoba lagi.
Kadang, “belajar” bukan hanya terjadi di ruang kuliah. Hidup sendiri adalah universitas paling keras. Ia mengajarkan kesabaran, keteguhan, dan kerendahan hati dengan caranya sendiri.
Doa yang Tidak Selalu Dijawab
Dalam hening pagi, saya berbisik pelan kepada Tuhan. Doanya sederhana, sering hanya satu kalimat: Ya Allah, cukupkanlah untuk hari ini. Tak selalu ada jawaban yang tampak. Namun saya belajar, jawaban tidak selalu hadir dalam bentuk uang di rekening. Kadang ia berupa ketenangan di dada, daya tahan di tengah lelah, atau kebaikan tak terduga dari seorang asing.
Tuhan mungkin tidak menjawab cepat, tetapi Ia selalu meninggalkan kekuatan secukupnya untuk bertahan.
Saya ingat satu kali, di tengah kegelisahan soal biaya hidup, tiba-tiba seorang kawan mengirim pesan: “Aku masak lebih, mampir ya.” Sepiring nasi hangat dan obrolan ringan malam itu terasa lebih berharga daripada seribu kata motivasi.
Seni Bersyukur di Tengah Kekurangan
Ada ironi dalam kemiskinan: ketika tak banyak yang dimiliki, hal-hal kecil terasa seperti karunia besar. Sepiring nasi dengan telur dadar bisa menjadi pesta kecil. Secangkir kopi hitam bisa terasa seperti martabat yang dituangkan dalam bentuk cair. Bahkan cahaya matahari; gratis, berlimpah, tak terhentikan, menjadi hadiah paling berharga.
Bersyukur bukan berarti menutup mata dari penderitaan. Ia justru lahir dari kemampuan melihat secercah manis di balik getir. Seni menemukan cahaya kecil di tengah dunia yang kadang terlalu gelap.
Menulis, Cara Saya Bertahan
Selain kopi, doa, dan matahari, ada jangkar lain yang menjaga saya agar tidak terhanyut: menulis. Dari keterbatasan finansial, kata-kata tumbuh. Dari sesak di dada, kalimat lahir dan memberi ruang bernapas.
Menulis bukan sekadar pekerjaan; ia adalah penyelamat. Di sana saya bisa menangis sekaligus tersenyum, mengeluh sekaligus berterima kasih. Mungkin kata-kata ini, lahir dari keterbatasan, bisa menjadi jembatan menuju sesuatu yang lebih baik. Mungkin ia bisa mencapai seseorang, di sudut lain dunia, yang sedang berjuang dengan caranya sendiri.
Kadang saya berpikir: kalau kopi memberi hangat di tubuh, maka menulis memberi hangat di jiwa.
Fragil, Tapi Masih Ada Harapan
Esok bisa saja sama, bisa juga berbeda. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, setiap pagi saya masih bisa menuang kopi, membuka jendela, dan menyambut cahaya matahari dengan senyum kecil. Itu saja sudah cukup menjadi bukti: harapan belum pergi.
Hidup memang rapuh. Tapi selama saya bisa menulis, berdoa, dan duduk bersama cahaya pagi, saya percaya harapan akan selalu ada. Ketidakpastian memang pahit, tapi justru di situlah pintu kemungkinan terbuka. Dan di balik segala kemungkinan itu, saya yakin ada Tuhan yang tak pernah meninggalkan.