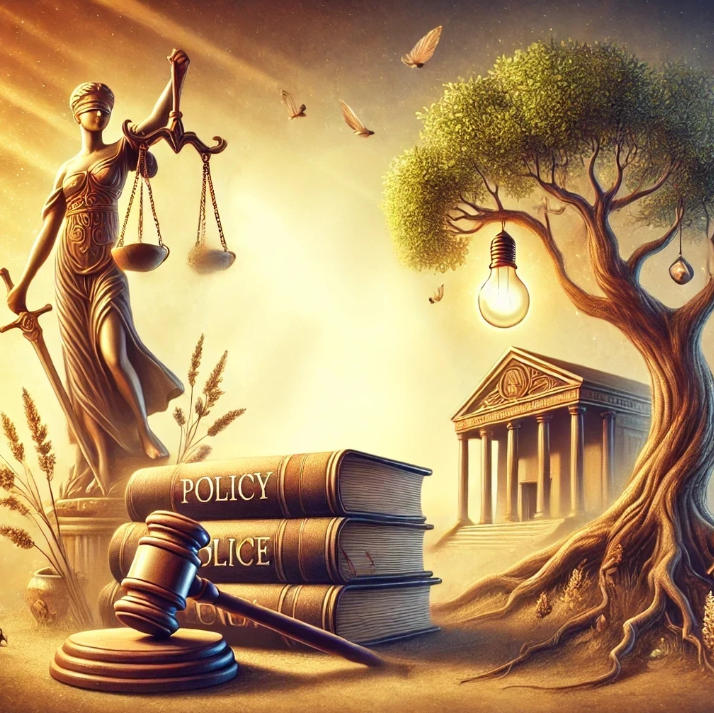Kebijakan (policy) sering kali berkelindan dengan kebijaksanaan (wisdom). Kebijakan dari segi etimologinya dapat diartikan sebagai tindakan atau prinsip yang diambil untuk mengarahkan keputusan (Ball, 2012). Sedangkan secara terminologi, kebijakan merujuk pada serangkaian keputusan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu masyarakat (Dye, 2017).
Adapun kebijaksanaan (wisdom) adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi tertentu dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan etika. Dalam konteks kebijakan, kebijaksanaan berarti memahami realitas di lapangan, memperhitungkan berbagai variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan, serta memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan (Drucker, 1993).
Kajian kebijakan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga sosial. Thomas R. Dye (2017) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai “whatever governments choose to do or not to do,” yang berarti kebijakan adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara itu, William Dunn (2018) mengemukakan bahwa kebijakan bukan hanya keputusan final, tetapi juga proses yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari politisi, birokrat, hingga masyarakat sipil.
Sejarah kebijakan dalam pemerintahan menunjukkan bahwa kebijaksanaan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Kebijaksanaan dalam konteks ini mengacu pada pemahaman yang mendalam tentang situasi yang ada serta kemampuan untuk merumuskan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan. Plato dalam “The Republic” menekankan bahwa seorang pemimpin yang bijaksana adalah mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang keadilan dan kebaikan bersama (Plato, 2003).
Dalam ranah kebijakan pendidikan, misalnya, kebijaksanaan menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Misalnya setelah Perang Dunia II berakhir dan Jepang berada dalam kondisi kehancuran akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, pemerintah di bawah kepemimpinan Kaisar Hirohito mengambil langkah strategis dengan mengumpulkan kembali sekitar 45.000 guru yang masih tersisa. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk segera memulihkan sistem pendidikan yang porak poranda akibat perang.
Para guru yang dikumpulkan kemudian ditempatkan di berbagai daerah, bahkan di bangunan darurat, untuk memastikan bahwa anak-anak Jepang tetap mendapatkan pendidikan meskipun dalam kondisi sulit. Selain itu, pemerintah mulai merancang kurikulum baru yang lebih menekankan pada nilai-nilai perdamaian dan pembangunan nasional, sejalan dengan reformasi yang didorong oleh Sekutu. Dengan kebijakan ini, Jepang berhasil membangun kembali sistem pendidikannya, yang kemudian menjadi salah satu faktor utama dalam kebangkitan ekonomi dan sosial negara tersebut pascaperang.
Dalam kebijakan ekonomi, kebijaksanaan dapat dilihat dalam kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah. Keynes (1936) dalam “The General Theory of Employment, Interest, and Money” menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang baik harus berdasarkan pemahaman yang dalam terhadap dinamika pasar dan perilaku masyarakat. Ketidakhati-hatian dalam merancang kebijakan dapat menyebabkan dampak negatif, seperti inflasi yang tidak terkendali atau pengangguran yang tinggi.
Dalam konteks sosial, kebijakan yang bijaksana juga memainkan peran penting dalam menangani isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan perlindungan lingkungan. Amartya Sen (1999) juga menekankan bahwa kebijakan sosial harus bertujuan untuk memperluas kebebasan individu, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Sen berargumen bahwa tanpa kebijakan yang bijaksana, pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat tercapai.
Salah satu contoh implementasi kebijakan yang kurang bijaksana adalah kebijakan urbanisasi yang tidak memperhitungkan kapasitas infrastruktur kota. Beberapa kota besar di dunia mengalami permasalahan kepadatan penduduk, kemacetan, dan degradasi lingkungan akibat kebijakan yang tidak dirancang secara matang (UN-Habitat, 2021). Sebaliknya, negara-negara seperti Denmark dan Finlandia menunjukkan bahwa kebijakan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan sosial dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman dan efisien (OECD, 2020).
Kebijaksanaan dalam kebijakan juga berkaitan dengan keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam pendekatan modern governance, kebijakan yang baik harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan lembaga internasional (Rhodes, 2017). Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan (Fischer et al., 2015).
Dalam dunia digital yang berkembang pesat, kebijaksanaan dalam kebijakan juga menjadi lebih kompleks. Misalnya, kebijakan mengenai perlindungan data dan privasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan nasional dan hak individu (Solove, 2020). Beberapa negara telah menerapkan regulasi ketat seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, yang bertujuan untuk melindungi data pribadi warganya dari penyalahgunaan oleh perusahaan dan pemerintah (European Commission, 2018).
Dari perspektif kebijakan lingkungan, kebijaksanaan diperlukan dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Contohnya, kebijakan energi hijau yang diterapkan di beberapa negara Eropa menunjukkan bagaimana kebijakan yang dirancang dengan visi jangka panjang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong penggunaan energi terbarukan (IPCC, 2021).
Aristoteles mengajarkan kita tentang konsep phronesis, kebijaksanaan praktis yang menjembatani pengetahuan universal dengan situasi khusus. Phronesis inilah yang menjadi roh dari setiap kebijakan yang efektif. Ketika kebijakan dirumuskan dengan kebijaksanaan, ia tidak sekadar menjadi rangkaian aturan yang kaku, tetapi menjadi organisme hidup yang mampu beradaptasi dengan kompleksitas realitas sosial.
Seperti seorang pemahat yang dengan cermat memahat batu menjadi karya seni, pembuat kebijakan yang bijaksana memahami bahwa setiap keputusan yang diambil akan meninggalkan jejak pada kanvas kehidupan masyarakat. Ia menyadari bahwa kebijakan bukan sekadar instrumen teknis, melainkan medium untuk mewujudkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat; keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia.
Dalam perjalanannya, kita menyaksikan bagaimana kebijakan yang dipandu oleh kebijaksanaan telah membawa kemajuan yang signifikan, sementara kebijakan yang tercerabut dari akar kebijaksanaan seringkali berujung pada kegagalan dan penderitaan. Ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, kebijaksanaan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar dalam tata kelola publik.