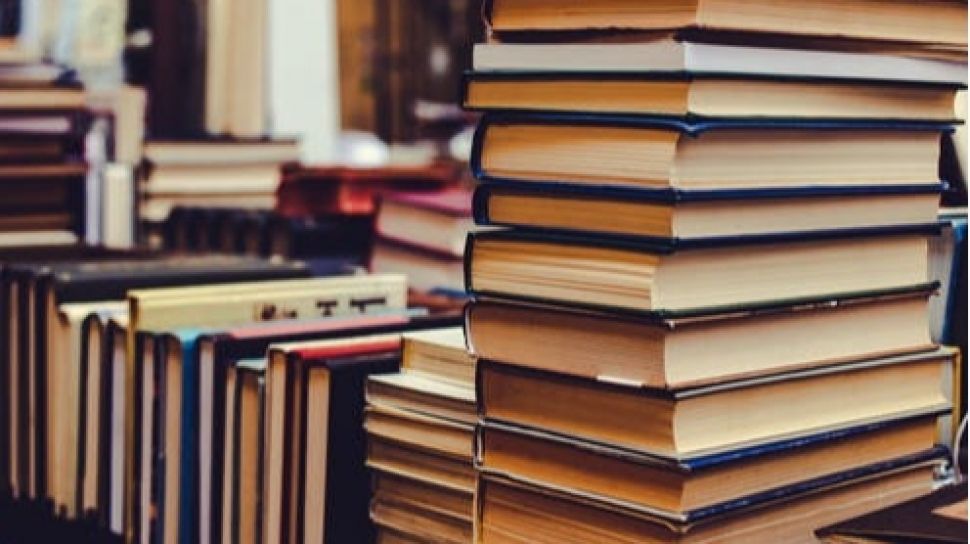Fiksi itu tidak mendidik. Kalimat ini sering terdengar di ruang-ruang diskusi kebijakan literasi, bahkan di balik rak-rak perpustakaan yang semestinya merayakan keragaman bacaan. Ironisnya, pandangan ini justru datang dari mereka yang dipercaya untuk menghidupkan budaya baca. Ketika fiksi disingkirkan atas nama akademik, kita lupa bahwa cinta membaca tak tumbuh dari jurnal ilmiah, melainkan dari halaman-halaman cerita yang menyentuh rasa. Perpustakaan semestinya tak melulu jadi ruang akademik yang kaku, namun juga bisa memaksimalkan fungsi sebagai ruang rekreasi.
Rekreasi dipahami sebagai upaya manusia mencari kesenangan. Salah satu bentuk rekreasi yang kerap dianggap sepele adalah membaca. Di Indonesia, hobi membaca masih dipandang membosankan, kalah menarik dibanding hobi fisik yang penuh energi. Dari sinilah muncul istilah “kutu buku” label bagi mereka yang dianggap hanya berkutat dengan teks, anti kegiatan fisik, bahkan dipersepsikan kurang gaul. Padahal tidak semua orang yang gemar membaca lantas menolak aktivitas fisik, membaca bisa berjalan seiring dengan kegiatan lain.
Fiksi yang Diperdebatkan
Namun yang lebih problematis, dunia membaca sendiri masih terjebak dalam dikotomi. Bacaan acap dibedakan menjadi berbobot dan tidak berbobot. Fiksi sering ditempatkan dalam kotak kedua, dianggap hanya hiburan, sementara nonfiksi dipuja sebagai bacaan intelektual. Persoalan ini bahkan merembet ke meja rapat pustakawan. Dalam forum-forum perpustakaan, diskusi mengenai jumlah kunjungan pemustaka hampir selalu disusul pertanyaan, “Buku apa yang paling sering dipinjam?” Jika jawabannya novel, maka seolah menjadi catatan merah bagi institusi.
Di ranah birokrasi, tekanan ini makin kuat. Berdasarkan aturan Perpustakaan Nasional, perpustakaan perguruan tinggi wajib memiliki dominasi koleksi nonfiksi akademik. Maka tak heran, lembaga pendidikan berlomba menambah koleksi ilmiah demi akreditasi. Strategi menarik minat baca pengunjung sering kali terpinggirkan. Padahal fungsi perpustakaan tidak berhenti pada penyediaan literatur akademik. Ia juga punya tanggung jawab menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat luas. Tak semua orang yang datang ke perpustakaan ingin belajar serius, banyak pula yang sekadar ingin bersantai, membaca novel kesukaan.
Sebagai pengunjung rutin, saya kerap merasakan jenuh jika hanya disuguhi buku akademik. Membaca novel fiksi menjadi penyegar, ruang bernapas yang membuat saya tetap betah kembali ke perpustakaan. Sayangnya, pilihan ini kerap dianggap tabu. Data kunjungan yang menunjukkan dominasi bacaan fiksi sering dipandang merugikan citra lembaga. Novel dianggap karya khayalan, tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka pembaca fiksi pun dicap kurang intelek, seakan hanya pembaca nonfiksi yang pantas disebut cerdas. Pertanyaannya, benarkah pembaca fiksi kurang kompeten?
Fiksi sebagai Pintu Masuk Literasi
Fiksi kerap direduksi sebagai bacaan ringan, padahal tidak sesederhana itu. Banyak karya sastra menuntut pembaca berpikir ulang, merenung, bahkan menantang cara pandang lama. Yang jelas, fiksi memperkaya kosakata melalui diksi yang berlapis, metafora yang jarang ditemui, dan kiasan yang melatih imajinasi. Inilah bekal awal yang tidak bisa diremehkan.
Riset mendukung pandangan ini. Dodell-Feder & Tamir (2018) menemukan bahwa membaca fiksi justru meningkatkan kemampuan kognitif sosial yakni memahami pikiran dan perasaan orang lain lebih signifikan dibanding membaca nonfiksi. Sementara studi Helena Hollis (2021) menunjukkan paparan fiksi berhubungan dengan keterbukaan berpikir kritis, sementara paparan nonfiksi cenderung mengarah pada absolutisme. Dua temuan ini menegaskan bahwa fiksi bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana melatih empati dan daya nalar.
Bagi perpustakaan, temuan ini seharusnya menjadi pijakan. Daripada menilai rendah minat baca fiksi, lebih tepat jika fiksi dilihat sebagai “pintu masuk.” Kebiasaan membaca novel bisa membentuk tradisi literasi, yang pada gilirannya mendorong pembaca menjelajah karya nonfiksi, ilmiah, hingga teks akademik. Mustahil memaksa orang langsung mencintai nonfiksi jika budaya membaca belum tertanam.
Gejolak di Meja Pustakawan
Gejolak inilah yang sering muncul di forum pustakawan. Di satu sisi, ada tuntutan birokrasi, koleksi akademik harus lebih banyak, laporan statistik bacaan nonfiksi harus tinggi. Di sisi lain, realitas lapangan menunjukkan novel dan cerita populer justru lebih diminati. Perpustakaan lalu terjebak dilema apakah mengikuti minat pengunjung atau tunduk pada aturan birokrasi?
Saya cenderung melihat keduanya bisa dipadukan. Perpustakaan bisa menggunakan fiksi sebagai strategi menarik pengunjung, lalu secara perlahan menggiring mereka ke bacaan nonfiksi. Program rak transisi misalnya, menyandingkan novel bertema sains dengan buku pengantar ilmiah, atau menempatkan cerita sejarah populer di samping literatur akademik. Dengan begitu, fiksi berperan sebagai jembatan, bukan sebagai lawan nonfiksi.
Mengubah Stigma
Menganggap pembaca fiksi kurang akademis jelas keliru. Faktanya, fiksi memberi kontribusi nyata dalam penguasaan bahasa dan kreativitas menulis. Banyak orang yang rajin membaca novel akhirnya mampu menulis dengan kaya diksi, alur, bahkan ide kritis. Di titik inilah terlihat, membaca dan menulis tak bisa dipisahkan.
Budaya membaca bisa dimulai dari mana saja. Dari komik, novel remaja, hingga karya sastra berat. Yang penting, ada kebiasaan membaca terlebih dahulu. Jika dasar ini sudah terbentuk, akses ke bacaan nonfiksi akan lebih mudah. Sayangnya, sebagian birokrat perpustakaan masih terjebak pada angka-angka akreditasi, sehingga gagal melihat nilai rekreatif dan strategis dari koleksi fiksi.
Padahal, rendahnya budaya membaca di Indonesia membutuhkan strategi kreatif. Menutup akses fiksi dengan dalih “tak akademis” justru kontraproduktif. Mungkin benar, fiksi tidak menghadirkan data empiris seperti nonfiksi. Tetapi fiksi menghadirkan rasa yang membuat orang jatuh cinta pada membaca. Dari rasa inilah kebiasaan terbentuk, dan dari kebiasaan inilah lahir pembaca nonfiksi yang kuat.
Perdebatan pustakawan soal fiksi dan nonfiksi seharusnya tidak lagi berakhir pada dikotomi berbobot versus tidak berbobot. Semua bacaan punya tempatnya. Fiksi adalah pintu, nonfiksi adalah jalan panjang. Tanpa pintu, orang tidak akan pernah melangkah. Karenanya, jangan remehkan pembaca fiksi. Mereka bukan kutu buku yang hidup di dunia khayal. Mereka adalah calon pembaca kritis, calon penulis, dan calon akademisi, asal perpustakaan berani mengubah stigma dan menjadikan fiksi sebagai sahabat dalam strategi literasi.