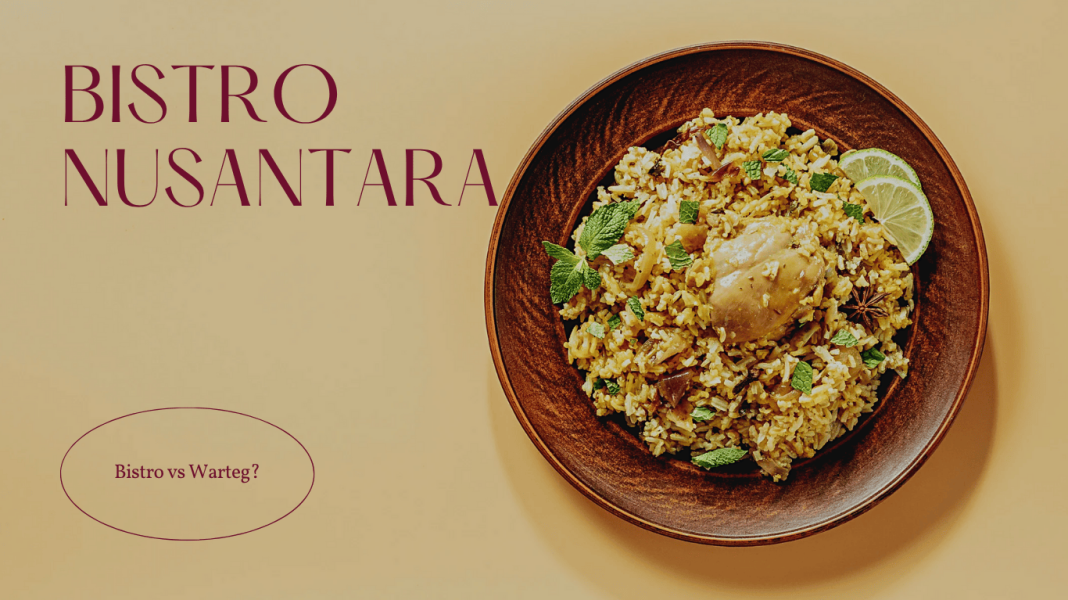Di balik kemeriahan “bistro Nusantara” yang menyajikan rendang sous-vide dan sambal matah infused truffle, tersembunyi pertarungan identitas: haruskah kita mengubah rasa demi pengakuan dunia, atau justru menjadikan tradisi sebagai harga mati?
Dua Wajah Kuliner Indonesia: Etalase vs. Kantong Budaya
Tampak seperti dunia cermin di lain sisi dari warteg, terdapat dapur yang yang membuat masakan lokal berubah nama menjadi “fried rice” dan melonjakan harga yang tak lagi Rp.15.000,- dalam satu porsi. Keduanya adalah anak sah dari setiap tukang masak dengan aneka racikannya.
Bistro mengklaim “penjaga otentitas” padahal ia mengganti kecap manis dengan balsamic glaze.Dalam diri saja masyarakat masih belum siap dengan beberapa konsekuensi atau yang dianggap inovasi? “Rendang wine? Itu penghinaan” (Minang,2017). Nama lokal dikorbankan dari “Ayam Geprek” menjadi “Smashed Chicken”, seolah kata Indonesia tak cukup bernilai, apalagi sampai merenggut makna budaya atau bahkan religi dalam makanan. Dari sini makanan tak lagi soal lidah tapi menjadi medan perang simbolik
Diplomasi Kuliner atau Imperialisme Rasa?
Strategi mengenalkan makanan lokal ke dunia merupakan alibi dari Bistro Nusantara, tapi mari kita sedikit melihat pelaku senior seperti Jepang misalnya, mereka tidak pernah mengganti “sushi” menjadi “vinegared rice roll”. Kata *washoku* (和食) justru dipatenkan sebagai warisan UNESCO.
Apa yang sebenarnya terjadi pada kita? Alih mengubah sambal tanpa peda, nasi goreng tanpa woke, bahkan sampai penambahan truffle pada nasi goreng merupakan “tokenism” untuk ornamen yang lebih mengarah ke justifikasi harga.Filsuf kuliner Claude Lévi-Strauss mengingatkan: “Makanan adalah bahasa.” Saat kita terjemahkan “nasi goreng” jadi “fried rice”, separuh kosakatanya hilang.
Batas Adaptasi: Di Mana Garis Merah?
Tentu batasan dibutuhkan dalam modifikasi makanan kita yang penuh makna religius sampai budayanya. Layaknya rendang yang tetap menjaga nilai kehalalannya karena kita faham non-muslim juga tidak masalah jika memakan Rendang halal kan?. Begitupun dengan filosofi lokal seperti gudeg dengan santan dan gula jawa karena ia simbol kesabaran dan agraris Jawa. Keaslian nama juga jangan terlupakan “sate” bukan “skewered meat” “tempe” bukan Javanese soybean cake”. Kita bisa melihat contohnya koki Malaysia di London menyajikan nasi lemak dengan salmon smoke — tapi tetap pakai *sambal ikan bilis* dan sebut namanya “Nasi Lemak 2.0”, bukan “coconut scented rice”.
Masih melihat dari negara tetangga, Thailand dapat mengemas tanpa menjual. Thailand punya Thai Select yaitu sertifikasi restoran otentik di luar negeri dengan syarat ketat, bahan impor maksimal 30%, harus ada menu pedas, nama menu wajib bahasa Thai “Tom Yum” bukan “sour spicy soup”. Dan yang terjadi Tom Yum Goong masuk 10 besar makanan terenak di dunia *versi CNN* tanpa mengganti nama bahkan mengurangi toleransi pedasnya.
Jalan Tengah: Bukan warteg vs bistro, melainkan kolaborasi
Mau bagaimanapun bistro tetap diperlukan sebagai perpanjangan tangan makanan lokal kita yang sangat kuat akan citarasanya. Maka klaim orisinalitas dalam bistro akan lebih jika “Rendang inspired beef curry” daripada rendang dengan pengatasnamaan orisinil dengan banyak modifikasi. Dan disisi lain warteg harus di kembangkan dari dokumentasi literasi oleh nenek moyang oleh universitas, kelas memasak oleh milenial, bahkan sampai pemerintah yang harus memproklamirkan “sate” dan “nasi goreng” sebagai istilah layaknya “sushi”.
Kuliner Nusantara bukan benda mati. Ia boleh berevolusi, tapi jangan sampai kehilangan roh. Bistro boleh menari di panggung global, tapi warteg tetaplah rumahnya. Sebab, seperti kata Pramoedya: “Seorang modern adalah dia yang akarnya paling dalam ke tradisi”. Berikan truffle pada nasi goreng jika perlu, tapi jangan korbankan terasi. Sebab disitulah identitas kita berbicara.