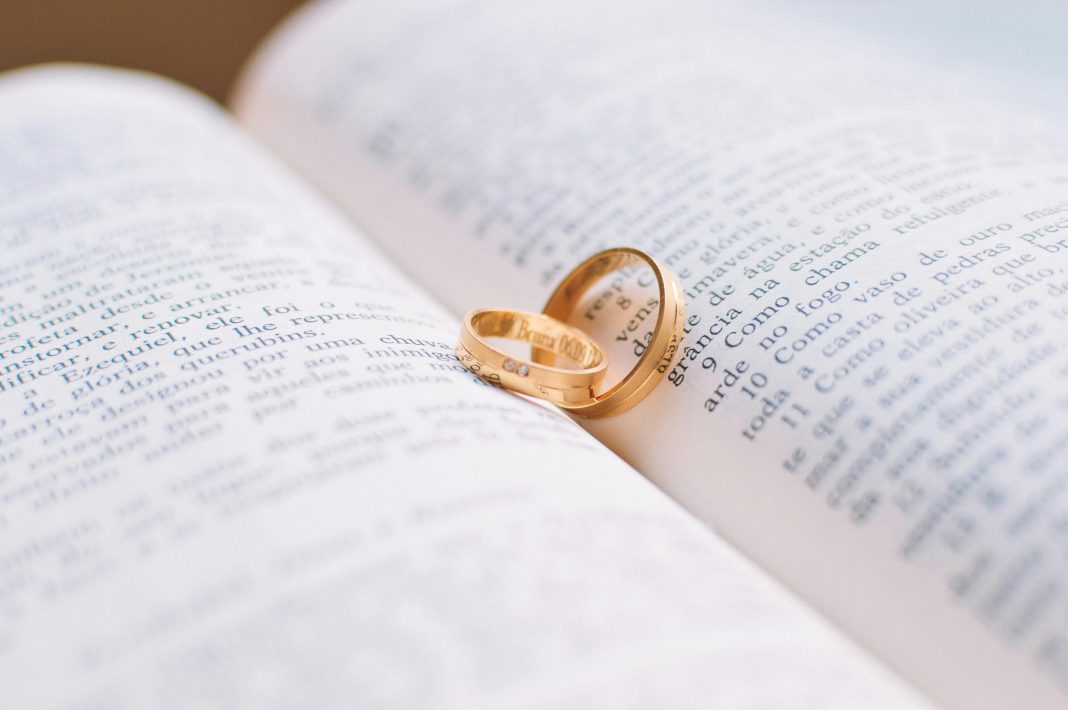Pendahuluan
Tuhan menjadikan pernikahan sebagai sarana yang tepat untuk melanjutkan dan mempertahankan eksistensi manusia di dunia ini. Dalam konteks masyarakat modern (yang hidup di kota) atau pun masyarakat tradisional (yang masih hidup di desa) pernikahan menjadi sebuah topik yang sekiranya menjadi penting untuk dibahas.
Keragaman adat dan budaya melahirkan keanekaragaman hukum yang berlaku pula di masyarakat. Apa yang menjadi pembahasan pada tulisan refleksi kali ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tradisional yang homogen perihal pernikahan dan kemudian terjadi perubahan ketika sudah masuk pada ranah masyarakat modern yang heterogen. Bagaimana perubahan sosial itu turut serta dalam mempengaruhi hukum yang tercipta di masyarakat sebagai sarana atau alat mencapai sebuah ketertiban?
Kerangka Teori
Ketika kita hendak membedakan hukum dari norma lainnya, maka penting bagi kita untuk mengadakan pemeriksaan apakah terdapat 4 atribut tersebut ada, yaitu otoritas legal, maksud untuk diberlakukan secara universal, unsur obligatio, dan sanksi.
Dalam masyarakat nasional, yang secara budaya majemuk (pluralistis), seorang warga yang tunduk pada sistem budaya yang berbeda mungkin lebih tunduk pada nilai budaya suku bangsanya jika ia harus melakukan peran tertentu, meskipun norma sosial untuk peran tersebut berbeda dengan norma sosial untuk suku bangsanya.
Dalam situasi seperti itu, dia menghadapi konflik norma atau nilai. Kemungkinan untuk tunduk pada norma yang lebih spesifik jangkauan daripada norma yang didasarkan pada budaya nasional perlu diteliti lebih lanjut.[1]
Hubungan antara hukum dan nilai-nilai budaya sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan hukum. Proses penciptaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah contoh di negara kita. Pembuatan peraturan itu memerlukan waktu yang lama.
Sejak tahun 1928, pergerakan wanita telah berjuang untuk undang-undang perkawinan dan keluarga. Keinginan itu terutama disuarakan sehubungan dengan kebiasaan yang merugikan wanita dan anak-anak, seperti perceraian yang tidak melindungi pasangan yang diceraikan dan mengawinkan anak hanya sesuai dengan keinginan orang tua. Karena berbagai golongan dalam masyarakat memiliki praktik yang berbeda, maka pertanyaan yang terus-menerus dan tidak dapat diselesaikan dengan baik adalah prinsip-prinsip manakah yang akan dipertahankan dalam undang-undang yang akan dibuat itu? Apakah mengikuti gagasan unifikasi, membuat undang-undang yang berlaku untuk semua golongan, atau bagaimana?[2]
Dalam diskusi tentang dampak sosial hukum, Lawrence Friedman dan Jack Ladinsky mendefinisikan perubahan sosial sebagai “setiap perubahan yang tidak repetitif dalam mode tingkah laku yang sudah mapan di dalam masyarakat” (Friedman dan Ladinsky, 1967: 50).
Di sini, kriteria “tidak repetitif” sangat penting karena definisi tersebut mengakui bahwa, jika ada, beberapa masyarakat benar-benar statis. Perubahan yang hanya terjadi dalam teknologi, kesejahteraan ekonomi, atau pandangan dasar masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang terus-menerus dan mungkin ada di mana-mana.
Hanya jika struktur sosial berubah, termasuk pola hubungan sosial, norma sosial, dan peran sosial, maka perubahan sosial dianggap sebagai perubahan sosial. Karena itu, perubahan dalam hubungan sosial yang sudah mapan antar kelompok ras dan etnik dalam sebuah masyarakat dapat menyebabkan perubahan sosial, tetapi tidak dapat dianggap sebagai perusahaan sosial untuk peningkatan atau penurunan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan. Meskipun jelas bahwa tujuan legislatif untuk manajemen ekonomi dan regulasi perubahan sosial berbeda, perbedaan ini sangat penting.[3]
Analisis dan Refleksi
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7, disitu dinyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”
Kemudian direvisi oleh UU No. 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun baik pihak pria maupun pihak wanita. Namun, jauh sebelum undang-undang ini dibuat dan disahkan, fakta yang terjadi di masyarakat memberikan kita informasi bahwasanya tak ada batasan minimum usia bagi anak yang hendak menikah –apalagi di masyarakat tradisional yang homogen.
Asal si anak sudah mencapai usia aqil baligh, maka jika si anak, baik karena keinginan sendiri atau atas dasar dorongan orang tua, ingin melakukan pernikahan, boleh-boleh saja dan lumrah-lumrah saja. Begitu juga dalam kaitannya dengan pencatatan pernikahan. Faktanya, di dalam konteks masyarakat kota, yang notabenenya modern dan heterogen, pun masih tetap dapat ditemukan beberapa anggota masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya –namun agakanya kita hanya akan berfokus pada usia minimum pernikahan saja.
Bagaimana sebenarnya alur antropologis-sosiologis yang ada di balik satir terciptanya UU No. 1 Tahun 1974 ini? Jika kita coba untuk menilik menggunakan kacamata antropologi dan sosiologi, maka kita akan menemukan sebuah fakta bahwa, trend menikah di usia dini telah menurun linear dengan meningkatnya angka kualitas pendidikan yang dienyam oleh wanita.
Fakta historisnya adalah, bahwa wanita-wanita yang hidup di zaman yang lebih awal, tidak mendapatkan pendidikan yang cukup baik. Pun juga mungkin berkaitan dengan pola pikir orang zaman itu yang mengatakan “ga perlu lah wanita sekolah tinggi-tinggi, toh nanti juga baliknya ke dapur, sumur, sama kasur doang.” Sehingga para orang tua tak ingin repot-repot mengeluarkan dan merogoh kocek yang cukup tinggi untuk menyekolahkan anak-anak gadisnya. “sudah, nikahkan saja si gadis” begitu kira-kira lumrahnya.
Seiring dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh wanita, maka lambat laun, sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan pikiran si wanita, trend menikah di usia dini pun menurun. Karena jelas si wanita berpikir bahwa, “kami sebagai wanita juga punya hak untuk berkarir dan menata hidup yang lebih baik. Bukan hanya untuk mengurusi suami saja.”
Oleh sebabnya, karena pola pikir dan trend yang lumrah terjadi di masyarakat berubah, maka hukum yang diciptakan pun mengikut pada perubahan sosial tersebut. Hal ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di India pun, undang-undang yang mengatur tentang usia minimum pernikahan, selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman (batas minimum usia menjadi semakin lebih tinggi dan tinggi).[4]
Kesimpulan dari refleksi singkat ini adalah bahwa ketentuan batas minimum usia pernikahan yang tercantum pada undang-undang perkawinan, berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang didorong oleh meningkatnya kualitas pendidikan yang diterima oleh wanita. Artinya, trend menikah di usia dini, menjadi menurun sehubungan dengan hal tersebut. Singkatnya, perubahan ketentuan minimum usia pernikahan berjalan linear dengan peningkatan kualitas pendidikan wanita.
Referensi
[1] “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1.”
[2] T.O. Ihromi, Antropologi Dan Hukum (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hlm. 9.
[4] Roger Cotterrell, Sosiologi Hukum (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), hlm.67.
[5] Lihat ihromi, Antropologi Dan Hukum, hlm. 14.