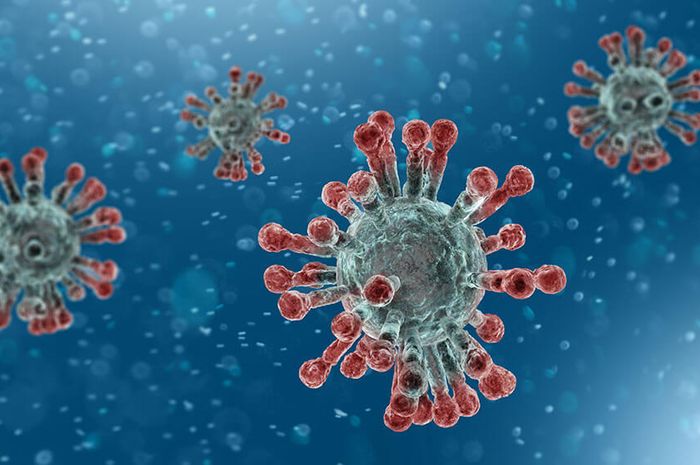Wabah, Jalan Terang Menuju Ateisme
Fenomena Covid-19 menghentak iman banyak kaum beragama! Apakah kepercayaan kepada Allah masih bisa dipertanggungjawabkan di hadapan fakta penderitaan dan ketidakdilan ini? Fakta menunjukkan bahwa manusia makin tunggang langgang di tengah gempuran wabah Covid-19.
Manusia telah bahu membahu mengatasi penderitaan ini namun usaha ini tampak absurd dan manusia merasa sunyi dan kesepian dalam perjuangannya. Telah sekain banyak suara teriakkan minta tolong membumbung naik ke hadapan Allah, namun Allah tampak diam saja. Doa-doa dipanjatkan, sujud takjub dan takzim mengalir deras kepada sosok yang bernama Tuhan itu namun Dia seperti tak memedulikannya.
Di hadapan kematian ribuan manusia yang tak berdosa ini, Tuhan yang disembah itu masih bermoralkah? Seorang manusia bahkan bisa berperilaku lebih baik daripada Allah karena memiliki hati dan niat untuk membantu, bersolider. Allah yang sungguh-sungguh mahakuasa dan mahabaik itu hendaknya tidak berdiam diri dan nampak lemah dan lelah semacam itu. Atau Tuhan sedang berpura-pura?
Dalam arti ini penolakkan Allah untuk ikut beritervensi dalam kehidupan manusia merupakan suatu perilaku yang tidak bermoral. Bagaimana mungkin Dia hanya diam sambil menyaksikan kematian dan penderitaan manusia setiap saat? Kendati manusia itu makhluk terbatas namun ia lebih bermoral daripada-Nya karena manusia berontak terhadap situasi penderitaan dan kematian. Sikap Allah yang membiarkan penderitaan ini terjadi sama dengan ketiadaan Allah. Tuhan sama sekali tidak adil dan lebih baik mengatakan Dia tidak ada daripada ada!
Kendatipun, mungkin, bagi seorang yang beragama, bisa lugas mengatakan bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Tapi bagi seorang ateis, klaim itu adalah lelucon absurd! Mana buktinya? Bukankah setiap hari manusia menderita? Maka, “berhentilah berdoa kepada Tuhan yang tidak bermoral itu dan percayalah kepada sains atau kebebasan manusia. Keduanya akan menuntunmu ke titik terang.”
Memastikan Pemikiran yang Memadai
Pertanyaan, apakah Allah itu ada, bukan sekadar melukiskan kekecewaan manusia terhadap Allah melainkan menukik lebih radikal pada upaya ingin membunuh Allah. Namun pertanyaan ini bisa langsung kena sergap: membunuh Allah itu, mungkinkah? Dengan cara apa, manusia bisa membunuh Allah? Bukankah ia akan jatuh kembali pada suatu proyeksi absurd? Berikut akan dijernihkan sejumlah hal.
Pertama, penderitaan–Covid-19–menerangkan adanya kebaikan sempurna. Realitas adanya penderitaan–Covid-19–pada hakikatnya bukanlah kejahatan melainkan hanya “keadaan kurangnya kebaikan” (privatio boni). Artinya ada suatu realitas kebaikan sempurna. Penderitaan ini menjadi semacam pentunjuk ke arah adanya suatu kebaikan sempurna itu. Dengan demikian realitas penderitaan harus ditempatkan dalam keseluruhan “ada”. Penderitaan ini memang diperlukan demi kebaikan yang lebih terang dan lebih besar itu.
Kedua, realitas negatif diperlukan demi kematangan peradaban dan manusia. Sejarah menunjukan bahwa peradaban terbentuk dan mengalami kematangan karena manusia berhasil mengatasi aneka realitas buruk. Peradaban dan kebudayaan umat manusia adalah produk upaya manusia mengatasi realitas-realitas negatif yang menerpa dan menyusahkannya.
Ketiga, realitas negatif sebagai sarana Tuhan menjalankan karya-Nya. Misalnya Firaun bertobat setelah anak sulungnya meninggal kena tulah dari Tuhan (Kel 12. 29). Artinya, apa pun yang dialami, penderitaan ataupun kejahatan, harus diterima karena sesuai dengan keadilan Tuhan. Orang mengakui kemahakuasaan dan keadilan Allah dengan menyaksikan adanya penderitaan dan kejahatan di dunia ini. Argumentasi ini sering dipakai oleh orang beriman untuk membenarkan wabah hari ini.
Keempat, penderitaan dan kejahatan lahir dari kebebasan manusia. Penderitaan ini bukan berasal dari Allah karena bertentangan dengan hakikat Allah yang mahabaik dan mahaadil. Tidak mungkin dari-Nya lahir yang buruk (Allah itu summum bonum). Penderitaan di dunia ini disebabkan oleh manusia yang salah menggunakan kebebasannya. Sikap dan tindakan pongah manusia sendirilah menghasilkan penderitaan dan keburukkan.
Lalu bagaimana dengan kematian bayi yang tak berdosa? Agustinus, seorang filosof cum teolog Kristen abad pertengahan, memecahkan masalah ini dengan teorinya tentang dosa asal. Baginya dosa asal kena pada setiap orang tanpa terkecuali. Maka, penderitaan anak-anak kecil (yang belum memiliki dosa pribadi) dimengerti sebagai hukuman atas dosa asal yang juga melekat pada anak-anak. Hanya dengan itu, keadilan Allah bisa dibelah.
Namun keempat argumen tersebut dinilai tidak mencukupi dan kurang radikal. Diperlukan jawaban yang lebih integral berhadapan dengan masalah penderitaan. Sebab persoalan penderitaan tetap tersembunyi baik bagi orang beragama ataupun kaum ateis. Penderitaan sebagai realitas negatif tidak terselami dan melibati upaya penjernihan yang tidak mudah.
Oleh karena itu, pertama, berhadapan dengan persitiwa penderitaan, manusia diharapkan mampu menerima penderitaan itu sebagai fakta yang ada dan akan selalu ada terlepas dari apakah anda ateis ataupun beragama. Sebab sungguhpun kaum ateis menolak eksistensi ada-Nya tidak menjadi jaminan bahwa ia akan bebas dari fakta penderitaan ini. Penderitaan tidak punya urusan dengan siapa anda dan status anda. Penderitaan ada sebagai fakta ontologi dari eksistensi manusia sebagai pengada riil. Ia melekat pada struktur ontologi manusia.
Oleh karena penderitaan itu fakta yang tak bisa ditolak. Kedua, di hadapan fakta penderitaan, manusia perlu mangaktifkan sikap yang lebih terbuka dan menerimanya secara realitis. Hanya dengan bersikap realistis, penderitaan bisa ditanggung dan diterima saat penderitaan itu menimpa kita. Dengan menanggung dan menerima penderitaan secara realistis, kita bisa memerangi dan mengatasinya dengan sekuat tenaga dan segala daya kemampuan kita.
Akhirnya, ketiga, pokok yang cukup penting adalah mengolah dan mengintegrasikan penderitaan itu dengan kehidupan manusia secara total. Penderitaan diterima dan diakui sebagai bagian faktual dari cara mengada manusia. Hanya dengan itu, ada kemungkinan bagi manusia untuk bisa mentransendensi diri melampaui sekadar realitas negatif: melepaskan diri dari situasi deterministik dan menyentuh pokok lain, yang bagi orang beriman sebut pengharapan.