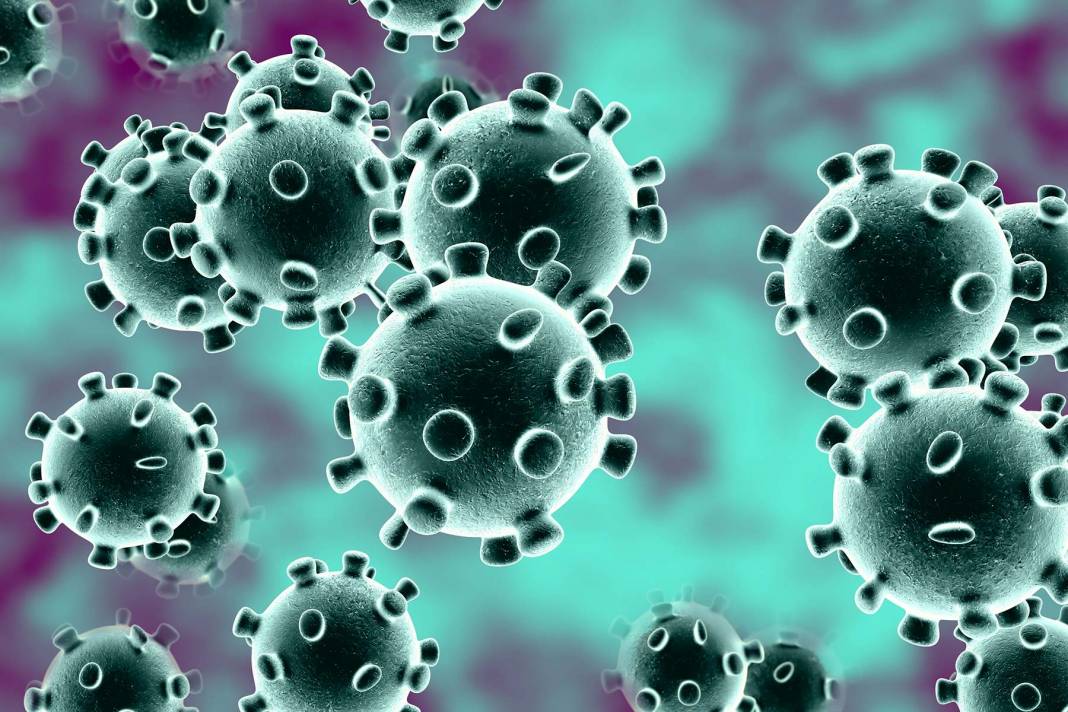Corona atau Covid-19 tak hanya memberikan dampak pada kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan teknologi, melainkan juga pemikiran keislaman. Banyak hadis yang bertebaran di media sosial, mulai dari yang sahih hingga yang dhaif. Semua itu merepresentasikan dua arus teologi besar, yakni antara yang pro tawakal dan pro ikhtiar.
Berkaitan dengan kondisi saat ini, ada tema hadis berpotensi menimbulkan polemik, yakni hadis-hadis tentang ‘adwa. Dijelaskan dalam Al-Muntaqa bahwa ‘adwa adalah la yu’dii syaiun syaian ay laa yatahawwalu syaiun minal maradi ila ghairi aladzi huwa bihi (tidak dapat sesuatu menginfeksi sesuatu sesuatu yang lain, atau tidak dapat sesuatu menyebabkan sakit pada yang lain dengan sendirinya). Jadi ‘adwa adalah keyakinan bahwa penyakit itu dapat menular dengan sendirinya.
Di banyak periwayatan, Nabi Muhammad saw dengan tegas mengatakan tidak ada ‘adwa, tidak ada thiyarah, dan seterusnya. Permasalahannya adalah hadis ini seolah-olah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Apalagi jika dihadapkan pada kondisi pandemi Corona seperti saat ini. Padahal Nabi saw juga berbicara tentang tha’un, sebuah penyakit ganas yang menular. Permasalahan lainnya adalah dari hadis yang membahas masalah ini semua sanadnya shahih.
Tentu saja hal ini akan mengundang polemik, apalagi jika dibaca dengan kaca mata neo jabariyah (fatalistik total). Tulisan ini berkepentingan memberikan sebuah pemahaman yang tepat (objektif) terhadap hadis ‘adwa. Jangan sampai gara-gara salah memahami hadis ini, malah menyebabkan bencana yang lebih besar.
Polemik Hadis ‘Adwa
Ada puluhan hadis yang membahas ‘adwa dengan redaksi yang berbeda-beda. Sebagai contoh hadis dalam Kitab Shahih Bukhari No. 5331: Dari Anas bin Malik ra, dari Nabi saw bersabda: “Tidak ada ‘adwa dan tidak pula thiyarah dan yang membuatku heran adalah al fa’lu.” Mereka bertanya: “Apakah al fa’lu itu?” beliau menjawab: “Kalimat yang baik.”
Hadis ‘adwa dengan redaksi seperti di atas juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Imam Ahmad. Jika dijumlah seluruhnya 24 hadis dengan sanad yang sahih. Namun, hadis-hadis ini jika berdiri sendiri akan bertentangan dengan banyak hadis lainnya yang berbicara tentang penyakit menular. Di sinilah letak polemik hadis ini.
Misal hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari No. 5289: Rasulullah saw bersabda: “Jika kalian mendengar wabah tersebut (tha’un) menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya.” Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada penyakit menular, yakni tha’un.
Begitu juga hadis yang yang terdapat dalam Musnad Ahmad No. 5147: Dari Ibnu ‘Umar dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian mendatangi tempat kaum yang diazab (terkena tha’un) itu kecuali dengan menangis dan jika kalian tidak menangis janganlah masuk kepada mereka, jangan-jangan kalian akan ditimpa musibah sebagaimana apa yang menimpa mereka.” Hadis ini juga menunjukkan bahwa tha’un adalah penyakit menular.
Dua hadis sebagai pembanding di atas semuanya sahih. Namun redaksinya jelas sekali menunjukan pertentangan (ta’aradul) satu dengan yang lainnya. Hadis ‘adwa menjelaskan tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, sementara dua hadis pembanding menunjukkan ada penyakit menular yang diakui oleh Nabi saw, yakni tha’un.
Solusi Pertentangan Hadis
Dalam menyelesaikan pertentangan hadis para ulama fikih menawarkan tiga metode, yakni nasakh, tarjih, dan jam’u. Pertama, metode nasakh (abrogration) digunakan apabila terjadi pertentangan dalil yang sama-sama kuat, kemudian yang dimenangkan adalah dalil yang datang belakangan.
Jika menggunakan metode itu maka yang dimenangkan adalah dalil tentang tha’un. Dengan asumsi hadis ini lahir di Madinah. Sementara hadis ‘adwa tentu lahir di Makkah, sebab berkaitan dengan masalah keyakinan-keyakinan jahiliah seperti thiyarah, hammah, ghul, dan fa’lu.
Namun, penulis tidak setuju dengan metode ini. Sebab ada perbedaan konteks antara hadis ‘adwa dengan tha’un. Hadis ‘adwa tidak murni membahas kesehatan karena melibatkan keyakinan jahiliah, sementara hadis tha’un murni membahas penyakit.
Jika hadis ‘adwa di-nasakh maka permasalahan jahiliah tidak akan terselesaikan. Lagi pula teori nasakh ini juga memiliki kelemahan, yakni siapakah yang memiliki otoritas me-nasakh hadis Nabi saw padahal hadis tersebut shahih?
Kedua, metode tarjih. Metode ini bertujuan mencari dalil yang paling kuat di antara dalil-dalil yang shahih. Jika diteliti, masing-masing hadis yang bertentangan tersebut sama-sama memiliki kualitas shahih. Jumlah sanadnya juga sama-sama banyak (mutawatir). Jika dilihat dari cara penyampaiannya (sighat tahammul) juga sama-sama meyakinkan. Metode ini menurut penulis juga tidak tepat jika digunakan untuk menyelesaikan polemik ini.
Ketiga, metode jam’u. Metode ini sering disebut dengan metode kompromi, yakni mendialogkan semua dalil yang bertentangan tersebut sehingga menghasilkan sebuah jalan keluar. Penulis lebih senang menyebutnya dengan metode rekonstruksionis, karena dalam dialog tersebut ada makna-makna dan pemahaman-pemahaman baru yang dimunculkan (dibangun) untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.
Dalam kasus pertentangan dalil di atas, antara hadis ‘adwa dan tha’un, yang semua shahih, maka metode yang tepat untuk menyelesaikannya adalah dengan metode jam’u. Asumsi yang perlu dibangun di awal adalah tidak mungkin Nabi saw mengeluarkan sebuah dalil yang bertentangan satu dengan lainnya. Jika ada pertentangan, pasti letaknya pada cara memahami dalil tersebut.
Prosedur Rekonstruksi Pemahaman
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan pertentangan dalil di atas, sebagai berikut: Pertama, mengumpulkan semua dalil terkait ‘adwa kemudian membanding-bandingkan satu dengan lainnya. Kedua, melakukan klasifikasi hadis terkait dengan redaksinya. Ketiga, mengambil kesimpulan makna dari dua proses sebelumnya.
Dari kajian penulis, hadis-hadis tentang ‘adwa ini memiliki tiga pola. Pertama, hadis ‘adwa tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan persoalan-persoalan keyakinan zaman jahiliah seperti thiyarah, thathayur, safar, hammah, ghul, dan fa’lu. Pengertian thiyarah adalah keyakinan nasib sial yang menyebab pesimisme akibat melihat kejadian-kejadian buruk.
Thathayur hampir serupa dengan thiyarah, yang menganggap peristiwa alam, suara burung, menunjukan dan memengaruhi nasib baik dan buruk seseorang. Safar adalah keyakinan bahwa bulan ini membawa sial.
Hammah adalah keyakinan adanya jin dan hantu yang mengganggu di padang pasir, serta keyakinan yang mati dapat hidup kembali. Ghul adalah keyakinan adanya ramalan bintang. Sementara fa’lu adalah yang disukai Nabi saw, yakni kalimat yang baik (motivasi positif).
Kedua, hadis ‘adwa ini berhubungan dengan ujian hidup manusia. Seperti hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari No. 5329. Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada ‘adwa, tidak ada thiyarah, dan sesungguhnya kesialan (ujian) itu terdapat pada tiga hal, yaitu: kendaraan, isteri dan tempat tinggal.”
Hadis seperti redaksi di atas sanadnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi. Hadis ini menunjukkan sebuah bantahan terhadap keyakinan jahiliah juga. Meskipun Nabi saw memberikan jawaban yang lebih realistis, bahwa ujian hidup (bagi laki-laki) terjadi pada tiga hal sebagaimana terdapat dalam hadis.
Ketiga, hadis ‘adwa ini berhubungan dengan unta yang tertular penyakit kulit (kudis). Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab Shahih Bukhari No. 5278, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada ‘adwa, dan tidak ada shafar dan tidak pula hammah. “Lalu seorang Arab Badui berkata: “Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan unta yang ada di pasir, seakan-akan (bersih) bagaikan gerombolan kijang kemudian datang padanya unta berkudis dan bercampur-baur dengannya sehingga ia menularinya?” Maka Nabi saw bersabda: “Siapakah yang menulari yang pertama.”
Begitu juga Shahih Bukhari No. 5328 dengan sedikit tambahan pada kalimat yang digaris miring: Dari Abu Hurairah ra berkata: Nabi saw bersabda: “Tidak ada ‘adwa, tidak ada shafar dan tidak pula hammah”. Lalu seorang Arab Badui berkata: “Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan unta yang ada di padang pasir, seakan-akan (bersih) bagaikan gerombolan kijang lalu datang padanya unta berkudis dan bercampur baur dengannya sehingga ia menularinya?”
Maka Nabi saw bersabda: “Lalu siapakah yang menulari yang pertama?” Setelah itu Abu Salamah mendengar Abu Hurairah mengatakan: Nabi saw bersabda: “Janganlah (unta) yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.”
Dua hadis ini jelas sekali menunjukan sikap Nabi saw terhadap ‘adwa. Kata kuncinya terdapat dalam kalimat terakhir, “Siapakah yang menulari yang pertama.” Kalimat ini menunjukkan bantahan, bahwa musibah itu tidak terjadi dengan sendirinya. Melainkan ada peran Tuhan di sana. Jika dilihat riwayat serupa dalam Sunan Ibnu Maja No 83, jawaban Nabi saw terhadap Arab Badui agak berbeda: “Semua itu adalah takdir, (jika bukan) lalu siapakah yang menulari unta yang pertama!”
Artinya, hadis ini benar-benar membantah keyakinan-keyakinan jahiliah yang meniadakan peran Tuhan di balik musibah yang terjadi. Orang-orang jahiliah (pra Islam) biasanya mengait-kaitkan musibah dengan benda-benda, peristiwa-peristiwa alam, dan berhala-berhala. Keyakinan tersebut dibantah dengan logika sederhana yang diajukan Nabi saw, siapakah yang menyebabkan penyakit pertama.
Hal menarik dari dua hadis di atas adalah, ada tambahan riwayat dari Abu Hurairah pada hadis yang kedua (Shahih Bukhari No. 5328) yang mengatakan Nabi saw bersabda: “Janganlah (unta) yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” Tambahan ini diperkuat dengan hadis dalam Shahih Muslim No. 4117, 4128, dan Sunan Abu Daud No. 3412.
Sekilas riwayat tambahan Abu Hurairah ini bertentangan, tetapi sesungguhnya menunjukkan keselarasan. Tambahan dari Abu Hurairah ini sebenarnya menunjukkan tugas manusia. Meskipun semua musibah tersebut terjadi atas kuasa Tuhan, namun manusia tidak boleh berpangku tangan, berdiam diri ketika musibah terjadi. Itulah sebabnya Nabi saw. bersabda: “Janganlah (unta) yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” Intinya manusia ditugaskan untuk berikhtiar, sementara hasilnya adalah Tuhan yang menentukan.
Beberapa Kesimpulan
Dari telaah dan kajian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan; Pertama, hadis ‘adwa harus dipahami sebagai bentuk respons tauhid, bahwa di balik musibah yang terjadi ada kuasa Tuhan di sana.
Hal itu sebagai bentuk bantahan keyakinan jahiliah seperti ‘adwa, thiyarah, hammah, dan safar, yang meletakkan kekuatan-kekuatan, benda-benda, dan keyakinan-keyakinan, selain Tuhan dapat memberikan madharat kepada manusia. Hal ini sesuai dengan Surah Ath-Thagabun/64: 11, yang menjelaskan bahwa musibah yang menimpa diri seseorang tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah.
Kedua, bahwa hadis ‘adwa jika dipahami secara partikular (sebagian-sebagian saja) akan menyebabkan banyak pertentangan. Namun jika dipahami secara komprehensif tidak akan menghasilkan pertentangan dengan dalil-dalil lainnya. Pemahaman yang komprehensif akan menghasilkan keteguhan iman dan upaya (ikhtiar) untuk menghindarkan diri dari musibah. Walalhu’alam bishawab.