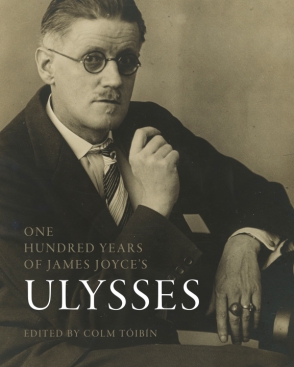Terlepas dari apakah seorang pembaca terpikat atau justru merasa asing dengan Ulysses (1920), satu hal yang tak terbantahkan adalah daya tarik intelektual dalam mengamati bagaimana James Joyce, melalui karyanya ini, secara radikal mengeksplorasi batas-batas naratif yang inheren dalam seni penulisan novel. Ulysses bukan sekadar bercerita; ia adalah sebuah demonstrasi puitis tentang potensi dan fleksibilitas medium novelistik. Pada permukaannya, alur kisah ini tampak sederhana: kita mengikuti jejak dua karakter utama—Stephen Dedalus, seorang intelektual muda berusia dua puluh dua tahun yang jelas merupakan alter ego Joyce sendiri, dan Leopold Bloom, seorang pria paruh baya berusia tiga puluh delapan tahun—saat mereka menjalani hari biasa pada tanggal 16 Juni 1904 di Dublin. Kedua kehidupan ini berjalan secara paralel, dengan interaksi awal yang samar sebelum akhirnya takdir mempertemukan mereka menjelang kepulangan Bloom ke rumah, di mana istrinya tertidur lelap.
Namun, kesederhanaan permukaan ini segera menguap ketika kita menyadari bahwa Joyce dengan sengaja menenun jalinan naratifnya berdasarkan struktur The Odyssey karya Homer. Bloom menjelma menjadi Ulysses modern, sang pengembara, sementara Stephen mengambil peran Telemachus, putra yang mencari ayahnya. Lebih jauh lagi, kompleksitas emosional dan dramatis ditingkatkan oleh kenyataan bahwa Molly Bloom, istri Leopold, dijadwalkan untuk menerima kunjungan dari kekasihnya, Blazes Boylan, selama ketidakhadiran suaminya. Sementara itu, Stephen bergulat dengan kewajiban finansial untuk membayar gajinya, sebuah tugas yang memicu berbagai godaan untuk menghambur-hamburkan uangnya, menyia-nyiakan waktunya yang berharga, dan yang paling penting, mengkhianati potensi kreatifnya yang besar.
Salah satu ciri paling mencolok dari Ulysses adalah kerumitannya yang berlapis-lapis, sebuah labirin linguistik dan struktural yang bagi sebagian besar pembaca (termasuk penulis catatan ini) terasa begitu padat hingga nyaris menghalangi eksplorasi lebih lanjut. Bahkan bab-bab pembuka yang tampak relatif lurus ke depan, seperti bab pertama dan kedua, menuntut perhatian penuh dan seringkali terasa sulit dipahami pada pembacaan awal. Beberapa bagian dari novel ini bahkan memerlukan pembacaan ulang berkali-kali serta dedikasi yang tak tergoyahkan, seringkali dibantu oleh panduan eksternal seperti kunci interpretasi atau rekaman audio—sebuah pendekatan yang penulis sendiri pilih untuk menavigasi kompleksitasnya. Upaya untuk sekadar “mengalir” melalui Ulysses tanpa memberikan perhatian cermat pada setiap kata tampaknya mustahil; bagi penulis, pendekatan semacam itu dengan cepat berujung pada kebosanan intelektual dan emosional.
Para pembaca yang jatuh hati pada Ulysses dengan penuh semangat menyatakan bahwa setiap kata dalam novel ini adalah sebuah permata tersembunyi, yang akan bersinar terang jika pembaca bersedia memberikan perhatian dan penghargaan yang layak. Mereka melihat Ulysses bukan sekadar rangkaian kalimat, melainkan sebuah ekosistem linguistik yang unik dan kaya, sebuah mikrokosmos yang mencerminkan kompleksitas “kehidupan itu sendiri,” sebuah frasa yang sering mereka gunakan untuk menggambarkan kedalaman karyanya. Mereka berpendapat bahwa esensi dari setiap novel terletak pada jalinan kata-kata yang saling berhubungan, namun Ulysses mengambil prinsip ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia memaksa pembaca untuk terlibat dalam tarian yang intim dengan setiap suku kata, menuntut pembacaan ulang yang sabar hingga jaring-jaring makna yang tersembunyi mulai terungkap dan terpatri dalam ingatan. Dalam pengertian ini, Ulysses berfungsi laksana penjaga gerbang yang ketat, hanya mengizinkan mereka yang memiliki ketekunan dan kapasitas intelektual untuk benar-benar menyelami dan menikmati kekayaan yang ditawarkannya.
Lebih dari sekadar menuntut perhatian, Ulysses juga menantang pembaca untuk merangkul kompleksitas linguistik yang tidak konvensional dan untuk bersedia melampaui batasan-batasan naratif tradisional. Gaya Joyce yang inovatif dan seringkali membingungkan dapat menjadi batu sandungan bagi sebagian pembaca, mengurangi dampak emosional yang mungkin dirasakan. Namun, bagi yang lain, justru kerumitan inilah yang memperdalam resonansi emosional cerita, menambahkan lapisan-lapisan makna yang tak terduga dan memperkaya pengalaman membaca secara keseluruhan. Gaya bahasa Joyce yang ekstrem, dengan segala keunikan dan tantangannya, dapat membuat novel ini terasa abstrak dan dingin bagi sebagian orang, namun bagi yang lain, ia adalah sumber kekayaan artistik yang tak tertandingi.
Dalam lanskap naratif yang rumit ini, kita diperkenalkan kepada Leopold Bloom, protagonis utama Joyce yang jauh dari sosok pahlawan konvensional. Ia bukanlah tokoh yang melakukan tindakan-tindakan heroik atau luar biasa. Justru, salah satu aspek paling menarik dari karakternya, selain latar belakangnya sebagai seorang Yahudi di Dublin yang didominasi Katolik, adalah sifatnya sebagai seorang pengamat yang penuh keingintahuan, seringkali dengan implikasi voyeuristik. Joyce tidak ragu untuk memperlihatkan kelemahan-kelemahan kecil Bloom, kesalahan-kesalahan yang membuatnya tampak manusiawi, namun ia juga memberikan berbagai alasan yang membenarkan atau setidaknya menjelaskan tindakannya. Di satu sisi, Bloom digambarkan sebagai seorang pria biasa dengan bakat-bakat tertentu—ia memiliki kecerdasan literer yang diakui di perusahaan periklanan tempatnya bekerja dan memiliki suara yang merdu sebagai seorang penyanyi.
Namun, di balik kesederhanaan luarnya, Leopold Bloom menyimpan kedalaman karakter yang tak terduga. Ia bukanlah prototipe pria Dublin pada masanya. Jauh dari tipikal, Bloom memancarkan kebaikan hati yang tulus, kerentanan emosional yang jarang ditunjukkan, pengetahuan yang melampaui batas keseharian, dan kapasitas untuk penderitaan yang mendalam. Ia mudah merasa bosan dengan rutinitas, memiliki rasa ingin tahu yang tak terpadamkan tentang dunia di sekitarnya, dan diliputi keraguan diri yang terus-menerus—semua kualitas yang menjadikannya berbeda dari mayoritas penduduk Dublin yang mengelilinginya. Terlepas dari kemungkinan adanya sisi gelap dalam kehidupan seksualnya, Bloom secara fundamental digambarkan sebagai sosok yang lebih berempati dan berbelas kasih dibandingkan dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, sehingga secara halus mengangkat pertimbangan moral terkait perilaku seksual dalam narasi.
Di sisi lain, kita diperkenalkan kepada Stephen Dedalus yang muda, seorang intelektual yang dipenuhi dengan keangkuhan, kepekaan yang berlebihan, dan arogansi yang kentara. Ia terperangkap dalam peran seorang pemboros yang menghambur-hamburkan potensi dirinya. Menjelang akhir narasi, Bloom merasakan dorongan kuat untuk menyelamatkan Stephen dari kehancuran diri, namun Stephen tampak terlalu terobsesi dengan citra dirinya dan terlalu enggan untuk menerima uluran tangan Bloom. Ia mudah tersinggung jika merasa diremehkan atau dihina, dan pandangan Stephen tentang dirinya sendiri dipenuhi dengan keagungan yang hampir tragis. Ia dihantui oleh keyakinan bahwa kegagalannya untuk berlutut di sisi ranjang kematian ibunya adalah penyebab kepergiannya (meskipun ibunya meninggal karena kanker). Ironisnya, Stephen menyadari adanya kekurangan kemurahan hati yang serupa dalam diri Bloom, namun dalam benaknya, ia justru menempatkan Bloom dalam posisi yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih besar. Ia melihat Bloom sebagai sosok ayah pengganti, sementara dirinya sendiri adalah anak yang membutuhkan bimbingan—sebuah dinamika emosional yang mungkin terasa meyakinkan bagi sebagian pembaca, namun tidak bagi yang lain. Di tengah ketegangan ini, tersirat semacam kerinduan sentimental yang disamarkan sebagai isyarat emosional yang lebih dalam, bahkan muncul saran (yang ditolak Stephen) agar ia menikahi putri Bloom yang masih muda, Milly.
Kemudian, kita bertemu dengan Molly Bloom, yang terkenal karena deskripsi suaminya tentang payudaranya yang indah dan besar, serta jawabannya yang afirmatif (“ya”) di akhir novel. Kita pertama kali melihatnya dari kejauhan di awal cerita, saat Bloom menyiapkan sarapan untuknya. Namun, kehadiran Molly mencapai puncaknya di akhir novel melalui monolog interiornya yang panjang dan terkenal. Sepanjang hari yang dilalui Bloom, pikirannya sering kali tertuju pada Molly. Ia membelikannya beberapa barang, mengenang pertemuan pertama mereka yang penuh gairah, dan merenungkan kehangatan, kelembutan, dan keintiman yang pernah mereka bagi.
Namun, di balik kenangan akan keintiman fisik, terungkap sebuah jurang komunikasi yang menganga antara Bloom dan Molly. Tidak ada indikasi bahwa mereka benar-benar terhubung secara fisik saat ini, atau bahwa mereka berbagi pemikiran terdalam mereka, terlibat dalam percakapan yang substansial tentang hal-hal yang penting bagi mereka. Bloom mengenang momen ketika hasrat fisik membuncah dalam dirinya, namun ironisnya, pemicunya adalah pemandangan seorang pria asing yang lewat di luar jendela—sebuah detail yang mengisyaratkan keterasingan emosional dalam hubungannya. Molly, bagi Bloom, tampaknya lebih merupakan proyeksi dari fantasinya sendiri, representasi dari berbagai perasaannya, namun pada dasarnya ia tetaplah sosok yang asing baginya. Keduanya berbagi objek sentimentalitas yang sama, seperti yang Bloom rasakan terhadap Stephen, namun di inti narasi, terasa kesepian yang mendalam bagi Bloom, kesedihan yang merayap, dan yang lebih mengkhawatirkan, sebuah indikasi bahwa Joyce sendiri mungkin tidak sepenuhnya memahami kompleksitas emosi kedua karakter ini.
Lapisan-lapisan gaya bahasa Joyce yang flamboyan dan terkadang membingungkan dapat ditafsirkan oleh sebagian pembaca sebagai pengalihan perhatian dari inti emosional cerita, sebuah hiasan permukaan yang menutupi ketiadaan eksplorasi yang mendalam terhadap dilema dan krisis hubungan yang sebenarnya antara Bloom dan Molly (atau bahkan antara Bloom dan Stephen). Ketika Molly akhirnya mengungkapkan pikiran-pikiran batinnya melalui monolog interior yang terkenal, pandangan dunianya sering kali bertentangan secara diametral dengan pandangan Bloom dalam hal-hal yang paling mendasar. Lebih lanjut, terungkap bahwa kejujuran bukanlah fondasi hubungan mereka; keduanya saling berbohong dan diliputi oleh kecurigaan satu sama lain. Ironisnya, tidak satu pun dari masalah mendasar dalam hubungan mereka yang diselesaikan pada akhir novel. Joyce tampaknya menyadari bahwa menyelesaikan konflik yang mengakar begitu dalam dalam rentang waktu satu hari akan terasa tidak realistis. Oleh karena itu, novel berakhir dengan jurang pemisah yang lebar dan tampak tak terjembatani—sebuah jurang yang diciptakan dan disadari oleh penulis—antara dunia batin pria dan wanita.
Meskipun monolog Molly dimaksudkan untuk menjadi representasi aliran kesadarannya, narator (atau penulis) tampaknya sangat dipengaruhi oleh konsepsi Joyce tentang dirinya. Molly menggunakan banyak sekali ekspresi verbal yang repetitif dan dangkal, seperti “tentu saja dia benar,” “siapa yang saya dapatkan surat terakhir dari,” dan “itu semua sangat baik bagi mereka tetapi untuk seorang wanita.” Jika ini memang dimaksudkan sebagai jendela menuju kehidupan batinnya, maka cara Molly berpikir tampak identik dengan cara dia berbicara secara eksternal. Dalam hal ini, ia mengingatkan pada Flora Finching, karakter dalam Little Dorrit karya Charles Dickens, yang juga memiliki kecenderungan untuk berbicara tanpa henti dan bertele-tele. Namun, dalam kasus Flora, kebisingan verbalnya secara patologis menutupi kekosongan batin, sementara kehidupan batin Molly justru dipamerkan secara vulgar, kontras dengan kehidupan batin wanita yang lebih bijaksana dan pendiam yang tampaknya tidak dipahami oleh penulis dengan lebih baik daripada pemahamannya tentang wanita yang lebih terbuka dan ekspresif seperti Molly.
Menarik untuk dicatat bahwa James Joyce menjalin persahabatan dan memberikan pujian kepada Italo Svevo, penulis novel Zeno’s Conscience. Perbandingan antara Ulysses dan Zeno’s Conscience menghadirkan sebuah kontras yang signifikan. Kedua protagonis, Zeno dan Stephen, sama-sama memiliki kecenderungan egoistis yang kuat, dan kedua novel mengeksplorasi tema-tema neurosis melalui karakter Zeno yang mirip dengan Bloom dalam kegelisahan eksistensialnya. Namun, salah satu aspek yang membedakan dan memberikan kepuasan tersendiri dalam novel Svevo adalah penggambaran istrinya. Ia dihadirkan bukan sekadar sebagai figur simbolis dalam pikiran Zeno, melainkan sebagai sosok dengan kecerdasan yang setara dan mampu berinteraksi secara intelektual dengan suaminya, sebuah representasi hubungan yang lebih seimbang dibandingkan dengan dinamika antara Bloom dan Molly.
Lebih jauh lagi, Joyce menyadari sepenuhnya bahwa setiap novel tidak hanya merupakan karya fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai catatan sosial dan historis zamannya. Dalam Ulysses, ia mengeksploitasi potensi ini secara maksimal. Melalui perjalanan Bloom dan Stephen mengelilingi Dublin selama kurang lebih dua puluh jam, Joyce seolah-olah merekam kehidupan kota tersebut dengan detail yang cermat, menangkap baik pemandangan yang luas maupun interaksi yang intim. Tanggal 16 Juni 1904 digambarkan bukan sebagai hari yang luar biasa, melainkan sebagai representasi hari biasa dalam kehidupan orang Irlandia—dengan segala kedamaian dan kemakmuran relatifnya, serta nuansa kontemporer yang melekat padanya. Salah satu tujuan utama Joyce adalah untuk menangkap esensi kehidupan sehari-hari di Irlandia dengan keseriusan dan detail yang hanya mungkin dicapai melalui penggunaan beragam gaya dan bentuk naratif (termasuk satu bagian panjang yang ditulis dalam format drama). Oleh karena itu, Joyce berpendapat bahwa pembaca perlu menemukan daya tarik dalam penggambaran kehidupan Dublin ini agar upaya untuk menavigasi kompleksitas novel terasa sepadan.
Pada akhirnya, muncul pertanyaan krusial: apakah Ulysses dapat dianggap sebagai “novel yang paling utama”? Jawabannya, menurut penulis, adalah afirmatif dalam beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, Ulysses juga unik dalam aspek lain: penilaiannya sepenuhnya subjektif dan individual. Novel ini tidak dapat dinilai berdasarkan standar universal atau melalui konsensus kelompok. Respon terhadap Ulysses bersifat biner—ia akan sangat sesuai dengan selera seseorang atau sama sekali tidak. Tidak ada jumlah persuasi atau lobi dari pembaca dengan preferensi yang berbeda yang dapat mengubah pandangan mendasar seseorang terhadap karya ini. Ulysses berdiri sebagai monumen sastra yang memecah belah, menantang pembaca untuk menghadapi kompleksitasnya dan membentuk opini mereka sendiri tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal.