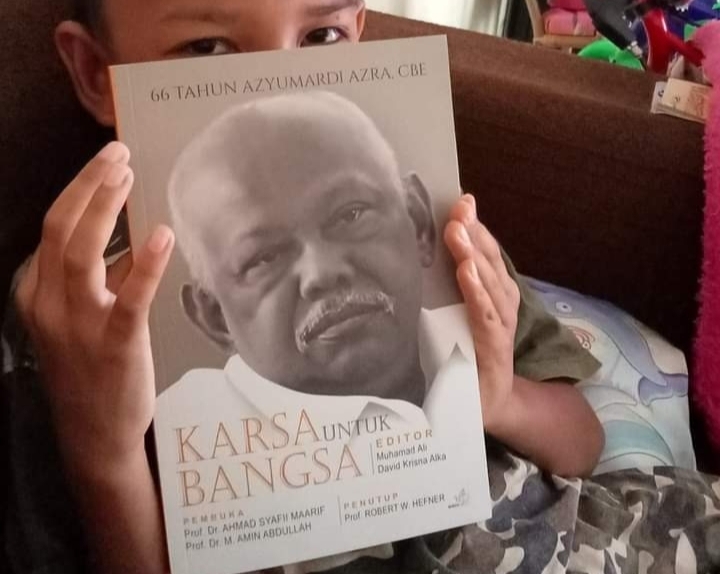Kaum intelektual baru (‘new intellectual’ atau lazim disebut cendekiawan) di masa kontemporer adalah ‘makhluk langka’ dalam masyarakat manapun secara global. Mereka hanya menjadi bagian kecil dari ‘inteligensia’, kaum terpelajar yang terutama berada di kampus. Intelektual yang berakar dari kampus (campus-based intellectuals) adalah orang terpelajar yang telah keluar dari kungkungan ilmunya yang sempit dan birokrasi kampus yang membelengg. Mereka bisa menjadi ‘public intellectuals’ yang dengan meminjam kerangka Antonio Gramsci (18911937) sebagai ‘organic intellectuals’, yaitu intelektual otonom dan independen yang berbeda dengan inteligensia dan ‘intelektual lama’ karena senantiasa bersuara bijak tapi tegas mewakili masyarakat yang tersisihkan kekuasaan politik represif.
Jika di masa silam, ada ‘intelektual lama’ (old intellectuals), yang kebanyakan muncul dan berkiprah bukan dari institusi pendidikan tinggi, tapi dari lingkungan sosial, budaya dan agama. Intelektual lama ini bisa pujangga dan pemikir dan tokoh agama, yang kemudian bisa disebut ‘begawan’. Di masa kontemporer dengan kompleksitas pemikiran dan wacana dalam berbagai kehidupan, dan juga karena semakin kompleknya kerumitan dinamika sosial, budaya, agama, politik dan seterusnya, kian sulit muncul intelektual lama, sehingga intelektual baru lebih hegemonik dalam berbagai wacana dan ranah kehidupan intelektual.
Kegamangan Intelektual
Meski jumlahnya selalu sedikit, intelektual (baru) sangat dibutuhkan masyarakat dan negara-bangsa manapun. Mereka adalah elan vital dan driving force untuk perubahan masyarakatnya ke arah kemajuan peradaban. Berkat ilmu pengetahuan, kepakaran, keahlian, pengalaman kehidupan dan kearifan imajinatif, mereka mampu melakukan refleksi tentang kondisi masyarakat dan menawarkan langkah dan terobosan untuk perbaikan dan kemajuan. Selalu ada intelektual—meski tidak banyak—yang memiliki keberanian dan sedia berbicara lantang baik di tingkat ide maupun praksis untuk terwujudnya perubahan ke arah lebih baik. Inilah yang membedakan intelektual dengan intelijensia, orang terpelajar, yang lebih sibuk dengan dan terkurung dalam ilmu, kepakaran dan minatnya yang sempit dan teknikal. Tetapi perubahan selalu menimbulkan kegamangan. Apalagi ketika perubahan yang ditawarkan intelektual misalnya menyangkut pemikiran dan praktek keagamaan yang telah mentradisi dalam waktu sangat panjang, dan karena itu dianggap sebagai tidak bisa dipersoalkan, apalagi diubah. Karena itu, intelektual yang menawarkan gagasan dan konsep yang mungkin terlalu abstrak bagi kalangan masyarakat sering mendapatkani; tidak jarang mereka dilihat dengan penuh prasangka dan bahkan dituduh sebagai ‘sesat’ dan ‘menyimpang’.
Kini kegamangan juga melanda banyak kalangan intelektual ketika mereka berhadapan dengan dinamika politik yang tidak sesuai dengan idealitas. Misalnya saja, kancah demokrasi Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir disebut banyak kalangan pengamat dan aktivis penguatan demokrasi sebagai mengalami kemunduran (decline), terperosok ke belakang (backsliding) atau menjadi cacat (flawed) dan ‘tidak liberal’ (illiberal). Oligarki politik dan oligarki bisnis bersekongkol dalam politik—membuat politik Indonesia semakin cenderung otoritarian.
Berhadapan dengan semua perkembangan ini, intelektual sering berada dalam dilema dan posisi sulit; pada satu pihak ia memiliki tanggungjawab moral publik untuk menyerukan dan mendorong perubahan sosial, budaya, agama, dan politik misalnya. Tetapi pada pihak lain ia mendapat tantangan yang tidak jarang sangat sengit dan bermusuhan dari penguasa, elit politik, pemuka sosial-budaya, kepemimpinan agama dan kalangan masyarakat. Bukan tidak jarang mereka menjadi target intimidasi dari aktor negara atau buzzer (pemengaruh) yang membela oligarki politik dan oligarki bisnis.
Tetapi justru di sinilah terletak tantangan integritas intelektual; tidak cepat menyerah pada berbagai tantangan. Intelektual, seperti ditegaskan penyair W.S Rendra(1935-2009), dalam menghadapi realitas sulit, mestilah tidak menjadi ‘begawan yang berumah di atas angin’ yang jauh mengawang atau menghindar dari kenyataan. Atau lebih parah lagi, seperti dikatakan Julen Benda(1867-1956) dalam karya besarnya La trahison des clercs (1927), melakukan pengkhianatan intelektual; yaitu mengkhianati kebenaran dan keadilan karena pertimbangan dan kepentingan politik dan ras—yang bisa diperpanjang, karena juga pertimbangan posisi sosial, kenyamanan finansial dan seterusnya.
Dalam keadaan itu, tidak heran kalau ada pakar yang pesimis dengan peran intelektual. Indonesianis terkemuka Benedict R.O.G. Anderson (19362015) dalam diskusi panel (juga penulis makalah ini sebagai narasumber panel) tentang ‘Public Intellectual in Asia’ (Manila, 2010) menyatakan pesimisme pada kemunculan dan peran intelektual. Ini tak lain karena kuatnya otoritarianisme politik. Meresponi pesimisme Ben Anderson, penulis berargumen masih ada ruang dan celah bagi intelektual publik untuk menunaikan kewajiban moralnya pada elit kekuasaan dan politik, kepemimpinan sosial-budaya dan agama serta masyarakat luas. Tinggal apakah intelektual yang bersangkutan punya kemauan dan keteguhan hati untuk mengaktualisasikan perannya.
Intelektual dan Politik
Argumen tentang intelektual dan politik terkait dengan kenyataan adanya kalangan intelektual yang setelah berjuang ‘dari luar’, kehilangan kesabaran. Mereka kemudian memutuskan berusaha memperbaiki keadaan ‘dari dalam’. Kelihatan mereka berkesimpulan, sekedar menjadi suara moral untuk perubahan ternyata tidak efektif sama sekali; perlu kekuasaan politik untuk mewujudkannya, dan itu harus melalui politik, kekuasaan—bermula dari parpol. Pada saat yang sama, kritisisme dan nurani intelektual mereka tidak mengizinkan mereka bergabung dengan parpol lama, yang mereka pandang sudah rusak dan tidak bisa dipercayai sama sekali. Karena itu, dalam pandangan mereka, satu-satunya jalan adalah mendirikan parpol mereka sendiri, yang mereka harapkan dapat mewujudkan cita-cita, dan tujuan-tujuan ideal mereka.
Tetapi, jelas dunia intelektualisme berbeda banyak dengan dunia politik, khususnya di Indonesia, yang masih belum menemukan bentuk dan proses yang mapan. Pada tingkat rakyat, idealisme kaum intelektual publik cenderung tidak bisa dipahami; terlalu abstrak dan teoritis; juga tidak memberikan insentif ekonomis yang mereka harapkan. Dukungan finansial yang dimiliki public intellectual turn politicians dapat dikatakan sangat tidak memadai untuk bisa menarik massa. Karena itu mereka gagal mendapat dukungan massa. Kegagalan ini pada gilirannya terbukti menjadi tahap perusakan diri sendiri (self-destruction)—menjadi self-fulfilling prophecy.
Akibatnya, tidak jarang intelektual publik yang terjun ke dunia politik, akhirnya hanya menemukan kekecewaan, dan bahkan hanya pada selfdestruction. Realitas dan proses politik yang mereka temui di lapangan menjadi sangat pahit ketika dihadapkan dengan idealisme dan cita moralpolitik mereka. Inilah ironi yang seyogyanya telah mereka ketahui sebelum terjun ke dunia politik. Inilah yang diingatkan Max Weber ketika intelektual publik mulai terlibat politik: “When intellectuals have entered into politics, they have done so…with inevitably disastrous results” (Jennings & KempWelch, Intellectuasl in Politics, 1997).
Ketika sampai pada politik kekuasaan, hanya ada dua pilihan bagi mereka; pertama, mengorbankan cita dan idealisme moral-politik mereka, dan berkompromi dengan realitas dan proses politik yang ada; dan, kedua, kembali ke dunia intelektualisme publik mereka sebelum integritas mereka betul-betul hancur.
Pilihan pertama sangat pahit. Pilihan kedua mungkin tak begitu pahit. Pilihan kedua juga lebih sesuai dengan kerangka etis dan moral kaum intelektual publik. Tetapi, tidak jarang ketika mereka kembali, damaged has been done, citra personal mereka sedikit banyak telah terganggu. Memulihkan citra ini bukanlah juga sesuatu yang mudah.
Inilah dilema intelektual publik. Intelektual publik berbeda dengan dengan intelektual murni atau intelektual privat—lebih pas disebut sebagai inteligensia—yang mungkin lebih sibuk dan puas dengan dunia intelektualisme mereka sendiri. Sebaliknya intelektual publik, keluar dari kungkungan minat intelektual yang sempit, memberikan perhatian dan kepedulian yang besar kepada masalah-masalah publik; menjadi pembawa suara moral dan etis bagi publik.
Sejak bermulanya liberalisasi politik Indonesia sejak awal masa pasca-Soeharto, kita menyaksikan adanya gelombang intelektual publik yang menerjunkan diri ke dalam politik kepartaian. Ada yang berhasil mencapai posisi puncak, seperti Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai presiden, namun berakhir tragis mengalami impeachment; atau Amien Rais yang menjadi Ketua MPR, yang pernah menguji dirinya dengan menjadi Capres dan terus mengembara di dalam belantara politik Indonesia yang tak memberi harapan padanya. Tetapi cukup banyak di antara mereka menemui akhir tragis, yang sulit diingkari merupakan semacam “self-destruction”.
Meminjam kerangka Richard A. Posner dalam Public Intellectuals: A Study in Decline (2003), jumlah intelektual publik independen, yang nonpartisan cenderung semakin berkurang. Bahkan hampir seluruh universitas secara global tidak bisa mengimbangi kemerosotan itu; generasi baru intelektual publik dari lingkungan universitas masih belum muncul juga secara signifikan. Universititas khususnya di Indonesia terbelenggu birokrasi dan pencapaian target ranking tingkat nasional dan internasional yang menyesatkan.
Konsolidasi Kolektif: Penutup
Karena itu, seperti dianjurkan Pierre Bourdieu dan Edward Said, perlu konsolidasi intelektual secara kolektif, yang diharapkan dapat menghasilkan produksi kolektif bagi penciptaan kerangka kondisi sosial budaya, politik, etis dan moral yang lebih kondusif bagi negara-bangsa.
Keadaan lingkungan politik dan sosial-budaya Indonesia juga terlihat tidak terlalu kondusif bagi ekspresi intelektual publik. Tetapi seperti ditegaskan di atas, masih ada ruang dan celah bagi intelektual publik untuk menunaikan tanggung jawab moral. Untuk itu perlu niat, tekad dan kesediaan berkorban untuk tujuan mulia.
Bahan Diskusi Perkumpulan Penulis Indonesia-Satupena
Jakarta, 24 Februari 2022