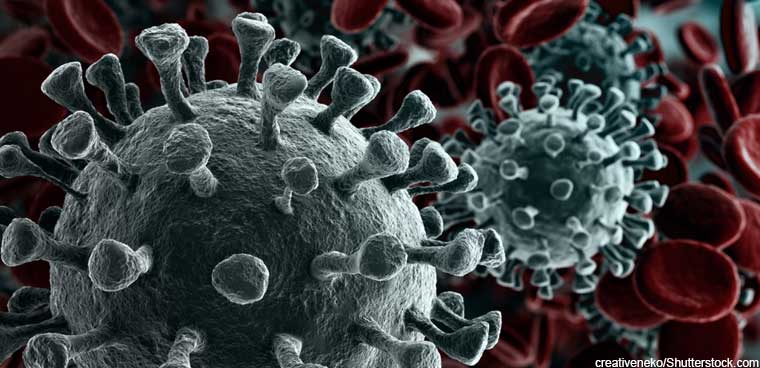“Vaksin masih belum tersedia 12-18 bulan ke depan,” tulis Akmal Nasery Basral, mengutip Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular AS, yang dimuat pada surat kabar Republika (Kamis, 23/4/2020). Ia menulis sebuah artikel berjudul Trias Covidiotica, yang disinggung moderator Pratiwi Retnaningdyah pada diskusi daring ke-5 World Book Day, Indonesia Online Festival, Jumat (24/4/2020). Pernyataan Bill Gates dan Anthony Fauci digunakan sebagai latar topik Akmal Nasery Basral dalam diskusi daring Sastra Bencana sebagai Katarsis di Era Pandemi.
Sekilas mengenai Trias Covidiotica, menurut Akmal Nasery Basral—yang telah menekuni dunia jurnalistik sekira 16 tahun—sebagaimana termuat pada surat kabar Republika bahwa ada tiga kelompok covidiot berdasarkan motif tindakan mereka, yaitu covidiot eksintensialis, covidiot borjuis-hedonis, dan covidiot spiritualis. Oleh karena itu, “Masyarakat Indonesia menghadapinya dengan cara berbeda-beda,” seperti yang disampaikan Pratiwi, pada sore ramadan hari pertama, dalam penyelenggaraan WBD 2020 yang diselenggarakan Perkumpulan Literasi Indonesia.
Pada diskusi daring sore itu, Uda Akmal—begitu sapa Pratiwi—mewakili Forum Akselerasi Masyarakat Madani sebagai ketua. Ia kemudian menautkan proses kreatif penulisan novel Genggam Cinta sebagai representasi katarsis dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menurut penulis Sang Pencerah itu, secara harfiah dalam sastra Jepang, Te Toriatte berarti Genggam Tangan. Namun, ia merasa perlu memberi sentuhan artistik pada judul, karena menurut penjelasannya, jika sekadar genggaman tangan, belum tentu ada cinta, terkadang sesama musuh pun bisa bergandengan tangan, tetapi tak ada cinta.
Berawal dari cerpen Swans of the Rising Sun, 2012, yang diikutsertakan dalam antologi Project Sunshine for Japan yang merupakan kampanye sedunia oleh Mansoureh Mana di Dortmun, Jerman. Kampanye tersebut dalam rangka mendukung para penyintas bencana nuklir Fukushima Daiichi Jepang.
Proyek kolaborasi tersebut memperingati 2 tahun triple disaster di Jepang pada tahun 2013. Ia tertarik ikut serta karena di antara para penulis itu terdapat penulis dari Jerman, yaitu Gunter Wilhelm Grass, penerima Nobel Sastra tahun 1999. Baginya, jika cerpennya itu ada dalam satu buku dengan penerima nobel sastra itu merupakan sebuah achievement. Bencana bagi penulis Sang Pencerah ini, berkaitan dengan natural disaster; gunung meletus, banjir bandang, tsunami. Semua hal tersebut berkaitan dengan perubahan ekosistem di lingkungan hidup manusia.
Sebuah Katarsis
Bagi Akmal Nasery Basral, menulis karya sastra, sumbernya bisa dari ragam peristiwa, kejadian yang ada di sekitar kita. Baik dari kehidupan pribadi, keluarga, orang-orang terdekat, lingkungan, bahkan sampai jauh dari kehidupan kita. “Dalam tingkat high fantasy, peristiwa yang tak pernah kita alami secara langsung, tetapi ia hidup dalam imajinasi,” jelas mantan wartawan majalah berita Gatra dan Tempo itu.
Ia menjelaskan bahwa sastra bencana, disaster literature, masuk ke dalam bentuk realisme; sesuatu yang nyata, sesuatu yang eksis, sesuatu yang sudah menjadi keseharian. Sejak karya sastra pertama dibuat oleh manusia pada zaman yang belum mengenal kertas dan buku, masih teriwayatkan pada pohon yang dicungkil, ditoreh pada dinding padas gua-gua, dan ragam cara lain. Kisah-kisah bencana telah menjadi bagian dari penceritaan yang dikabarkan oleh mereka yang melihatnya pada saat itu.
Fungsi pertama dari sastra bencana ini—menurut pria yang mengaku lebih dulu belajar di FISIP Sosiologi, sebelum mendalami kesusastraan—yakni, sebuah kesaksian, sebuah testimoni, bahwa sebuah peristiwa yang lingkupnya di luar kemampuan manusia, orang per orang untuk menanggungnya. Ketika peristiwa itu terjadi, ia telah mengubah struktur, baik lingkungan, sosial, budaya, alam, bahkan teknologi belakangan ini.
Bencana secara sederhana, lanjutnya, dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa yang tiba-tiba, mendadak, terkadang tidak diantisipasi oleh manusia. Namun, pengaruh dan dampak bencananya luar biasa. Bukan sekadar, misal, jika bangun pagi terlambat, pengaruhnya hanya terlambat berangkat ke kantor. Peristiwa tersebut bisa diperkirakan sebelumnya. Bencana memiliki dampak jauh lebih besar, tidak terbayangkan oleh manusia.
“Fungsi pertama dari peristiwa bencana ketika dikabarkan, bukan dalam bentuk news, berita, melainkan diolah dengan estetika sastra. Jika menggunakan rumus Horatius, salah satu paling tua, dulce et utile; ada unsur keindahan. Ia dikemas menjadi cerita yang enak dibaca, nikmat dipahami, meskipun berisi tentang bencana.
Namun kemudian, et utile, maknanya bisa menjadi pengingat kesadaran internal sebagai individu bahwa betapa kecilnya kita di tengah jagat raya ini, begitu pun sebagai kolektivitas manusia. Meskipun, manusia ini spesies cerdas di alam raya, tetapi ketika dihadapkan dengan bencana, biasanya gamang. Terkadang, kalah dengan bencana itu sendiri.
Bencana yang diabadikan dalam bentuk sastrawi—sajak, prosa, nonfiksi—harus memiliki fungsi lain, sebagai penyadaran dan pembelajaran bagi umat manusia,” jelas Akmal, “Kemudian diwariskan secara turun-temurun, misal, masyarakat di kawasan Simeuleu, Aceh. Mereka sudah tahu berdasarkan tradisi sastra lisan mereka. Bahwa jika sudah ada gempa bumi tertentu dengan kekuatan tertentu, akan ada bentuk-bentuk pengabaran sastra lisan yang membuat mereka harus menyelamatkan atau melarikan diri ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Itu salah satu bentuk sastra lisannya,” tuturnya dalam diskusi daring.
Ia memberi contoh tentang sastra tulisan yang hidup di dunia teks cetak dan digital yang sangat penting. Jika membaca buku Krakatoa: Saat Dunia Meledak 27 Agustus 1883 karya Simon Winchester, misalnya. Kita belum lahir pada tahun 1883, jika mencari dokumentasi videonya juga sulit.
Pada buku itu, Simon menuliskannya dengan narasi yang sangat indah meskipun membahas peristiwa bencana besar. Bahkan, dampak abunya sampai ke Eropa, memengaruhi pergerakan tentara Napoleon saat itu. Namun, ketika masuk ke dalam karya itu, kita bisa mendapatkan sebuah rekonstruksi kejadian seolah-olah berada di masa itu, tersedot ke tahun itu, berada dalam peristiwa yang gigantik.
Contoh lain yang ia sampaikan, yaitu karya sastra yang lebih lama lagi, salah satu karya sastra yang dianggap paling tua di dunia, Oddyses yang ditulis Homer. Oddyses sebagai tokoh protagonis mengalami bencana enam kali di lautan. Laut dalam sastra bencana sering kali diangkat oleh manusia. Peristiwa di lautan kemudian belakangan familiar dalam konteks tsunami, kecelakaan kapal laut, yang banyak diolah oleh berbagai penulis di belahan dunia.
Dalam budaya populer, Akmal mengisahkan peristiwa Titanic pada 1912, menjadi salah satu bencana yang menginspirasi banyak seniman. Di tangan James Cameron, peristiwa tersebut menjadi sebuah film yang meraih 14 nominasi dalam ajang Academy Awards tahun 1998.
Akmal Nasery Basral juga menuturkan bahwa sastrawan asal Sumatera Barat, HAMKA, dalam proses kreatif penulisan novel dari peristiwa tenggelamnya kapal Van der Wijck pada tahun 1936 sebagai latar penceritaannya. Bencana tenggelamnya kapal tersebut dijadikan katarsis oleh HAMKA untuk mempertanyakan adat-budaya Makassar dan Minangkabau yang meresahkan hatinya.
Mengenai kapabilitas bencana sebagai salah satu topik karya sastra, Eka Budianta (sastrawan) mengajukan sebuah pertanyaan menarik, “Apakah ini sebagai bentuk hiburan atau keberanian?” Dalam jawabannya, Akmal memaparkan tentang bagaimana ia mengajak para korban bencana gempa di Lombok (2018) untuk mencurahkan perasaan mereka menjadi sebuah puisi atau cerpen, atau tulisan apa pun.
Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi katarsis dalam mengurai kesedihan bagi mereka yang mengalami secara langsung bencana tersebut. Sedangkan, mereka yang terlibat, tetapi hanya berperan sebagai pengamat, ia bisa mendapat stimulus untuk melakukan hal serupa karena juga mengalami kegelisahan terhadap peristiwa yang diamati.
Sastra—atau katakanlah karya—bisa menjadi media untuk menuangkan kegelisahan. Secara tidak langsung, proses tersebut membutuhkan keberanian penulis untuk berdamai dengan emosi atau perasaan yang melingkupinya. Kelak, ketika ia membaca karyanya bertahun-tahun mendatang, ia mungkin akan merasa terhibur melihat seberapa banyak ia telah mengatasi kegelisahan yang dulu dirasakannya.
Bertahan Lewat Kata-Kata
Pratiwi Retnaningdyah menyatakan bahwa sastra bencana memiliki karakteristik yang mencerminkan kemampuan manusia untuk menghadapi kondisi ‘gelap’ akibat bencana yang dialaminya. Literature disaster tak hanya menyajikan bencana dalam wajah yang estetis, tetapi ia juga memiliki peran dalam merekam sejarah perubahan ketakutan menjadi kekuatan manusia untuk menghadapi marabahaya.
Tak bisa dimungkiri, kisah-kisah yang bersumber dari peristiwa bencana di dalamnya memuat detail peristiwa yang gelap dan pilu. Manusia harus mengakui bahwa ia tak bisa mengendalikan segala sesuatu. Di hadapan bencana, ia amat kecil dan tak berdaya. Ketidakberdayaan itu menumbuhkan ketakutan tentang eksitensinya di lingkungan yang ia tinggali. Sebagai makhluk survival, rasa takut bisa menjadi salah satu cara untuk mempertahankan diri. Ketakutan itu membangunkan kekuatan untuk mencari terang dari situasi yang sulit.
Bencana bagi manusia, barangkali serupa ari-ari pada bayi. Gelap-sulitnya bencana menyuntikkan kekuatan pada jiwa manusia untuk terus mempertahankan spesiesnya. Jika bencana itu kemudian terkubur, ia mungkin telah membantu manusia terlahir kembali dalam kisah dan wujud baru. Pun bila keduanya terkubur bersamaan, sastra bencana bisa digunakan untuk merekam proses pergulatan mahadahsyat sebagai bekal emosi kolektif kepada generasi selanjutnya.
Wabah pandemi Covid-19 dipertanyakan Eka Budianta sebagai kemungkinan lahirnya angkatan sastra Covidiot sebagaimana angkatan sebelumnya—angkatan 45 dan 60-an—yang juga terlahir karena peristiwa bencana. Akan tetapi, mungkin terlampau dini untuk menyimpulkan hal tersebut sebab karya-karya yang merekam wabah ini, karya-karya yang terlahir dari situasi pandemi ini mesti memiliki kekuatan untuk bertahan secara kuantitas maupun kualitas.
Sejauh peristiwa pandemi Covid-19 ini berlangsung, belum ada yang tahu kapan tepatnya peristiwa ini berakhir. Namun, semoga saja, kelak, bencana ini terekam menjadi sebuah literature disaster sebagai penanda bahwa manusia telah lahir kembali pada kali sekian bersama sebuah ari-ari bernama bencana.
Pratiwi sebelum menutup diskusi menyampaikan tentang kondisi menantang seperti sekarang dapat menjadi bahan karya sastra bencana bagi para penulis tentang kegelapan sebagai kabar lain untuk manusia yang menghuni bumi di masa mendatang. “Menjadi saksi, prasasti, dan legacy,” timpal Akmal, kemudian diskusi benar-benar berhenti dengan salam literasi.
Pamali dalam Sastra Lisan
Bencana bagi manusia, barangkali serupa ari-ari bayi. Meski akhirnya mesti dibuang setelah bayi dilahirkan, tetapi ia telah tuntas menopang sang bayi untuk tumbuh dan bertahan.
Bencana selalu ada di hampir sepanjang sejarah manusia. Nuh dan banjir bandang, Musa-Firaun yang mengalami wabah belalang, kutu, sampai sungai Nil yang berubah menjadi darah, Muhammad dan wabah demam Madinah, pernah menjadi cerita bencana yang dikisahkan oleh guru mengaji saya.
Sejarah juga telah mencatat, seperti dikutip bbc.com Indonesia, banyak wabah yang menyebabkan depopulasi manusia secara besar-besaran, misalnya wabah Black Death pada 1347 di Eropa yang telah menewaskan 200 juta orang. Wabah ini disebabkan oleh Yersinia Pestis, bakteri yang sama menjangkit orang-orang di Konstantinopel, 800 tahun sebelum Black Death terjadi.
Ketika saya beranjak dewasa, kisah-kisah mengenai bencana tidak lagi dituturkan serupa dongeng, ia hadir dalam peristiwa di layar kaca, di ponsel, di hidup sehari-hari yang sibuk. Bencana telah jadi makanan yang lazim disantap, sebagian mengalami, sebagian mengamati tetapi tampaknya, tak ada yang benar-benar terbiasa.
Jika mengingat lebih jauh, sebelum mengenal tradisi tulis, masyarakat kita telah lebih dahulu melakukan tradisi lisan yang menghasilkan folklor. Di daerah saya, Sunda, tradisi lisan semacam itu banyak berisi cerita yang mengandung ‘pamali’. Misalnya saja, di salah satu situs kampung adat, Kampung Naga, ada sebuah Hutan Larangan yang ‘pamali’ untuk didatangi manusia. Jika ‘pamali’ itu dilanggar, maka akan terjadi bencana kepada penduduk setempat.
Cerita ‘pamali’ tentang hutan diceritakan secara turun-temurun kepada masyarakat penghuni kampung adat tersebut. Bukan tanpa alasan, masyarakat di Kampung Naga melarang eksploitasi sekecil apa pun di Hutan Larangan demi mencegah terjadinya bencana ekologi yang tentunya akan berdampak terhadap kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut sejalan dengan maksud Akmal Nasery Basral yang mengatakan bahwa sastra berfungsi sebagai penyadar agar manusia belajar dari peristiwa atau bencana yang terjadi pada manusia sebelumnya.
Artikel ini dalam rangka Festival Literasi dan WBD 2020