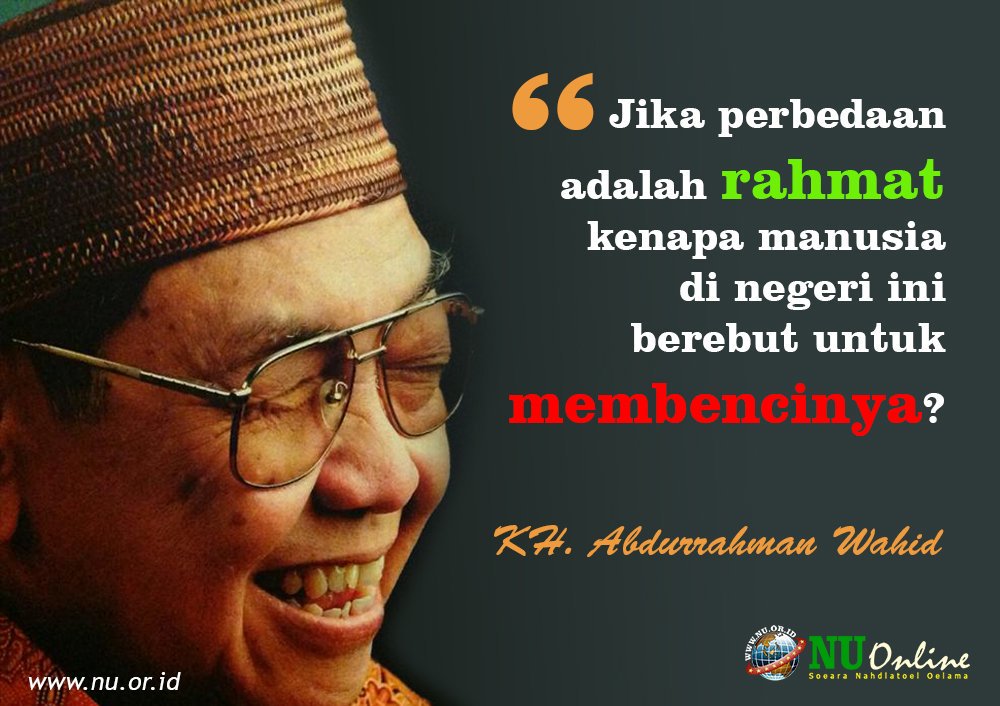Dalam tulisan Kita adalah Rakyat, bukan Umat (Geotimes, 22/2/2017) saya menguraikan salah satu potret kegagapan psikologis dalam beragama adalah ketika narasi umat yang diteguhkan sebagai identitas keagamaan dijadikan sebagai pembelah untuk melokalisir kebenarannya berdasarkan apa yang diyakini sambil menyalahkan pihak lain. Bahkan, puncaknya, apa yang diyakini benar digunakan sebagai cara untuk menebar kebencian.
Dalam tulisan Kita adalah Rakyat, bukan Umat (Geotimes, 22/2/2017) saya menguraikan salah satu potret kegagapan psikologis dalam beragama adalah ketika narasi umat yang diteguhkan sebagai identitas keagamaan dijadikan sebagai pembelah untuk melokalisir kebenarannya berdasarkan apa yang diyakini sambil menyalahkan pihak lain. Bahkan, puncaknya, apa yang diyakini benar digunakan sebagai cara untuk menebar kebencian.
Kenyataan ini berlangsung di berbagai sarana tempat ibadah di berbagai agama. Dalam Kristen ada pembelahan jemaat A dan jemaat B. Ketika seseorang menjadi umat gereja A, maka dia tidak diperkenankan untuk masuk dalam umat gereja B. Demikian juga dalam agama-agama lain, tak terkecuali dalam Islam.
Dampaknya, meminjam istilah Muhidin M Dahlan, timbul pendefinisian sarana ibadah seperti “masjid umat” yang membatasi lingkup jamaahnya berdasarkan arah keyakinannya dan “masjid bukan umat” yang dianggap tidak sejalan dengan pandangannya.
Pembelahan Identitas Umat
Hadirnya fenomena masjid umat yang hanya melokalisasi bangunan syariahnya sesuai dengan apa yang diyakini cukup lama berlangsung di Indonesia. Ketika masjid umat di suatu tempat sudah mengidentifikasi dirinya sebagai pelestari ajaran peribadatan yang sudah ditegaskan oleh tokoh agamanya, maka pihak lain dianggap bukan umatnya. Dari sini kemudian muncul pembedaan masjid umat yang afiliasi teologisnya sepadan dan masjid beda umat yang afiliasi teologisnya berseberangan.
Namun demikian, sepanjang perseberangan paham keagamaannya menyangkut wilayah furu’atul fiqhiyah, di mana yang dipersoalkan menyangkut apakah qunut boleh atau tidak, bagaimana mengawali takbiratul ihrom, dan beberapa bacaan dalam salat, saya kira masih masuk tahap kewajaran ikhtilaf yang lazim terjadi. Sebab, perseberangan ini bisa jadi dilatari oleh perbedaan rujukan dan mazhab yang dipedomani dalam menjalankan peribadatannya. Semisal, ada kelompok tertentu yang memegangi pendapat Imam Syafi’ie dan ada yang memegangi pendapat Imam Maliki, maupun imam-imam mazhab lainnya.
Secara empiris, justru yang menjadi persoalan sangat krusial ketika pembedaan masjid umat dan masjid bukan umat ini sudah dimasukkan ke dalam wilayah sosial maupun kepentingan tertentu, yang ujungnya adalah mendiskreditkan sesama jamaah dan orang lain. Hal ini sebagaimana marak terjadi di banyak masjid yang meneguhkan identitas keumatannya bukan lagi berdasar imam mazhab dalam beribadah, tetapi merujuk pendapat orang-orang tertentu yang “telanjur” ditokohkan dan dianggap memiliki massa, meski kapasitas pengetahuan keagamaannya terbilang tidak mumpuni.
Berbekal tendensi pemahaman keagamaan yang parsial, ada upaya melokalisir identitas keumatan dalam lingkup tertentu yang wilayahnya sangat profan. Yaitu, ketika tokoh yang dirujuk secara kebetulan berafiliasi pada kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik tertentu, maka tokoh tersebut melokalisir identitas keumatannya sesuai dengan apa yang sedang dijalani.
Akibatnya, ajaran keagamaan yang disampaikan berbasis pada apa yang menjadi keinginan “pemangku kepentingan” tadi, dan bukan berdasarkan kepada jati diri perbedaan (ikhtilaf) itu sendiri sebagaimana lazimnya dalam kajian fiqh.
Berbekal kembali al-Qur’an dan hadis (ar ruju’ ilal qur’an was sunnah), misalnya, seseorang yang ditokohkan membuat panduan keumatan di masjidnya dengan cara membelah kecenderungan pemikiran pemahaman tentang agama. Bahkan, tak jarang pula umatnya diajak untuk mendoakan agar seseorang yang sedang dipangku dalam jaringan keberagamaannya agar memperoleh “syafaat kekuasaan” untuk mencapai hajatnya.
Di antara modus yang dilakukan adalah mengedepankan seremonialitas peribadatan yang dihiasi dengan lip service keagamaan dan seolah-olah dianggap sebagai representasi umat beragama secara keseluruhan. Meskipun secara kritis dapat dicermati bahwa kadar representasi yang dilakukan tak lebih dari pendakuan sepihak untuk menguatkan barisan umatnya yang seakan-akan besar.
Ironisnya, dalam seremonialitas ini, yang disampaikan bukannya pesan-pesan kedamaian dan persaudaran sesama manusia yang hidup di Indonesia. Sebaliknya yang diumbar berbagai ujaran kebencian dan permusuhan dilekatkan dalam identitas keumatan. Seolah-olah dalam tubuh keberagamaan yang dilazimkan mengalir hanyalah darah sesama umat dan bahkan yang hanya satu kelompok.
Manufakturisasi Masjid
Dalam kondisi perseberangan cara pandang keagamaan yang tak lagi berbasis pada perbedaan (ikhtilaf) yang genuin, di mana yang seharusnya perbedaan itu menjadi ruang untuk saling berdiskusi dan mengisi dengan argumentasi fiqhiyah lantaran perbedaan mazhab, tapi yang ditonjolkan justru perbedaan latar belakang politik dan ekonomi, maka masjid pun akan menjadi bancakan manufakturisasi.
Dalam konteks ini, merujuk cara berfikir Russell T. McCutheon tentang kerangka “manufakturisasi” yang dikupas dalam Manufacturing Religion: The Discourse on Sui Generis Religion and The Politics of Nostalgia” yang mengkritisi aspek sosio-politik yang melingkupi wilayah agama, maka masjid pun akan mengalami jebakan serupa. Yakni, dengan mekanisme manufakturisasi, para jamaahnya akan dibelah dalam dua identitas yang berseberangan: yang mendukung kepentingannya akan disebut sebagai umatnya dan yang tidak mendukung akan disebut sebagai bukan umatnya.
 Konsekuensinya, bagi orang yang disebut bukan umatnya akan diperlakukan secara semena-mena. Salah contoh yang marak terjadi saat ini adalah munculnya beberapa spanduk di tiga masjid di Jakarta yang menerakan kalimat “masjid ini tidak mensholatkan jenazah pendukung & pembela penista agama”.
Konsekuensinya, bagi orang yang disebut bukan umatnya akan diperlakukan secara semena-mena. Salah contoh yang marak terjadi saat ini adalah munculnya beberapa spanduk di tiga masjid di Jakarta yang menerakan kalimat “masjid ini tidak mensholatkan jenazah pendukung & pembela penista agama”.
Dalam sosiologi kritis, bila isi dari spanduk di atas kita pahami lebih jauh, sesungguhnya yang mereka lakukan itu bisa jadi sebentuk strategi untuk mempengaruhi berbagai pihak agar mendukung calon yang diusung. Selain itu, yang bersangkutan ingin menakut-nakuti banyak pihak bahwa dalam persoalan mati pun, dukungan politik menjadi common denominator yang menentukan kualitas ibadah seseorang.
Dengan demikian, bila masjid yang seharusnya menjadi pusat syiar keberadaban dan seharusnya dimakmurkan dengan kegiatan yang baik, termasuk bagaimana melibatkan banyak orang agar tertarik menjalankan ibadah di dalamnya, lalu dihadapkan dengan perilaku kenaifan yang meneguhkan cara pandang peyoratif, tidakkah masjid pun akan dijebak dalam serangkai manufakturisasi yang justru menguntungkan pemangku kepentingan yang berpusat di pusaran kekuasaan?
Lalu, ketika pusaran kekuasaan ini sudah menggurita di wilayah masjid, bagaimanakah dengan nasib umatnya? Akankah orang yang boleh masuk masjid adalah yang dianggap umatnya? Dus, berarti bila ditilik dalam logika mafhumul mukahalafah, berarti yang bukan umatnya tidak boleh masuk masjid tersebut?
Di sinilah, problem narasi umat yang hingga ini masih diseret dalam kubangan klaim kebenaran (truth claim). Apalagi dalam klaim kebenaran itu membawa-bawa nama Tuhan bahwa masjid yang sudah mengakui seseorang sebagai umatnya adalah yang paling diberkati. Dan ini, tentu menjadi tantangan signifikan dalam kehidupan berbangsa, di mana masjid dan rumah ibadah lainnya bisa digunakan sebagai penyanggah pondasinya.
Maka, bila masjid dan rumah ibadah sudah dibelah dalam identitas keumatan yang absurd dan sarat dengan kepentingan kekuasaan, jangan salahkan orang yang tidak lagi ingin pergi ke masjid. Sebab, di dalam masjid itu sendiri sudah ada pengkotak-kotakan yang lebih dipusatkan pada kepentingan. Bukan pada titik temu perbedaan (ikhtilaf) yang berbasis pada kesyariatan yang memanusiakan.