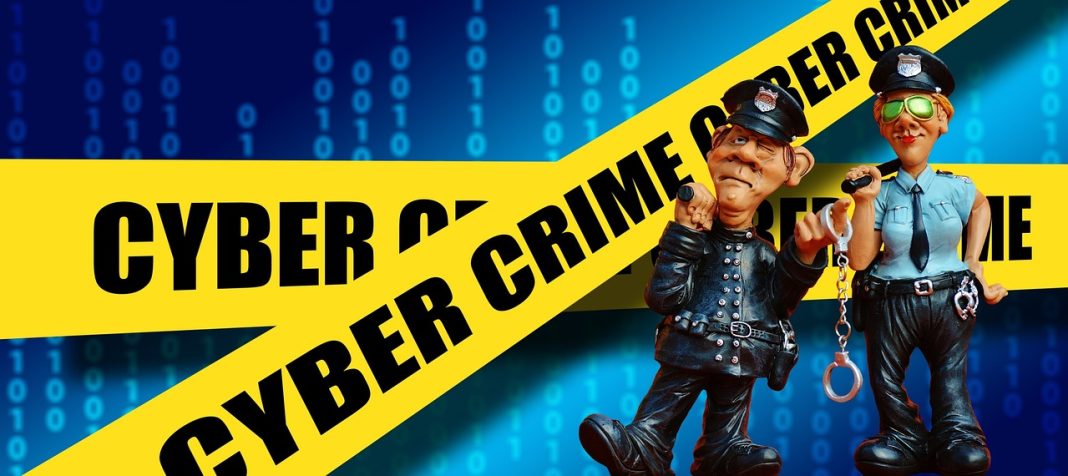Kasus Ferry Irwandi baru-baru ini yang melibatkan TNI menambah daftar pertanyaan publik terkait dinamika hubungan sipil dan Aparat di Indonesia. Pada peristiwa ini framing media massa membingkai kasus melalui dua perspektif dominan: Pertama sebagai pelanggaran HAM oleh aktor militer, dan kedua sebagai bagian dari kompleksitas penegakan hukum di daerah rawan konflik.
Framing pertama banyak ditemukan di outlet independen, sementara media nasional cenderung mengadopsi narasi resmi dari institusi TNI. Perbedaan ini mencerminkan fragmentasi diskursus dalam pemberitaan kasus-kasus sensitif.
Lantas apa yang terjadi dengan Aparat? Mengapa insitusi keamaan selalu menganggap kaum muda sebagai ancaman? Dan kenapa kasus semacam ini sering terjadi?
Pertama, setelah runtuhnya World Trade Center (11 September), perang yang dimulai tidak hanya ditujukan terhadap terorisme internasional tetapi juga meluas ke arah kaum muda sebagai bentuk terorisme domestik. Dalam konteks ini, jika musuh asing didefinisikan berdasarkan identitas keagamaan sebagaimana yang dilakukan terhadap umat Islam di belahan dunia lain, maka kaum muda khususnya para aktivis muda semakin dianggap sebagai ancaman internal yang harus diwaspadai dan dikendalikan.
Proses menggambarkan kaum muda sebagai musuh dalam rumah telah dilakukan secara sistematis sejak neoliberalisme menjadi dominan sebagai sistem ekonomi dan politik di Eropa (terutama Inggris) dan Amerika Serikat. David Harvey, dalam bukunya A Brief History of Neoliberalism (2005), menyatakan bahwa sejak akhir tahun 1970-an, terjadi percepatan yang signifikan dalam penerapan model pemerintahan, ideologi, dan kebijakan neoliberal di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa.
Kedua, fenomena kriminalisasi aktivis hingga upaya pembungkaman Ferry Irwandi menunjukkan bagaimana rezim neoliberal bekerja melalui aparatus negara untuk meredam perlawanan politik kaum muda. Mekanisme pengawasan dan kriminalisasi terhadap aktivis menjadi instrumen penting dalam mempertahankan status quo politik-ekonomi ini.
Catatan Teoritis
Dalam kuliahnya di Collège de France, Foucault menunjukkan bagaimana neoliberalisme Chicago School mentransformasi konsep homo economicus menjadi entitas yang selalu menghitung rasionalitas tindakannya dalam semua aspek kehidupan (Foucault, 2008).
Sedangkan Giorgio Agamben berargumen bahwa biopolitik modern didasarkan pada pembedaan antara kehidupan yang layak dilindungi (bios) dan kehidupan yang dapat dibunuh tetapi tidak dikorbankan (zoē). Konsep “keadaan pengecualian” (state of exception) menjadi pusat analisis Agamben, dimana hukum ditangguhkan untuk menciptakan ruang di mana kekuasaan dapat beroperasi tanpa batas (Agamben, 2005).
Sementara itu, konsep “nekropolitik” menggambarkan bagaimana biopolitik dapat berubah menjadi kekuasaan untuk menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati. Kritik-kritik ini menunjukkan bahwa konsep biopolitik terus berevolusi untuk memahami bentuk-bentuk baru kekuasaan dalam konteks kontemporer (Esposito, 2008).
Upaya Pembatasan Peran Pemuda
Kasus-kasus semacam Ferry mengungkapkan pola yang lebih luas dimana negara menggunakan kerangka hukum anti-terorisme dan keamanan nasional untuk membungkam kritik. Bahwa rezim neoliberal di Indonesia telah mengembangkan “biopolitik pengawasan” yang menargetkan khususnya kaum muda progresif melalui kombinasi pendekatan hukum dan media.
Dalam konteks ini, kita melihat bagaimana narasi “ancaman keamanan” digunakan untuk mengaburkan akar masalah politik sebenarnya dari protes-protes yang dilakukan kaum muda.
Represi terhadap aktivis di Indonesia sering kali mengikuti pola yang terjadi di negara-negara neoliberal lainnya: pertama, delegitimasi melalui stigmatisasi media; kedua, kriminalisasi menggunakan instrumen hukum; dan ketiga, normalisasi melalui aparatus budaya populer.
Ditandai dengan perombakan fondasi demokrasi publik: sekolah, perpustakaan, taman umum, alun-alun, serta ruang publik lainnya yang seharusnya menjadi ruang bagi dialog, partisipasi, dan perlawanan justru menjadi sasaran pembatasan dan pengurangan.
Mirip dengan pola di Indonesia, di Nepal, pengawasan digital terhadap aktivis muda meningkat tajam pasca-undang-undang keamanan siber. Sementara di Prancis, penggunaan teknologi pengenalan wajah selama protes menunjukkan konvergensi antara neoliberalisme dan negara pengawasan (Bigo, 2020).
Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan sekadar alat represi, melainkan teknologi kekuasaan yang melekat dalam pemerintahan neoliberal. Kasus Irwandi menjadi contoh nyata bagaimana wacana neolib bekerja secara sistematis untuk mengubah aktivisme politik menjadi masalah keamanan.
Persis di situ, pemikiran kritis serta partisipasi warga justru dianggap gangguan. Kaum muda, yang secara historis menjadi kekuatan progresif, kini dilemahkan melalui pengemasan ulang identitasnya menjadi “generasi milenial”, “generasi digital”, atau “generasi produktif” dan istilah-istilah lainnya yang mengaburkan peran politik mereka.
Dalam narasi neoliberal, pemuda bukan lagi simbol harapan, melainkan ancaman keamanan dan dilihat sebagai konsumen pasif, beban ekonomi, atau kelompok yang perlu diawasi.
Kehidupan mereka kini dibentuk oleh logika pasar, utang, keadaan darurat keamanan, dan pengawasan massal. Seperti dinyatakan Hardt dan Negri, masyarakat telah berubah menjadi mesin inspeksi di mana setiap institusi mencatat, mengawasi, dan menyimpan data—penjara tidak lagi fisik, tapi menyebar di seluruh tatanan sosial.
Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan bagian dari “metafisika militer” ala C. Wright Mills bahwa aliansi elit politik, militer, korporasi, dan akademik yang menciptakan perang terus-menerus demi menjaga kekuasaan dan keuntungan. Dalam sistem ini, pemuda bukan lagi pelaku sejarah, melainkan objek kontrol.