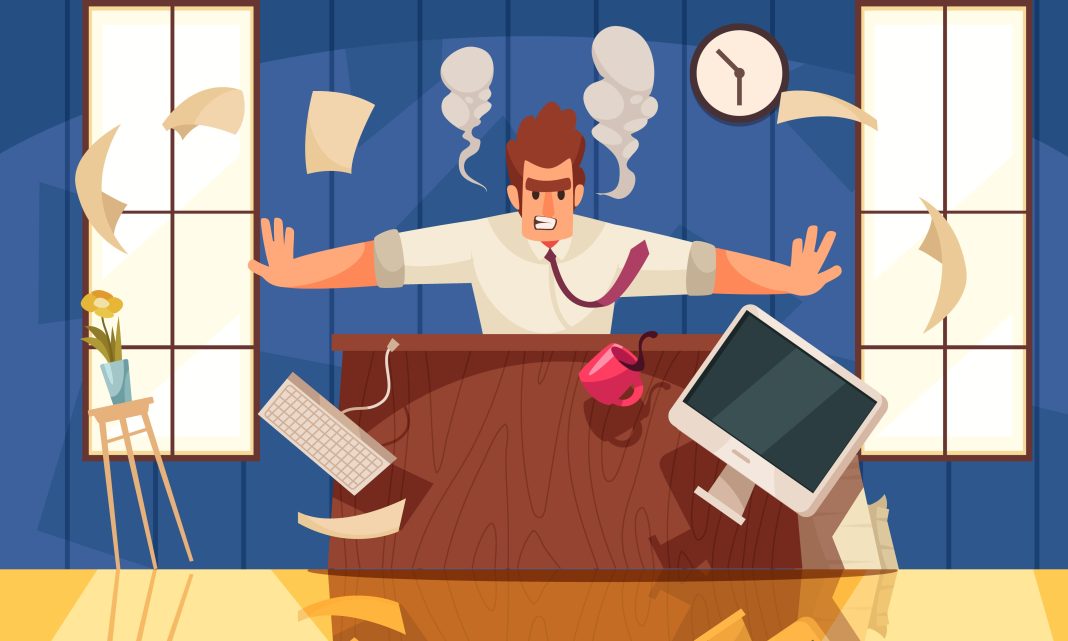Kenapa saat ingin ambil cuti, merasa perlu memoles alasan agar terlihat valid? Seolah-olah butuh rehat saja belum cukup, tanpa harus ada embel-embel urusan keluarga, sakit, atau urusan lainnya yang mendesak untuk diselesaikan.
Kalau ditanya kenapa cuti, ya, alasannya karena mau menikmati hidup dengan hanya sekadar rebahan damai tanpa dihantui grup WhatsApp kantor. Titik.
Persoalannya, kenapa kita merasa bersalah saat ingin memanfaatkan hak cuti hanya untuk merawat kewarasan diri sendiri?
Budaya Kerja yang Menanamkan Rasa Bersalah
Rasa bersalah saat hendak cuti tanpa alasan yang “masuk akal” bukan semata bawaan lahir. Ia hasil pengasuhan panjang dari budaya kerja yang terlalu cinta pada kesibukan. Dalam ekosistem ini, pegawai ideal adalah mereka yang tak kenal lelah, nihil izin, dan bisa diajak rapat mendadak kapan saja, termasuk saat sedang makan bakso.
Maka tak heran, cuti pun harus tampil meyakinkan. Kalau bisa, bumbui sedikit tragedi. Sebab, istirahat tanpa penderitaan akan dianggap kemewahan yang tak pantas. Liburan karena suntuk? Tidak cukup mulia. Istirahat karena bosan? Terlalu manja. Tapi kalau bilang harus antar keluarga ke dokter spesialis jantung, nah, itu yang layak disetujui. Padahal, sering kali persetujuannya disertai dengan catatan: “Tetap bawa laptop dan standby handphone, ya.”
Banyak kantor memperlakukan cuti seperti sidang skripsi. Harus ada latar belakang, rumusan masalah, dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara moril. Konon, cuti yang tidak jelas maksud dan tujuannya akan mengganggu stabilitas operasional, mencoreng citra produktivitas, dan berpotensi menurunkan semangat kerja tim.
Tapi karena tahu budaya kerja tidak memberi ruang untuk kejujuran seperti itu, banyak orang memilih menyamarkan niat baiknya. Ada yang menyusun skenario keluarga sakit, ada yang pura-pura ikut seminar, bahkan ada yang rela datang ke kantor dulu baru izin pulang demi menjaga reputasi. Di tengah semua itu, jarang sekali yang berani bilang jujur: Saya capek. Saya ingin tidur. Tolong izinkan saya rebahan.
Rehat Diam-Diam, Waras Pelan-Pelan
Fenomena cuti “sembunyi-sembunyi” ini lebih lazim dari yang kita kira. Banyak pegawai yang saat cuti, tetap membawa laptop. Bukan karena terlalu loyal, tapi karena takut kalau-kalau ada yang menuduh mereka kabur dari tanggung jawab. Ada pula yang sedang cuti tapi masih aktif merespons pesan grup, agar tidak dibilang memanfaatkan hak secara berlebihan. Ironisnya, orang-orang ini justru lebih sibuk saat cuti daripada saat masuk kerja.
Bagi sebagian orang, cuti bukan lagi hak, melainkan utang. Harus ditebus dengan laporan lengkap, persiapan pengganti, dan tak jarang dihantui perasaan bersalah berkepanjangan.
Kita hidup di zaman yang membingungkan. Teknologi sudah canggih, kerja bisa dari mana saja, tapi rasa lelah justru makin tidak punya tempat. Alih-alih memberi ruang untuk istirahat, banyak sistem kerja hari ini malah menyamarkan kelelahan sebagai semangat dan menilai seseorang dari seberapa sering ia terlihat online.
Bekerja dari rumah, misalnya, membuat batas antara ruang pribadi dan ruang kerja semakin kabur. Cuti pun jadi absurd, kalau ujung-ujungnya tetap pegang laptop dan standby di grup, apa bedanya dengan hari kerja biasa? Akibatnya, banyak orang merasa terus bekerja, tapi tidak pernah benar-benar hadir. Terus bergerak, tapi tidak pernah pulih.
Kalau kita tidak bisa dengan jujur berkata, “Saya butuh istirahat”, maka siapa lagi yang akan memperjuangkannya? Pasalnya, kelelahan hari ini bukan cuma milik individu, ia sudah jadi kelelahan sistemik. Maka memulihkan diri bukan sekadar kebutuhan personal, tapi tindakan kecil untuk bertahan di tengah hiruk-pikuk dunia.
Normalisasi Rehat Tanpa Drama
Sesekali cuti tanpa rencana mulia itu sah-sah saja. Mau hanya tidur siang, maraton drama Korea, atau sekadar menatap langit tanpa beban, semuanya valid. Kita tidak harus menunggu burnout untuk bisa mengambil jeda. Bahkan, cuti sebelum kekacauan itu datang bisa dibilang bentuk pencegahan yang jauh lebih murah daripada biaya konseling.
Cuti juga tidak perlu selalu produktif. Kalau hari kerja saja kita rela menyisihkan waktu berjam-jam untuk rapat yang bisa jadi email, maka saat cuti, bolehlah sesekali menyisihkan waktu untuk tidak jadi siapa-siapa. Tidak jadi pegawai. Tidak jadi admin. Tidak jadi pengingat deadline. Hanya jadi manusia yang ingin diam.
Cuti Itu Hak, Bukan Penghargaan untuk yang Lelah
Cuti bukanlah medali untuk pegawai teladan. Ia tidak perlu direbut, dilobi, atau dipertanggungjawabkan secara spiritual. Ia diberikan karena kita manusia, bukan mesin. Jadi kalau mau cuti, jangan repot-repot menyusun alibi. Tidak usah menulis ada urusan mendesak, cukup bilang: “Saya ingin jeda.” Cukup.
Sebab, percaya atau tidak, pekerjaan bisa menunggu, yang tidak bisa menunggu terlalu lama adalah kewarasanmu sendiri.
Survei Deloitte Global 2025 (dipublikasikan di GoodStats pada 3 Juni 2025) mengungkapkan bahwa 74% Gen Z dan 68% milenial merasa mereka harus mengambil cuti karena stres, bukan karena dramatika atau alasan besar. Hal serupa juga tampak dalam survei LinkedIn, yang menunjukkan bahwa sekitar 35% Gen Z merasa bersalah saat mengambil cuti, bahkan ketika mereka membutuhkannya.
Ini menunjukkan bahwa rasa bersalah saat istirahat bukan sekadar isu lokal, tapi gejala global dari budaya kerja yang menjadikan produktivitas sebagai tolok ukur moral. Maka, cuti seharusnya dilihat sebagai kebutuhan untuk menjaga kesejahteraan, bukan hanya hadiah bagi yang punya alasan ‘luar biasa’.