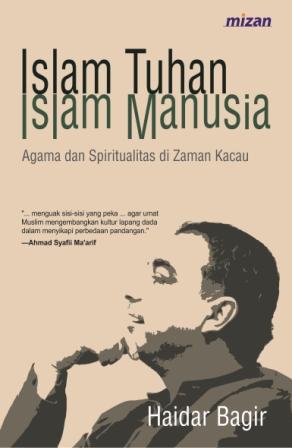Modernitas dan Teknologi
Teknologi, sebagai dampak bawaan dari modernitas, bak sebuah pisau yang memiliki dua sisi bertolak belakang. Satu sisi bisa sebagai alat yang sangat bermanfaat dan di sisi yang lain, hal itu bisa menjadi alat destruktif mencelakakan orang. Dalam konteks ini, kehadiran media baru dengan adanya media sosial memunculkan dua hal tersebut. Kehadiran media sosial, jika digunakan dengan baik, membuka pasar seluas-luasnya sehingga memungkinkan melakukan akumulasi kapital menjadi berlipat dari sebelumnya. Selain lebih efektif, media sosial menghubungkan pelbagai orang, dari berbeda latarbelakang, komunitas, dan institusi untuk berinteraksi dan bertransaksi. Apa yang disebut dengan pasar sebagai tempat fisik di mana orang bertemu telah mengubah menjadi ruang maya yang menembus batas-batas geografis.
Karena itu, seburuk apapun ekonomi ataupun aktivisme yang ditawarkan, baik serius ataupun berbentuk hiburan, selalu menemukan konsumen dan pembacanya. Sebaliknya, media sosial bisa menjadi alat destruktif untuk memecah solidaritas kemanusiaan, menebar kebencian, menguatkan radikalisme, dan meneguhkan konservatisme beragama di tengah algoritma internet yang cenderung membelah opini yang disukai oleh penggunanya.
Di tengah situasi semacam itu, kehadiran buku Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau karya Haidar Bagir, menjadi “resep” yang bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara kita beragama di era kekacauan. Resep ini merupakan ekstraksi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini diajukan dalam kepala kita, tapi belum menemukan peta jawaban, mulai dari krisis global yang ditandai dengan kembalinya orang kepada spiritual, di satu sisi, dan memunculkan konservatisme di sisi yang lain. Kesalehan beragama di ruang publik, secara kontradiktif justru menguatkan radikalisme dan praktik takfiri. Islam sebagai agama kelembutan dan penuh kasih sayang, namun yang dominan wajah brutalitas agama di tengah praktik persekusi. Layaknya mendiagnosa penyakit, persoalan-persoalan ini satu persatu dibahas dalam buku ini dengan detail dan berimbang.
Tiga Persoalan
Secara garis besar, Haidar membagi tiga persoalan utama yang selama ini kita hadapi, baik sebagai warga negara maupun masyarakat Muslim Indonesia. Pertama, dalam level internasional, alih-alih mengalami stabilitas keamanan, baik sosial, ekonomi, politik, ataupun spiritual, dengan prosedur aturan dan kesepakatan yang dibuat sebagai aturan main, dunia yang kita hadapi saat ini sedang mengalami fase peluruhan. Hukum internasional yang selama ini dijadikan pegangan dalam membangun hubungan bilateral antara satu negara dengan negara yang lainnya tidak lagi menjadi pegangan yang disepakati. Solidaritas sosial kemanusiaan yang menjadi agenda penting membangun peradaban dalam sebuah negara dan bangsa memunculkan perpecahan, baik atas nama suku, agama, dan ideologi. Kepentingan sumber-sumber ekonomi menjadi panglima setiap kekuasaan untuk merebutnya. Di sini, perang, baik skala besar dan kecil kemudian menjadi jalan yang ditempuh. Optimisme menjadi surut. Akibatnya, publik internasional memunculkan wajah suram mengenai masa depan dunia.
Kedua, menguatnya radikalisme dan takfirisme. Kondisi dunia internasional tersebut kemudian berimbas dan merembes dalam praktik keagamaan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan menguatnya radikalisme dan praktik takfirisme. Memang, radikalisme memiliki akar yang panjang, baik secara histogiorafis maupun ideologis di Indonesia. Bagi Haidar, radikalisme bukan hanya dua persoalan tersebut. Radikalisme beririsan erat antara frustasi karena faktor-faktor sosial ekonomi dan tingkat keterasingan seseorang dalam memandang persoalan hidup serta persaingan keagamaan dan politik dalam level lokal, nasional, dan global. Di tengah situasi tersebut, pragmatisme dalam beragama menjadi pilihan dan pegangan. Kondisi tersebut menjadi target utama sekelompok pemuka agama yang menawarkan doktrin-doktrin teks agama yang literal. Sementara itu, upaya untuk memperkuat tingkat keyakinan dalam beragama ini diteguhkan dengan praktik takfirisme, mengkafirkan kelompok yang lain sambil meneguhkan keyakinannya yang paling benar. Upaya mengkafirkan ini tidak hanya kepada kelompok yang secara agama berbeda, melainkan juga kelompok Islam itu sendiri, seperti Syiah dan Ahmadiyah. Dalam menjelaskan takfirisme ini, Haidar, dengan sistematis, menjelaskannya dalam aspek sejarah, ideologi, hingga konteks muktahir di tengah memanasnya geopolitik di negara-negara teluk.
Ketiga, Teknologi Informasi (TI). TI memberikan perubahan signifikan dalam masyarakat. Selain meningkatkan kemampuan berkomunikasi, TI menjadi medium yang efektif dan memudahkan dalam melancarkan arus komunikasi di mana pun kita berada, tanpa sekat geografis yang selama ini dianggap sebagai penghalang laju gerak. Harus diakui, bagi Haidar, TI “membuka Kotak Pandora yang memungkinkan orang memalsukan pesan” dengan memanfaatkan TI tersebut. Dengan merujuk McLuhan, ia berpendapat bahwa media bukan hanya berfungsi sebagai penyebaran informasi, melainkan sebagai pesan itu sendiri. Melalui TI, informasi bisa dikemas dengan cara yang memikat sehingga orang tertarik dan terhanyut di dalamnya. Kemudahan mencari informasi dengan berselancar di dunia maya inilah yang memungkinkan orang bisa tersesat dan mengalami disorientasi. Kondisi ini mengakibatkan dan memunculkan generasi yang instan; apapun serba mudah dicari tapi kehilangan tingkat refleksi dan kedalaman atas informasi yang diserap di tengah derasnya informasi yang didapatkan. Situasi ini yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan menyebarkan informasi-informasi bohong (Hoax) di media sosial. Artikulasi Hoax menjadi massif ketika ada momentum-momentum politik, seperti Pilpres dan Pilkada. Akibatnya, kondisi tuna kepercayaan ini membelah masyarakat kepada ikatan kelompok yang disukainya saja. Melalui wajah ruang online ini, kita membangun interaksi di masyarakat secara riil dengan penuh kecurigaan dan kekhawatiran kepada orang lain hanya karena berbeda pandangan, etnik, dan agama.
Resep Beragama
Untuk mengatasi tiga hal tersebut, Haidar menawarkan semacam formula yang menjadi resep. Untuk konteks Internasional dan Indonesia, revitalisasi kesadaran kolektif bangsa dengan “meletakkan budaya sebagai tempat persemaian seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun agama”. Dalam budaya ini terdapat “suatu falsafah hidup berbangsa dan bernegara, yang memuat nilai-nilai filosofis, ideologis, sekaligus praktis”. Pancasila menjadi jalan utama untuk membentuk dan merevitalisasi kebudayaan Indonesia tersebut yang sempat ditafsirkan secara sepihak saat rezim Orde Baru berkuasa. Nilai-nilai Pancasila ini yang mesti dipraktikkan dan menjadi nilai dasar dalam interaksi dan pergaulan sesama anak bangsa, bukan menjadi sekedar slogan kosong. Sementara itu, dalam konteks beragama, ia menawarkan gagasan wajah kemanusiaan Islam. Maksudnya, wajah Islam itu bukan untuk Tuhan, melainkan untuk manusia. Meskipun manusia tidak pernah luput dari kesalahan, dengan kemampuan penalaran dan proses ikhtiar yang dimiliki, Islam itu agama yang sepenuhnya untuk manusia. Puncaknya, manusia sebagai orang beragama adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan. Di sini, tindakan intoleransi memunculkan benih-benih kebencian tidak sesuai dengan Islam.
Dalam menawarkan resep wajah Islam wajah Manusia ini, Haidar mengemukakan terma-terma kunci dalam Islam yang bisa didiskusikan dan kemudian menjadi solusi dalam bab III sampai V dalam buku ini; mulai dari gagasannya untuk mengajak kembali melihat penafsiran teks-teks Islam yang lebih terbuka, menanamkan nilai-nilai kemoderatan Islam, menguatkan kembali dialog antar agama sebagai bagian dari kekayaan peradaban, mempertautkan Islam dan Budaya Lokal. Selain itu, Ia mengajak untuk mendiskusikan kembali isu-isu yang selama ini hangat di masyarakat. Misalnya, mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan kafir di dalam Islam dan mendialogkan Sunni-Syiah yang akhir-akhir ini menjadi wacana kebencian sekelompok ormas. Dalam bagian ini, ia menjelaskan pentingnya peranan akal di dalam Islam yang selalu disebutkan dalam Alquran dan Hadis Nabi sebagai fondasi kita dalam beragama. Tidak kalah menarik, ia mengajukan Islam sebagai agama kasih sayang dan cinta dengan mengajukan jalan sufi sebagai tawaran. Asketisme sufi dan semangat yang tumbuh di dalamnya ini yang semakin terpinggirkan dalam wacana maupun praktik beragama di Indonesia akhir-akhir ini. Bahkan, lebih ironis, praktik-praktik sufi melalui tasawuf semacam ini dengan kemunculan pelbagai organisasi keagamaan Islam di Indonesia dijadikan arena takfiri bagi mereka yang berpaham literal.
Dengan wawasan filsafat yang luas, dipandu dengan kedalaman diskursif Islam dan kemampuan membaca persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan umat Islam di Indonesia, buku ini penting untuk dibaca, bukan hanya masyarakat Muslim melainkan semua kalangan dari pelbagai latarbelakang. Selain membuka wawasan berpikir, menguak akar persoalan yang terjadi, menunjukkan nilai khazanah kekayaan dan kearifan Islam, buku ini menjadi resep beragama di era paska kebenaran (post-truth) semacam ini, di mana media sosial adalah wajah yang membentuk ruang publik dan praktik keberislaman dan keindonesiaan kita akhir-akhir ini. Dengan bahasa yang mengalir dan pembahasan yang proporsional dan padat, buku ini menjadi bacaan ringan yang bisa memandu kita untuk berhati-hati dalam menyikapi isu-isu di dalam Islam, yang seringkali dijadikan agenda politik bagi mereka yang memiliki kepentingan tertentu.
Makalah ini dipresentasikan dalam acara Tadarus Buku: Islam Tuhan Islam Manusia, diadakan oleh Penerbit Mizan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Jumat 9 Juni 2017 di Auditorium Widya Graha Lantai 2 Gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto No.10 Jakarta Selatan. Sumber Kolom LIPI.