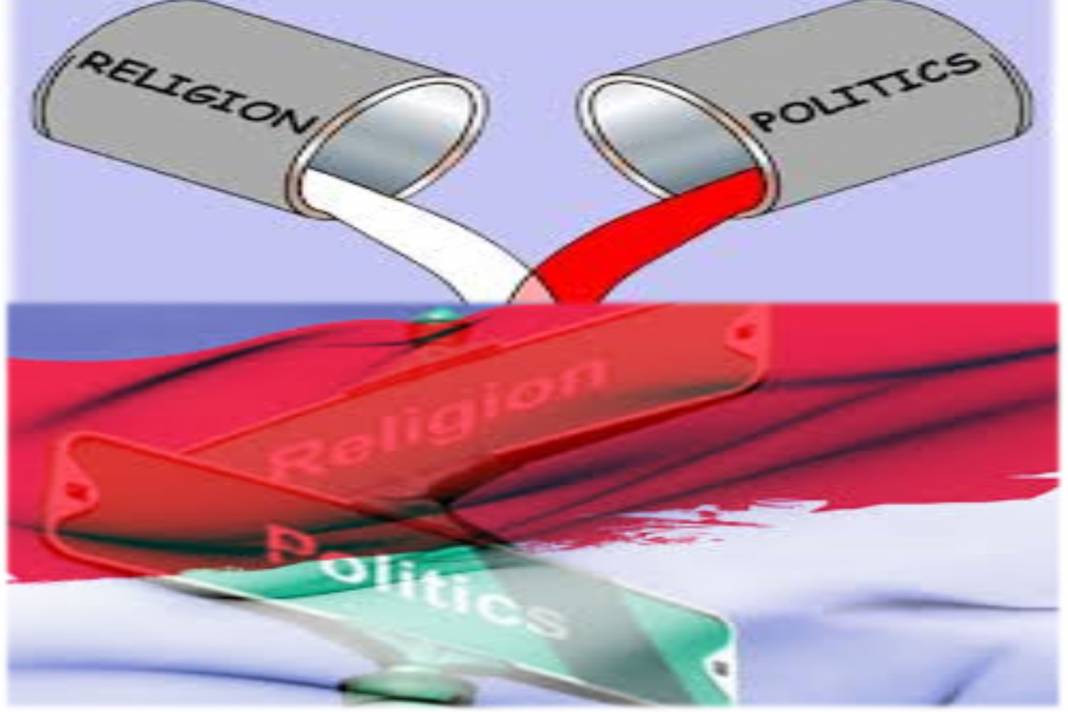Isu agama selalu hadir—atau dihadirkan?—dalam dinamika politik Indonesia. Contoh teranyar yang sering diangkat ke permukaan adalah preseden Pilkada DKI Jakarta 2017.
Banyak pengamat beranggapan terpilihnya pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Ibukota mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sebagai kemenangan “kelompok yang memainkan isu agama” dalam kontestasi politik. Preseden ini menyembulkan kekhawatiran menjalari gelaran-gelaran politik berikutnya—lokal maupun nasional—terutama Pilkada serentak yang akan digelar untuk beberapa daerah tingkat satu dan dua pada 2018 serta Pemilu 2019.
Kekhawatiran seperti ini wajar, karena agama—sering dikelompokkan dalam rumpun SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)—merupakan realitas sensitif sarat simbol yang menyentuh wilayah keyakinan serta identik dengan ritualitas dan sakralitas. Ketika agama ditarik masuk ke dalam wilayah politik praktis, maka tak pelak ia akan ikut “dimainkan” atau “dipermainkan” untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu dalam rangka kekuasaan.
Tentu kita ingin semua proses politik berlangsung fair, bersih, jujur, dan adil sehingga menghasilkan kepemimpinan dan kebijakan yang benar-benar mampu memajukan negara, memakmurkan bangsa, dan menyejahterakan rakyat. Maka penting untuk kita pahami dan hayati bahwa proses politik adalah bagian dari cara kita mengelola negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Kita memilih sistem demokrasi untuk melancarkan sirkulasi kepemimpinan dan kebijakan sebagai bagian dari proses politik. Demokrasi sebagai sistem tidaklah sempurna, hanya saja kita melihatnya sejauh ini sedikit lebih baik dari sistem-sistem lain yang pernah ada dan dipraktikkan bangsa-bangsa di dunia, dan lebih memungkinkan bagi tercapainya tujuan-tujuan bernegara.
Di antara persoalan terkait demokrasi politik yang kerap muncul ke permukaan adalah kompatibilitasnya dengan agama. Ada sebagian yang berpendapat demokrasi tak sejalan dengan agama, karena itu agama dan politik tak bisa dicampuradukkan, harus dipisahkan. Pendapat lain menyatakan agama dan politik harus berjalan seiring, tak boleh dipisahkan.
Islam dan Politik Agama
Meski merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia dengan gugusan kepulauan yang dihuni beragam etnik dan suku ini tidak secara definitif dikategorikan sebagai—untuk tidak menyebut bukan—negara Islam. Maka tidak ada ketentuan tertulis yang mensyaratkan pemimpin negara harus beragama Islam. Tidak ada pula ketentuan negara yang mengikat bahwa warga beragama Islam wajib menjalankan syariat agamanya.
Siapa pun warga negara Indonesia berhak dan punya kans menjadi pemimpin formal negara, tanpa batasan apakah ia beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau Khonghucu—bahkan termasuk apabila ia menganut suatu aliran tertentu yang hidup di bumi Indonesia selain enam agama tersebut. Artinya, agama tidak dalam posisi menjadi penentu kepemimpinan negara.
Seiring dengan itu, setiap warga negara bebas menganut agama “apa saja?”
Dengan begitu, apakah berarti agama dan keyakinan akan ketuhanan tidak lagi memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan sosial? Di manakah posisi agama dalam konstruksi kehidupan berbangsa dan benegara? Apakah agama hanya serupa simbol identitas—laiknya suku, ras, dan golongan—yang diperlukan di kala tertentu lalu diabaikan pada kala yang lain?
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan agama sebagai “ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.”
Dalam konteks Islam, tata keimanan masuk wilayah akidah, tata peribadatan masuk wilayah syariat, dan tata kaidah pergaulan masuk wilayah hukum dan akhlak. Idealnya, sistem akidah dan sistem syariat serta sistem hukum dan akhlak adalah ajaran integral yang berlaku universal.
Muslim yang secara rigid menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi dan sosialnya jamak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan agamanya. Ia menjadikan ajaran Islam sebagai referensi utama dalam menentukan sikap dan tindakan.
Spirit politik keislaman modern, misalnya, telah mewarnai jagat Nusantara sejak awal abad ke-20, dan terus berkembang di era pergerakan sebelum kemerdekaan hingga kini. Setidaknya, spirit tersebut bisa dilihat mulai ketika Tirtoadisurjo (1880-1918) mendirikan Sarekat Dagang Islam di Batavia (Jakarta) pada tahun 1909, diikuti oleh Haji Samanhudi (1868-1956) di Surakarta pada tahun 1911. Organisasi ini lalu berubah nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912, dan terus berkembang di masa kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto (1882-1934) di Surabaya, diikuti cabang-cabang lainnya di berbagai wilayah Nusantara.
Sarekat Islam merupakan organisasi pertama berbasis rakyat, yang meski berumur tidak lama, organisasi ini relatif berhasil meletakkan dasar serta menampilkan citra Islam sebagai kekuatan sosial dan politik rakyat.
Di masa-masa pergerakan, spirit keislaman mewarnai wajah-wajah Nusantara melalui gerakan-gerakan sporadis. Pemimpin-pemimpin muslim di masa itu bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi taktis. Hasil dari pergerakan mereka pun lokalistik-parsialistik, dan mudah sekali dipatahkan.
Meskipun muslim di Indonesia mayoritas, tidak serta merta pergerakan politik berlabel Islam mendapat dukungan luas. Faktanya, belum pernah tercatat partai politik Islam meraih suara mayoritas, baik pada masa Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), maupun Orde Reformasi.
Partai politik berbendera Islam kerap diberi stigma sebagai politik aliran, sehingga persepsi yang berkembang bahwa ibarat baju, partai Islam terlalu “sempit” untuk Indonesia yang majemuk. Tentu, persepsi ini tidak sepenuhnya salah—untuk tidak juga menyatakan benar. Ketika parpol Islam mengusung visi keislaman, selalu timbul reaksi ketakutan kalau Indonesia akan menjadi negara Islam.
Sebagian kalangan memprediksi partai politik berbendera Islam di Indonesia lambat laun akan ditinggalkan. Indikasinya bisa dilihat dari sejarah partai politik nasional sejak era Orla hingga kini, belum pernah ada partai politik berbendera Islam yang benar-benar berhasil mendapat dukungan mayoritas.
Secara umum, baru Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia) di era Orla yang bisa dikatakan cukup fenomenal. Di era reformasi, dari sekian banyak partai politik berbendera Islam, hanya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang mampu bertahan hingga saat ini. Itupun dengan perolehan suara stagnan, bahkan cenderung menurun.
Tentu ini merupakan tantangan bagi partai politik berbendera Islam untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan performanya di mata publik. Namun tidak berarti menghalalkan segala cara, misalnya, dengan mempolitisasi ajaran-ajaran Islam sedemikian rupa demi meraup suara mayoritas. Sebab jika itu dilakukan, maka tidak saja umat muslim yang dirugikan, Islam pun sebagai agama luhur akan coreng-moreng.
Politik agama sejatinya adalah politik untuk menegakkan keluhuran. Adapun politisasi agama hanya akan membawa pada kehancuran. Maka kita nyatakan, “politik agama: yes, dan politisasi agama: no.”