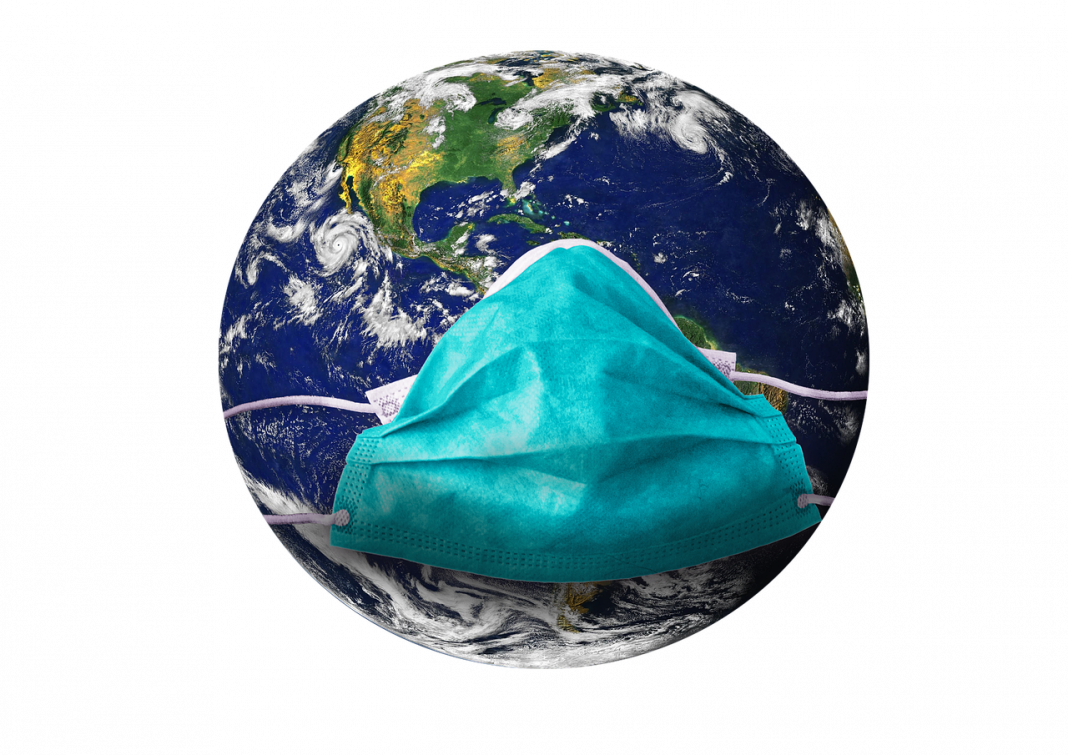“Musuh terbesar kita sekarang bukanlah virus (Corona) itu sendiri. Tetapi ketakutan, rumor, kabar bohong, dan prasangka. Sementara modal terbesar kita adalah fakta, akal, dan solidaritas.” Pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom, tersebut agaknya sangat tepat untuk merespons “kepanikan global” saat ini yang terjadi karena mewabahnya virus COVID-19—atau sering disebut sebagai virus Corona.
Sejak pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu, virus Corona memang sudah menginfeksi puluhan ribu orang dan menyebar ke lebih dari 60 negara. Tidak terkecuali ke Indonesia. Setelah sempat mengklaim bebas dan aman dari virus Corona, Senin (2 Maret 2020) dalam jumpa pers, Presiden Joko Widodo menyebut ada dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif terinfeksi virus Corona.
Kedua WNI itu sebelumnya terlibat kontak langsung dengan seorang Warga Negara (WN) Jepang yang positif virus Corona, sehingga keduanya ikut terpapar virus tersebut. Meskipun bukan kasus yang pertama bagi WNI, tetapi kasus tersebut menjadi yang pertama terjadi di wilayah Indonesia. Adapun, WNI pertama yang terinfeksi virus Corona adalah TKW Indonesia yang tinggal atau berdomisili di Singapura.
Penimbunan Masker
Pasca pengumuman yang sangat mengejutkan tersebut, sebagian masyarakat Indonesia langsung melakukan panic buying. Banyak masyarakat yang berbelanja keperluan medis dan hidup secara berlebihan, karena takut akan penyebaran virus Corona yang semakin meluas.
Berbagai toko ritel dan apotek diserbu oleh konsumen yang memburu produk hand sanitizer, masker, obat-obatan, multivitamin, hingga makanan kaleng, mie instan, minuman kemasan, dan popok. Fenomena panic buying tersebut akhirnya membuat stok barang berkurang secara drastis, bahkan ada yang “ludes”. Terutama masker, sebab dianggap sebagai alat yang efektif mencegah penularan virus Corona.
Sesuai dengan teori permintaan, harga barang akan relatif naik apabila permintaan naik. Maka, harga masker sekarang ini juga mengalami kenaikan yang fantastis akibat permintaan yang sangat tinggi. Di apotek harga masker bisa naik sampai seribu persen. Seperti contoh, harga masker yang biasanya hanya dijual Rp 30 ribu per boks, saat ini dijual Rp 300 ribu.
Meskipun demikian, masyarakat terpaksa tetap membeli karena khawatir akan kehabisan stok. Sementara itu, di sisi yang lain, justru ada sebagian oknum masyarakat sedang “memancing di air keruh” dengan menimbun masker. Penimbunan tersebut dilakukan untuk memainkan stok dan harga.
Dari aspek hukum, tindakan penimbunan masker dapat dijerat pasal 107 Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 itu intinya menjelaskan, bahwa para pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu saat terjadi kelangkaan barang, bisa dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
Aturan tersebut yang mendasari polisi untuk bergerak cepat dalam menggrebek sejumlah lokasi penimbunan masker di berbagai wilayah, seperti Jakarta Barat, Semarang, Makassar, dan sebagainya.
Ideologi Kompetisi
Sementara itu, dari sisi moralitas, tindakan menimbun masker menjadi contoh nyata untuk perbuatan “amoral” (tidak bermoral). Dalam situasi krisis seperti sekarang yang seharusnya membutuhkan kolaborasi antar masyarakat, justru ada oknum nakal “egois” yang mencari oportunitas material.
Menurut Novi Candra, Co-Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), cara berpikir egois demikian merupakan salah satu produk dari sistem pendidikan yang selalu berorientasi pada kompetisi. Dalam sistem pendidikan kita saat ini, kompetisi memang menjadi sesuatu hal yang seolah “didewakan”. Mulai dari kompetisi berebut peringkat di kelas, sekolah, hingga dalam berbagai ujian.
Pada sistem pendidikan seperti itu, nilai-nilai konsumtivisme dan kompetisi menjadi arus utama (mainstream), sedangkan nilai-nilai solidaritas dan kolaborasi sosial harus terpaksa terpinggirkan. Hal tersebut yang dikiritik oleh teori pedagogi kritis. Kompetisi membuat orang hanya memikirkan keselamatan dirinya, bahkan jika diperlukan boleh mengorbankan orang lain.
Menurut Henry Giroux, “menjatuhkan” dihargai lebih tinggi dalam kompetisi, daripada kerjasama solidaritas (Wattimena, 2018). Oleh sebab itu, jangan berharap nilai-nilai adiluhung seperti kemanusiaan, kepekaan moral, serta keterlibatan sosial akan lahir dari ideologi kompetisi.
Henry Giroux bukan satu-satunya tokoh yang mengkritik ideologi kompetisi dalam pendidikan. Alfie Kohn, tokoh pendukung “pendidikan progresif”, dalam tulisan yang berjudul The Case Against Competition (1987), menyimpulkan bahwa kompetisi dalam pendidikan pada dasarnya buruk.
Persaingan ibarat gula atau permen pada gigi. Mula-mula manis dan menyenangkan, tetapi pada akhirnya merusak gigi. Anak-anak akan menjadi egois, superior, serta menganggap remeh orang lain. Tidak mengherankan, apabila negara seperti Finlandia lebih fokus menerapkan sistem pendidikan yang berbasis pada kolaborasi dengan prinsip “cooperation not competition”.
Pendidikan Nirempati
Ideologi kompetisi yang kental dalam pendidikan tersebut juga melahirkan “hidden curriculum” di lingkungan sekolah dalam wujud pendidikan tanpa empati (nirempati). Empati, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk merasakan keadaan emosional yang dirasakan oleh orang lain/mengambil perspektif orang lain.
Namun, keterampilan tersebut mulai tersisih di sekolah, sebab terdepak oleh kultur kompetitif. Pada akhirnya, pendidikan gagal memainkan perannya sebagai proses yang semestinya dapat melatih dan mempertebal empati. Hal itu yang kemudian teraktualisasi dalam fenomena maraknya kasus penimbunan masker.
Kita mungkin perlu belajar dari negara Denmark, yang secara konsisten selalu masuk dalam daftar tiga negara paling bahagia di dunia menurut data PBB selama tujuh tahun terakhir. Sejak tahun 1993, kurikulum Denmark memperkenalkan “kelas wajib empati”. Dirangkum dari artikel situs educateinspirechange.org, program kelas empati dimulai pada usia enam tahun sampai usia enam belas tahun.
Selama satu jam setiap minggu, anak-anak mendapatkan pelajaran empati dalam jam mata pelajaran tersendiri. Di kelas, siswa mendiskusikan masalah-masalah pribadi maupun kelompok dengan suasana santai dan mencoba mencari solusi bersama.
Seperti halnya Finlandia, Denmark juga menerapkan pendidikan empati karena lebih memprioritaskan nilai-nilai kolaborasi, ketimbang kompetisi. Alih-alih mencari peserta didik yang terbaik melalui perlombaan, kurikulum Denmark fokus kepada membangun dan meningkatkan keterampilan siwa yang unik satu sama lain dengan didukung oleh pembelajaran kolaboratif.
Hal itu juga sesuai dengan semangat konsep pembelajaran Abad 21 yang salah satunya memuat nilai kolaborasi. Ke depan, kita berharap ada transformasi pendidikan yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah ini. Pendidikan sejatinya mempertajam pikiran dan memperhalus perasaan.