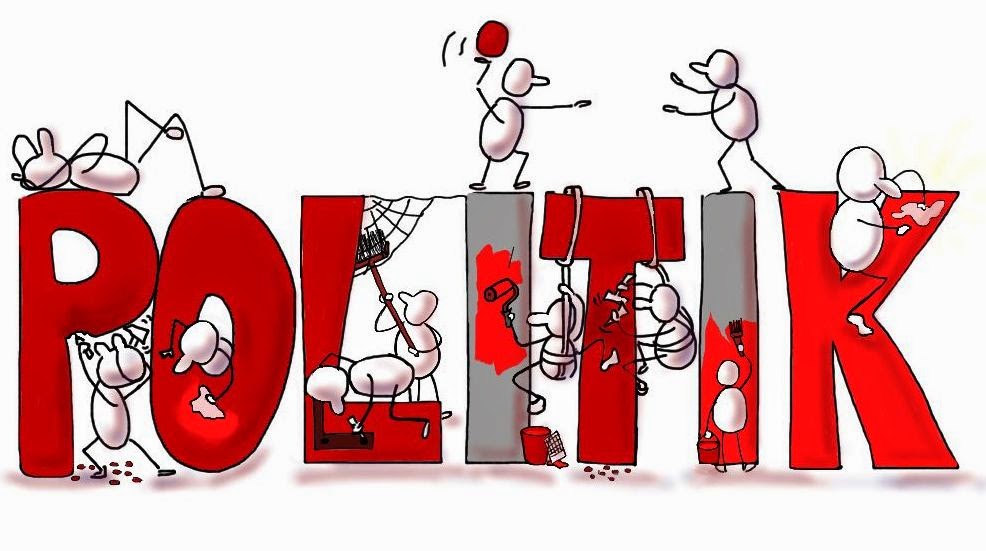Syahwat itu ibarat api yang selalu menyala-nyala ke atas. Dalam batas wajar, seperti api kompor, api akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di luar batas wajar, seperti kompor meledak, api akan membahayakan bagi kehidupan manusia. Salah satu bentuk syahwat yang sedang marak diperbincangkan pada tahun politik ini adalah ambisi meraih kekuasaan, terutama jabatan legislatif dan eksekutif yang diperebutkan melalui pemilu.
Menurut al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulumiddin, ambisi terhadap kekuasaan itu lebih unggul daripada ambisi terhadap harta, karena meraih harta melalui lantaran kekuasaan itu lebih mudah dibandingkan meraih kekuasaan melalui lantaran harta. Terbukti, banyak pejabat yang sebelumnya miskin, mendadak kaya raya setelah menjabat. Sebaliknya, banyak hartawan yang gagal terpilih menjadi pejabat, sekalipun sudah menggelontorkan dana kampanye yang begitu banyak.
Dalam batas wajar, ambisi meraih kekuasaan dapat ditoleransi. Misalnya, Nabi Yusuf AS secara terang-terangan mengajukan diri beliau kepada Raja Mesir agar diangkat sebagai “Menteri Ekonomi Mesir”. Keinginan beliau disampaikan dengan bahasa lugas, “Mohon jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (hemat), lagi berpengetahuan (cermat)” (Q.S. Yusuf [12]: 55).
Ambisi meraih kekuasaan yang ditunjukkan Nabi Yusuf AS dapat ditoleransi, karena dalam batas wajar, dengan mempertimbangkan tiga argumentasi.
Pertama, Nabi Yusuf AS sudah mendapat kepercayaan (trust) terlebih dahulu dari Raja Mesir dan para pembesar negara Mesir, “Raja Mesir berkata: ‘Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami’” (Q.S. Yusuf [12]: 54).
Kedua, Nabi Yusuf AS merasa bertanggung-jawab untuk melaksanakan ide gagasan beliau. Dalam Tafsir al-Jalalain dinyatakan bahwa Nabi Yusuf AS dimintai pendapat terkait solusi atas potensi krisis pangan yang berkepanjangan di Mesir. Beliau berkata: “Himpunlah makanan; tanamlah tanaman sebanyak-banyaknya pada tahun ini, lalu simpanlah hasil panennya beserta tangkainya sekaligus”. Raja Mesir bertanya, “Siapa yang mengurusi semua itu?”. Saat itulah Nabi Yusuf AS mengajukan diri sebagai Menteri Ekonomi Mesir.
Ketiga, Nabi Yusuf AS memiliki kompetensi yang relevan (sesuai) dan mumpuni untuk menyandang jabatan sebagai Menteri Ekonomi Mesir, karena beliau memiliki watak hemat (hafizh) dan berwawasan luas (‘alim). Dua karakter yang dibutuhkan bangsa Mesir agar keluar dari krisis pangan berkepanjangan.
Ibn ‘Asyur dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir mengulas Surat Yusuf [12]: 54 sebagai berikut: Ayat ini merupakan landasan atas kewajiban mempromosikan diri sendiri untuk memimpin jabatan publik, jika meyakini bahwa tidak ada lagi orang lain yang patut menyandangnya.
Karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan bagian dari nasihat kepada umat; terutama jika dia diduga kuat termasuk orang yang lebih mengutamakan kemaslahatan publik (altruis) dibandingkan meraih manfaat pribadi (egois). Sesungguhnya Nabi Yusuf AS meyakini bahwa beliau adalah orang yang paling pantas menyandang jabatan itu, karena beliau merupakan satu-satunya orang mukmin di tempat tersebut”.
Di luar batas wajar, ambisi meraih kekuasaan tidak dapat ditoleransi. Misalnya, Abu Dzar RA pernah meminta suatu jabatan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda: “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jabatan itu amanah. Sesungguhnya jabatan itu merupakan kehinaan dan penyesalan di hari kiamat, kecuali bagi orang yang meraihnya dengan benar dan melaksanakan tanggung-jawab jabatannya” (H.R. Muslim).
Berdasarkan telaah Hadis tersebut, setidaknya ada tiga aspek yang menyebabkan ambisi meraih kekuasaan tidak dapat ditoleransi.
Pertama, tidak memiliki kompetensi yang relevan dan mumpuni. Kendati Abu Dzar RA adalah pribadi yang taat beragama, namun dipandang “lemah” oleh Rasulullah SAW dalam mengemban amanah jabatan. Salah satu alasannya, watak agamis itu cenderung terlalu jujur dan berbaik sangka kepada siapapun, seperti yang ditunjukkan Abu Musa al-Asy’ari sebagai wakil kubu Sayyidina ‘Ali RA dalam peristiwa tahkim; sedangkan dalam politik kekuasaan itu sarat siasat yang menuntut sikap diplomatis dan waspada, seperti watak politis yang ditunjukkan Amr ibn al-‘Ash sebagai wakil kelompok Mu’awiyah.
Kedua, meraih jabatan dengan cara yang batil. Terkait cara meraih jabatan, al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulumiddin mengemukakan satu cara yang dinilai haram dan dua cara yang dinilai mubah. Cara yang dinilai haram adalah meraih jabatan melalui pencitraan palsu (talbis), melalui perkataan maupun perbuatan. Misalnya, menampilkan citra ahli ibadah di depan publik, padahal faktanya malas ibadah di ruang privat. Termasuk cara yang haram adalah meraih jabatan dengan cara suap-menyuap (money politic) dan kampanye hitam (black campaign) dengan menyebar fitnah yang keji (hoax) tentang lawan politiknya.
Sedangkan cara pertama yang dinilai mubah adalah melalui pemaparan fakta positif. Misalnya, kisah Nabi Yusuf AS yang mengaku memiliki sifat hemat dan cermat (Q.S. Yusuf [12]: 55) dan faktanya memang demikian. Cara kedua yang dinilai mubah adalah melalui penyembunyian fakta negatif. Misalnya, saat berkampanye, calon legislatif tidak menginformasikan kasus korupsi yang menimpanya. Namun, jika dia berkampanye “anti korupsi”, padahal dia sendiri korupsi, maka inilah yang disebut pencitraan palsu (talbis).
Ketiga, tidak memenuhi tanggung-jawab amanah jabatan yang diemban. Misalnya, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan, terutama melalui aksi korupsi yang merugikan masyarakat. Inilah contoh sikap pemimpin yang dikecam Rasulullah SAW, “Setiap pemimpin yang menguasai urusan umat muslim, lalu meninggal dunia dalam keadaan menipu umat muslim, maka Allah mengharamkan surga baginya” (H.R. Bukhari).
Tulisan ini menggarisbawahi bahwa batas wajar ambisi kekuasaan yang ditoleransi adalah kekuasaan yang diperoleh dengan cara-cara yang diperkenankan syariat Islam; dilandasi kompetensi yang relevan dan mumpuni untuk memikul amanah kekuasaan; serta memanfaatkan kekuasaan untuk kemaslahatan publik, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan; sesuai Kaidah Fikih, Tasharruf al-Imam Manuth bi al-Mashlahah; Kebijakan Pemimpin itu Berdasarkan Kemaslahatan Publik. Jika yang terjadi sebaliknya, maka ambisi kekuasaan dinilai melampaui batas wajar, sehingga tidak dapat ditoleransi.
Harapannya, paparan di atas dapat dijadikan sebagai alternatif pertimbangan untuk menentukan pilihan calon legislatif dan eksekutif dalam pemilu. Setelah itu, siapapun yang terpilih, tidak perlu sakit hati, karena kekuasaan merupakan hak “prerogatif” Allah SWT yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya.
Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 26).
Foto: http://ranahriau.com/berita-2475-politik-dan-kekuasaan.html