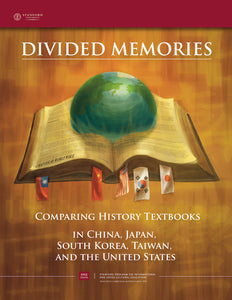Bayangkan sebuah rumah terbakar di tengah malam. Tak ada saksi, tak ada laporan polisi, dan tak ada sidang pengadilan. Tapi puing-puing hangus, bau asap, dan jeritan yang tertinggal di udara adalah bukti bahwa tragedi itu nyata.
Menolak keberadaan api hanya karena tak ada surat resmi yang menyatakan rumah itu terbakar adalah bentuk penyangkalan yang absurd—dan itulah logika yang kini dipakai untuk membungkam sejarah.
Ketika ARAH menyebut pernyataan Ribka Tjiptaning sebagai hoaks karena “tak ada putusan pengadilan” yang menyatakan Soeharto bersalah, kita sedang menyaksikan bentuk klasik dari kesesatan berpikir: Argumentum ad Ignorantiam.
Logika ini menganggap bahwa ketiadaan bukti formal adalah bukti bahwa sesuatu tidak pernah terjadi. Padahal, dalam konteks sejarah, ketiadaan putusan justru bisa menjadi bukti bahwa mekanisme hukum telah gagal.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang seharusnya menjadi ruang pengungkapan sejarah, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Alasannya? UU KKR dianggap mengabaikan keadilan korban karena mengaitkan kompensasi dengan amnesti pelaku.
Maka, menuntut bukti hukum atas tragedi yang tak pernah diberi forum adalah seperti menyalahkan korban karena tak punya akta kematian.
Laporan Komnas HAM tahun 2012 menyebut sembilan bentuk pelanggaran HAM berat yang sistematis dan meluas pasca-1965, dengan korban jiwa diperkirakan mencapai 500 ribu hingga 3 juta orang.
Ini bukan sekadar opini, melainkan dokumen negara yang bersifat pro justicia. Tapi di era post-truth, fakta seperti ini justru dianggap “menyesatkan” karena bertabrakan dengan emosi kolektif yang telah direkayasa selama puluhan tahun.
Sejarah kita seperti cermin retak. Kita hanya melihat potongan-potongan yang nyaman bagi kita, dan menolak bagian yang mengganggu. Ketika seseorang mencoba menyatukan pecahan itu, ia dituduh menyebar kebencian. Padahal, yang ia lakukan hanyalah menunjukkan bahwa cermin kita selama ini tidak utuh.
Retorika Ribka dan Tanggung Jawab Komando
Apakah pernyataan Ribka terlalu simplistis? Tentu. Tapi ia bukan sedang menulis disertasi, melainkan menyuarakan counter-narrative terhadap hegemoni sejarah. Retorika “pembunuh jutaan rakyat” adalah metonimi: menyebut Soeharto sebagai simbol institusi yang ia pimpin. Seperti menyebut “Istana” untuk merujuk pada pemerintah, atau “Hollywood” untuk industri film.
Komnas HAM menunjuk Kopkamtib sebagai pelaku pelanggaran HAM, dan Kopkamtib berada langsung di bawah komando Presiden Soeharto. Ini bukan soal opini, tapi soal tanggung jawab komando.
Dalam hukum internasional, seorang pemimpin bertanggung jawab atas tindakan bawahannya jika ia tahu dan membiarkan hal itu terjadi. Seperti kapten kapal yang tetap bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal, meski ia tidak memegang kemudi saat badai datang.
Selama 32 tahun, publik dicekoki narasi tunggal seperti film G30S/PKI. Narasi ini seperti soundtrack yang diputar berulang-ulang hingga kita lupa bahwa ada lagu lain yang tak pernah diputar. Pernyataan Ribka, meski kasar, berfungsi sebagai pemecah kebekuan narasi. Ia mengganggu kenyamanan yang dibangun dari pengulangan.
Ironisnya, yang dianggap “menyesatkan” bukan manipulasi sejarah, tapi justru upaya mengingatkan bahwa sejarah kita belum selesai. Ini seperti menyalahkan jam alarm karena membangunkan kita dari tidur panjang.
Dan ketika ARAH menyebut pernyataan Ribka “harus dilaporkan karena menyesatkan publik”, kita melihat bentuk lain dari kesesatan berpikir: Appeal to Consequences. Kebenaran tidak ditentukan oleh dampak sosial atau emosional yang ditimbulkannya. Fakta tetap fakta, meski membuat kita tidak nyaman.
Pahlawan, Pelanggar, dan Sejarah yang Dewasa
Gelar pahlawan sering dijadikan pengalih perhatian. Publik dipaksa memilih: Soeharto pahlawan atau pelanggar HAM. Padahal, tokoh sejarah bisa menjadi keduanya. Menyangkal salah satunya adalah bentuk whitewashing sejarah—seperti melukis ulang mural sejarah dengan warna yang hanya kita sukai.
Sejarah bukan album foto keluarga yang hanya menampilkan momen bahagia. Ia juga berisi luka, kehilangan, dan keputusan yang keliru. Menjadi bangsa yang dewasa berarti mampu menatap sejarah dengan dua mata: satu untuk prestasi, satu untuk luka.
Solusinya bukan pidana, tapi rekonsiliasi. Negara harus menghidupkan kembali KKR dengan mandat baru: mengungkap kebenaran dan memulihkan hak korban, bukan menukar amnesti dengan diam. KKR yang dulu gagal karena terlalu mirip pasar tawar-menawar: korban diberi kompensasi jika pelaku diberi amnesti. Padahal, keadilan bukan transaksi. Ia adalah pengakuan bahwa luka itu nyata dan layak disembuhkan.
Di sisi pendidikan, kita harus berhenti menghafal sejarah dan mulai mengajarkan siswa untuk berpikir kritis. Bayangkan kelas sejarah sebagai laboratorium pemikiran, bukan museum narasi tunggal. Siswa harus diberi dua dokumen yang bertentangan—misalnya Laporan Komnas HAM dan narasi Orde Baru—lalu diajak bertanya: mengapa dua versi ini ada? Siapa yang menulisnya? Untuk siapa?
Sejarah yang dewasa bukan sejarah yang bersih, tapi sejarah yang berani mengakui luka. Ia seperti pohon tua yang tetap berdiri meski batangnya penuh bekas luka. Justru dari luka itulah kita belajar bertahan, tumbuh, dan tidak mengulang kesalahan.