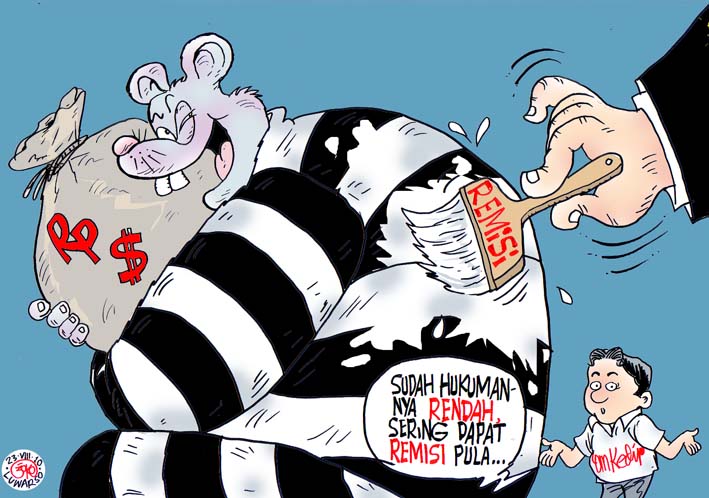Bagi pegiat gerakan anti korupsi, penetapan 41 orang anggota DPRD Kota Malang oleh KPK tidak terlalu mengagetkan. Lahirnya Malang Corruption Watch (MCW) tahun 1999 bukan tanpa alasan.
Konfigurasi politik dan tampilnya politisi yang tuna moral memaksa para pegiat gerakan masyarakat sipil untuk tampil melakukan pendidikan politik kepada warga. Korupsi adalah monster yang sangat berbahaya, menjadi lintah yang menggerogoti uang rakyat dengan dalih memperjuangkan hak-hak rakyat. Ini menjadi slogan yang kerap kita dengar dari elit politik negeri ini. Salah satunya anggota DPRD Kota Malang.
Saya yang pernah menjadi bagian dari MCW tidak terlalu kaget saat KPK menciduk para anggota DPRD karena berjamaah melakukan korupsi.
Tentu menjadi renungan kita semua. Kota Malang yang dikenal Kota Industri, Parawisata dan Pendidikan (TRIBINA CITA) menjadi sarang empuk dan nyaman bagi politisi yang memiliki perangai korup.
Tengok saja misalnya penetapan tersangka kasus korupsi yang melibatkan Sri Rahayu (Yayuk) Ketua DPRD tahun 1999-2004 yang divonis 1 tahun 6 bulan lantaran melakukan korupsi APBD 2,1 miliar oleh pengadilan Negeri Malang (newsdetik.com.18/10/05).
Meskipun Kota Malang bukan satu-satunya daerah di mana DPRD-nya ditetapkan secara massal oleh KPK, misalnya Sumatra Utara dengan 38 DPRD yang tersandung kasus korupsi.
Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apa peran dan komitmen perguruan tinggi terhadap pemberantasan korupsi? Bukankah perguruan tinggi hadir sebagai laboratorium untuk melahirkan peradaban dan keadaban, di manakah mahasiswa dan para aktivis mahasiswa sebagai garda depan dalam melakukan perubahan dan kontrol sosial? Ataukah iklim Malang yang dingin sedingin nyalinya untuk mengutuk kemungkaran sosial.
Semoga dugaan saya keliru, perguruan tinggi tak hanya sibuk berkhotbah kepada mahasiswa bahwa ukuran mahasiswa yang baik dan cerdas adalah mahasiswa yang rajin kuliah, cepat lulus sehingga menjadi sarjana dan cepat mendapatkan pekerjaan, atau sibuk dan larut dengan tuntutan borang di mana akhirnya abai terhadap kemungkaran sosial yang ada di sekitarnya
Pun begitu juga dengan mahasiswa, kelas intelektual yang seringkali mendeklarasikan diri sebagai agen perubahan sosial. Tulisan Eko Prasteyo dalam buku Bangkitlah Gerakan Mahasiswa (2015) terbitan Intrans Publishing dalam lembar pertama menjadi cemeti agar gerakan dan daya ktritis mahasiswa tidak padam.
Eko sengaja menampilkan kata-kata di lembar pertama bukunya yang berbunyi “ kau ingin jadi apa? Pengacara,untuk mempertahankan hukum kaum kaya yang secara inheren tidak adil? Dokter? untuk menjaga kesehatan kaum kaya, dan menganjurkan makanan yang sehat, udara yang baik, dan waktu istirahat kepada mereka yang memangsa kaum miskin? Arsitek untuk membangun rumah nyaman untuk tuan tanah ?lihatlah di sekelilingmu dan periksa hati nuranimu. Apa kau tak mengerti bahwa tugasmu adalah sangat berbeda: untuk bersekutu dengan kaum tertindas , dan bekerja untuk menghancurkan sistem yang kejam ini ( Victor Serge Bolshevik)
Sungguh menggetarkan kutipan Eko yang ditempatkan dalam lembar pertama buku itu. Bagi mahasiswa yang berjibaku dengan tumpukan tugas rutin kuliah tetapi masih meluangkan waktu untuk menghibahkan sebagian waktunya untuk terlibat dalam organisasi kemahawasiswaan, hal itu menjadi tugas mulya. T
ak hanya itu, berorganisasi tak hanya melakukan rekruitmen kader sebanyak-banyaknya sampai kadang bermusuhan antar organisasi ekstra kampus (omeks) lantaran rebutan kader. Dan pada gilirannya sibuk dan terlelap dengan rutinitas pengkaderan meminjam istilah Mansour Fakih menjadi buruh organisasi.
Tetapi tumpul melihat realitas sosial yang menindas. Bagaimana mungkin mahasiswa memiliki daya kritis dan sensitif terhadap realitas sosial politik yang semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, jika hanya sibuk dengan membaca media sosial yang tidak dibarengi dengan literatur yang memadai seperti buku. Realitas inilah yang menjadi keperihatinan kita.
Dua variable penting di atas antara perguruan tinggi dan mahasiswa seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keterilbatan perguruan tinggi untuk lantang menyuarakan nilai-nilai moral dan peradaban dalam ruang publik menjadi niscaya.
Organisasi mahasiswa tumbuh sebagai lumbung moral untuk meneriakan kebenaran dan protes sosial manakala ada persoalan sosial yang dinilai merugikan rakyat, seperti korupsi. Tentu perguruan tinggi ikut mensuport keberadaan mahasiswa yang tumbuh dan menyebar di berbagai organisasi ekstra kampus untuk mengasah dan mempertajam mata batinnya, bukan dibungkam.
Publik memahami, Kota Malang menjadi tumpuan banyak orang dalam pemberantasan korupsi. Karena di Malang ada kampus swasta seperti Muhammadiyah dan Unisma. Keduanya menjadi representasi kedua organisasi sosial keagamaan di republik ini. Tahun 2010 Muhammadiyah dan NU menerbitkan sebuah buku yang ditulis dan dikerjakan bersama oleh Muhammadiyah dan NU.
Buku yang diterbitkan oleh Mizan itu berjudul “ Koruptor itu Kafir, telaah fiqih korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Kita mengapresiasi dengan terbitnya buku itu. Tetapi kurang bermakna jika buku itu tidak dijadikan rujukan utama bagi para intelektual kampus yang ada di Muhammadiyah dan Unisma agar spirit pemberantasan korupsi lahir dari kedua kampus itu. Jika tidak, maka buku itu hanya dipajang sebagai aksesoris dalam rak perpustakaan kampus.
Sejatinya, Kota Malang sebagai kota pendidikan menjadi contoh pelayanan publik yang baik bagi daerah lain yang jauh dari kampus. Selain kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan UIN Malang, dan beberapa kampus yang ada di Malang. Dengan demikian berapa ribu bahkan juta mahasiswa yang ada di Malang, berapa kaum intelektual yang berserak di Kota Malang.
Lantas adakah korelasi positif dengan banyaknya kaum intelektual di Malang dengan pelayanan publik yang baik bagi warga Malang. Adakah implikasi bahwa dengan berjubelnya intelektual di Malang mampu melahirkan elit politik semakin beradab atau justru sebaliknya? Atau keberadaan kaum intelektual justru semakin menumbuh suburkan pragmatisme politik yang bermuara pada maraknya korupsi.