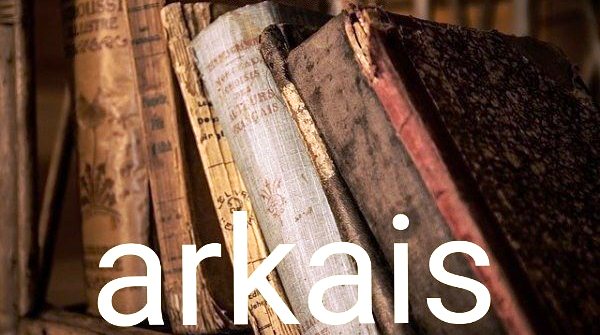Salah satu kesenangan membaca adalah tatkala menemukan diksi-diksi ”baru”. Kata baru mesti diberi kutip karena bisa jadi memang bukan definisi baru yang sebenarnya. Yang berarti anyar; belum ada sebelumnya; belum lama ada; segar.
”Baru” di sini juga bisa dimaksudkan sebagai diksi yang sudah lama ada, tapi otak kita baru sempat mendaftarnya. Di kitab besar panduan para penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemudian muncul istilah ragam klasik dan ragam arkais.
Secara lebih kafi, di KBBI ada lima ragam bahasa. Di samping klasik dan arkais, terdapat ragam hormat, cakapan, dan kasar. Walakin, tulisan ini sedang fokus pada perbincangan ragam klasik dan arkais. Ketiga lainnya dibahas kapan-kapan saja. Kalau sempat dan ada waktu.
Baiklah! Di tengah dunia literasi yang sedang disetel kenceng-kencengnya di ibu pertiwi ini, baik oleh independen maupun negara, tak heran kalau dua ragam kata di atas menduduki posisi penting. Menurut KBBI, ragam klasik dimaknai sebagai ragam kata tradisional yang memiliki keindahan. Juga merupakan kata yang digunakan dalam kesusastraan Melayu Klasik. Sedangkan ragam arkais, masih dari sumber yang sama, berarti kata yang tidak lazim dipakai lagi.
Paling tidak ada dua alasan kenapa dua ragam kata itu perlu dibumikan kembali. Pertama, sudah jemu dengan ragam populer (hormat dan cakapan) yang kerap muncul. Kedua, kata klasik dan arkais itu sulit dicarikan padanan dalam ragam populer. Kalaupun ada bukan berupa kosakata, melainkan frasa (gabungan kata).
Saya sendiri sangat bahagia ketika membaca buku, dan terutama novel, yang di dalamnya terserak kata-kata yang tidak umum –dalam ukuran wawasan saya. Maka, referensi fardu saya adalah kitab KBBI. Mujurnya, penulis-penulis era kiwari sudah sangat baik dalam menyuguhkan tulisan-tulisan yang kaya diksi.
Contohlah, manakala kita sudah jenuh dengan kata berkuasa atau sewenang-wenang. Maka, kata klasik yang bisa menggantikan adalah adikara. Kelas kata ini adalah kata sifat (ajektif) sehingga bisa digunakan dalam kalimat berikut: Kepala desa itu bertindak adikara sehingga banyak rakyatnya yang menderita.
Di deretan vokal A juga masih banyak kata lainnya yang bisa dijadikan padanan dan yang saya cantumkan ini, walaupun klasik, sudah lazim digunakan: adun (elok; indah), ahmak (bodoh; kurang pikir); aksa (jauh); amsal (misal, umpama, contoh); anom (muda); arik/mengarik (raih/meraih, rengkuh/merengkuh), azmat (hebat, ramai sekali), dan masih banyak lainnya.
Kata bahari juga dapat digunakan manakala kata kuno dan dahulu kala sudah dianggap terlalu biasa. Bahari menunjukkan suatu zaman yang sudah lampau. Begitu pula kata bahtera, yang ternyata dalam KBBI dikategorikan klasik, untuk menyubstitusi kata kapal atau perahu. Lain bahtera dan bahari, lain lagi balairung. Balairung diperlukan karena tidak ada kata yang benar-benar mewadahi makna kata tersebut. Yaitu balai atau pendapa besar tempat raja dihadap rakyatnya. Namun, kalau pergi ke Universitas Indonesia (UI) maupun Universitas Gadjah Mada (UGM), misalnya, Saudara sudah pasti akan menjumpainya.
Nah, bentuk-bentuk klasik sebagaimana segelintir contoh di atas akan sangat berguna dalam dunia kepenulisan. Apalagi bagi penyair, novelis, cerpenis, esais, kolumnis, dan -is -is yang lain. Kemampuan memahami kosakata klasik ini akan berfaedah untuk kekayaan kata-kata atau struktur, di samping tentu saja konten yang tak kalah penting.
Andai Saudara ”agak malas” untuk membuka kamus, tesaurus, dan sejenisnya, saya akan ”berbaik hati” untuk membabarkan beberapa kata klasik sebagai padanan kata populer (ini bukan kata spesifik yang jarang digunakan dalam keseharian, misalnya kata apilan yaitu papan tebal untuk dinding pada haluan kapal atau untuk menempatkan meriam. Bukan! Itu sangat klasik dan jarang –atau malah tak pernah– digunakan juga).
Ada belasah yang bermakna pukul; bena yang bermakna acuh/peduli; bentala (bumi/tanah); bersewaka (melayani/menghamba); bestari (luas dalam pergaulan/pendidikan); bianglala (pelangi –kata ini identik dengan sastrawan D. Zawawi Imron). Sampai pada tertumus (tersungkur jatuh), utas (mahir/pandai), dan wirawan (pahlawan, gagah berani).
Bentuk klasik, barangkali, masih sering beredar dari satu buku ke buku lainnya. Tapi, bentuk arkais, sepertinya, cukup jarang menghiasi tulisan-tulisan saat ini. Kalaupun ada, pastilah penulisnya menguasai betul perbendaharaan diksi sehingga cakap menuliskannya. Atau, bisa jadi para penulis seperti ini juga punya misi serupa dengan saya: ”menghidupkan” kembali kata-kata arkais. Ragam arkais ini, di KBBI, ditukaskan sebagai bentuk yang tidak lazim digunakan. Tidak lazim berarti tidak umum atau tidak biasa digunakan. Akan tetapi, di dunia karya sastra, terutama, justru kata yang tak lazim ini mengasyikkan dan menantang.
Beberapa waktu lalu saya menemukan kalimat ini: Satu hal lagi, yang menjadikan buku ini sangat pantas untuk dikoleksi adalah keunikan dan keindahan desain sampulnya yang bisa membuat kita menjura takzim kepada si perancang: Teguh Sabit. Itu saya dapat ketika sedang mendaras ulasan seseorang pada novel yang tengah menjadi perbincangan luas, Kura-Kura Berjanggut (Azhari Aiyub). Saya menjumpai kata menjura. Kata ini, secara jujur, belum saya mengerti –karena keterbatasan pandangan dan minimnya perbendaharaan kata saya.
Terang saja saya bergegas mencari di kitab KBBI dan menemukan bahwa menjura memiliki makna membungkuk dengan menangkupkan kedua tangan (dengan maksud menghormat). Bentuk seperti inilah yang saya maksud dengan kata yang sukar dicarikan padanan dalam bentuk lazim. Dan terima kasih saya haturkan kepada mereka yang telah memberi ”nyawa” untuk kata-kata arkais ini.
Jika kita, lagi-lagi, sudah bosan dengan kata kekal atau abadi, bolehlah kiranya kata abid digunakan. Kata yang dalam makna lainnya berarti beribadah. Adicita juga bisa digunakan manakala kata ideologi sudah demikian menjamur. Begitu juga kata afsun (pesona), ajun/terajun (tertinggal jauh/terlambat), akil (berakal/cerdik), anggara (buas/liar), dan bagal (terlampau besar/kuat).
Berikut satu huruf diwakili satu-dua kata (dipilih yang punya kemungkinan besar digunakan sehari-hari): bujut (kusut); ceku (tekan); dangka (sangka, duga, kira); efendi (tuan, sebutan kepada orang yang dihormati); getis (mudah patah, getas); halim (lemah lembut); intikad (kritik, sanggahan); jelah (terang, jernis).
Lalu ada kambus/terkambus (tertimbun oleh pasir); kirana (elok, cantik); labas (habis sama sekali); lenggana (enggan, tak sudi); meloka (melihat); mungut (tertatih-tatih; terhuyung); nyenyat (sunyi); peresih (putih bersih); ranyah (gelisah); dan syur (menarik hati –kata ini sering dikonotasikan negatif, padahal maknanya netral).
Kemudian ada taki (berdebat); umbang (tampak besar dan menakutkan); wiweka (sangat berhati-hati); wiyata (pengajaran); dan zamin (tanah, negeri).
Tugas berikutnya, dari mana ragam klasik dan terutama arkais itu muncul? Sang empunya, KBBI, belum sampai pada penjelasan asal usul kata. Tapi, suatu ketika, di sebuah forum, saya lamat-lamat mendengar bahwa pihak Balai Bahasa akan berupaya menyusun kembali kamus yang lengkap dengan asal usul lemanya. Kita tunggu saja!