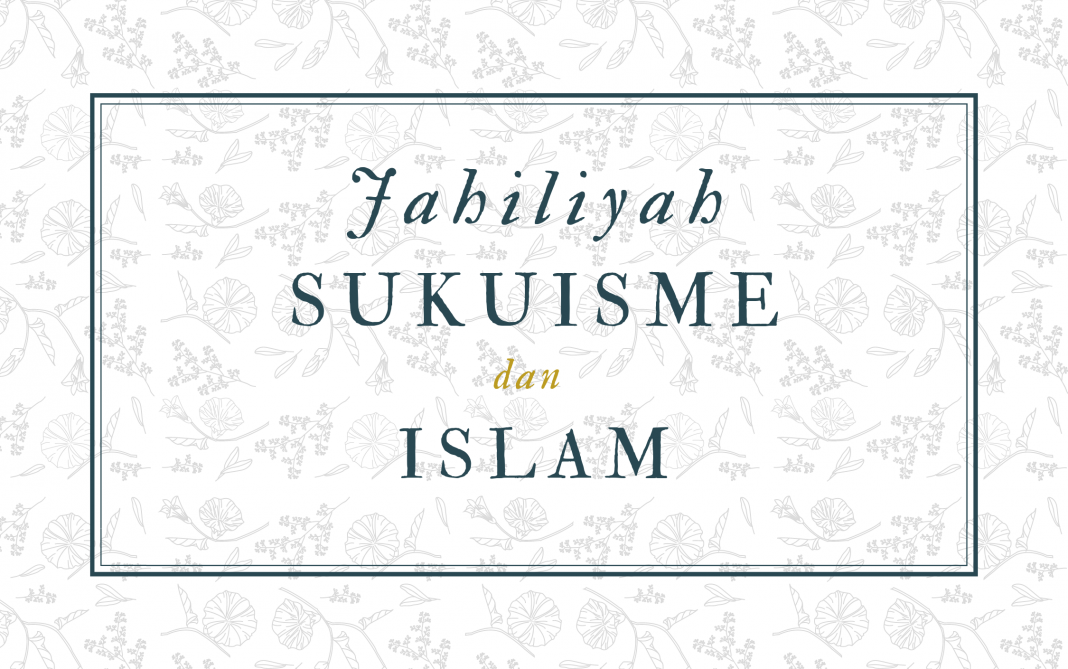Etika Kesukuan
Tradisi kesarjanaan Islam mengenali masyarakat Arab pra-Islam sebagai jahiliyah. Dari sudut pandang teologis, karakteristik dasar dari masyarakat jahiliyah adalah kepercayaan paganistik. Mereka melakukan penyembahan dan penyandaran hidup kepada beragam tuhan personal yang turut dibentuk personifikasinya dalam wujud patung dan pahatan. Namun dari sudut pandang sosiologis dapat dilihat bahwa secara esensial karakteristik jahiliyah adalah perihidup sukuisme (tribalism).
Kehidupan di gurun pasir Arab yang gersang dan cadas begitu keras dan kulit untuk dilakoni, sehingga jalan terbaik untuk bisa mempertahankan hidup adalah dengan saling tergabung dalam suku-suku. Kondisi geografis ini mendorong terciptanya pandangan sosiologis yang khas bagi dunia Arab dan peradaban Timur Tengah pramodern. Mereka membina kehidupannya di dalam banyak sekali suku, qabilah, dan bani.
Ketergantungan pada suku menciptakan satu ekses besar: hilangnya kemandirian dan kemuliaan individu. Tradisi jahiliyah ini mengajarkan bahwa seseorang dapat menjadi mulia apabila ia mengorbankan diri kepada suku, namun tidak sebaliknya. Menurut pandangan kuno ini, suku tidak membutuhkan individu, karena ia adalah satu-satunya harapan yang setiap individu miliki untuk bertahan hidup.
Semua ini menciptakan sebuah etika sosial yang jelas. Individu diperintahkan untuk mengorbankan apa pun yang ia miliki demi kelestarian sukunya. Kita bisa melihat dengan jelas etika pengorbanan ini dalam kebiasaan perang mereka. Peperangan menjadi penentu punah atau lestarinya eksistensi sebuah suku.
Semua aktivitas dan tradisi sukuisme ini membuat orang-orang yang hidup di dalamnya memandang perang sebagai sebuah kemestian alam. Mereka mempercayai bahwa selama dunia masih berputar dengan siang dan malamnya, maka selama itu pula perang tidak bisa dihindari. Dan sebagai konsekuensi tradisi mereka ini, masyarakat terjebak untuk bergantung pada maskulinitas. Otot dan fisik berada di hierarki teratas kehormatan. Sebagai pemasok otot dan keringat bagi suku-suku yang berperang, kaum lelaki dianggap lebih bernilai daripada kaum perempuan.
Ekonomi Kesukuan
Ekonomi dengan demikian berjalan melalui sistem penyerahan upeti kepada tetua-tetua suku. Mereka membiarkan kekayaan berputar hanya di antara keluarga-keluarga utama yang memimpin suku-suku.
Konsentrasi absolut kekayaan ini membuat keluarga-keluarga miskin semakin bergantung pada petinggi suku. Dengan cara yang sangat efektif, ekonomi membuat sukuisme dan perang tampak semakin niscaya, alami, dan mustahil dibongkar.
Dengan perekonomian yang menjamin kelestarian suku-suku tersebut, maka kemiskinan juga dipandang sebagai nasib yang sudah ditentukan sejak dari alam arwah. Tidak ada kemungkinan untuk sebuah keluarga miskin keluar dari jeratan kemiskinannya.
Ekonomi jahiliyah juga memberikan ruang yang besar untuk pertumbuhan pemujaan atas maskulinitas. Sementara kaum lelaki dihargai karena mereka dapat berfungsi dalam ekonomi ini, anak-anak perempuan yang terlahir akan menjadi pertanda kemiskinan dan kehinaan bagi orangtua mereka.
Kehidupan jahiliyah Arab tidak memungkinkan bagi individu dan kelompok marginal –budak, fakir, dan perempuan– untuk meningkatkan kualitas hidupnya, secara politik maupun ekonomi.
Hukum Kesukuan
Dan begitu pun secara hukum, kehidupan jahiliyah tidak memberi hak-hak kesetaraan bagi semua individu. Rasa keadilan jahiliyah saat itu tertulis dalam ajaran mata dibalas mata, dan nyawa dibalas nyawa, tidak peduli itu mata siapa atau nyawa siapa. Selama suku dapat dibela, hukum tidak akan memperhatikan individu mana yang harus dikorbankan.
Akibat dari persepsi hukum, ekonomi, politik, dan sosial yang seperti itu, kesetiaan seorang manusia kepada suku adalah nilai tertinggi yang bisa ia miliki. Apabila terjadi sengketa dan perang antara dua suku, maka adalah suatu ketabuan apabila kita membela pihak suku yang dizalimi, jika yang menzalimi berasal dari suku tempat kita berasal.
Etika jahiliyah ini terpatri paling kuat dalam ajaran yang memerintahkan untuk membela saudara sesuku, entah ia itu dizalimi, atau pun menzalimi.
Dalam kondisi irasionalitas seperti itulah Muhammad mengintrodusir Islam kepada masyarakatnya. Segala hal yang tidak mengindahkan hak-hak individu dan kaum minoritas yang telah membudaya selama berabad-abad, ditantang secara terbuka oleh Islam.
Tantangan Islam terhadap sistem kesukuan yang mendominasi kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat Arab kala itu, menjadi alasan paling masuk akal yang menjelaskan mengapa kaum budak, wanita, dan minoritas yang termarjinalkan adalah segmen-segmen masyarakat yang paling terdorong dan termotivasi untuk bergabung dengan Islam.
Bagi kita yang hidup setelah tak ada lagi perbudakan, narasi emansipasi Islam terdengar biasa saja. Tapi, bagi kaum termarginalkan saat itu, Islam adalah harapan satu-satunya.
Teologi Kesukuan
Kita telah berbicara tentang kondisi geografis yang sulit dan mendorong masyarakat jahiliyah Arab untuk menggantungkan nasibnya pada suku-suku. Akan tetapi, di samping alasan geografis ini, ada pula alasan teologis yang mendorong mereka untuk merasa tidak mampu berdiri sendiri menghadapi kerasnya kehidupan padang pasir.
Mereka tidak memiliki satu Tuhan yang benar-benar dapat dipercaya untuk membantu kehidupan mereka. Terutama individu-individu yang terhimpit dan termarginalkan, mereka tidak menemukan Tuhan yang maha kuasa dalam sistem kepercayaan Arab saat itu.
Setiap suku dan setiap rumah bergantung pada tuhan-tuhan yang berbeda. Tuhan milik keluarga penguasa dan suku penguasa tentu saja adalah tuhan yang paling bertenaga, jauh lebih berkuasa daripada tuhan orang-orang biasa.
Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada tuhan yang benar-benar “Tuhan”, yang menjadi pengadil atas semua orang, yang setiap saat bisa dimintai pertolongan dan keadilannya. Tidak adanya satu Tuhan yang akan mengadili semua orang secara sama rata juga berarti tidak ada pula arena pengadilan yang maha adil.
Dalam sistem kepercayaan Islam yang dibawa oleh Muhammad, hari akhirat adalah juga hari pembalasan, tempat di mana keadilan akan benar-benar diputuskan hanya oleh Tuhan. Hanya saja, untuk saat itu, semua suku-suku Arab jahiliyah tidak sampai mampu menerima kepercayaan akan hari akhirat ini.
Mereka tidak ingin membuat dirinya takut akan pembalasan Tuhan di kehidupan setelah mati. Hal ini sebab mereka tahu bahwa apabila akhirat itu benar maka mereka akan memperoleh hukuman paling besar di sana, mengingat ratusan penindasan dan kezaliman yang mereka perbuat terhadap banyak orang di dunia.
Alasan dasar dari gagasan akan adanya kehidupan akhirat adalah kebutuhan manusia akan pengadilan yang paling adil. Gagasan ini dimajukan untuk membuat manusia percaya bahwa masih terdapat harapan memperoleh keadilan dari Tuhan. Disebabkan oleh ketidakadilan yang selalu saja manusia alami di dunia ini, mereka pun mulai menggantungkan harapan pada keadilan setelah mati.
***
Dengan penjelasan ringkas di atas, saya ketengahkan fenomena Islam sebagai antitesa historis atas irasionalitas sukuisme Jahiliyah saat itu. Bagi kita, Muslim modern di Indonesia, rasionalitas dan humanisme berbasis Islam akan menjadi sumber energi untuk aktivitas kita yang lebih baik.