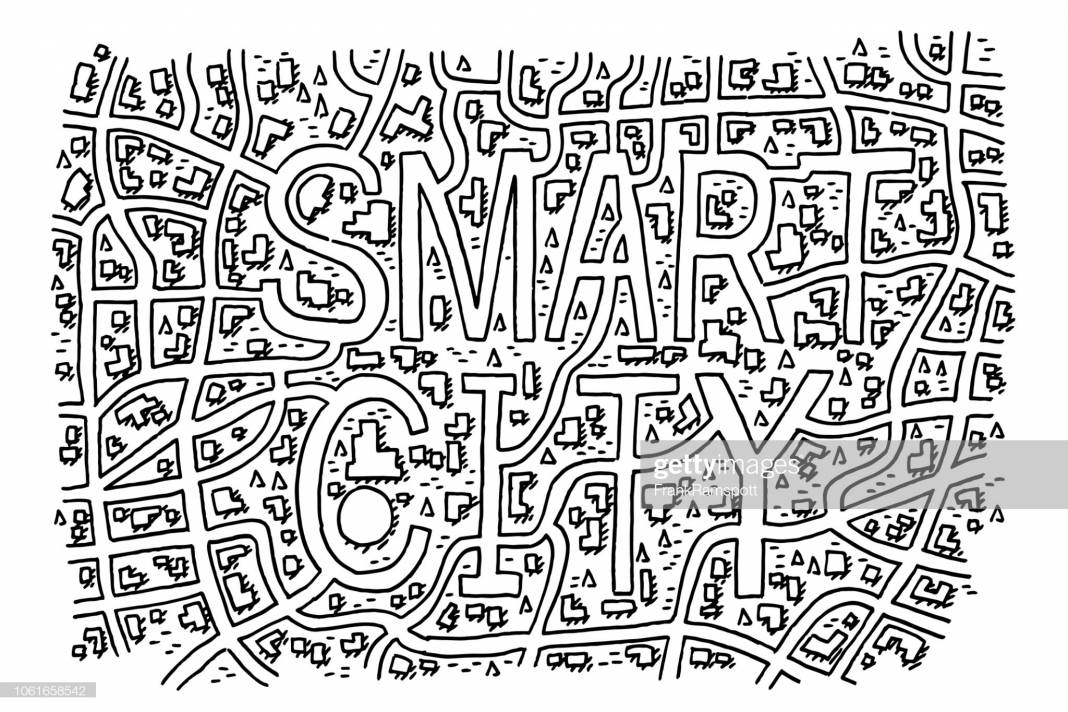Meski fase sedang hangat-hangatnya sudah berlalu. Tapi saya kira ini waktu yang paling tepat untuk mengajukan pertanyaan tentang, adakah hal-hal berubah ketika kota menjadi pintar?
Saya rasa hari-hari masih saja sama, kita hampir mati tercekik dinding kota yang jaraknya tak sampai sedepa satu dengan yang lain atau bahkan tanpa jarak. Lihatlah, ruko-ruko tumbuh memenuhi semua sisi jalan utama kota.
Meski, memang ada kompleks-kompleks perumahan dengan jalan-jalan yang disertai taman, atau juga tempat ibadah yang megah dan di pintu masuk berdiri gapura mewah disertai satpam yang berjaga sepanjang waktu.
Menjadikan muskil bagi warga kota yang biasa-biasa saja dengan uang pas-pasan, atau bahkan untuk membeli makan saja mesti pikir-pikir dulu untuk tinggal dan menikmati ruang urban yang begini lapang, aman dan ekslusif tentu saja.
Tetapi maha baik pemerintah, diliputi banyak siasat agar supaya yang terhitung miskin mempunyai rumah tinggal sebagaimana warga kota lainnya, maka dibuatlah satu skema yang disebut dengan perumahan subsidi.
Perumahan ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sebagaimana peruntukkanya, rumah bagi yang berpendapatan rendah ini seringkali tampak rentan.
Luasan tanah begitu terbatas, tanpa dapur, dibangun berderet hingga delapan rumah dan secara otomotis tidak akan ada jendela di samping kiri dan kanan, dengan sisa halaman berkisar 2 hingga 3 meter pada bagian depan-belakang.
Melihat kenyataan ini sembari mengimajinasikan 4 orang—Ayah, Ibu, dan Dua orang Anak—sebagai tipe keluarga ideal Indonesia mesti hidup berdesakan di dalamnya membuatku seringkali megap-megap kesulitan bernapas, begini rupakah stratifikasi ruang tinggal kita hari ini.
Soal kesesakan ruang (crowding) seperti yang tersirat dalam narasi di atas barulah satu dari sekian yang tidak terurai dalam menyoal kota pintar sebagai salah satu label yang dikejar-kejar oleh berbagai pemerintah agar terlihat canggih, maju dan keren.
Padahal inilah di antara soal mendasar yang dihadapi kota belakangan, kepadatan (density), kemacetan (congestion), kriminalitas dan berbagai isu lainnya direduksi menjadi perihal tekhnologi dengan berlomba menjadi kota pintar.
Seperti melakukan digitalisasi, atau berfokus pada penciptaan aplikasi online berbasis smartphone, misalnya. Secara prinsipal hal seperti ini untuk kasus kota-kota Indonesia tampaknya belum mampu mengurai kompleksitas persoalan kota terutama masalaah keseharian yang sifatnya strukturalis.
Kota pintar sederhananya dapat dimaknai sebagai kota yang diusahakan untuk terdigitalisasi melalui pengintegrasian teknologi informasi dan komonukasi atau penerapan Internet of Things (IoT) dalam berbagai macam pengelolaan demi efesiensi pelayanan publik.
Berangkat dari defenisi semacam inilah mengapa kota pintar bahkan di negara yang memproduksi teknologi canggih sekalipun tetap menuai kritik sebab lahinrya sisi pengawasan yang terlalu, privacy menjadi rentan, dan terutama smart city berkelindang dengan sistem yang sangat kapitalistik. Dalam hal ini sepenunya ditundukkan oleh modal, segelintir pemilik industri yang yang menguasai kemajuan teknologi.
Di Indonesia, kota pintar mendorong beberapa kerja yang tadinya dioperasionalkan melalui tubuh manusia kini digantikan oleh mesin. Smart city tidak lebih dari sekedar gimmick dalam membranding kota dan tentu juga Sang wali kota.
Sebab pertanyaan mendasar tentang berubakah wajah kota secara berarti ketika ia telah dinobatan sebagai kota pintar? Jawabanya sepertinya tidak juga. Malah pertanyaan berlipat tentang ke mana kini tubuh-tubuh yang tergantikan mesin ini pergi? Sehingga benarkah kota pintar dengan kata kunci “Technologi, Connecting, Smart, Big data dan lainnya” merupakan hal yang paling diinginkan dan dibutuhkan oleh warga kota saat ini.
Mengingat kota berurusan dengan soal manusia. Bahwasanya infrastruktur, bangunan kota dibentuk untuk melayani masyarakatnya. Lalu apa guna segala yang canggih-canggih dan modern itu jika tidak dapat dimanfaatkan, diakses oleh mayoritas penduduk kota itu sendiri. Sehingga merefleksikan apa “makna smart city” yang bergeliman tekhnologi bagi keberlanjutan kota dan kesejahteraan warga menjadi genting,.
Modernitas memang mempesona. Sebab itu dibutuhkan refleksi dan lebih banyak pertanyaan yang perlu diajukan tentang kota pintar. Mengingat sebuah prasa yang pernah diungkapkan oleh arsitektur inggris Cedric Price bahwa “Technology is the answer. But what is the question?”.
Nah, apakah kita telah mengajukan pertanyaan yang tepat, sehingga jawaban untuk megatasi kompleksitas kehidupan urban adalah “Smart City”. Siapa yang mengajukan pertanyaan dan siapa yang memberikan jawaban, penting untung ditelusuri. Saya kira warga kota yang was-was, hidup terlunta belum diberi kesempatan untuk terlibat dalam perbincangan semacam ini.
Smart city sejauh ini baru mampu dihidupi oleh smart citizen. Mereka yang punyai gawai dan duit. Inilah apologia kota pintar, mereka yang terekslusi dari kota sebab didahulukannya kecanggihan teknologi tidak pernah ditampakkan secara nyata. Namun pemerintah dengan bangga mengejar predikat kota pintar sebagai suatu kemajuan.
Tanpa peduli jikalau ada yang terdehumanisasi, terlempar jauh dari keseharaiannya, dan hidup terlunta tanpa kerja. Siapa peduli jikalau ini ilusi lebih menguntungkan dan memanjakaan mereka yang sedikit jumlahnya, punya kuasa dan melek teknologi agar supaya hidup lebih chill.