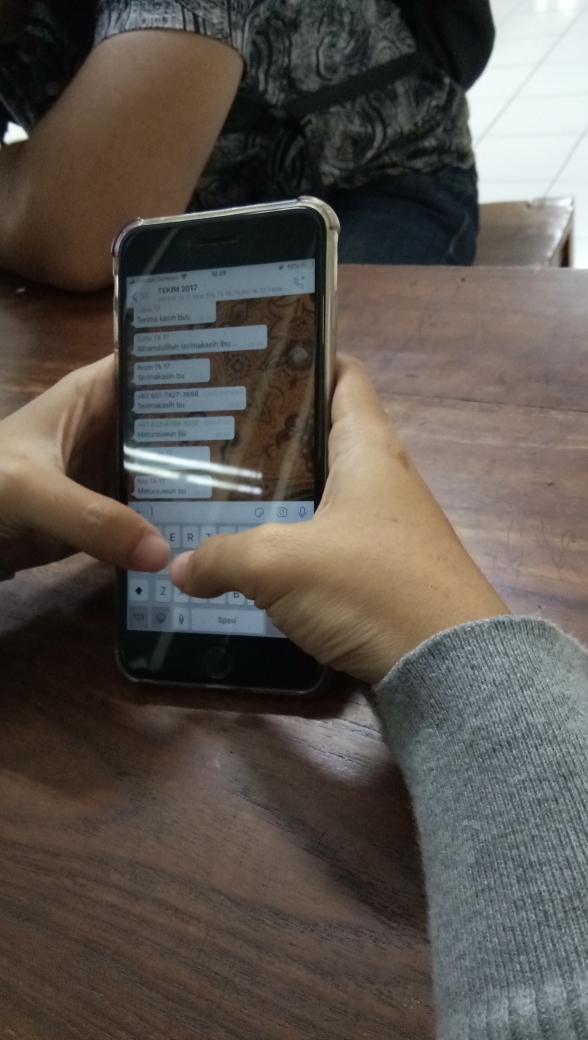Pada tanggal 21 Mei 2019 jelang pukul 23.00 WIB ketika saya hendak mengucapkan “selamat malam” dan “semoga mimpi indah” kepada kekasih di kota lain. Sekaligus menyampaikan “jangan lupa reformasi 1998” dengan cara berkirim pesan berformat video dan foto via WhatsApp. Tiba-tiba selang beberapa menit kemudian ponsel berdering keras memberitahukan sesuatu pesan tidak terkirim.
Seperti biasa periksa koneksi adalah perintah otomatis media bila ingin pesan terkirim. Pesan yang dikirim ulang juga tak kunjung berselancar setelah jaringan terkoneksi. Perasaan ini semakin khawatir jika malam itu tak tersampaikan kalimat sebelum tidur terhadap kekasih dalam hubungan jarak jauh.
Dapat dipastikan hubungan kita mengalami persoalan pelik selama beberapa hari berikutnya. Karena harus diakui komunikasi adalah interaksi penting dalam jalinan asmara kita. Keterhambatan media senyatanya menjadi biang kerok hubungan sosial retak seiring akses sulit terjangkau dari ruang.
Selain sentuhan media sosial melalui smartphone yang saya genggam untuk berkomunikasi jarak jauh ini. Apa lawan media sosial? Sebenarnya merupakan akumulasi pertanyaan seorang rekan kepada saya untuk menanggapi dominasi wacana yang diproduksi media. Meski yang dimaksud media adalah media mainstream seperti surat kabar atau portal berita online.
Tapi dalam perdebatannya mengenai sistem jaringan informasi. Media sendiri adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan. Sedangkan hubungan antar individu merupakan satu kesatuan sosial yang kompleks. Dengan seiring berjalannya waktu media mengalami transformasi teknologi yang dirancang oleh pembuatnya.
Sebagai alat berteknologi itu sendiri, media tidak bisa berorientasi pada tujuan melainkan terhadap aturan main (algoritma). Maka informasi yang beredar pun tersebar luas dalam jaringan-jaringan yang membentuk kelompok.
Oleh sebab itulah, jika media sosial (WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, dan Telegram) lebih memprioritaskan kebutuhan personal. Sedangkan media mainstream berupa surat kabar atau portal berita online (internet) lebih mengarusutamakan kepentingan publik.
Maka ketika ponsel sudah berada di genggaman tangan seseorang. Suatu pendapat secara ilmiah akan tergambar sesuai keinginan dan kepentingan seseorang dalam kerangka media sosial yang termanfaatkan.
Birokrasi Politik
Sewaktu kekasih saya marah-marah karena tidak mendapat ucapan romantis selama tanggal 21-22 Mei 2019. Pemerintah konon sedang gonjang-ganjing menghadapi kerusuhan pasca penghitungan Pilpres 2019 di depan Kantor Bawaslu. Melalui Kominfo pembatasan internet bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mencegah persebaran berita hoax diberlakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Beruntung kemudian akses internet segera normal sehingga hubungan jarak jauh saya dengan kekasih berlangsung membaik. Namun, persoalan media sosial tidak berhenti sampai disini saja.
Karena pemerintah dengan aturan pembatasan media sedang menciptakan legitimasi totalitarianisme. Maka birokrasi politik dengan tujuan, sasaran, dan perencanaan untuk percepatan pembangunan yang kondusif seringkali menjadi pameo perubahan sosial bagi pemerintah.
Pengalaman buruk birokrasi politik yang sedemikian rupa di Indonesia sempat terjadi. Saat Orde Baru menggerakkan birokratisasi politiknya dengan tangan besi dapat membredel surat-surat kabar yang kritis. Reformasi mengulang hal yang sama membatasi internet bagi komunikasi warga negara. Sesungguhnya, perubahan sosial itu sendiri tidak ada dalam birokrasi politik Indonesia dewasa ini (ilusi).
Mengingat kerusuhan terjadi bertepatan dengan reformasi yang menyejarah pada bulan Mei 1998. Pemerintah justru membungkam gagasan-gagasan dari pihak lawan dengan subversif.
Terbaca dengan pemerintahan Jokowi mengalami krisis legitimasi ke dalam, yang disebabkan usaha mencari kambing hitam dalam kepentingan kelompok dan golongan minoritas melalui birokrasi politik. Maka media sosial sebagai cikal bakal gerakan sosial akan menjadi senjata perubahan sosial itu sendiri bagi penguasa.
Membaca pesan penting reformasi Mei 1998 adalah perubahan struktur politik. Pemerintah tidak menjadikan kesempatan (kerusuhan) sebagai pembuktian terbalik dari peristiwa politik bersejarah itu.
Kenyataan pola yang digunakan justru berbanding lurus terhadap dalang kerusuhan Mei 1998 adalah negara. Maka pembatasan media sosial oleh pemerintah merupakan ingatan publik yang sesungguhnya dari perubahan sosial yang dikehendaki masyarakat dalam kehidupan bernegara.
Sebagaimana Roem Topatimasang memahami tentang gerakan sosial atau perubahan sosial mempunyai syarat pokok. Berubahnya struktur dan relasi kekuasaan merupakan syarat-syarat pokok ini. Dengan adanya fenomena media sosial dalam berbagai kasus politik. Ia menegaskan itu baru cikal bakal gerakan sosial pada tahap penggalangan opini dan melakukan solidaritas.
Sungguh pemerintah dengan pembatasan media sosial adalah bentuk perlawanan birokrasi politik terhadap kebebasan pendapat. Sedangkan tuntutan dan kebutuhan warga semakin hari semakin terdesak memenuhi ruang publik. Alasan kecepatan perubahan direspons serentak oleh media sosial. Maka pemerintah telah menggali kuburnya melawan kehendak masyarakat dari krisis legitimasi yang justru ia rekayasa sendiri.
Alkisah, bila saya ingin melanjutkan hubungan serius dengan kekasih ke jenjang pernikahan. Tak mungkin hanya mengandalkan media sosial saja sebagai perantara komunikasi kita.
Sebab, setelah itu aksi harus dilakukan orang secara langsung. Saya harus bertemu, bertatap muka, dan memohon restu kepada orang tua kekasih untuk meminang anaknya. Dengan demikian hal ini tidak mungkin dilakukan di dunia maya tapi di dunia nyata.
Dalam situasi beginilah, kerusuhan seperti tragedi Mei 1998 dan drama Pilpres 2019 tidak memerlukan informasi, data, dan fakta di lapangan. Sebab, pemerintah sendiri justru menutup akses dan ekses seluruh peristiwa politik yang terjadi.
Maka media sosial sebagai pemicu akan menggerakkan massa aksi bertumpah ruah di jalanan ibukota. Seperti halnya aksi politik 212 tidak menutup kemungkinan terulang kembali di kemudian hari. Begitu.