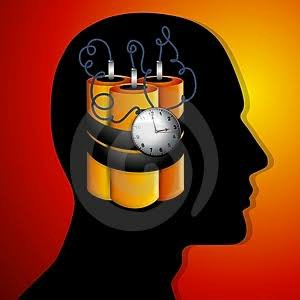Belajar Dari Aksara Bangsa Andes
Dua jam sebelum kabar pertama tentang bom di sebuah gereja di Surabaya (berikut di beberapa lokasi lain), saya menerima ledekan dari teman-teman kos, karena untuk jalan-jalan pagi pun saya menyambinya dengan membaca buku. Meski saya tersenyum karena ‘kemesraan manusia’ mereka, saya tidak bisa menahan sebuah pertanyaan serius yang mampir di kepala: “Asingkah mereka melihat orang yang menekuri buku?”
Ada akibat fatal dari ‘terasingnya manusia dari aksara’. Akibat itu membuat mata rantai bencana kemanusiaan menjadi langgeng. Berawal dari dangkalnya pengetahuan, yang berdampak pada dangkalnya nalar, dan bermuara pada dangkalnya kemanusiaan. Untuk melihatnya, mari kita menyimak sejenak sejarah aksara.
Adalah Bangsa Sumeria, antara 3500–3000 SM, yang menemukan ‘tulisan’ pertama di dunia. Waktu itu, aksara masih hanya berupa simbol-simbol sederhana yang ditulis dengan cara ‘menekan dan membuat bentuk tonjolan’ di sebuah lempeng lempung. Aksara itu diperlukan untuk urusan adminstrasi kerajaan, misalnya, untuk mencatat hasil pajak hingga urusan piutang. Sistem aksara untuk keperluan terbatas itu disebut sebagai “Aksara Terbatas”.
Kebalikannya disebut sistem “Aksara Penuh”, yakni sistem tanda material yang bisa melambangkan bahasa lisan secara—kurang lebih—sempurna. Bangsa Sumeria tidak mengembangkan Aksara Penuh karena kebudayaannya tidak memerlukan. Namun zaman berkembang: manusia didorong oleh hasrat mencipta yang besar. Manusia ingin menulis maklumat atau surat, hingga menggubah syair dan mencatat ramalan. Aksara Terbatas tidak bisa memenuhi kebutuhan ini. Aksara Penuh kemudian mulai dikembangkan.
Kontribusi besar aksara pun dimulai. Aksara penuh memungkinkan manusia mencatat berbagai informasi penting yang bisa diwariskan pada generasi setelahnya. Mencatat hal-hal yang pernah terjadi, untuk mengatas hal-hal yang akan terjadi. Entah itu data faktawi, entah itu pemikiran. Homo sapiens memulai perjalanan besar mendokumentasikan hal-hal yang penting bagi mereka.
Pertanyaannya adalah, apakah ada bangsa yang mempertahankan Aksara Terbatas, di tengah megahnya perkembangan peradaban manusia? Ada. Salah satunya adalah Bangsa Andes di Amerika Selatan, dengan sistem Aksara Terbatas yang bernama quipu. Bangsa Andes mengolah informasi lewat benang yang dipintal menjadi simbol-simbol. Itulah quipu. Dengan itu mereka menghitung dan mencatat data.
Namun, hari ini pengguna quipu sudah punah. Sistem aksara itu dihajar kolonialisme. Ketika Spanyol menaklukkan Amerika Selatan, Spanyol menggunakan orang-orang Andes untuk mengoperasikan quipu dan mengurus administrasi. Perlahan, kemudian, Spanyol mengganti quipu dengan bahasa latin. Akibatnya, sistem aksara Andes mati, dan mati pulalah kebudayaan mereka.
Poinnya adalah: Bangsa Andes ‘nyaman’ berada dalam kesederhanaan budaya, hingga mereka sadar sedang berhadapan dengan pihak serakah yang berkuasa, yang tega melakukan kekerasan fisik dan budaya. Bangsa Andes tidak memiliki catatan apapun tentang kejadian-kejadian penting di masa lampau, yang bisa mereka rujuk kala menghadapi situasi-situasi teror dan terjajah.
Mungkin mereka pernah punya pengalaman menghadapi “macam bentuk serangan” bangsa lain, namun mereka tidak pernah mencatatnya. Saat konflik terjadi, para sepuh bangsa mereka yang mungkin mengetahui itu dalam ingatan, mati satu per satu. Mereka hanya punya sistem Aksara Terbatas yang terbatas dalam mendokumentasikan pengalaman bangsa mereka. Mereka tidak punya sistem Aksara Penuh yang memungkinkan mereka belajar secara maksimal.
Apa yang ‘Aksara Penuh’ Indonesia Pernah Catat Tentang Teror
Bangsa Indonesia punya sistem Aksara Penuh, namun berasa seperti Aksara Terbatas. Aksara Penuh kita telah merekam beberapa kekacauan terorganisir dalam sejarah, tapi masih saja ‘rekaman’ itu tidak dirujuk dalam latah-latah kita kala mengecam tindakan teror.
Hampir semua kecaman dikaitkan dengan agama. Media (bersama aparat) mengkampanyekan slogan “Kami tidak takut” pada teror dan teroris. Pertanyaannya: siapa terorisnya? Framing itu mengarahkan kesadaran masyarakat bahwa teroris adalah individu atau kelompok kecil yang berinisiatif mengebom suatu tempat didorong oleh ideologi kekerasan dalam agama. Kenapa bukan “pihak tertentu yang berkepentingan secara politik dan ekonomi?” Kemungkinan itu kuat, tapi kesadaran kita digiring pada satu tafsir.
Saya pikir kita mesti belajar laporan Aksara Penuh kita tentang pengalaman bangsa Indonesia menghadapi kerusuhan: bahwa kerusuhan yang terorganisir di level mikro, hampir selalu, punya kaitan dengan kepentingan pihak tertentu di level makro. Pelaku hanyalah bidak dari agen lapangan, yang menerima dana dan instruksi dari pemain atas.
Cobalah untuk menengok catatan Aksara Penuh kita tentang situasi Indonesia di rentang 1952–1959 atau di rentang 1996–2001. Dokumen penting yang menganalisis tajam tentang itu menunjukkan bahwa kerusuhan tidak terjadi secara alami, melainkan bentukan rekayasa oleh suatu jejaring.
Seharusnya, tugas aparat dan media lebih dari sekedar melaporkan keadaan korban dan berkampanye tentang keberanian menghadapi teroris. Media terutama harus berani melakukan investigasi dan reportase kritis untuk mengungkap jejaring teror, aliran uang, dan hubungan langsung dengan pemain di level atas. Selalu ada nama lagi (orang, institusi) bila kasusnya ditelusuri. Karena kecil kemungkinan kasus teror semacam ini dilakukan karena dorongan agama.
Mungkin memang pelaku membenci umat beragama tertentu, tapi darimana ia mendapatkan bom, dan mengapa rumah ibadah yang dipilih, bukannya sektor-sektor vital kaum yang mereka incar (misalnya pusat bisnis saat sedang tutup), menunjukkan bahwa pelaku bukanlah inisiator utama. Rumah ibadah adalah simbol, dan menyerang simbol bisa mengirim pesan lebih kuat untuk menanam kecurigaan dan sentimen. Pilihan itu bukan pekerjaan orang pintar, melainkan orang bodoh putus asa—yang dibayar.
Sekali media dan aparat berhasil membongkar dan membuktikan, bahwa semua kekacauan semacam ini tak lebih dari langkah-langkah catur politik belaka, kemudian berani mempublikasikannya agar seluruh masyarakat mengerti, maka semua asumsi bahwa sentimen agama merupakan biang keladinya menjadi hancur.
Bukannya tanpa guna menjadi latah mengecam teror dengan membawa nama agama, namun bila tidak membongkar akar masalah, teror tetap berhembus. Jangan sampai, perlawanan kita salah sasaran karena dibangun dari asumsi yang keliru, dan ketidakpekaan kita pada kemungkinan lain yang aksara kita telah tuturkan.
Maka, saat aparat dan media belum mampu (mau?) bekerja dengan mendengar ‘tuturan’ aksara kita, kita harus menggunakan aksara untuk kepentingan yang tak kalah genting: kontra-narasi.
Kita harus telaten mempublikasikan seruan untuk menahan “gelombang paranoid”. Rasa curiga dan bermusuhan (yang diarahkan pada kelompok masyarakat tak bersalah) jangan sampai dibiarkan. Bila tidak, pikiran manusia itu sendiri akan menjadi bom waktu yang akan meledakkan kemanusiaan.