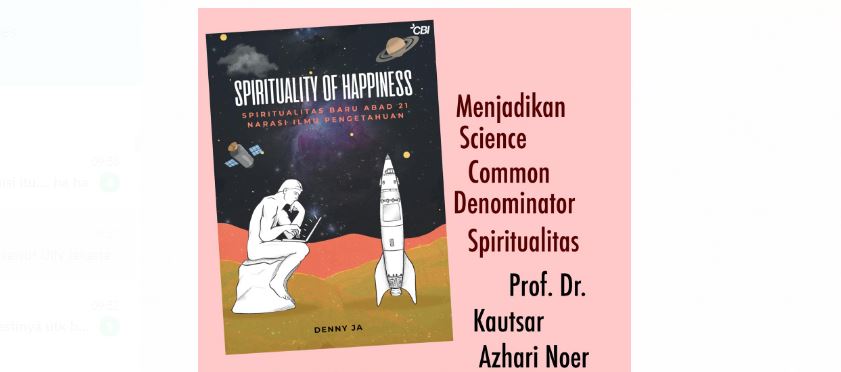Ketika mendengar atau membaca nama Jalaluddin Rumi, saya langsung teringat pada jalan cinta menuju Tuhan yang diusungnya.
Jalan cinta menuju Tuhan adalah jalan utama yang ditempuh Sufi besar kelahiran Balkh (sekarang di Afghanistan) ini. Pasti cintanya yang tak henti-henti menyembur dari lubuk hatinya yang terdalam dapat dibaca dalam karya-karya.
Tidak mengherankan bila William C. Chittick menulis sebuah karya tentang jalan cinta dalam ajaran spiritual Rumi. Karyanya berjudul The Sufi Path of Love: The Sipritual Teachings of Rumi (1983).
Chittick menulis juga sebuah karya tentang jalan pengetahuan (gnosis) berkenaan dengan metafisika Ibn ‘Arabi tentang imajinasi. Buku itu berjudul The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-‘Arabi’s Metaphysics of Imagination (1989).
Catatan pendek ini ditulis bukan untuk membicarakan perbandingan Rumi dan Ibn ‘Arabi. Tapi bermaksud memberikan catatan tentang karya Denny JA yang berjudul Spirituality of Happiness: Spiritualitas Baru Abad 21, Narasi Ilmu Pengetahuan.
Saya kira tidak salah jika disimpulkan bahwa karya ini menunjukkan pandangan penulisnya bahwa spiritualitas baru, yang menurutnya baru berlangsung 70 tahun, merupakan hasil seleksi riset sains. Khususnya positive psychology dan neuroscience. Dua ilmu ini juga baru berusia sekitar 70 tahun.
Paragraf pertama pada “Pengantar” buku ini dimulai dengan mengutip tulisan Rumi, “Spirit untuk memenuhi panggilan hidup sudah ditanam di hatimu” (h. III). Paragraf terakhir pada “Epilog” juga mengutip tulisan Rumi, “Hidupkanlah Cinta dalam segala tindakan. Maka samudra maha dalam mengalir ke dalam sukmamu: samudra kebahagiaan, samudra ekstasi” (h. 125).
Dengan kata lain, buku ini dibuka dengan perkataan Rumi dan ditutup dengan perkataan Rumi. Nama Rumi disebut tidak kurang dari 63 kali dalam karya ini. Ucapan-ucapan Rumi dijadikan rujukan oleh Denny JA untuk mengukuhkan ide spiritualitas baru yang diyakininya membawa kebahagiaan.
Terus terang saya juga mengagumi Rumi di samping Ibn ‘Arabi tanpa mengecilkan para Sufi lain. Perkataan Rumi, “Spirit untuk memenuhi panggilan hidup sudah ditanam di hatimu,” dijadikan pintu masuk oleh Denny JA untuk menegaskan bahwa neuroscience membuktikan bahwa hati, yang “menggerakkan individu memburu panggilan hidup,” ditanamkan di otak manusia. “Dalam bahasa neuroscience, hati itu ada di otak manusia” (h. III).
Saya kira yang dimaksud dengan “spirit” (kata Inggris yang telah diindonesiakan) di sini adalah “roh Tuhan” atau “roh ilahi” (al-rūh al-ilāhī). Itu ditanamkan atau ditiupkan oleh Allah ke dalam hati manusia seperti difirmankan-Nya: “Kemudian Dia membentuknya secara sempurna dan seimbang dan meniupkan kepadanya roh-Nya” (Q 32: 9).
Sebuah pertanyaan perlu diajukan: “Di mana posisi roh (Inggris: spirit) pada manusia? ” Manusia terdiri dari tiga unsur: roh (rūh), jiwa (nafs), dan jasad (jasad, jism). Roh menempati kedudukan tertinggi dan jasad menempati kedudukan terendah. Tempat jiwa (nafs) adalah antara roh dan jasad.
Karena itu, nafs sekaligus memiliki kecenderungan jasmani, kecenderungan material, dan kecenderungan rohani, dan kecenderungan spiritual.
Ketika unsur jasmani menguasai nafs, ia tertarik kepada kesenangan dan keuntungan duniawi. Tetapi, ketika nafs berkembang kepada tingkat lebih tinggi, dalam arti dikuasai oleh unsur rohani, ia menjadi tertarik kepada asalnya, yaitu Tuhan.
Maka selalu ada tarik-menarik antara kecenderungan jasmani, yang mengarah kepada kejahatan, pada satu pihak, dan kecenderungan rohani, yang mengarah kepada kebaikan, pada pihak lain. Mana yang menang di antara dua kecenderungan ini tergantung pada mana yang lebih kuat dan berkuasa.
Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa hati adalah pusat manusia sebagai mikrokosmos. Pada waktu yang sama ia adalah pusat tubuh jasmani, energi vital, emosi, dan jiwa, dan juga tempat pertemuan antara wilayah manusia dan wilayah samawi.
Di hatilah roh (spirit) berdiam. Betapa hebat realitas hati, pusat misterius. Bila dilihat dari sudut pandang eksistensi duniawi kita, realitas hati kelihatan kecil. Namun demikian, seperti dikatakan oleh Nabi Muhammad, hati adalah Tahta Tuhan, yang meliputi alam semesta.
Ketidakterbatasan luasnya hati sang gnostik digambarkan oleh Tuhan sendiri melalui sebuah hadis qudsi. “Langit dan bumi-Ku tidak mampu memeluk-Ku. Tapi hati hamba-Ku yang mukmin memeluk-Ku.”
Denny JA mengatakan, di dalam otak itu, ahli neuroscience juga menemukan apa yang disebut hormon bahagia, happy hormones. Itu adalah Dopamine, Serotonin, Oxytocine, dan Endorphine. Ini hormon yang jika tumbuh, dan dihidupkan, ia memberikan rasa bahagia, damai, ekstase, serta rasa mengalami hidup bermakna (h. III).
Tapi Jangan menganggap, happy hormones selalu melahirkan perilaku positif secara spiritual, secara moral, secara etis. Tidak, tidak seperti itu. Perilaku negatif, perilaku yang jauh dari spiritualitas, patut dikemukakan di sini, karena Denny JA tidak menjelaskannya.
Saya meminjam penjelasan Dr. Berry Juliandi, Msi, Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI). Ia menulis tentang rasa bahagia bagi orang yang menyebarkan hoaks. Menurutnya, ada sensasi-sensasi yang sengaja dicari oleh orang yang menyebarkan hoaks, antara lain ingin mendapatkan pujian tentang informasi yang ia bagikan.
“Orang itu kalau dapat informasi atau fakta baru, terlepas itu hoaks atau bukan, dia tidak terlalu mikir itu apa. Dia ingin jadi orang yang pertama yang menyebar itu supaya terlihat pintar, menaikkan reputasi dia, dia yang tahu duluan,” ujar Berry.
Membagikan informasi tersebut akan membangkitkan neurotransmitter di otak. Hormon-hormon yang menghasilkan perasaan senang membuat seseorang ketagihan untuk melakukannya lagi dan lagi. “Kan kadang suka dijawab tuh di WA Group ‘terima kasih sharingnya.’
Oksitosin [terproduksi], hormon yang membuat kita senang. Jadi itu ada reward. Akibatnya apa? Akhirnya kita terus-terus lagi melakukan itu,” tukasnya. Menjadikan neuroscience sebagai common denominator, standar, ukuran, atau panduan spiritualitas adalah sikap yang tidak tepat karena spiritualitas adalah pengalaman langsung berjumpa dengan Sang Kekasih, melihat Sang Kekasih, di mana pun dan kapan pun.
Bila dilihat dari kacamata Sufi, kacamata Rumi, misalnya. Spiritualitas bekerja di wilayah non-fisis, wilayah metafisik, wilayah spiritual, wilayah rohani, yang berdampak pada wilayah fisis, wilayah empiris.
Ingat, kata “spiritualitas” adalah kata yang berasal dari kata Inggris “spirit,” yang kata Arabnya adalah rūh. Istilah “spiritualitas” diterjemahkan “rūhaniyyah.” Adapun wilayah sains, termasuk neuroscience, adalah wilayah fisis, wilayah empiris.
Bisakah sains, khususnya neuroscience, menjelaskan pengalaman spiritual al-Hallaj yang disebut “istighrāq” (keadaan tenggelam dalam Tuhan), yang dibela dan dipuji oleh Rumi? “Istighrāq” adalah pengalaman menyatunya sang hamba dengan Kekasihnya bagaikan teggelamnya lalat dalam madu sehingga ia hancur. Lalat tiada lagi. Yang ada hanya Madu.
Inilah yang dimaksud dengan perkataan “Anā al-Haqq.” Orang menganggap perkataan itu adalah pengakuan yang sombong. Padahal pengakuan yang benar-benar sombong adalah pengakuan perkataan “Anā al-‘abd” (Aku adalah hamba). Adapun “Anā al-Haqq” adalah sebuah ungkapan kerendahan hati terdalam.
Orang yang mengatakan “Anā al-‘abd” menegaskan dua wujud: wujudnya sendiri dan wujud Tuhan. Tetapi orang yang mengatakan “Anā al-Haqq” membuat dirinya bukan-wujud (non-existence). Ia menyerahkan dirinya seraya berkata, “Anā al-Haqq,” yakni “Aku tiada, Dia-lah segala-galanya: tidak ada wujud selain wujud Tuhan.” Inilah lubuk terdalam kerendahan hati.
Saya kira pengalaman spiritual seperti ini tidak terjangkau oleh neuroscience karena pengalaman ini adalah wilayah spiritual, wilayah non-fisis. Saya khawatir memaksakan penggunaan sains untuk menjelaskan spiritualitas bisa terperosok ke dalam reduksionisme. Atau, bisa menjadi semacam ideologi yang dibela mati-matian oleh para penganutnya.
Mengapa penulis buku yang kita diskusikan ini mengambil Rumi sebagai rujukan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan spiritualitas baru, yang baru berumur sekitar 70 tahun? Mengapa tidak mengambil guru spiritual kontemporer yang, jika ada, menjadikan sains sebagai common denominator spiritualitas?
Sungguh, pengalaman spiritual, pengalaman mistikal, menurut para ahli, tidak bisa dilukiskan. Paling banter, kita hanya bisa mengatakan, tanda utama (bukan ukuran) spiritualitas adalah moral.
Ada prilaku kelompok-kelompok yang merasa diri mereka benar menjalankan apa yang mereka yakini sebagai perintah Allah. Atau mendapat bisikan dari Allah, meledakkan bom untuk menghabisi musuh Allah. Atau membajak pewasat terbang, dan menyandera orang-orang tak berdosa di sebuah bangunan. Itu semua jauh dari spiritualitas.
Betul bahwa sains dan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam kehidupan ini. Tapi jangan lupa bahwa sains dan teknologi menimbulkan efek negatif, yang di antaranya sangat mengerikan. Sains dan teknologi memudahkan manusia berbuat baik, tetapi juga memudahkan manusia berbuat jahat.
Berkat kemajuan sains dan teknologi, muncullah mesin-mesin untuk membangun industri-industri. Ini melahirkan kapitalis-kapitalis yang menindas rakyat kecil. Penggunaan sains dan teknologi melahirkan polusi udara yang merusak lingkungan dan kesehatan.
Persaingan beberapa negara untuk menunjukkan kekuatan politik dan militer telah mendorong mereka memproduksi senjata nuklir. Mengutip Defence News, SIPRI (Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockhol) memperkirakan, pada akhir 2019, sembilan negara memiliki total 13.400 hulu ledak nuklir.
Rusia adalah pemilik hulu ledak nuklir terbesar, menurut angka SIPRI, dengan total 6.735 dan 1.570. Semua senjata itu dalam posisi siaga tempur. AS mengikuti dengan sekitar 5.800 hulu ledak nuklir dan 1.750. Itu juga dalam posisi siaga tempur. Keadaan ini sangat membahayakan masa depan dunia jika negara-negara itu tidak bisa menahan diri. Sangat mengerikan!
Sebenarnya masih banyak bagian buku ini yang perlu diberi catatan kritis, termasuk perkembangan historis spiritulitas dibagi menjadi tiga gelombang: (1) gelombang pertama, yang dipandu oleh mitologi; (2) gelombang kedua, yang dipandu oleh wahyu Tuhan; dan (3) gelombang ketiga, yang dipandu oleh riset sains.
Karena ruang terbatas, maka saya cukupkan catatan ini sampai di sini. Buku yang kita diskusikan ini kaya dengan informasi. Bahasanya mengalir dan mudah dipahami oleh para pembaca.
Karya ini, saya kira, mengundang polemik karena menyampaikan pemikiran yang berbeda dengan karya-karya lain tentang tema yang sama atau berdekatan. Polemik atau diskusi yang sehat bisa memberikan manfaat kepada para pembaca. Semoga! Wa Allāh a‘alm bi al-shawāb.