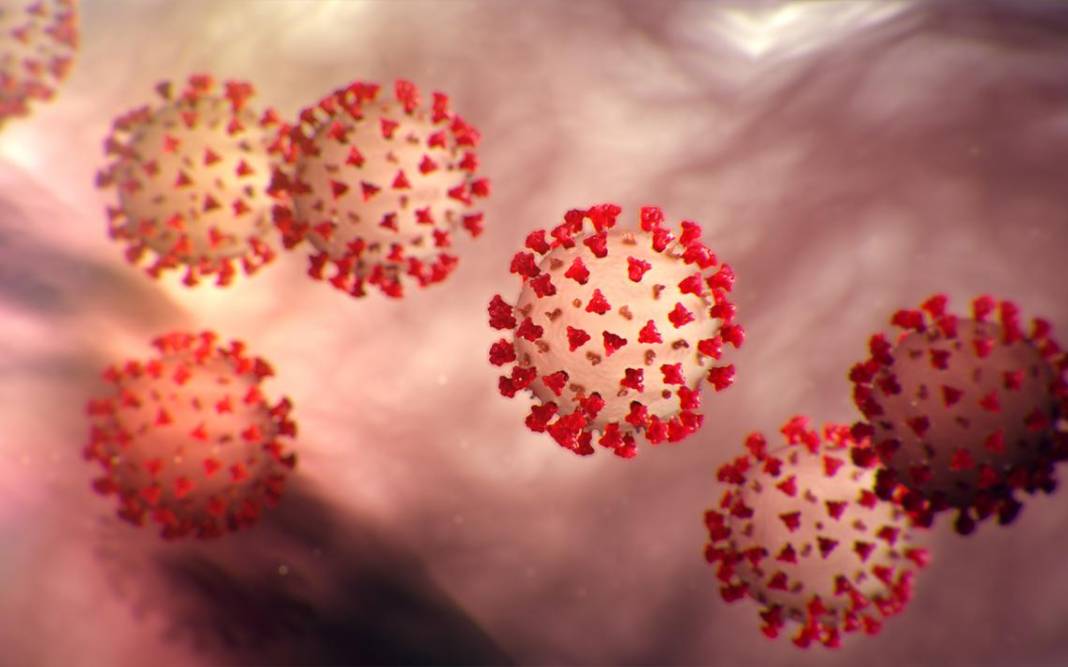Dalam Islam lazim dikenal ungkapan: makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Intinya, makanlah dengan porsi secukupnya, tetap kita sisakan ruang kosong di lambung, biar kita tetap sehat mampu bergerak lebih leluasa.
Ungkapan itu berlaku juga dalam hal kita menyerap pengetahuan dan informasi. Pengetahuan dan informasi apapun. Terlalu banyak menyerap informasi dan pengetahuan tampaknya tidak selalu membuat akal dan pikiran kita sehat. Meski bisa kita paham manusia memiliki hasrat dan gampang tergoda untuk mengetahui tentang lebih banyak hal. Dalam bahasa kekinian, manusia itu cenderung kepo penasaran.
Contoh sederhana dalam hal relasi orang pacaran. Katanya sudah saling kenal, eh tapi masih kepo juga dengan sesekali ngintip percakapan whatsapp pasangannya. Katanya sudah putus, bubaran, tetapi masih juga ngepoin akun sosmed mantannya. Apa hasilnya? Yang terjadi bukan membuat hati puas, pikiran tenang, malah, makin penasaran, pusing, uringan-uringan. Tersulut cemburu karena sang pacar dan mantan hobinya flattering, bikin kesengsem cowek (cowok cewek) dirubung gombalan.
Saya mengalaminya untuk pengetahuan dan informasi yang berbeda. Sekali lagi, ini pengalaman saya. Entah dengan pengalaman Anda.
Untuk saat ini, pengalaman saya terkait pengetahuan dan informasi mengenai Covid-19. Begitu banyak informasi tentang covid yang tampil dalam kesadaran saya. Entah itu melalui medsos maupun langsung masuk melalui saluran pribadi seperti whatsapp.
Awal waktu terjadinya pandemi, informasi yang bersarang dalam pikiran saya sangat menambah pengetahuan saya tentang sejarah, bahaya dan pola penyebaran covid, sehingga membantu saya lebih sadar tentang risiko dan kemungkinan terinfeksi virus jahat dan kejam ini.
Dengan begitu informasi tersebut membantu saya lebih waspada dan berhati-hati berkativitas, terutama ketika di luar rumah. Selain itu membuat saya lebih berdisiplin mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari covid.
Namun, belakangan ini, informasi soal covid yang masuk dalam pikiran, menurut saya agak berlebihan dan efek psikologisnya agak kontradiktif dengan akumulasi informasi pengetahuan yg diterima.
Di satu sisi pengetahuan saya bertambah mengenai perkembangan covid, tetapi di sisi lain hati dan pikiran saya resah karena informasi itu terasa membingungkan. Berikut Saya berikan beberapa contoh informasi tersebut:
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200612074519-20-512482/kasus-kasus-kematian-corona-yang-membingungkan-gugus-jatim
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/04/pandemic-confusing-uncertainty/610819/
Coba kita lihat. Ilmuwan dan virolog saja kebingungan dengan kelakuan virus “jancuki” ini. Katanya virus ini pintar ngumpetnya, cakap mengelabui dan sukses menyusup ketubuh manusia. Catat ya, virusnya yang sukses! Sementara ilmuwannya belum sukses menaklukkan dan menemukan vaksinya.
Bahkan dikatakan dalam berita tersebut bahwa virus ini tidak hanya mengkooptasi sel-sel tubuh tapi juga mengeksploitasi bias-bias kognisi atau pengetahuan manusia. Bias kognisi ini bisa kita lihat dari cara kita menampilkan kebenaran data perkembangan Covid, terutama soal jumlah atau tingkat kematian karena Covid di negeri ini.
Di satu sisi pemerintah berpendirian datanya sudah benar dengan kalkulasi status positif berdasarkan tes swab PCR, di sisi lain ada kelompok yang melihat pemerintah menutupi tingkat kematian yang senyatanya empat kali lipat lebih banyak dari pada data pemerintah, dengan catatan jika memasukkan data kematian ODP dan PDP.
Belum lagi kalau kita bicara adanya informasi yang berseliweran — dan tidak sedikit masyarakat yang percaya — bahwa virus ini bukan alamiah sifatnya, tapi buatan manusia. Covid ini praktik konspirasi global yang aktornya tidak lain adalah Bill Gates melalui Big Pharma. Lazimnya teori konspirasi — bak Hantu Jeruk Purut — status kebenarannya dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing.
Data survei Lapor Covid-19 tentang Persepsi Risiko Covid memperlihatkan sebagian besar (58%) masyarakat mengaku tidak tahu ketika disodori pertanyaan apakah virus dibuat secara sengaja dibuat oleh manusia. Yang menarik — tetapi terasa kecut membacanya — data mereka yang menyatakan bahwa benar (18%) virus itu buatan manusia selisihnya sangat tipis dengan yang menilainya salah (23%). Ini menegaskan ketidakpastian atau ketidakjelasan status risiko covid di benak masyarakat. Ini menjadi PR besar bagi kita semua, terutama pemerintah ditengah jumlah yang terinfeksi makin bertambah.
Sebagai mana diulas dalam portal The Atlantic di atas, covid, risikonya nyata tetapi tidak terlihat. Sangat berbeda dengan gempa bumi atau bahaya puting beliung, misalnya. Ketika puting beliung atau gempa bumi menerjang, bahayanya jelas, risikonya jelas, dan akibatnya terlihat. Jelas kapan harus berteduh, dan kapan aman untuk keluar.Berbeda dengan virus yang berada di bawah ambang jangkauan indra. Sehingga, kapan kita celaka, kapan selamat, tidak jelas. ( but viruses lie below the threshold of the senses. Neither peril nor safety is clear).
Bisa dimengerti jika kemudian banyak masyarakat terlihat bersikap masa bodoh dengan risiko dan dampak covid ini. Kemungkinan karena mereka tidak mengetahui dan melihat secara langsung bukti empirisnya.
Masih merujuk pada survei yang sama, data mengungkapkan mayoritas (94%) tidak mengetahui orang yg dia kenal mati karena covid. Bagi orang awam, realitas empiris yang dialami secara langsung lebih dipercaya dan dipahami ketimbang data statistik yang masih diragukan dan menjadi perdebatan di sebagian kalangan.
Jika awal pandemi, virus hanya melalui droplet yakni cairan dari mulut atau hidung, sehingga untuk mencegahnya cukup dengan menjaga jarak sekira satu atau dua meter, dan potensi kebahayaannya hanya bertahan dalam hitungan menit, sekarang lebih canggih lagi, ternyata bisa menular dalam bentuk aerosol.
Aerosol adalah partikel cairan di udara yang lebih kecil dari 5 mikrometer, yang berasal orang yang bernafas, bercakap-cakap, menyanyi, atau tertawa. Terutama di dalam ruangan tertutup, partikel sangat kecil ini bisa terus mengambang di udara selama beberapa jam.
Coba kita banyangkan, untuk bernafas saja kita dicurigai dan dibatasi. Apalagi tertawa dan bernyanyi? Entah dunia macam apa ketika kita tidak lagi mendengar lagi orang bernyanyi, yang ada cuma bergumam: mmmhhh…mmmhh..
Baiklah, kita terima dengan lapang dada temuan ilmuwan soal penularan dalam bentul aerosol ini. Kita pakai masker, face shield, plus sanitizer dan menjaga jarak 10 meter, sehingga kalau bicara dengan orang lain pakai mikrofon, cukup dengan chat wa. Atau, bagi daerah yang susah sinyal, kita kembali ke teknologi waktu kita kanak-kanak: menggunakan dua kaleng yang terhubung dengan benang.
Masalahnya, apakah ada jaminan dalam satu bulan atau satu tahun mendatang tidak ada temuan baru, katakan misalnya, karena kecerdasan virus yang “njelehi” ini ternyata bisa menular lewat kentut atau kedipan mata? Taruhan! Tidak ada yang bisa menjamin, bahkan WHO sekalipun.
Dengan segala temuan terkini yang mencemaskan ini sagalanya sangat mungkin. Baca saja di Google, yang awalnya virus bersarang di saluran pernafasan hingga ke paru-paru, ternyata juga bisa nyasar ke testis atau buah “titit”.
Entah apa yang terjadi, misalnya, andai kata ada sejumlah lelaki yang sudah siap-siap bercinta dengan pasangannnya, lima menit sebelum bercinta lalu mendengar bunyi: twing! Temannya mengirim sms atau pesan whatsapp dengan isi tautan berita ini.
Lama-kelamaan temuan demi temuan para ilmuwan yang diberitakan oleh media terkesan sebagai informasi yang menakut-nakuti ketimbang memberikan solusi.
Mungkin ini yang dimaksudkan Robin Hogarth bahwa kita sedang “dikutuk pengetahuan”. Makin banyak pengetahuan bukan membuat kita makin well informed dan tercerahkan, melainkan makin cemas, stres, uring-uringan.
Belum lagi kalau kita membaca unggahan bertubi-tubi status kawan-kawan di sosmed — yang secara formal tidak memiliki kompetensi — bicara soal bahaya covid. Ampun deh, menyesakkan pikiran dan perasaan, melebihi sesak nafas.
Sebagai manusia biasa, terus terang umpatan semacam “asu kalian” sudah di ujung lidah, siap saya semprotkan ke para pembawa informasi itu.
Tetapi batin ini terus mengingatkan saya agar sebaiknya tidak menyeret-nyeret “asu” (anjing) dalam perkara pendemi ini. Anjing bukan pihak yang bersalah dan bertanggung jawab mengatasi covid.