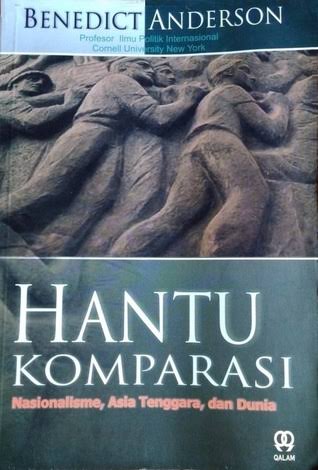Penolakan terhadap RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang oleh sejumlah kalangan, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) dicurigai beraroma “anti komunisme” memperlihatkan bahwa komunisme masih menjadi “hantu” yang menakutkan. Maka, hantu semacam itu layak untuk diwaspadai, bahkan jika perlu diusir sejauh mungkin.
Namun, hantu yang umumnya tak terlihat di depan mata itu sesungguhnya tidak hanya ditemukan di negara kita, tapi juga di negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand. Jadi, hantu yang dinamai komunisme itu ternyata menjadi subjek tak nampak yang masih saja gentayangan dan kerap direkayasakan untuk menakut-nakuti banyak orang.
Dalam bukunya yang berjudul Hantu Komparasi. Nasionalisme, Asia Tenggara, dan Dunia (Qalam, 2002), Benedict Anderson membuat kajian menarik tentang dunia politik pasca runtuhnya komunisme di Indonesia dan Thailand.
Menurutnya, meski komunisme, baik PKI (Indonesia) maupun CPT (Thailand), secara institusional sudah berakhir, namun keduanya masih dipandang sebagai ancaman dan/atau musuh sepanjang segala abad.
Hanya bedanya, jika di Indonesia komunisme selalu diperlakukan sebagai hantu yang sedapat mungkin selalu diusir dengan segala cara, namun di Thailand hal itu justru diundang untuk hadir sebagai hantu yang hidup dalam kebudayaan bawah sadar masyarakatnya.
Jadi, hantu komunisme itu harus secara sungguh-sungguh dikaji-ulang, diinterogasi, dan jika mungkin dipulihkan dan dikuatkan kembali, daripada sekadar dirawat dan dijaga sebagai “bahaya laten” misalnya.
Perbedaan itu tentu membawa implikasi yang sedemikian kontras dan cukup mendalam. Pertama, di Indonesia hantu komunisme selalu ditampilkan secara sadis dan kejam. Catatan historis dari Pipit Rochijat memperlihatkan betapa mayat-mayat dari orang-orang yang dituduh sebagai PKI dipertontonkan di depan publik bukan berbentuk sebagai manusia. Itu artinya, mereka sudah tidak dapat dikenali lagi dan dibuang ke berbagai tempat seperti dilarung di sungai.
Pemandangan seperti itu bukan saja menjadi tampak menjijikkan dan mengerikan, tapi sekaligus membuat banyak orang tidak dapat menjawab pertanyaan berikut ini: “Saya PKI atau bukan PKI?” (Indonesia, 1985). Sebab, jika tahun-tahun sebelum 1965-1966, PKI selalu dituduh kejam dan biadab, lantas mengapa mereka justru mendapat perlakuan yang serupa, bahkan diturunkan hingga ke anak-cucunya?
Semantara di Thailand, komunisme, atau lebih tepatnya Marxisme, justru menjadi “bahan bakar” bagi kaum akademisi, khususnya sejarawan alternatif, untuk mempelajari mengapa CPT runtuh begitu cepat, bahkan mendahului Uni Soviet. Dengan kata lain, komunisme yang sempat berperan sebagai gerakan radikalisme di Thailand, dan Asia Tenggara pada umumnya, dengan mudah menguap tanpa sebab musabab yang masuk akal.
Padahal, dibandingkan dengan Indonesia yang para aktivisnya kebanyakan adalah “pribumi” yang otodidak atau lulusan sekolah menengah atas di zaman Hindia Belanda, di Thailand sebagian besar didominasi oleh kaum imigran dari daerah-daerah pesisir Cina tenggara yang disebut “luk jin” atau “Sino-Thai”. Mereka tumbuh di sepanjang rel kereta api dan membentuk kelas pekerja serta mengarahkan kiblat komunismenya pada Cina ketimbang Eropa atau Uni Soviet. Boleh jadi karena asal-usul yang cukup kontras itulah, komunisme tidak sekadar dijadikan korban (victim), melainkan penyintas (survivor).
Kedua, hantu komunisme di Indonesia yang setelah tahun 1965-1966 pun masih tetap dikembangbiakkan, baik secara legal maupun ilegal, terbukti telah menciptakan ketakutan yang beranak-pinak secara turun-temurun. Sastrawan Pramoedya Ananta Toer (PAT) misalnya, yang beragam karyanya selalu dicurigai berpaham “kiri”, sama sekali tak pernah mendapatkan keadilan lantaran tiadanya proses hukum yang dijalaninya.
Syukurlah, bahwa sesudah lebih dari 20 tahun Orde Baru tumbang, salah satu tetraloginya yang berjudul Bumi Manusia sempat difilmkan pada 2019, meski ironisnya, tak pernah ditontonnya. Sosok PAT yang sesungguhnya dapat menjadi narasumber sejarah bagi bangsa Indonesia justru dibungkam dan siapapun yang membelanya niscaya akan dihukum.
Sebaliknya di Thailand, para aktivis, yang kebanyakan merupakan para pemikir radikal pada dasawarsa 1980-an dan awal 1990-an, justru semakin tergerak untuk menelusuri dan mendalami jejak langkah komunisme secara signifikan alih-alih sebagai sejarah alternatif. Hal itu menjadi perangai yang membuat komunisme tidak hanya menjadi jasad yang terkubur tanpa batu nisan.
Karena itu, tidak sedikit orang muda yang rela mengorbankan masa depannya hanya demi mendapatkan pengetahuan tentang sejarah dan dinamika komunisme di Thailand. Meski ujung-ujungnya tak bisa menghindar dari pengawasan melekat dari junta militer, mereka masih mampu menunjukkan minat dan perhatiannya yang cukup besar pada subjek-subjek baru, termasuk komunisme.
Ketiga, hantu komunisme sesungguhnya merupakan produk dari keyakinan yang sukar digoyang dengan pengetahuan. Maka masuk akal jika di Indonesia tidak mudah untuk membawanya ke hadapan sains yang pada dasarnya berperangai ilmiah.
Maka bukan kebetulan jika keyakinan terhadap hantu komunisme bukan berakar pada sejarah yang telah dibelokkan, tetapi justru pada politik yang direkayasakan untuk membentuk “komunitas-komunitas terbayang” (Anderson, 2001). Yaitu, kumpulan orang-orang yang meski tidak saling kenal, belum pernah berjumpa, bahkan bertegur sapa, mereka rela untuk menghabisi sesamanya, bahkan dirinya sendiripun siap untuk dikorbankan.
Sedangkan di Thailand yang steril dari kolonialisme praktis bebas dari politik seperti di atas, meski dominasi dari politik dinasti dan militerisme tampak begitu kuat. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah dari para aktivis komunisme untuk menawarkan beragam perspektif alternatif di luar politik yang dominan.
Tak heran, komunisme tidak dipandang sebagai musuh atau lawan yang harus dimusnahkan, namun dibiarkan untuk beradu gagasan dan gerakan dengan berbagai kelas sosial dalam masyarakat, khususnya dari kalangan borjuasi. Hanya sayangnya, komunisme tampak layu sebelum berkembang lantaran tak ada pengalaman untuk menjadi nasionalis, apalagi radikalis yang senyatanya.
Sebab pada kenyataannya, mereka hanya tampil dengan identitas “kecinaan” yang absurd dan traumatis. Bahkan pada akhirnya lebih menyerahkan proyek nasionalisme pada rahib-rahib Buddha yang reaksioner, para pemimpin militer sayap kanan, dan monarki yang berpedoman pada tradisi dan imajinasi kerakyatan.
Dari ketiga kontras di atas, bukan kebetulan bahwa di Indonesia hantu komunisme masih efektif dan operatif dibanding di Thailand. Meski sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, hantu itu tidak dapat hidup di sembarang tempat, apalagi bertahan hingga kini.
Karena itu, diperlukan sejumlah kajian yang tajam dan berperspektif komparatif dalam menyusun sejumlah kebijakan penting dan mendasar yang berkait dengan jejak langkah “hantu” komunisme, termasuk dalam RUU HIP di Indonesia.