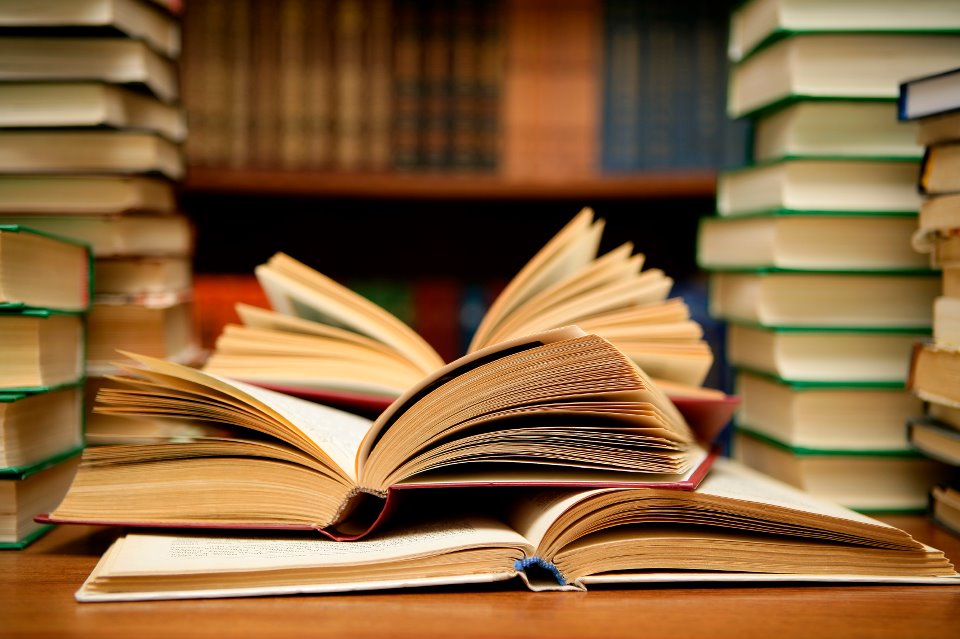Menarik bahwa, sesudah kepergian dua sosok intelektual publik kita, yaitu Daniel Dhakidae (DD) dan B. Herry Priyono (BHP), tampak ada kebutuhan untuk melahirkan intelektual publik baru. Sebab dari kedua sosok itu, dunia intelektual, terutama di Indonesia, bukan hanya telah merasa kehilangan, tetapi juga semakin tampak bahwa ada yang mangkir atau absen dalam kehidupan kaum intelektual, baik pada tataran lokal, regional, maupun global.
Apakah itu? Jawabannya, seperti telah dikaji oleh Benedict Anderson di koran Bangkok Post (June, 28, 2010) dan dipertajam oleh Pierre Marthinus di koran The Jakarta Post (July, 15, 2010), bahwa kalangan intelektual hanya menjadi kalangan “perekayasa kebijakan” (policy architects) dalam masyarakat yang semakin plural dan tanpa batas ini.
Itu artinya, mereka yang sesungguhnya berkemampuan untuk menembus dan melestarikan pengetahuan lama dan rahasia itu sekadar memproduksi beragam ilmu yang menyenangkan untuk ditonton dan membahagiakan untuk dinikmati. Itulah mengapa kalangan intelektual semacam ini ibarat peniup seruling bagi ular (snake charmer) yang suka menari-nari begitu mendengar bunyi yang dimainkan.
Dengan permainan seperti itu, para pembuat kebijakan yang berperan sebagai penyambung lidah rakyat itu pun tidak lebih hanya mengikuti apa yang dimainkan oleh kaum intelektual hingga saat ini. Permainan yang kerap mengabaikan suara dan kepentingan rakyat itu mudah ditebak sekadar menghasilkan pro dan kontra yang seolah-olah menggantung di awang-awang.
Contohnya, terkait dengan penanganan berbagai kasus korupsi, yang diperdebatkan selalu hanya berkutat pada jumlah uang yang telah membuat negara mengalami kerugian dan rakyat menjadi semakin miskin, bahkan sengsara. Seakan-akan uang itu adalah milik dari nenek moyang yang telah dicuri dan wajib untuk dikembalikan.
Sementara pada kenyataannya, belum ada satu pihakpun yang pernah mengaku merasa malu telah melakukan tindak pidana yang membuat banyak orang menderita. Bahkan para koruptor yang tertangkap tangan justru dengan senyum lebar sembari melambai-lambaikan tangannya tampil di media cetak dan eletronik mirip dengan artis-artis kenamaan.
Tak heran, ketika diadili dan divonis dengan hukuman penjara sekalipun, mereka masih dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun rela menjalaninya karena seperti ada jaminan bahwa kehidupannya tidak akan jauh berbeda dengan hidup bebas di luar sana. Inilah yang membuat masyarakat merasa ragu dan pesimis bahwa hukum telah ditegakkan dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu, hukum yang selama ini lebih sering terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas bukanlah isapan jempol belaka, bahkan semakin dimaklumi saja alias dipandang sebagai banal semata.
Sebaliknya, kalangan intelektual yang di mata publik beraksi seperti pawang singa (lion tamers) justru semakin langka dan dibuang dari pikiran. Mereka yang selalu berbekal cambuk dan kursi kecilnya untuk mengajari hewan-hewan yang dipandang liar dan buas itu malah disingkirkan dan, jika perlu, diasingkan agar dapat segera menuntaskan masalah daripada sekadar mendengar kritik yang hanya memerahkan telinga dan muka semata.
Kalangan intelektual ini tampak lebih sering menjadi “musuh” bagi mereka yang gemar membalikkan punggung terhadap kekejaman-kekejaman. Masuk akal jika di tengah masyarakat yang selalu dibuat tidak stabil dalam berpendapat, mereka lebih rela mengorbankan nyawanya daripada sesamanya. Maka, mereka dengan jelas dan tegas akan menolak, bahkan menghantui, siapapun yang masih berpegang pada keyakinan yang lebih sukar digoyang daripada pengetahuan.
Tanpa berintensi dan berpretensi membandingkan sosok intelektual manapun, termasuk DD dan BHP, Pramoedya Ananta Toer (PAT) agaknya dapat ditunjuk sebagai representasi atau penampakan dari mangkirnya intelektual publik kita saat ini. Sosok PAT yang telah diakui sebagai sastrawan kenamaan itu bukan saja telah membuktikan kemahakaryaannya seperti lewat tetraloginya di Pulau Buru, tetapi juga perjuangannya yang bukan semata-mata “shadow boxing” belaka.
Dengan kata lain, seluruh karya sastranya tidak hanya untuk membuat para pembacanya sekadar “berlatih bertinju dengan bayangannya sendiri”, melainkan justru bertarung di atas ring yang telah disiapkan. Karena itulah, PAT sama sekali tidak pernah memanfaatkan mitos-mitos yang dipandang justru meniadakan nalar dalam setiap karyanya seperti pantangan untuk mengenakan baju hijau ketika berkunjung ke pantai selatan.
Sebab konon bagi siapapun yang melanggar pantangan itu akan terseret ombak lantaran dibawa oleh Nyai Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan. Justru segenap mitos itu dilawannya dengan menggunakan nalar bahwa baju hijau adalah simbol dari seragam pasukan Belanda yang tak terkalahkan dan berkuasa secara dominan di setiap koloninya, termasuk Hindia Belanda.
Tentu, baik DD maupun BHP, memiliki nalar yang khas sebagai bagian dari kaum intelektual publik di Indonesia. Dengan kekhasannya masing-masing, mereka telah memainkan peran dan memberi sumbangan yang tidak kecil dalam dunia akademis. Namun, penting untuk selalu diwaspadai dengan jeli bahwa yang mangkir dari intelektual publik itu tidak pernah akan hilang begitu saja. Tetap diperlukan segenap upaya untuk mendidik generasi baru dari intelektual publik yang mampu membongkar setiap pemangkiran dan menata ulang agar siap menjadi pawang singa daripada sekadar peniup seruling bagi ular.