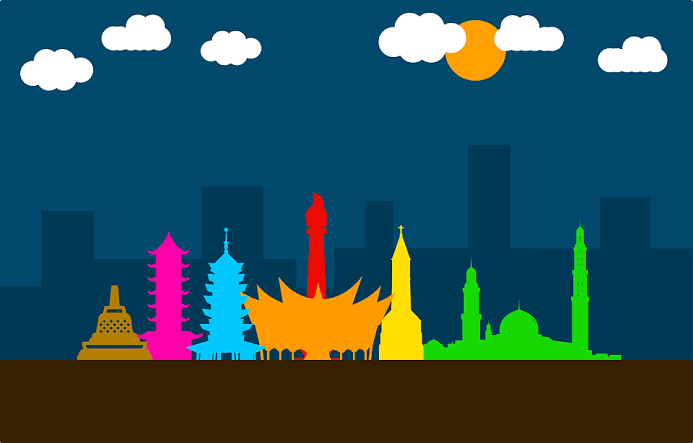Sampai saat ini masih ada orang yang masih beranggapan jika membahas tentang agama, kita membahas sesuatu yang sakral, benar-pasti, suci, objektif, absen analisis (untouchable), dan sudah selesai (given). Padahal tema agama bisa dikaji dari sisi ilmu agamanya atau dikaji di sisi fakta keberagamaan yang menyejarah. Fakta ini adalah pengalaman religiusitas manusia dalam meniti perjalanan spiritualnya dalam kurun ruang dan waktu tertentu (Ahmed, 2016; Eliade, 1987). Pembeda ini sangat signifikan bagi kita semua sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berdampak buruk seperti konflik sosial dan kekerasan atas nama agama.
Mengkaji agama di sisi fakta keberagamaan menjadi sangat penting karena kita harus memiliki kepekaan munculnya ekstrimisme, fundamentalisme, dan radikalisme agama. Tanpa pendekatan ini, maka kita bisa jadi terjebak dan tertipu oleh para pengkhotbah agama yang mengajak ke tindakan radikal.
Banyak sarjana sejarah, ilmu sosial, dan humanities mengkaji tentang agama sebagai fakta sosial dan kebudayaan walaupun sarjana tersebut bukan ahli agama (pastur, rabi, biksu, ustadz, ulama, dan fuqaha). Dalam konteks ini Islam dipahami bukan sebagai sistem kepercayaan atau bentuk keimanan yang sakral (Tibi, 2012).
Sebut saja Samuel Huntington (RIP), Bassam Tibi, Tariq Ramadan, Robert Heffner, John L Esposito, John O. Voll, Stephen Chan, dan yang lainnya menulis tentang fakta agama dalam konteks perilaku keberagamaan masyarakat baik di level lokal maupun global, di aspek sosial-politik, dan budaya.
Selain itu, negara-negara di dunia pun membahas tentang fakta keberagamaan yang sudah cukup berbahaya, karena misalnya adanya gerakan populisme, stabilitas politik global terancam. Jadi kajian ilmu sosial dan humanities tentang agama sangat penting bagi orang awam (masyarakat umum) sebagai benteng keberagamaan mereka.
Islamologi
Dalam Islam, studi tentang fakta agama (bagaimana agama menjadi instrumen politik dan ideologi) dinamai Bassam Tibi dengan “Islamologi”, yakni Islam sebagai fakta sosial-politik dan kebudayaan, bukan Islam sebagai kepercayaan atau sakralitas seseorang dengan Tuhannya.
Lebih lanjut, seorang Professor hukum Islam di Monash University dan sekaligus ulama NU Australia-New Zealand, Nadirsyah Hosen juga mengkaji Islam sebagai islamologi. Walaupun beliau yang ayahnya pendiri Institut Ilmu al Quran (IIQ, 1977) juga ahli Islam. Karya-karya ringannya, “Saring Sebelum Sharing (2019), Islam Yes Khalifah No 1 & 2 (2018), memberi pemahaman realitas para pengklaim beragama Islam, tapi mendistorsi dan menyalahi ajaran Islam. Nadir menunjukkan fakta-fakta keberislaman yang kontradiksi dengan ajaran Islam itu sendiri demi hasrat kekuasaan.
Misalnya sebagai ahli hukum Islam, Nadir menunjukkan beberapa peristiwa sejarah politik penyimpangan Dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Dalam karya-karyanya, Nadir menjelaskan bahwa dinasti-dinasti itu merupakan sistem kerajaan yang despotis dengan banyak korban pembantaian manusia, tapi dewasa ini seringkali dipahami sebagai pemerintahan kekhalifahan yang diklaim suci.
Seorang professor antropologi dan sosiologi King Fahd University, Arab Saudi, Sumanto al-Qurtubi juga banyak membahas Islam dalam konteks Islamologi dalam dimensi sosial dan budaya. Beliau mengkaji fenomena ajaran Islam yang secara kebudayaan juga dipraktekkan di agama lain (misalnya, Yahudi dan Kristen). Dan dalam konteks sejarah sudah berlangsung jauh sebelum Islam. Misalnya tradisi berpakaian jilbab, sistem kerajaan yang dipraktekkan dinasti-dinasti Islam pasca pembunuhan Ali bin Abi Thalib.
Seseorang yang hanya belajar ilmu agama (teologi, kalam, tafsir, dan hafalan-hafalan kitab) perlu belajar dan memahami ilmu sosial dan humanities (antropologi, politik dan Hubungan Internasional). Seseorang yang belajar agama dan menjadi penceramah pun perlu diperlengkapi metodologi berpikir ilmu sosial dan humanities sehingga tidak salah arah.
Perlengkapan sederhana dari ilmu sosial dan humanities menjadi sangat penting disampaikan sebagai pendekatan, metodologi berpikir baik untuk orang awam (masyarakat umum) maupun para penceramah (dai) yang paham betul ilmu agama. Kini semakin banyak ceramah tentang politik kekuasaan dan ideologi yang dilegitimasi dengan ayat dan hadis, tanpa metodologi berpikir yang jelas. Paham tentang ilmu agama belum tentu paham tentang proses sejarah dan konteks keberagamaan. Ini fenomena berbahaya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Problem absennya ilmu sosial dan humanities pada pengkaji ilmu agama dan para penceramah memberi efek yang luar biasa bagi masyarakat lokal dan global seperti semakin bertambahnya pengikut Islam transnasional (Jamaah Islamiyah, negara Islam, ‘Salafiyah politik’, HTI, terorisme dan sejenisnya).
Selain itu, para pengikutnya ini merasa suci dan benar seolah-olah dekat dengan Tuhannya walaupun faktanya justru melakukan penistaan/penodaan agama dengan tindak kekerasannya. Demikian pula penceramah, dan peng-aku ustadz atau ustadz jadi-jadian yang berkhotbah dengan emosi meluap-luap penuh amarah (suara tinggi) diikuti dengan tema dan diksi-diksinya.
Problem absennya ilmu sosial dan humanities di kalangan penstudi ilmu agama dan masyarakat dapat dipecahkan dengan pertama-tama semua orang harus paham perbedaan antara fenomena (fakta) sosial-budaya tentang Islam dan Islam dalam konteks kepercayaan yang suci, teologi, usul fiqih, fiqih, dan ilmu kalam.
Mengkaji proses pengalaman keberagamaan justru memberi pemahaman bahwa orang beragama merupakan proses perjalanan umat kemanusiaan untuk kembali kepada Penciptanya dengan melalui berbagai macam pos-pos tantangan, godaan, dan tragedi. Jadi tidak dengan cara penghakiman, pengkafiran, dan penyalahan (dosa).
Langkah berikutnya adalah sistematisasi ajaran ilmu sosial dan humanities serta metodologinya dalam setiap kajian ilmu agama, khususnya untuk para dai, ustadz, atau para agen agama manapun juga sehingga mereka diperlengkapi instrumen yang tepat, jelas, dan kontekstual serta jelas batasannya di ruang publik.
Mereka tidak seenaknya asal kutip teks suci atas nama kesucian agamanya dan disampaikan di ruang publik padahal dibalik itu bermuatan subjektifitas kepentingan dirinya dan kelompoknya. Hal-hal semacam ini harus secara dini dicegah dan diidentifikasi oleh seluruh kalangan baik di level kebijakan dan masyarakat umum demi stabilitas sosial baik di lingkungn lokal maupun global.
Hal yang termudah dan sederhana untuk memahami pengelaman keberagamaan bagi masyarakat umum adalah bagaimana kita melihat sejauh mana praktek keseharian seseorang yang berislam dengan kata-katanya. Jangan sampai ceramah dan kata-katanya ‘agamis’, suci, tapi tindakannya justru mengingkari, menodai, dan menista agamanya. Saya kira masyarakat kita dan masyarakat global sudah memulai kewaspadaan ini.
Saya kira sudah saatnya para intelektual ilmu sosial, humanities, agamawan dan pemerintah, khususnya di Indonesia yang mayoritas Islam lebih meningkatkan kepeduliannya di ilmu sosial dan kemanusiaan. Hal ini menjadi lebih penting lagi ketika dewasa ini, perkembangan teknologi justru melemahkan peran ilmu sosial dan humanities.
Selain itu, ilmu sosial dan humanities juga penting menjadi software bagi sarjana eksak dan IT, karena tanpa sentuhan ilmu-ilmu tersebut, metodologi berpikir mereka cukup mengkhawatirkan. Misalnya pola-pola berpikir oposisi biner: hitam-putih, iya-tidak, benar-salah, 0-1, dan baik-buruk. Jika dibiarkan hal ini akan menjadi bom waktu krisis keberagamaan kita dan meningkatnya konflik sosial. Jadi kita tidak bisa menafikan kajian ilmu sosial dan humanities untuk pemahaman kompleksitas hidup dan sikap arif dalam menghadapinya.