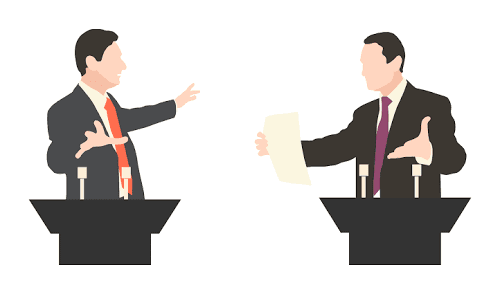Dialog adalah percakapan tanpa akhir antara dua orang atau lebih demi tujuan yang baik bagi atau menurut versi yang berdialog. Saya tidak ingin mendefinisikan konsep dialog versi filsafat atau versi lain. Dialog di sini lebih pada sejauh mana pengalaman seseorang berproses dengan aktivitas berkomunikasi dua arah untuk saling mengisi, memahami dan membuahkan solusi. Dialog ini membebaskan manusia, debat yang justru menjerumuskan seseorang kepada kesombongan dan pengerasan hati.
Kini isu yang mengkhawatirkan adalah debat dijadikan fondasi demokrasi Indonesia. Apa saja diperdebatkan padahal tradisi ini bersumber dari demokrasi Barat. Debat ini membuat relasi antara masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah, menjadi kaku dan sering kali konfliktual.
Jadi perlu berhati-hati dalam berdebat, karena tidak semua dimensi kehidupan dibuat ajang debat. Menjadi signifikan tradisi dialog yang primordial bangsa ini justru diutamakan. Perlu menempatkan proporsi yang tepat dan proporsional antara debat dan dialog.
Dialog dan Debat
Dialog lebih cocok dipahami dalam konteks budaya Jawa sebagai rembug. Oleh sebab itu, dialog kurang pas disamakan dengan debat yang memiliki istilah kebenaran dan argumen. Di Jawa, debat tidak mengena. Dalam ruang sosial, debat dianggap fenomena cekcok. Hal ini tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat.
Dialog lebih pas dalam konteks diskusi, karena dalam diskusi percakapannya saling menopang dan berkelanjutan. Dialog membuahkan sesuatu yang terbarukan dengan fondasi rajutan bersama para pesertanya. Di dalamnya banyak hal yang secara tiba-tiba muncul untuk dilanjutkan dirajut.
Dialog tidak membutuhkan cara berpikir kaku sistematis seperti para ilmuwan yang sifatnya sangat deduktif dan rasional. Dalam dialog, kita membutuhkan kemauan untuk berpikir dalam konteks membantu proses berpikir yang lain demi kebersamaan dan kontekstual dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dialog adalah estafet berpikir sampai tujuan bersama. Hal ini jauh berbeda dengan debat.
Dalam berdebat, sejak dari awal pun seseorang sudah membawa bangunan kebenarannya sendiri. Ia mempersiapkan amunisi, argumen, sistematika berpikir lengkap dengan berbagai macam preposisi dan hipotesanya. Dengan debat, niat seseorang tidak ‘membantu proses’ berpikir dalam perdebatan, tetapi justru menghancurkan proses berpikir yang lain demi mengukuhkan, menguatkan, dan menjustifikasi kebenarannya. Walaupun dalam hatinya mengatakan bahwa sekiranya dirinya salah, dan pesan ini sampai ke otaknya, tetapi secara oral, seseorang tidak akan pernah mengakuinya.
Dalam berdebat, seseorang tabu atau cenderung enggan menyatakan bahwa dirinya salah atau lemah argumennya. Seseorang tersebut terus menerus mencari justifikasi demi kebenaran yang dibawanya sejak awal tanpa mengambil poin sedikit pun dari pihak lawannya. Dalam debat, penjelasan tentang argumen lawan justru bukan untuk dilanjutkan lebih jauh dan berkembang, tetapi justru diputarbalikkan untuk menyerang balik demi argumen kebenarannya.
Hal itu berbeda dengan dialog yang justru di dalam ruang diskusi, setelah pembicaraan seseorang dilanjutkan (dipotong) oleh pihak lain, pihak lain itu menjelaskan sisi lain yang sekiranya tidak atau belum dibahas oleh pembicara sebelumnya atau memperekuat pihak sebelumnya dengan eksplorasi lebih dalam dan menyakinkan.
Dengan demikian, pembicara sebelumnya kembali meresponnya dengan berkata, “Oh, iya, saya ternyata tidak sejauh itu berpikirnya,” atau berkata “Ternyata saya terlewat ya pada hal-hal semacam itu. Di sini saya dapat pengetahuan baru”.
Dalam dialog, seseorang juga tidak hanya mengakui kekurangannya, tetapi bisa saja melanjutkan pembicara terakhir yang mengembangkan diskusi lebih jauh dan seterusnya.
Studi Kasus
Misalnya problem WNI yang menjadi anggota ISIS dan ingin pulang ke Indonesia. Ada perdebatan bahwa WNI yang menjadi bagian dari ISIS boleh kembali dan argumen sebaliknya, WNI yang menjadi bagian dari ISIS tidak boleh kembali. Mereka yang membolehkannya berkeras demi urusan kemanusiaan, dan sebaliknya, yang menentang WNI eks-ISIS untuk kembali karena urusan keamanan nasional.
Sejak awal keduanya sudah berangkat dari titik yang berbeda dengan bangunan argumen dan justifikasi di posisi yang berbeda. Sejak awal, argumen kemanusiaan dikedepankan dan sebaliknya sejak awal pula argumen tentang keamanan nasional beserta bukti dan konsekuensi-konsekuensinya dipaparkan. Dalam debat bisa jadi yang paling persuasif akan menang. Logika atau kondisi debat tidak membutuhkan rekonsiliasi, tetapi membutuhkan kemenangan atau voting dipenghujung debat demi memutuskan kebijakan yang taktis.
Sedangkan dalam dialog, tujuannya bukan serta merta untuk kebijakan tetapi memperluas cakrawala pihak yang ikut dalam dialog. Toh, jika akhirnya ada pengambilan kebijakan, hal itu diputuskan oleh yang otoritatif dengan selalu bertanya kepada peserta (partisipan) dialog bukan dengan cara voting.
Dalam konteks kasus di atas, proses dialog lebih mengutamakan proses menimpali setiap percakapan dalam diskusi tersebut. Misalnya, diawali dengan pertanyaan, “Bisakah kita menerima eks-ISIS? Bukankah mereka awalnya warga negara Indonesia juga? Mereka tentunya mempunyai pengalaman yang buruk di Suriah yang bisa dibagi di Indonesia sehingga hal itu dapat mencegah warga Indonesia yang lain untuk kemudian terjebak ke tindak terorisme atau radikalisme”.
Lalu ada yang menimpali, “Dalam konteks itu, saya setuju, tetapi jika mereka berpura-pura sadar dan mengebom lagi di Indonesia, bagaimana? Itu kan tujuan utama mereka untuk masuk surga dengan tiket VIP”
Lalu ada pembicara lainnya yang menimpalinya lagi, “Ya, makanya harus ada tahapan agar mereka dapat diidentifikasi aman untuk pulang. Semacam ada penyortiran beberapa tahap yang dilakukan oleh pengamat dan para ahli, bagaimana kalau begitu?”
Lalu pembicara lain yang menimpalinya lagi, “Bisa jadi seperti itu, lalu apa usulannya agar mereka aman kembali?”
Namun ada juga yang lalu menimpalinya, “Saya kira, kita tidak perlu memusingkan semua itu, sebab dengan ikut menjadi bagian dari ISIS, maka ikatan dengan negara atau kewarganegaraan mereka sudah putus dan mereka telah memutuskan secara sadar dan tidak dengan cara baik-baik (pergi diam-diam, dll). Mereka tidak ada sense of belonging sama sekali atas bangsa dan negara ini, Lalu buat apa kita terima? Hal ini bukan kepentingan nasional kita yang utama.”
Lalu ada yang melanjutkannya, “Jika mereka tidak ke Indonesia, lalu apa ada negara atau wilayah yang bisa mereka tinggali? Lalu keluarga mereka yang ada di Indonesia bagaimana? Apakah dipisah dengan keluarga mereka justru membuat hidup mereka makin sengsara? Bisa bisa mereka akan balas dendam kepada bangsa ini digenerasi berikutnya. Karena cara ini justru mengakumulasi kebencian ke generasi kelompok mereka.”
Ada yang menguatkan, “Iya, bisa jadi mereka malah akan melakukan pembalasan ke Indonesia jika tidak diterima kembali. Ini masalahnya bukan cuma pemikiran rasional, tapi urusan sakit hati dan emosi. Saya kira hal ini perlu dipertimbangkan”.
Lalu ada yang menimpalinya, “Hal itu bukannya konsekuensi mereka ya? Mereka pergi bergabung dengan ISIS adalah tindakan dengan sadar dan niat mendalam penuh keyakinan, lalu begitu datang konsekuensi/resiko, mengapa kok jadi kita yang harus menanggung beban mereka. Apakah itu adil?”
Dan seterusnya. Jadi dialog itu banyak arah dan terus berkembang, tidak melulu berkubu lalu menjadi semakin ekstrim perbedaannya. Dialog itu bertujuan untuk membuahkan solusi Bersama (mufakat). Hal ini sudah menjadi tradisi primordial bangsa kita. Oleh sebab itu, tulisan ini menekankan bahwa kembalilah kita ke tradisi dialog dalam membangun peradaban keindonesiaan. Kembalikan tradisi dialog dalam konteks dan proporsinya dan letakkan tradisi debat juga pada wilayahnya secara proporsional dan pantas.