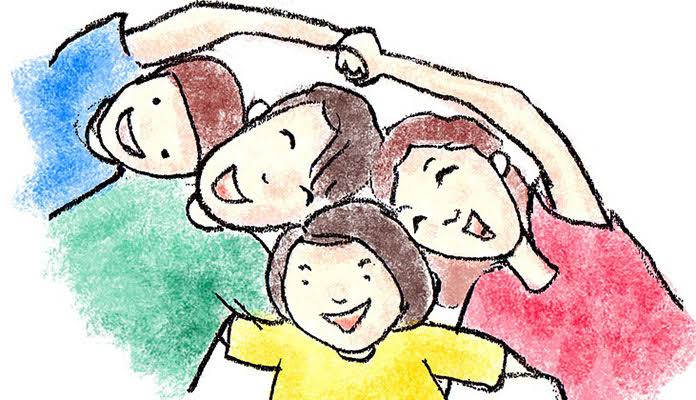Tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tahun. Peringatan itu menjadi momentum yang tepat untuk mendalami makna dari keluarga, khususnya di zaman yang oleh pujangga Jawa kenamaan, R. Ng. Ronggawarsita III (1802-1873), telah diramalkan sebagai zaman edan. Itu artinya, cara pandang terhadap keluarga di zaman ini diharapkan dapat semakin berkembang dan menjadi semacam sekolah yang memungkinkan setiap orang untuk belajar secara bebas dan mandiri.
Dalam konteks ini, Sasaki Shiraishi dalam bukunya, Pahlawan-pahlawan Belia. Keluarga Indonesia dalam Politik (KPG, 2001), menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja Indonesia, khususnya di era Orde Baru, memiliki makna khusus. Artinya, mereka bukan semata-mata dipandang berdasar usia antara 6-12 untuk anak-anak dan 13-22 tahun untuk remaja, namun juga dianggap memiliki kekuatan yang disebut liar dan labil. Karena itu, tak jarang mereka mendapat pengawasan yang melekat (waskat), entah dalam bentuk lisan (kata-kata) maupun tulisan (simbol). Apalagi suara mereka yang diibaratkan seperti bunyi wek-wek-wek dari sekumpulan bebek kerap dinilai sebagai suatu kegaduhan dari pada sebuah kreativitas. Maka, tak heran jika keberadaan mereka tampak lebih sering diabaikan daripada diperhatikan hingga saat ini.
Pada titik ini, Hari Keluarga Nasional dapat menjadi media yang
efektif dan operatif untuk lebih memperkenalkan keluarga sebagai sekolah. Itu artinya, keluarga dihadirkan bukan sekadar sebagai ruang-ruang kelas yang menjejali peserta didik dengan beragam ilmu belaka. Namun, hal itu perlu juga didukung dan dibantu dengan menciptakan hubungan sosial yang berpotensi membiarkan setiap orang bebas berkreasi dan berinisiatif. Salah satunya dengan membentuk relasi kekeluargaan atau famili-isme yang oleh Ki Hadjar Dewantara dijadikan dasar bagi gerakan pendidikan nasional, khususnya melalui Taman Siswa di tahun 1920-an.
Apa sesungguhnya kekhasan dari gerakan pendidikan itu? Pertama, sebagai bagian penting dari gerakan nasionalis awal di Indonesia, sejak semula pendidikan dirancang dengan membebaskan anak-anak untuk bermain dan belajar menurut kemampuan dan kemauan sendiri. Tentu saja para guru tetap mengawasi dan membimbing mereka bukan dengan mata yang menghukum, tetapi memberi keteladanan yang mencerminkan tanggungjawab dan perhatian berdasar kesetaraan dan persaudaraan.
Kedua, penyebutan bapak atau ibu terhadap mereka yang lebih tua bukan dilandasi oleh hubungan kekuasaan atau otoritas yang menyiratkan superioritas dan inferioritas status, melainkan hormat pada yang dituakan. Dengan kata lain, hubungan antara anak dan bapak atau ibu dimungkinkan untuk berbeda pendapat misalnya. Namun, perbedaan itu tidak membuat siapa pun berhak untuk menghakimi, bahkan menghukum, mereka yang dianggap tidak setara, apalagi tidak bisa atau punya apa-apa. Penghargaan seorang terhadap yang lain adalah kunci dari gerakan pendidikan yang toleran, plural, dan tajam.
Ketiga, dalam pendidikan tidak dikenal adanya hukuman. Yang bersalah dituntut untuk membuat suatu pengakuan dan dituntun untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan secara ksatria. Dalam arti ini, anak-anak didik diajar untuk tahu diri, mengerti tugas dan konsekuensi dari segala keputusan beserta tindakannya. Hal itu digambarkan dengan baik dalam sebuah cerita pewayangan di mana sosok Abimanyu tidak takut menentang kakeknya demi dapat bertemu dengan Arjuna, ayahnya sendiri.
Begitu pula dengan para pemuda (Sukarni, Wikana, dan Singgih) yang menculik Sukarno-Hatta dan dibawa ke Rengasdengklok sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945 demi ketetapan hati dan rasa cinta yang berkobar-kobar pada Indonesia. Pada tataran inilah sosok bapak atau ibu sebagai pemandu, guru, dan penjaga memainkan peran dan fungsi penting dalam konsep kekeluargaan/famili-isme yang dikaji ulang melalui pendidikan di sekolah atau kelas.
Tiga kekhasan pendidikan dengan model gaya keluarga” di atas tampak masih relevan dan signifikan untuk dioperasionalkan di masa kini mengingat masalah dan tantangan dalam dunia pendidikan saat ini semakin tak terduga. Terutama dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah, dunia pendidikan diharapkan mampu mengembangkan bukan hanya segala potensi akademik, tetapi sekaligus jiwa dan roh kebebasan dari para pembelajar.
Mengutip pesan penuh makna dari Ki Hadjar Dewantara bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah”, maka menjadikan keluarga sebagai sekolah bukanlah sesuatu yang tak terbayangkan sama sekali.