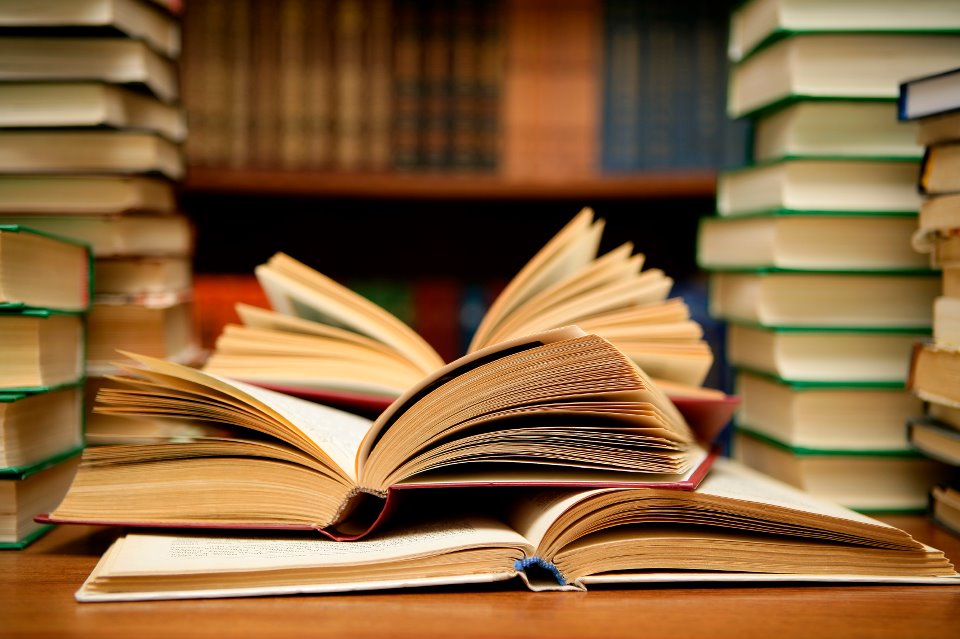Dalam sebuah postingan di sebuah media sosial beberapa waktu lalu, seorang ustadz bernama Sufyan Baswedan, yang mengaku sebagai dai Salafi, menuduh ulama besar dunia Syekh Yusuf Al Qaradhawi bukanlah ulama yang punya ilmu. Ia menyebut Al Qaradhawi tak perlu diambil ilmunya. Tak pelak, pernyataan ini menimbulkan kehebohan di sejumlah kalangan umat Islam di medsos.
Sebagai ulama Mesir yang sangat terkenal Tanah Air, Yusuf Abdullah al-Qaradhawi bukanlah sembarangan orang. Ia adalah ulama moderat yang pernah menjadi ketua umum Persatuan Ulama Dunia (International Union of Muslim Scholars) dan sudah menulis 148 buku hingga usia senja beliau sekarang 94 tahun, penerima King Faisal International Prize, dan lain-lain.
Sebaliknya, dibandingkan al-Qaradhawi, Sufyan Baswedan tidak memiliki rekam jejak yang jelas, baik secara intelektual (semisal jumlah buku yang telah ditulis) ataupun ketokohannya di kalangan umat Islam, baik lokal atau global (kecuali pengakuannya sebagai dai Salafi).
Bagi yang memahami kiprah gerakan Salafi baik di Arab Saudi (lebih popular dengan sebutan sebagai Wahabi) ataupun di Tanah Air, kita dengan gampang mengidentifikasi karakter mereka yang terbiasa mengafirkan (takfir) dan mengambinghitamkan (scapegoating) kelompok Islam yang mereka anggap menyimpang, termasuk kelompok Islam arus utama semisal Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Mereka tak segan-segan menganggap tokoh-tokoh semisal Gus Dur dan Buya Hamka sesat.
Beda pendapat bukan berarti harus bermusuhan dan memfitnah ulama lain yang bukan satu golongan dengan kita. Itu namanya kebusukan. Sayangnya dai-dai Salafi model Sufyan Baswedan dan pengikutnya bukanlah tipe-tipe kelompok Islam dengan kepasitas keilmuan yang tinggi serta memiliki dada yang lapang yang mampu menghargai perbedaan pendapat.
Apa yang menimpa para dai semisal Sufyan Baswedan sejatinya menunjukkan jurang yang menganga lebar (a great yawning gap) antara intelektualitas dan adab. Problem ini sebetulnya menyiratkan bahwa sejumlah pendakwah kita terbentur dengan dua krisis akut.
Pertama, lokalisasi pemikiran. Seorang Sufyan Baswedan begitu percaya diri menilai ulama sekaliber Yusuf Al Qaradhawi tak pantas diikuti lantaran sikapnya yang membatasi lingkar otaknya hanya pada referensi (buku dan tokoh) tertentu secara eksklusif. Artinya ia melokalisasi pemikiran pada ‘spot’ tertentu sehingga keyakinan dan pemahaman agama yang muncul berlari di tempat dan tertutup.
Ketertutupan bahkan resistensi terhadap pemikiran lain tak ada hubungannya dengan level pendidikan seseorang. Ia merupakan buah dari kesempitan jiwa. Ron Ritchhart, seorang psikolog dari Universitas Harvard, menyatakan bahwa kecerdasan otentik lebih merupakan kebiasaan alih-alih hadiah. Ini adalah kecenderungan untuk ingin tahu tentang dunia di sekitar kita, untuk menghargai pemahaman dan pengetahuan daripada keyakinan dan pikiran tertutup.
Layaknya moralis yang selalu memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat, seorang intelektual sejati bakal melihat dunia dan memperlakukan orang lain dengan pikiran terbuka dan rasa ingin tahu, bukan ‘sempit kalang’ karena kebencian dan kebodohan.
Keyakinan itu seperti palu. Ia terkadang menjadi alat yang hebat, tetapi lain waktu bisa menimbulkan masalah. Namun keyakinan di atas pijakan kemerdekaan berpikir selalu memikirkan kemungkinan alternatif, melebihi apa yang sudah Anda ketahui.
Bila toleransi lebih bersifat pasif, keterbukaan pikiran berwatak aktif sebab ia mendorong seseorang bergerak melewati batas interpretasi yang dipahaminya selama ini.
Inilah yang menjelaskan mengapa para ulama empat madzhab tak pernah saling menjelekkan, Buya Hamka memilih berqunut di kala shubuh ketika menjadi imam di kalangan jamaah warga NU, atau sikap ulama top Salafi allahyarham Syekh Bin Baz yang mengakui keluasan ilmu Yusuf Al Qaradhawi terlepas perbedaan antara keduanya.
Bagi mereka, kebenaran dan pendapat adalah hal yang berbeda, dan hanya ketika mereka mengeksplorasi pengetahuan dan asumsi di balik pemikiran sendiri, mereka dapat menyesuaikan pendapat tersebut lewat sikap-sikap toleran tanpa harus mengorbankan keyakinan sendiri. Ulama paripurna mengerti tentang integrasi antara ilmu dan adab.
Kedua, lemahnya tradisi menulis. Kelemahan para dai Salafi di Tanah Air adalah mereka jarang melahirkan buku-buku secara produktif dan menghabiskan banyak waktu berceramah yang ditayangkan secara visual lewat media sosial.
Konsekuensinya mereka tak pernah atau tak terbiasa berpikir dialektis. Buku-buku paham Salafi yang beredar lebih banyak terjemahan dari ulama-ulama mereka di Timur Tengah yang tidak memiliki konteks yang aktual dengan realitas umat Islam di Tanah Air. Hal ini kontras dengan ulama dan cendekiawan dari NU dan Muhammadiyah yang terbilang produktif menghasilkan karya-karya yang kompatibel dengan corak keislaman di Indonesia.
Nama-nama semisal Imam Al Ghazali, Imam Syafi’i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Yusuf al Qaradhawi, Buya Hamka, M Natsir, Nurcholish Madjid atau Quraish Shihab selalu berkibar dan bertahta di hati umat bertahun-tahun karena buku-buku mereka. Usia karya-karya intelektual mereka melebihi umur biologis mereka yang dibatasi ruang dan waktu.
Tidak saja ulama, para pemimpin besar juga dikenang lewat tulisan-tulisannya. Kalau kita mengacu kepada Amerika Serikat, banyak presiden negara Paman Sam bukan hanya suka membaca tapi juga penulis.
Setidaknya ada 18 otobiografi yang ditulis oleh mantan presiden Amerika Serikat, di antaranya George W. Bush, Bill Clinton, George H. W. Bush, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, Herbert Hoover, Calvin Coolidge, Martin Van Buren, dan Theodore Roosevelt.
Bahkan beberapa bulan lalu, mantan presiden Obama meluncurkan karya terbarunya, A Promise Land. “Lebih dari 887.000 unit buku terjual dalam semua format dan edisi di AS dan Kanada pada hari pertama penerbitan, termasuk untuk pre-order. Ini adalah buku pertama terbesar untuk total penjualan, jika dibandingkan dengan buku apa pun yang pernah kami terbitkan,” kata penerbit A Promise Land. Harry S. Truman, Presiden Amerika Serikat ke-33, berkata, “Not all readers are leaders, but all leaders are readers” (“Tidak semua pembaca adalah pemimpin, tetapi semua pemimpin adalah pembaca”). Artinya pemimpin adalah pembaca.
Ulama yang menulis (bukan sekadar tesis atau disertasi) lazimnya memiliki pemikiran yang mendalam dan tidak cenderung menghakimi sebab tradisi intelektual ini menggiringnya bersentuhan dengan gagasan penuh nuansa ala pelangi, ketimbang dunia hitam putih semata. Inilah adab mulia dari orang-orang berilmu.
Kerja-kerja dakwah bukanlah aktivitas mengklaim kapling surga untuk pengikut sendiri dan memfatwakan kelompok Islam lainnya sebagai golongan sesat. Dakwah adalah upaya berkelanjutan (istimrariyah) membawa umat ke jalan Allah, walaupun ia muncul dengan wajah yang berbeda atau pilihan jalan yang beraneka ragam. Bila pesan dakwah adalah bagian dari ilmu, cara berdakwah (uslub) adalah perwujudan adab. Wallâhu a`lam.