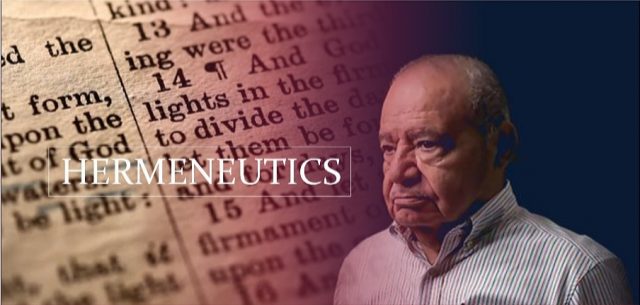Pada bagian akhir tulisan ini penulis ingin memberikan kritik terhadap gagasan Syahrur tersebut. Selama ini kritik yang dilancarkan kepada Syahrur menurut penulis tidak seimbang, karena yang digunakan perspektifnya berbeda. Para kritikus tersebut menggunakan metode keilmuan klasik, sementara Syahrur berangkat dari teori linguistik strukturalis yang tidak ada kaitannya dengan keilmuan tersebut.
Para pengikut Saussure sebenarnya telah banyak melakukan pengembangan terhadap teori strukturalis. Bahkan seperti Derrida telah meninggalkan gagasan Saussure, dan membuat aliran baru, yakni post-strukturalis. Syahrur dalam hal sintesis terhadap konsep linguistik strukturalis tidak begitu memedulikan pembaharuan-pembaharuan tersebut.
Berikut ini beberapa catatan kritis terhadap pemikiran Syahrur. Pertama, teori Syahrur lebih tepat jika dikatakan sebagai strukturalis-tekstualis. Pernyataan ini sebagai bantahan terhadap ulama yang menyebut teori Syahrur dengan historis-ilmiah.
Ciri dasar strukturalis adalah makna yang dibangun dari sebuah bahasa terletak dari struktur yang membangun bahasa itu sendiri. Historisitas yang terletak di luar struktur bahasa, tidak begitu dipedulikan dalam pencarian makna. Peneliti menemukan Syahrur banyak mengabaikan sisi historisitas ini dalam konsep-konsepnya.
Sebagai contoh ketika Syahrur membahas konsep zina dan fahisya (perbuatan keji). Langkah yang dilakukan Syahrur diawali dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang zina. Syahrur kemudian melakukan pemaknaan dengan konsep sintagmatik, mencari relasi makna dari ayat-ayat tersebut. Konteks ayat yang dimaksud Syahrur sebenarnya bukan konteks historis yang sesungguhnya, melainkan relasi makna pragmatik dan sintagmatik dari ayat. Itulah yang dimaksud Syahrur dengan konteks ayat.
Dalam kajiannya tersebut, Syahrur menemukan perbedaan antara konsep zina dengan fahisya. Zina menurut Syahrur adalah hubungan pernikahan (sexual orientation) yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan (bukan suami-isteri) secara terang-terangan. Untuk memperkuat argumentasinya tersebut, Syahrur mencuplik hadis yang menjelaskan bahwa untuk membuktikan seseorang itu berzina atau tidak harus dengan empat orang saksi.
Menurut Syahrur jika zina tidak dilakukan secara terang-terangan, tidak mungkin Nabi Muhammad saw mensyaratkan dengan empat orang saksi. Lebih lanjut Syahrur mengatakan bahwa zina itu hubungan pernikahan (sexual orientation) antara laki-laki dan perempuan (bukan suami-isteri) yang disertai empat orang saksi. Hukuman pelaku zina adalah 100 kali cambuk untuk yang belum menikah dan rajam bagi yang telah menikah. Syahrur tidak mempermasalahkan hukuman ini.
Sementara fahisya (perbuatan keji) yang dimaksud Syahrur adalah hubungan pernikahan (sexual orientation) bukan suami-isteri yang dilakukan secara diam-diam (terselubung). Perbuatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai zina. Oleh sebab itu Syahrur menolak adanya hukuman bagi pelakunya. Menurut Syahrur, cukuplah pelakunya bertaubat karena mengingat Allah.
Dari argumentasi di atas jelas sekali Syahrur mengisolasi makna zina dan fahisya dalam konteks ayatnya saja, atau dari makna pragmatik dan sintagmatiknya saja. Posisi hadis yang dikutip Syahrur hanya sebagai keterangan penguat atau tambahan untuk mengukuhkan tesisnya. Padahal jika Syahrur mengkaji sisi historis yang sebenarnya, tidak hanya dari Al-Qur’an saja, melainkan dalam hadis-hadis juga, pasti akan ditemukan fakta-fakta lain yang bertentangan dengan gagasannya tersebut.
Di dalam hadis diceritakan ada seorang laki-laki bernama Muiz datang kepada Nabi saw dan menceritakan bahwa ia telah menyentuh wanita. Awalnya Nabi saw tidak begitu menghiraukannya. Namun laki-laki tersebut terus mendatangi beliau dan minta disucikan dari dosa. Lalu Nabi saw bertanya: “Apakah kamu hanya meremas-remasnya saja?” Laki-laki itu menjawab: “Lebih dari itu ya Rasulullah.” Lalu kemudian Nabi saw bertanya lagi: “Apakah kamu sadar (tidak gila)?”.
Lalu Laki-laki itu menjawab: “Saya waras”. Nabi saw masih tidak yakin, dan bertanya lagi: “Apakah kamu benar-benar memasukinya?” Lalu laki-laki itu menjawab: “Benar ya Rasulullah.” Mendengar jawaban itu Nabi saw kemudian menyuruh sahabat untuk mencambuknya.
Hadis ini menjawab semua teori Syahrur tersebut (zina dan fahisya). Jika memang pelaku fahisya tidak perlu mendapatkan hukuman, lalu mengapa Nabi saw memerintahkan sahabat untuk menghukumnya?
Penulis tidak berkeinginan masuk dalam perdebatan fikih lebih jauh, biarlah pembaca menilainya sendiri. Penulis hanya ingin menunjukkan bahwa teori linguistik strukturalis yang digunakan Syahrur memiliki celah yang sangat berat (fatal) jika hanya berdiri sendiri. Jika Syahrur ingin membuka diri, dengan memperhatikan sisi historis yang lebih lengkap (syumul), mungkin hasilnya akan berbeda.
Kedua, kelemahan dari pendekatan strukturalis-tekstualis adalah hanya terpaku pada makna yang tercipta dari unsur-unsur pembentuk bahasa saja atau pada makna hasil dari relasi struktur-struktur yang membentuknya. Padahal bahasa komunikasi melampaui itu semua. Dalam bahasa komunikasi terkadang sebuah perintah tidak memuat unsur perintah, begitu juga kalimat larangan belum tentu memuat kata larangan.
Sebagai contoh, diamnya seseorang tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan. Diamnya seseorang bisa jadi mengandung makna tidak suka. Bisa juga diamnya seseorang menunjukan ketidakmampuan mengungkap perasaan atau mendefinisikan sesuatu. Jika Al-Qur’an juga memuat konsepsi bahasa, tentu juga ada model bahasa seperti tersebut di atas.
Penulis melihat, Syahrur terjebak pada model strukturalis-tekstualis saja. Dia tidak mau melihat makna batin (miqshad) yang terkandung dalam sebuah ayat. Syahrur seperti kelompok zahiriyah, yang mencoba mengikat ayat-ayat hukum dengan memasukan konsep bahasa qath’i dan zanni dalam memahami ayat.
Kita ketahui konsep qath’i dan zanni ini sebenarnya banyak ditolak oleh para mufassir, baik klasik maupun kontemporer. Sebab, konsep ini menjadikan sebuah penafsiran menjadi hitam dan putih. Konsep ini juga menutup peluang terjadinya kontekstualisasi penafsiran.
Antitesis terhadap teori tersebut adalah maqasidu syari’ah. Dalam perspektif bahasa, sebenarnya maqasidu syari’ah adalah cara untuk memahami bahasa batin dari sebuah kalimat, dalam hal ini ayat. Jadi maqasidu syari’ah sebenarnya cara memahami tujuan mulia dari sebuah ayat, jika ayat tersebut menunjukkan larangan, maka dicarilah hakikat alasan larangan itu ditulis dalam ayat tersebut.
Begitu juga sebaliknya, jika sebuah ayat menunjukkan sebuah kewajiban, maka perlu dicari hakikat alasan kewajiban itu ditulis dalam ayat. Hanya dalam maqasidu syari’ah sebuah tafsir akan berkembang dan kontekstualisasi hanya terjadi dalam gagasan ini.
Jika dilihat pada contoh penafsiran tentang zina dan fahisya, maka dapat disimpulkan bahwa Syahrur tidak memerhatikan maqasidu syari’ah dari sebuah larangan zina. Hifzu nasl (menjaga keturunan) merupakan tujuan dari perkara zina tersebut. Bahkan sebaliknya konsep fahisya yang digagas Syahrur malah menciptakan, dan memberikan peluang terjadinya perbuatan keji.
Meskipun begitu, pemikiran Syahrur harus diapresiasi dengan baik. Sintesis yang dilakukannya, dengan menerapkan linguistik-strukturalis dalam studi Qur’an, dapat memberikan perspektif baru dalam konstruksi syariah dan penafsiran terhadap Al-Qur’an. Dialah orang pertama, yang mencoba keluar dari pakem yang selama ini juga mengalami kemandegan. Semoga ke depan, ada intelektual yang mampu mengembangkan gagasan Syahrur ini dengan mengkombinasikan berbagai pendekatan lainnya secara lebih kreatif lagi. Wallahu’alam. Selesai.