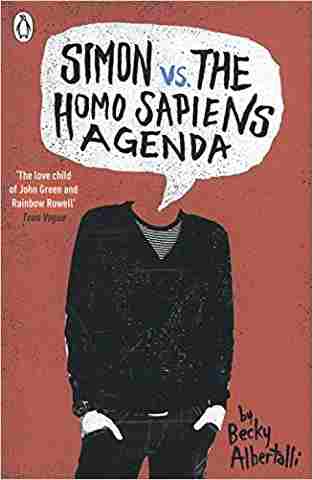John Batista berusia 16 tahun ketika ia membaca “Simon vs. the Homo Sapiens Agenda,” sebuah novel Young Adult (YA) yang mengeksplorasi tema cinta queer.
Meskipun saat itu ia bukan pembaca berat, Batista terhubung secara mendalam dengan buku tersebut: “Buku itu mengirim saya masuk ke ‘lubang kelinci’ (membaca) ini.”
Kini berusia 22 tahun, Batista membagi waktunya antara belajar Bahasa Inggris di York University dan pekerjaan IT. Kecintaannya pada buku tidak mereda, katanya, tetapi menjadi hampir tidak mungkin untuk menemukan waktu — dan energi — untuk membaca sebagai hiburan.
“Membaca membutuhkan usaha yang berkelanjutan, dan saya pikir orang-orang di generasi saya hanya sibuk,” jelasnya. “Antara sekolah dan pekerjaan, sulit menemukan satu jam untuk terlibat dalam sesuatu yang terasa membutuhkan lebih banyak usaha daripada menonton TV atau film.” Membaca, kata Batista, tidak dipandang sebagai sesuatu yang bisa dilakukan untuk bersantai: “Saya memiliki antrean panjang buku yang menumpuk.”
Pengalaman Batista mewakili generasi yang tumbuh dengan internet dan media sosial, yang menurut para ahli telah berkontribusi pada penurunan rentang perhatian kaum muda secara stabil. Sebuah studi Statistik Kanada tahun 2024 menemukan bahwa 42 persen warga Kanada berusia antara 15 dan 24 tahun menghabiskan setidaknya 20 jam seminggu untuk penggunaan internet umum. Kelompok usia yang sama menggunakan smartphone mereka setidaknya sekali setiap jam, sementara hampir setengahnya melaporkan menggunakannya setiap 15 menit.
Dan meskipun kaum muda masih tertarik pada buku — sebuah survei baru-baru ini menemukan 37 persen warga Kanada berusia 18 hingga 29 tahun membaca antara enam dan 11 buku tahun lalu — sebagian besar menghabiskan waktu luang mereka menonton TV atau film, bermain video game, atau menjelajahi media sosial dan internet.
Jason Boyd, seorang profesor Bahasa Inggris di Toronto Metropolitan University (TMU), telah melihat tren ini terwujud secara real time. “Sangat menantang bagi mahasiswa saat ini untuk menemukan ruang mental yang bebas dari gangguan media sosial untuk duduk dan meluangkan waktu untuk memberikan perhatian seperti yang dibutuhkan untuk membaca karya fiksi,” kata Boyd. “Bahkan jika mereka ingin membaca, ponsel mereka bergetar dengan notifikasi setiap beberapa menit dan itu membuat sangat sulit untuk fokus.”
Menambah masalah adalah fakta bahwa alat AI generatif seperti ChatGPT semakin memudahkan siswa sekolah menengah dan universitas untuk melewatkan tugas membaca atau buku, merampas kesempatan mereka untuk mengembangkan kebiasaan mental yang diperlukan untuk terlibat dengan fiksi sastra. Studi terbaru menunjukkan bahwa 60 persen siswa Kanada yang kuliah di universitas, perguruan tinggi, atau sekolah menengah mengatakan mereka menggunakan AI generatif untuk tugas sekolah mereka.
“Alat-alat ini ada di ujung jari mereka dan itu membuat mereka menjadi pilihan yang mudah bagi siswa yang merasa kewalahan, atau tidak ingin terlibat dengan mata kuliah atau literatur,” kata Boyd. Akibatnya, kaum muda saat ini kesulitan meluangkan waktu untuk membaca fiksi — dan terutama fiksi sastra.
“Banyak mahasiswa saya belum membaca buku dalam lima atau enam tahun,” kata Angela Misri, seorang novelis dan profesor jurnalisme di TMU.
Misri mengatakan perubahan ini menandakan masalah masyarakat.
“Kita adalah pendongeng,” kata Misri. “Jika kita tidak dapat fokus pada cerita selama lebih dari 30 detik, kita akan menjadi masyarakat yang sangat tidak sabar, di mana orang tidak dapat memahami perspektif orang lain dengan nuansa apa pun.”
Kekhawatiran atas kebiasaan membaca siswa dengan munculnya AI generatif telah mencapai puncaknya dalam beberapa bulan terakhir.
“Sejumlah besar mahasiswa akan muncul dari universitas dengan gelar, dan masuk ke dunia kerja, yang pada dasarnya buta huruf,” kata seorang profesor Amerika baru-baru ini dalam esai viral yang merinci meluasnya penggunaan AI untuk menyontek di kampus. “Baik dalam arti harfiah maupun dalam arti buta sejarah dan tidak memiliki pengetahuan tentang budaya mereka sendiri, apalagi budaya orang lain.”
Namun tidak semua pendidik siap panik — setidaknya belum.
Arthur Redding, yang telah mengajar sastra Amerika di York University selama 20 tahun, percaya bahwa siswa harus diyakinkan tentang manfaat inheren dari membaca — yaitu menumbuhkan kapasitas mereka untuk menarik diri, merenung, dan berkontemplasi, jauh dari layar komputer atau smartphone.
“Apa yang saya coba lakukan — dan selalu ada siswa yang merespons ini — adalah menunjukkan kepada mereka bahwa membaca adalah salah satu dari sedikit tempat dalam hidup Anda di mana Anda dapat menghasilkan kesenangan dan kegembiraan dan kepuasan,” katanya.
Natalie Neill, seorang penulis dan profesor Bahasa Inggris di York University, yang mengkhususkan diri dalam sastra romantis abad ke-19, menyebut kaum muda sebagai “pencari”: “Mereka haus akan belajar dan mereka ingin mengisi kekosongan dalam pengalaman mereka. Jika Anda dapat menyajikan membaca sebagai cara untuk membuat penemuan baru, itu sangat menarik bagi mereka.”
Neill mengatakan bahwa pendidik harus bersedia menemui kaum muda di mana mereka berada. Misalnya, alih-alih menugaskan seluruh novel, ia sering memberikan potongan teks yang lebih kecil — katakanlah, 50 halaman — kepada mahasiswa tahun pertamanya untuk mendorong pembacaan yang terfokus.
Cara penting lainnya untuk melibatkan siswa dalam fiksi sastra adalah memilih buku yang tepat.
Neill menunjuk pada “Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” karya Robert Louis Stevenson. “Ada begitu banyak tema untuk dianalisis, Anda bisa menyelaminya, tetapi itu juga merupakan cerita doppelganger yang benar-benar luar biasa yang dapat mengajarkan siswa tentang periode Victoria.”
Redding menyebut “Frankenstein” karya Mary Shelley sebagai “buku termudah” yang pernah dia ajarkan.
Tidak hanya cerita itu penting bagi imajinasi budaya kita, jelasnya, itu juga novel yang menciptakan fiksi ilmiah dan novel pertama tentang kecerdasan buatan.
“Ini kuno dan memiliki semua hal hebat tentang yang luhur dan tentang romantisme. Ini adalah novel epistolari dan ada bagian besar dari buku itu, tidak ada yang terjadi, bukan? Namun, siswa selalu melahapnya.”
Namun bagi Redding, cara paling ampuh untuk menumbuhkan kecintaan pada sastra adalah dengan menekankan nilai intrinsiknya: sebagai sumber kesenangan, mesin empati, dan sarana untuk lebih memahami diri sendiri.
“Membaca menempatkan saya di luar dunia saya yang terbatas,” katanya. “Dan dalam pengalaman itu saya menjadi kurang menghakimi, saya menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan perbedaan manusia.
“Tapi untuk mengingat James Baldwin (dalam The Fire Next Time), membaca bukan hanya tentang memaksimalkan kapasitas Anda untuk mencintai dan bertemu orang lain, dan melihat orang lain sebagai manusia; ini tentang belajar mencintai dan bertemu diri sendiri, dan melihat diri sendiri sebagai manusia seutuhnya dan penuh martabat.”
Misri, novelis dan profesor di TMU, juga tetap optimis. “Bukan berarti kaum muda kehilangan kemampuan membaca. Bukan berarti kita berevolusi atau semacamnya,” candanya. Dia percaya bahwa pendidik harus fokus pada gagasan memperkenalkan agensi: “Kita perlu bertanya kepada kaum muda: Jika Anda memiliki perpustakaan di depan Anda dengan semua buku dan cerita yang tersedia, apa yang akan Anda baca, dan bagaimana Anda akan membacanya?”
Sebagian dari itu melibatkan perluasan apa yang secara tradisional dipahami sebagai kanon sastra Inggris — kumpulan buku yang terkenal bias kulit putih dan laki-laki. “Mengapa siswa masih membaca ‘The Outsider’?” tanyanya. “Saya membaca itu ketika saya masih di sekolah menengah.”
Ini adalah upaya yang sudah berlangsung di Ontario, di mana beberapa sekolah menengah meninggalkan Shakespeare demi penulis Pribumi seperti Tanya Talaga, Duke Redbird, dan Lee Maracle. Di tingkat universitas, para profesor mencampur novel klasik dengan karya kontemporer dari penulis yang beragam ras dan gender untuk menjaring kaum muda: penulis seperti Percival Everett, yang novel pemenang penghargaan tahun 2024 “James” mengimajinasikan ulang “Adventures of Huckleberry Finn,” atau Ocean Vuong, penulis Vietnam-Amerika yang berpengaruh yang novel debutnya “On Earth We’re Briefly Gorgeous” mengeksplorasi tema queer dan identitas imigran.
Ini juga berarti menggali dunia sastra Kanada yang luar biasa beragam.
Jacob Alvarado adalah seorang penyair berusia 24 tahun yang tinggal di Toronto. Seperti banyak rekan-rekannya, ia tumbuh dengan membaca fiksi, tetapi kehilangan minat saat remaja. Baru ketika ia mulai belajar menulis kreatif di Sheridan College ia menemukan kembali kecintaannya pada buku.
“Semuanya klop ketika saya menemukan permadani kaya penulis luar biasa yang kita miliki dari negara ini,” katanya.
Sejak pandemi, Alvarado telah terlibat dengan penulis di acara buku yang berlangsung di seluruh kota dan menemukan koneksi manusia di toko buku indie.
“Saya pasti bisa mengerti mengapa orang terkadang pesimis dan ya, mungkin novel sastra tidak berada di pusat budaya seperti dulu,” katanya.
“Tapi ada terlalu banyak kantong kuat penulis muda dan calon penerbit yang melakukan pekerjaan hebat di luar sana.”
“Semuanya klop ketika saya menemukan permadani kaya penulis luar biasa yang kita miliki dari negara ini.”