
Nobel Perdamaian memang tak pernah menghiasi dinding kamarnya. Tapi, jangan ragukan pengaruh besarnya bagi sejarah India dan dunia. Soekarno salah satu tokoh yang terjangkiti virus pemikirannya. Berkali-kali Proklamator RI menyitir buah pikir Gandhi. “Nasionalisme saya adalah kemanusiaan,” kata Bung Besar. Tak kurang Nelson Mandela dan Martin Luther King Jr. pun mengaku diilhaminya. Inspirasi dari pria mantan pengacara ini adalah pusaka peradaban dunia.
Masihkah relevan membicarakan Gandhi? Di tengah noraknya fenomena agama masa kini, masihkah kita bisa mengikuti jejak langkahnya?
Sekilas Sketsa tentang Gandhi
Gandhi pernah menceritakan sendiri kisahnya dalam Semua Manusia Bersaudara (1988). Buku ini menjadi sumber primer dalam usaha melukis sosoknya. Kita akan coba pelajari sepak terjang pemikiran dan perjuangannya. Khususnya, dalam konteks fenomena beragama di Indonesia sekarang.
Di Porbandar, 2 Oktober 1869, lahir seorang bayi laki-laki. Anak itu bernama Mohandas Karamchand Gandhi. Ibunya seorang perempuan saleh bernama Pulitbai, istri ketiga Karamchand Gandhi.
Keluarga Ghandi masuk dalam kasta Bania. Rupanya, mereka berasal dari pedagang bahan pangan. Tetapi sejak tiga generasi, mereka menjabat tugas pemerintahan di negara bagian Kathiawad.
Masa kecilnya tak terlalu istimewa. Dia bukan anak jenius yang menarik perhatian. Malah, Gandhi kecil mengalami kesulitan belajar, pemalu, serta penakut. Namun, benih semangat humanisme sudah bertunas sejak dini di sanubarinya. Belum genap umurnya 12 tahun, Gandhi sudah protes pada ajaran agamanya. Dia berani mempertanyakan dogma yang tidak manusiawi. Paham “tidak boleh bersentuhan” kepada kasta lebih rendah ditudingnya bukan perintah agama.
Rakyat India menggelari Gandhi sebagai Mahatma. Artinya, seseorang dengan jiwa besar. Dia tidak mengharapkan gelar itu. Pernah satu kali, dia malah mengkritik ketika orang mendirikan patungnya di sebuah kuil. Dia benci kalau diperlakukan sebagai orang penting. Kebenaran adalah yang terutama bagi pencetus gerakan swadesi ini. Bukan parade gelar dan jabatan.
Pemikiran dan Cara Perjuangan Gandhi
Pada dasarnya, ide-ide Gandhi sederhana. Kita tidak perlu kejeniusan “Einstein” untuk memahami maksud dan tujuannya. Aforisme “kebenaran selalu sederhana” tampaknya pas disematkan kepadanya. Justru, bagian tersulit dari “filsafat”-nya adalah pengamalannya.
Konsep tentang Tuhan adalah simpul adicita Gandi. Inilah motor perjuangannya. Dia mengatakan, “Tiada Tuhan lain selain Kebenaran”. Kebenaran berasal dari suara dalam diri. Dia hanya menjumpai manusia si rendah hati. “Bila Anda memang ingin berenang di gelanggang samudera kebenaran”, kata Gandhi, “Anda memang harus mengosongkan diri sampai titik nol.”
Oleh karena itulah, Tuhan hanya dijumpai dalam kehidupan. Dia adalah pancaran sinar cinta kasih. Rasa sayang pada kehidupan menjadi sarana utama. Semangat kebenaran universal menunjukkan wajahnya tidak pada sembarang orang. Dia menghampiri mereka yang mampu menyayangi ciptaan terburuk sama seperti dirinya sendiri. Tuhan adalah etika dan moralitas.
Syahdan, tujuan akhir Gandhi hanyalah ingin mencapai Tuhan. Keheningan dan doa adalah ritualnya. Moksa merupakan gaya hidupnya. Sebuah tingkatan hidup yang terlepas dari ikatan keduniawian.
Berdasarkan butir-butir keyakinan inilah, Gandhi memasang rumusan tentang religiositas. Agama hanyalah cara, bukan tujuan. Fungsinya cuma alat. Dia tidak sempurna karena lahir dari manusia invalid. Oleh karena itulah, agama selalu bersifat paradoks. Semua agama itu benar, sekaligus juga mengandung kesalahan. Akibatnya, semuanya sama berharganya, sehingga harus saling menghargai.
“Hakikat agama adalah moralitas,” ini pengakuan Gandhi. Perannya menciptakan damai. Rutinitasnya menyirami benih kasih dengan hujan pengampunan. Agama pengampu watak umat untuk memainkan melodi harmoni cinta. Dengan begitu, kita bisa pahami bahwa “Sesungguhnya tiada agama yang lebih tinggi selain kebenaran dan keadilan”. Inilah denyut nadi agama. Tanpa memperjuangkan ini, detak jantung agama pun berhentilah sudah.
Dari kedua pilar inilah kita bisa menyelami satyagraha dan ahimsa. Dua prinsip dasar roh perjuangannya. Satyagraha berarti mengunggulkan kebenaran lebih dari segalanya. Bersandar padanya berkonsekuensi melenyapkan pembelaan diri. Radiasi satyagraha membuat lawan tak usah menderita, melainkan diri sendirilah yang menanggung dera. Inilah ahimsa: prinsip pantang kekerasan.
Ahimsa sentral dalam perjuangan Gandhi. Dia meyakini bahwa inilah satu-satunya cara memberitakan Kebenaran Tuhan. Beliau tak percaya agama bisa tersebar lewat kata. Hanya tindakan yang membuat agama meluas. Cinta kasih, dalam ahimsa, mengetuk lembut jendela hati manusia.
Ahimsa berlawanan dengan natur manusia. Nafsu kita pada dasarnya condong pada himsa (kekerasan). Sebuah sifat alami hasil dari sebuah proses evolusi panjang peradaban. Siapa kuat, katanya, dia bertahan. Subjek berdaya hancur besar berpeluang hidup lebih tinggi ketimbang yang lemah.
Padahal, alam membuktikan sebaliknya. Bumi tetap lestari, walau di tengah pemusnahan. Dari observasi itu, Gandhi berkesimpulan bahwa ada hukum yang lebih tinggi daripada pembinasaan. Hukum itu bersifat mulia dan memelihara. Dijaganya semesta kehidupan manusia. Itulah hukum cinta.
Tuhan adalah kasih. Inilah dasar dari ahimsa. Bentuk positif kasih sayang dan belas kasihan terbesar. Cinta adalah senapan paling ampuh untuk merobohkan musuh. Kerasnya hati dan hinanya kebodohan akan lumpuh di hadapannya. Gandhi percaya pada kekuatan ini.
Berpantang kekerasan berarti mempercayai keadilan. Tanpa ini, kesediaan menjalani penderitaan mustahil dijalankan. Keadilan tak bisa dicapai dengan berbalas kekerasan. Ahimsa bukan mengelak diri dari perkelahian melawan ketakadilan. Sebaliknya, ini adalah pertarungan yang lebih aktif dan nyata melawan kejahatan. Karena balas dendam sejatinya hanya menambah daftar kejahatan.
Jelaslah bahwa satyagraha dan ahimsa adalah sebuah cara perjuangan. Keduanya tak bisa diceraikan. Bagi Gandhi, cara adalah tujuan itu sendiri. Begitu cara dikerjakan, tujuan serta merta mencerminkannya. Cara mulia, pertanda agungnya tujuan. Sebaliknya, cara salah, indikasi tersesatnya arah impian.
Relevansi Pemikiran Gandhi di Indonesia
Agama di Indonesia sedang gamang. Eksistensinya mengkhawatirkan. Fenomena sekarang memperlihatkan wajah garang agama lebih tampak dari senyum ramahnya. Dia menyumbang banyak masalah. Fakta menunjukkan, agama lincah mengoyak rajutan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kemanusiaan diacuhkan, bahkan dikhianatinya. Semua berawal sejak agama takluk pada rayuan gombal perempuan cantik bernama politik.
Sebenarnya, itu tak ada salahnya. Bahkan, Gandhi akan memberkati perkawinan itu. Dengan tegas dia menyatakan, setiap orang yang melarang agama terjun kepolitik, sesungguhnya tidak mengerti agama. Politik adalah ladang perjuangan dalam mewujudkan impiannya tentang kemanusiaan.
Namun, persoalannya tidak berhenti di situ. Setidaknya, ada dua fokus utama jika mengacu pada fenomena di Indonesia. Pertama, tentang tujuan. Kedua, tentang cara. Seperti diungkap sebelumnya, bagi Gandhi keduanya tak bisa ditalak-tigakan.
Gandhi menyelami politik dengan alasan jelas. Dia melihat posisi taktis bidang ini dalam mewujudkan nilai-nilai yang diyakininya. Dia melihat politik berperan vital dalam mewujudkan perdamaian. Jalur ini diyakininya bisa menaikkan valuta kemanusiaan. Lereng penuh diplomasi ini dipercayainya berdaya menghidangkan kemerdekaan bagi semua orang. Politik baginya tidak bicara tentang kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tapi, demi semesta kemanusiaan.
Berbeda jika mengamati situasi Indonesia terkini. Tujuan sekelompok penganut agama melompat ke politik sangat bias. Isu-isu yang diangkatnya murahan. Malahan, nyaris tak berguna. Dia seperti tidak pernah membicarakan persoalan penting rakyat Indonesia. Dia sibuk mengurusi receh, sampai lupa perkara utama: tentang manusia.
Gandhi mengatakan bahwa agama adalah alat untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi, itu terbalik di sini. Agama, oleh sekawanan orang, malah diperalat. Mereka merelakan diri digunakan sebagai perkakas untuk kepentingan segelintir kelompok. Jabatan religius digincu agar berotoritas membangun tirani. Ajarannya dipermak supaya cocok dengan nafsu kekuasaan.
Mengenai cara, Gandhi memang organisator ulung. Dia mampu menghimpun massa untuk bergerak dengan satu tujuan. Dia punya keterampilan “provokasi”. Dia bisa menggugah kesadaran, mengaduk-aduk perasaan, syahdan menggelorakan perjuangan. Namun, itu semua dilakukannya selaras dengan prinsip ketuhanan yang diyakininya. Tuhan adalah kasih, etika, dan moral.
Teladan hidup digunakan Gandhi untuk “menghasut” banyak orang untuk bertindak. Ketika kebijakan industri tekstil Kerajaan Inggris merugikan rakyat India, dia melawan. Tapi, bukan dengan membakari pabrik. Dia memboikot produk itu dengan memintal kain sendiri. Dia pun menentang monopoli garam oleh penjajahnya. Gandhi mengajak rakyat India untuk memproduksi sendiri.
Umat Muslim dan Hindu berkelahi sampai jatuh korban. Gandhi tidak memihak pada Hindu, agamanya sendiri. Dia pun tidak membela umat Muslim. Dia memilih bertanggung jawab atas tragedi ini. Dia menderitakan dirinya sendiri. Dia berhenti makan; berpuasa sampai perang itu berakhir.
Satyagraha dan ahimsa adalah pedang tombaknya dalam menggalang massa. Dia mendidik dengan integritas. Dia menumpulkan parang dan menyediakan secangkir teh untuk musuhnya. Caranya memperjuangkan prinsip adalah dengan damai, pantang kekerasan, dan pengampunan.
Lihatlah peristiwa nyata di Indonesia. Semuanya berbalikan dengan teladan Gandhi. Sekawanan orang berjubah religius membakar amarah massa dengan ujaran kebencian. Mereka dididik untuk merawat dendam. Matanya digelapkan oleh ambisi cetek menjurus caper. Kekerasan dalam bentuk kata dan pentungan jadi idola. Caranya berjuang sudah jelas adalah cerminan tujuannya.
Sekali lagi, tak ada salahnya jika agama mengurusi politik. Ladang itu pun harus digemburkan tanahnya dengan bajak firman Tuhan. Politik juga medan dakwah bagi agama. Tapi, kemurnian tujuan dan konsistensi caranya tetap perlu dijaga.
Persis inilah warisan pusaka Gandhi. Gelar Mahatma memang pantas dikalungkan kepadanya. Dia taat dalam asas perjuangannya. Harmonisasi antara tujuan dan cara mampu dijaganya ketat. Keduanya tak dibiarkannya saling menikam.
Sementara, kini, di sini, fenomena sekelompok penganut agama dan pemimpinnya justru sebaliknya. Tujuan dibiarkan mengkhianati cara, pun sebaliknya. Itu pertanda perjuangannya tak punya prinsip. Motifnya nafsu semata.
Dalam situasi seperti inilah, teladan Gandhi masih tetap relevan. Dia harus terus hidup. Itu demi mendewasakan kita di Indonesia. Kita harus belajar bahwa melaksanakan cinta bukanlah perkara mudah. Tak salah jika satyagraha dan ahimsa (memang) adalah sebuah mahakarya abadi. Ajaran ini akan terus relevan selama manusia tidak mampu mengekang nafsu dan ambisi duniawinya.

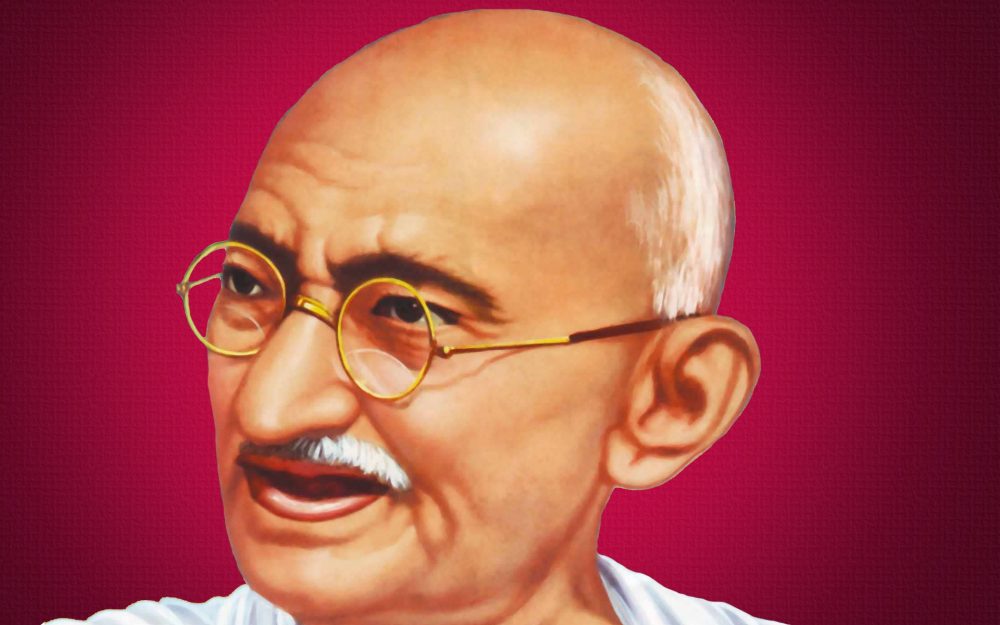
![Ormas Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai menyinggung umat muslim beberapa waktu lalu, di pusat Kota Lhokseumawe, Aceh, Jumat (14/10). [ANTARA/ Rahmad]](https://geotimes.co.id/wp-content/uploads/2016/11/antarafoto-unjuk-rasa-kecam-ahok-141016-rmd-1-300x200.jpg)