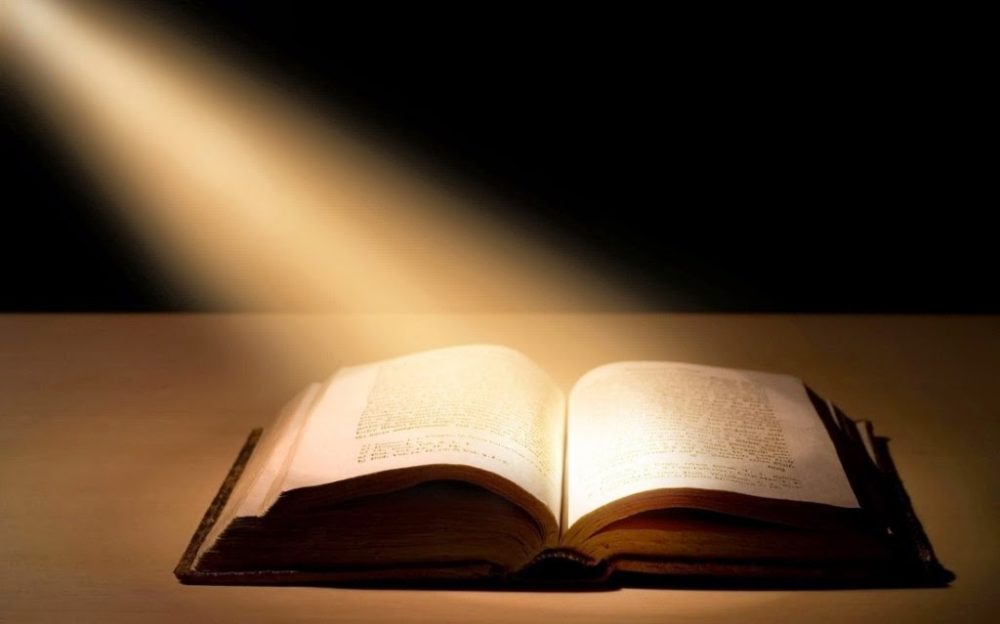Ada kesalahan asumsi umum bahwa tafsir kontekstual itu mengabaikan teks al-Qur’an atau menolak nilai-nilai universal al-Qur’an. Lebih parah lagi, tafsir kontekstual dianggap menjadikan teks al-Qur’an bersifat inferior (lebih rendah) dari konteks penafsirnya. Kesalahan asumsi ini umumnya bermuara dari ketidakpahaman tentang bagaimana cara tafsir kontekstual bekerja atau berfungsi.
Ada kesalahan asumsi umum bahwa tafsir kontekstual itu mengabaikan teks al-Qur’an atau menolak nilai-nilai universal al-Qur’an. Lebih parah lagi, tafsir kontekstual dianggap menjadikan teks al-Qur’an bersifat inferior (lebih rendah) dari konteks penafsirnya. Kesalahan asumsi ini umumnya bermuara dari ketidakpahaman tentang bagaimana cara tafsir kontekstual bekerja atau berfungsi.
Pijakan utama tafsir kontekstual adalah teks dan konteks. Tanpa teks, tafsir model ini tak bisa bekerja. Ketika sarjana asal Pakistan, Fazlur Rahman, mengusulkan metode “double movement” untuk menggali pesan-pesan dasar (basic élan) al-Qur’an, dia menekankan pentingnya mengetahui konteks al-Qur’an, bahkan bagaimana teks al-Qur’an dipahami oleh audiens pertama di zamannya.
Metode “double movement” yang diusulkan Rahman itu pun dimaksudkan untuk merespons gagasan teoritisi Jerman Hans-Georg Gadamer yang menganggap makna teks sepenuhnya tergantung perspektif pembaca yang dibentuk oleh konteks zamannya. Gadamer berargumen, setiap pembacaan/pemahaman dipengaruhi oleh konteks-konteks tertentu yang mengitari pembaca.
Dalam karya besarnya, Truth and Method (1975), ia menulis “understanding is, essentially, a historically effected event.” Artinya, tidak ada pemahaman yang tidak dipengaruhi oleh sejarah pembacanya.
Bagi Rahman, pandangan Gadamer ini terlalu ekstrem karena mengabaikan sejarah teks. Saya kira, kritik Rahman salah alamat. Yang ditekankan Gadamer, horizon pembaca tidak berdiri sendiri melainkan berdialektika dengan horizon lain. Proses pembauran horizon (fusion of horizons) itu membentuk pengetahuan seseorang dan mempengaruhi pemahaman teks.
Namun demikian, Rahman dan Gadamer bersepakat bahwa pemahaman teks tidak bisa terlepas dari konteks. Saya akan mengelaborasi poin terakhir ini dengan mendiskusikan di mana sebenarnya makna teks berada untuk menunjukkan keniscayaan tafsir kontekstual.
Tiga Pendekatan
Salah satu poin penting dalam filsafat hermeneutika adalah pertanyaan berikut: Di manakah makna sebuah teks berada? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dikembangkan piramida hubungan antara penulis (author), teks (text) dan pembaca (reader). Bisakah pembaca memahami teks sebagaimana dimaksudkan oleh penulisnya? Apakah teks mengandung makna yang beragam? Mengapa setiap pembaca menafsirkan sebuah teks yang sama secara berbeda?
Sebagai respons atas pertanyaan di atas, muncul tiga pendekatan yang didasarkan pada hubungan penulis-teks-pembaca itu. Pertama, pendekatan yang memusatkan pada penulis (author-centered approach). Dalam pendekatan ini, makna teks dipahami terletak pada kehendak sang penulis. Ketika seorang menulis sebuah teks, ia bermaksud mengkomunikasikan sesuatu. Dengan demikian, makna yang benar adalah yang sesuai dengan maksud penulis.
Dan untuk mengetahui makna teks diperlukan penelusuran bukan hanya terhadap konteks sang penulis tapi juga faktor yang menyebabkan lahirnya teks. Dalam tradisi tafsir al-Qur’an–atau kitab suci agama apa pun–perlu pemahaman tentang asbab al-nuzul atau sebab-sebab turunnya wahyu. Apa iklim yang menyebabkan munculnya teks? Apakah sebuah teks merespons suatu peristiwa tertentu? Jika konteks-konteks tersebut bisa dibongkar, maka locus makna teks akan terkuak.
Pendekatan kedua disebut text-centered approach karena menekankan pada teks, bukan penulisnya. Pendekatan ini diminati oleh kaum strukturalis dan menjadi dominan sejak lahirnya apa yang disebut “New Criticism” tahun 1950-an. Pendekatan ini menekankan dua hal: otonomi teks dan peran pembaca dalam memproduksi makna sebuah teks.
Otonomi teks merupakan batu loncatan pendekatan yang memusatkan pada teks ini. Makna teks tidak lagi tergantung pada apa yang dimaksudkan oleh penulisnya. Sebab, kita memang tidak akan pernah tahu secara pasti apa makna yang dikehendaki oleh sang penulis. Roland Barthes, dalam esainya yang ditulis tahun 1967, secara gamblang menggambarkan bahwa ketika sebuah teks sudah berada di ruang publik, maka penulisnya telah mati (the death of the author).
Pendekatan ketiga menekankan pentingnya peran pembaca, dan karenanya disebut reader-centered approach. Pendekatan ini mengembangkan model kedua lebih jauh lagi dengan berargumen bahwa, bukan hanya penulisnya mati, makna teks tergantung pada pembacanya. Pembaca berbeda memahami sebuah teks yang sama secara berbeda.
Bahkan, sebagian penggagas model ketiga yang radikal menyebutkan bahwa pembaca menciptakan makna sebuah teks. Namun, ada juga yang berargumen bahwa sebuah makna diproduksi dari interaksi antara teks dan pembaca. Dengan kata lain, makna merupakan produk dari kolaborasi antara pembaca dan teks, dan bukan semata ciptaan pembaca.
Makna Teks dalam Tiga Dunia
Mungkin ada yang bertanya: Lalu, di mana letak penafsiran literlek atau harfiah dalam tiga model pendekatan di atas? Semua pendekatan di atas mengaitkan penafsiran dengan konteks, apakah itu konteks penulis, teks ataupun pembaca. Jadi, tafsir kontekstual itu tak terhindarkan!
Memang, banyak orang salah kaprah mengkontraskan tafsir kontekstual dengan tafsir literlek. Lawan makna literlek sebuah teks itu bukan makna kontekstual, melainkan makna metaforikal. Jika sebuah teks tidak dimaknai secara harfiah, berarti yang dikembangkan adalah makna majaziyah atau figuratif (mistikal and alegorikal).
Nah, untuk lebih menegaskan keniscayaan tafsir kontekstual, berikut saya berikan ilustrasi yang dapat memudahkan kita memahami tiga model pendekatan di atas. Di manakah makna teks al-Qur’an itu berada? Ada tiga asumsi, yakni di dalam teks, di belakang teks dan di depan teks.
Text-centered approach mengasumsikan bahwa makna berada di dalam teks itu sendiri. Tugas seorang mufasir adalah menyingkap makna yang sudah ada dalam al-Qur’an. Karena Allah tidak mewahyukan diri-Nya (seperti dalam Kristen), melainkan kemauan-Nya dalam firman yang berbentuk kata-kata, maka watak teks menjadi sentral dalam memahami kehendak Allah.
Karena itu, para mufasir mengembangkan berbagai metode untuk menyingkap makna teks al-Qur’an. Ada yang menggunakan metode tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an (menafsirkan al-Qur’an dengan bagiannya yang lain), ada yang menggunakan filologi atau tata bahasa, dan ada juga yang menekankan aspek literer dari al-Qur’an.
Sekali lagi, model tafsir yang menekankan aspek-aspek teks ini tidak harus bersifat literlek. Sebaliknya, asumsi dasarnya adalah teks menyimpan lautan makna yang dapat disingkap oleh mufasir dengan beragam metode yang mereka kembangkan. Di sini ada semacam relativitas makna teks.
Author-centered approach berangkat dari asumsi berbeda: ada makna tertentu yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap teks al-Qur’an. Makna teks tidak berada di dalam teks, melainkan di belakang teks (in the author’s mind). Untuk mengetahui makna di belakang teks, para mufasir dapat menggunakan sumber-sumber di luar al-Qur’an seperti asbab al-nuzul atau sejarah hidup Nabi. Pandangan ini masih cukup dominan dalam tradisi tafsir, walaupun sudah mulai disadari kompleksitasnya.
Sementara itu, reader-centered approach menganggap makna teks tidak berada di dalam atau di belakang teks, melainkan di depan teks. Pendekatan ini mengakui adanya proses pembacaan yang kompleks. Tanpa penulis memang tak akan ada teks, tapi tanpa pembaca teks tak punya makna.
Lihat saja apabila al-Qur’an tidak dibaca, maka pasti tidak punya makna. Sebuah teks akan punya makna apabila terjadi pertautan antara pembaca dan teks. Artinya, makna teks tidak bermula dari sejak adanya teks, melainkan ketika dibaca. Itulah mengapa makna tidak berada di dalam atau di belakang teks, melainkan di depannya ketika teks dan pembaca saling berhadapan.
Tentu saja tiga dunia makna teks tersebut tidak bersifat mutually exclusive (terpisah satu sama lain). Seorang mufasir dapat mengadopsi salah satunya atau semuanya. Banyak mufasir mengintegrasikan ketiganya. Dan pilihan metodologis para mufasir itu pun dipengaruhi oleh konteks tertentu.
Baca juga: