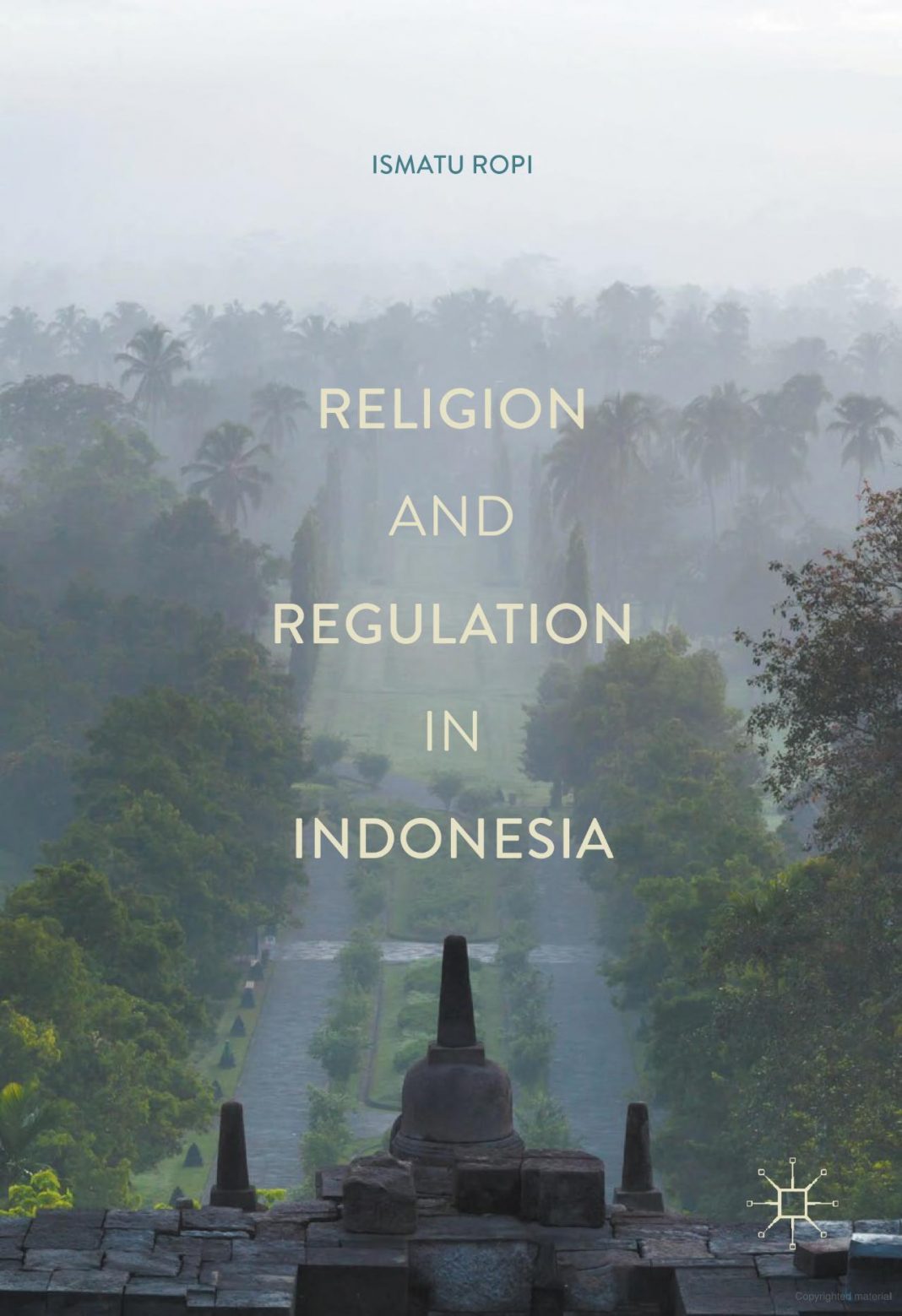Persoalan paling mendasar yang masih mendekam dalam kehidupan beragama di Indonesia berkelindan dengan bagaimana negara mengatur dan merekognisi agama-agama yang eksis di dalamnya. Alih-alih telah selesai dengan sistem non-teokratis dan non-sekularnya, terbukanya kran demokrasi pasca reformasi 1998, justru menyulut beberapa kelompok yang sempat dan telah disumbat suaranya untuk kembali berteriak lantang menyuarakan perihal sistem dan formulasi terbaik yang dapat menampung aspirasi keagamaan mereka.
Alih-alih berhasil menjadi negara paripurna, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” justru menjadi batu sandungan tersendiri bagi kelompok-kelompok non-konformis atau non-ortodoks, seperti aliran-aliran kepercayaan atau kebatinan, kelompok gerakan keagamaan baru (new religious movement), serta penganut agama leluhur (indigenous people), untuk mendapatkan rekognisi administratif yang setara lagi adil, seperti yang didapat oleh kelompok arus utama.
Problem itu menunjukkan bahwa ada yang belum selesai dengan regulasi agama di negara kita. Di permukaan ia tampak tenang dan tidak bermasalah, namun di dasar akar rumput ia menampilkan riak-riak penuh gejolak dan ketidakstabilan. Serumit itukah pengaturan negara terhadap agama-agama yang ada di Indonesia? Sepilah-pilih itukah negara memperlakukan pilihan agama non-ortodoks dari warga negaranya?
Buku Religion and Regulation in Indonesia yang ditulis Ismatu Ropi ini menjadi salah satu medium penting untuk menguliti masalah regulasi agama di Indonesia yang dibaca melalui analisis sejarah dan politik. Melalui buku ini, Ropi menvisualisasikan dengan cukup bernas perihal peraturan-peraturan yang diintroduksi oleh pemerintah Indonesia berikut dengan konsekuensinya terhadap kehidupan beragama warga negara yang hidup di dalamnya.
Karya ini merupakan konversi dari disertasi Ropi di the Australian National University (ANU), Canberra. Pada bagian mukadimahnya, Ropi mengaksentuasikan bahwa karyanya ini bukanlah kajian legal yang dimaksudkan untuk memaparkan secara holistik terkait bagaimana dan harus seperti apa undang-undang itu diterapkan pada isu-isu agama, melainkan, diarahkan pada upaya untuk melihat dampak buruk dari penerapan undang-undang tersebut terhadap kebebasan beragama dari setiap kelompok berikut dengan keterbatasan atas ekspresi terhadap kebebasan itu.
Urgensi Regulasi Negara terhadap Agama
Secara umum, Ropi memandang bahwa tujuan adanya regulasi terhadap agama dalam suatu negara adalah baik, sepanjang regulasi tersebut diorientasikan untuk mengakui, mengelola, dan secara bersamaan difungsikan untuk mengatur kehidupan beragama sebagai salah satu bagian dari pelayanan pemerintah terhadap pilihan agama dari warga negara yang hidup di wilayah tersebut. Untuk menjelaskan persoalan regulasi negara terhadap agama itu, pada bagian kedua dan ketiga Ropi mengulas pelbagai jenis model regulasi, model konstitusi, jenis rezim, dan komposisi masyarakat berdasarkan pengalaman pelbagai negara untuk menteorisasikan tentang politik regulasi yang berlangsung di wilayah Indonesia ini.
Bagi Ropi, regulasi yang dibentuk negara untuk mengelola kehidupan beragama warga negaranya adalah baik, sepanjang kebijakan tersebut akomodatif terhadap semua kelompok beragama. Tetapi, pada saat yang sama, Ropi memberikan lampu peringatan bahwa regulasi itu juga harus mengakomodasi sekaligus memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh kelompok-kelompok minoritas terpenuhi secara proporsional dan mampu mengurai potensi konflik yang memungkinkan bergejolak. Sebaliknya, Ropi menilai bahwa regulasi negara itu akan menjadi buruk apabila aspirasi dari kelompok yang secara kuantitas lebih sedikit ketimbang yang mayor justru sengaja ditanggalkan.
Berkaitan dengan bagaimana negara menerapkan regulasi pada agama-agama, Ropi mengklasifikasikannya pada lima level revelasi yang berbeda yaitu, netral, favoritisme, diskriminasi, restriksi, dan persekusi. Masing-masing level tersebut diulas secara definitif berikut dengan studi kasus yang terjadi berdasarkan pengalaman beberapa negara.
Sebagai contoh, pada level persekusi, Ropi mendefinisikannya pada setiap regulasi yang cenderung menampilkan corak kekerasan dan bersifat koersif terhadap kelompok minoritas. Pada kasus-kasus tertentu, persekusi juga mengacu pada setiap tindakan pelecehan, baik terhadap kelompok ataupun individu. Salah satu contoh revelasi negara yang persekutif itu dapat dilacak dari perlakuan pemerintah Myanmar terhadap kelompok Muslim di Rohingya; yang mana umat Muslim di sana tidak di akui sama sekali tempat tinggalnya dan dalam beberapa momentum seringkali di persekusi oleh militer Myanmar.
Dalam kaitannya dengan kasus di Indonesia, Ropi mencatat bahwa ada banyak kasus yang menvisualisasikan bagaimana model revelasi diterapkan di negara ini. Sebagai misal, Ropi mengidentifikasi bahwa kepemimpin rezim Orde Baru menjadi salah satu potret buram dari perlakuan negara terhadap kelompok-kelompok nor-konformis — seperti Ahmadiyah, Syiah, dan Saksi Yehuwa — yang disinyalir konfrontatif dengan kepentingan politik atau agama rezim. Dalam kasus tersebut, pemerintah tidak hanya bertindak diskriminatif ataupun persekutif, melainkan juga memberikan keberpihakan yang berlebihan kepada kelompok-kelompok arus utama, terkhusus kepada Islam.
Reifikasi Agama
Pada bagian keempat, Ropi mendedah proses reifikasi makna “agama” di Indonesia; dari yang awalnya tidak memiliki kriteria baku (untuk disebut agama), menjadi sistem terinstitusionalisasi yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia sekaligus menjadi identitas pembeda antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya, termasuk di dalamnya sebagai alat politik. Proses reifikasi agama di Indonesia dapat dilacak dari Nagarakÿtÿgama Jawa Kuno — kumpulan naskah-naskah hukum Majapahit pada abad ke-14 — yang difungsikan oleh kerajaan itu sebagai sumber hukum yang mengikat interaksi komunal masyarakat dengan sistem yang diberlakukan di kerajaan.
Namun, definisi agama model demikian tidak bertahan lama. Ropi menilai bahwa agenda kolonialisme, yang terutama bermula sejak kedatangan Portugis dan Belanda pada akhirnya mengubah konsepsi tentang agama dan kebijakan politik yang diproduksinya. Berdasarkan temuannya, Ropi mencatat ada tiga kecenderungan umum bagaimana Belanda mengatur urusan agama.
Pertama, sejak pertengahan 1500-an hingga pertengahan 1700-an Belanda bersikap netral atau menjaga jarak tertentu dari agama. Kedua, di tahun 1800-an Belanda bersifat akomodatif tetapi pada saat yang sama memantau kegiatan keagamaan; dan ketiga, dari pertengahan 1800-an hingga 1900-an dan seterusnya bersifat represif dan mempertahankan kontrol ketat terhadap aktivisme Islam (h. 46-47).
Selain itu, Ropi turut mengidentifikasi bahwa datangnya misonaris Kristen ke Indonesia turut memengaruhi berubahnya makna agama menjadi simbol kemajuan sosial dan pendidikan. Transformasi makna agama itu, dapat dilihat dari berlakunya sistem pendidikan dan administrasi hukum Eropa yang telah dan sedang berlaku dalam konteks Indonesia modern saat ini. Sampai titik ini, Ropi hendak menegaskan bahwa keterlibatan rezim dalam kehidupan beragama merupakan bagian penting yang tidak pernah absen dari sistem politik Indonesia yang berlangsung hingga masa kiwari saat ini.
Selanjutnya, pada lima bab berikutnya (5, 6, 7, 8, 9) Ropi menapaktilasi bagaimana sengitnya perdebatan para founding fathers dalam menentukan bentuk negara (the form of government) dan dasar negara (the basis of the state), berdirinya Kementerian Agama sebagai konsesi bagi umat Islam, dan digunakannya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai acuan regulasi bagi kehidupan beragama di Indonesia.
Bagi Ropi, disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara berikut dengan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah serpihan-serpihan penting untuk melihat bagaimana negara merekognisi agama. Pancasila sendiri dianggap sebagai kalimatun sawa’, meminjam istilah Nurcholish Madjid, untuk melerai perdebatan apakah negara ini harus menerapkan sistem sekular atau teokratis. Sementara, “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah idiom yang diperkenalkan Muhammad Hatta sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan Hadikusomo tentang penghapusan tujuh kata Islam dalam pembukaan UUD 1945.
Problemnya, alih-alih dengan sila itu negara mendukung heterogenitas kehidupan beragama warga negaranya, namun yang tampak justru adalah penyederhanaan; semua agama seolah dianggap memiliki konsep yang sepenuhnya sama dan semua agama diberangus agar seolah-seolah bertuhan pada Tuhan yang satu.
Ambivalensi dari sila itu, yang penilaiannya serupa dengan Ropi, salah satunya dapat dilihat pada Azis Anwar Fachrudin Polemik Tafsir Pancasila (2018), yang menyatakan bahwa ungkapan dan tafsir terhadap Pancasila, termasuk pula tafsir terhadap sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak sepenuhnya stabil melainkan sangat tergantung dan menyisakan lubang yang menganga bagi perbedaan pemahaman, dan bahwa setiap penafsirannya sangat memungkinkan bersifat politis atau bahkan polemik.
Sebagai lanjutannya, pada bab kesepuluh, Ropi mengulas pergeseran agenda politik rezim Orba yang mengalihfungsikan peran Kementerian Agama, dari yang awalnya berperan sebagai perwakilan politik kelompok Islam menjadi institusi yang difungsikan untuk mempromosikan kebijakan pembangunan rezim sekaligus sebagai kontrol ketat bagi kegiatan-kegiatan keagamaan.
Konsekuensinya, negara banyak sekali melakukan pembatasan aktivisme keagamaan dari kelompok-kelompok yang dituduh distingtif dengan kebijakan pemerintah seraya membenarkan diri atas nama pemeliharaan stabilitas nasional dengan mengeluarkan sejumlah regulasi untuk menjaga kerukunan — atau meminjam istilah Trisno Sutanto, lebih tepat jika disebut dengan ‘perukunan’ — antar umat beragama.
Salah satu kebijakan rezim Orba dalam menciptakan (p)erukunan antar agama itu ialah memberi wewenang sangat besar melalui UU No.1/PNPS/1965. Dengan UU itulah negara menggunakan Departemen Agama untuk menghakimi kelompok-kelompok yang disinyalir konfrontatif dengan kebijakan Orba. Dalam kasus ini, rezim tersebut secara restriktif melarang beredarnya beberapa kelompok sempalan, termasuk pula melarang perkembangan Konghucu, dan secara bersamaan menegaskan ortodoksi kelompok keagamaan arus-utama.
Regulasi yang Bertumpuk dan Bejibun
Sebagai akibat dari kontrol rezim Orba yang sangat ketat itu, pada bab-bab berikutnya (11, 12, dan 13), Ropi mengidentifikasi bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang paling banyak mengatur sekaligus paling detail mengawasi cara beragama warga negaranya. Berdasarkan temuannya, Ropi mencatat bahwa ada 110 peraturan lebih yang telah dikeluarkan oleh rezim Orba sepanjang tahun 1965 sampai dengan 1995 guna mengontrol kehidupan beragama warga negaranya (hal. 141).
Nahasnya, peraturan yang sedemikian bejibunnya itu tidaklah secara serius dijadikan sebagai pijakan untuk menjamin hak kebebasan beragama bagi seluruh kelompok keagamaan, khususnya bagi mereka yang berasal dari kalangan minoritas. Alih-alih mengakomodasi, banyaknya peraturan itu justru berimbang dengan masifnya kasus pelanggaran kehidupan beragama.
Terdapat banyak kasus yang menjadi dasar bahwa negara tidak sungguh-sungguh mengelola, mengatur, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan beragama warga negaranya. Bahkan, semua hal tersebut berjalan di atas landasan hukum yang kuat, mulai dari UU, peraturan, maupun instruksi dan surat menteri. Efeknya, regulasi-regulasi itu sangat berdampak signifikan terhadap kondisi kebebasan beragama serta unsur yang lainnya.
Sebagai salah satu buktinya, pada bagian terakhir bukunya, Ropi menampilkan tiga kasus yang menjadi persoalan lama namun masih suluh dan menjadi masalah besar bagi kehidupan beragama warga negara di Indonesia hingga hari ini. Masalah pertama berkaitan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Rumah Ibadah, sementara yang lainnya berkaitan dengan regulasi yang restriktif terhadap kelompok Ahmadiyah, dan UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
Menariknya, dari ketiga regulasi yang kontroversial itu, terutama dalam persoalan kasus terakhir, Ropi memberikan penilaian yang berbeda dari kalangan aktivis kebebasan beragama secara umum. Ropi mencatat bahwa pemerintah lebih banyak memakai UU itu dengan istilah valification law (larangan untuk menyalahgunakan agama) dibanding blasphemy law (larangan menodai agama). Perbedaan itu dipandang Ropi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana negara menjaga kebebasan beragama setiap warga negaranya, melainkan juga berkaitan dengan boleh atau tidaknya pihak negara mengambil tindakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan ajaran agama agar tidak salahgunakan.
Jika UU penodaan agama itu menjadi salah satu fitur yang memperunyam — untuk tidak mengatakannya merusak — kehidupan beragama di Indonesia, maka pertanyaan umum yang dapat disodorkan kepada buku Ropi ini, ialah apakah digunakannya istilah valification law mengandaikan bahwa agama harus mendapat jaminan dari negara agar bebas dari penghinaan? Bukankah yang dijamin dalam kebebasan beragama, seperti yang tercantum dalam naskah DUHAM dan ICCPR, ialah manusianya, tidak agamanya? Dengan demikian, mengapa agama harus dilindungi dari penghinaan dan kenapa UU itu masih terus dilanggengkan hingga hari ini?