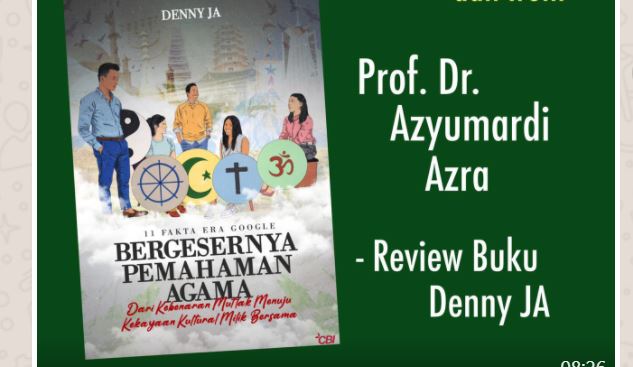- Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021
Fenomena, gejala, dan ekspresi keagamaan kontemporer di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia sangat kompleks.
Itu dilihat dalam kemunculan dan perkembangan teologi, doktrin, dan ritual agama itu sendiri maupun terkait bidang-bidang kehidupan lain.
Fenomena agama dalam tiga dasawarsa terakhir—sejak 1990an sampai sekarang menampilkan banyak fenomena kontradiktif.
Sebagian kontradiksi dan sekaligus ironi itu bisa disimak dalam karya Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama—Dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama (Jakarta: 2021).
Denny mengemukakan 11 argumen yang merupakan fakta baru dan lama yang mengubah pemahaman [dan sekaligus praksis] agama.
Menurut dia, inti perubahan kehidupan dan praksis keagaman dalam masa yang dia sebut ‘era Google’ itu, perlahan tapi pasti, akan terjadi pergeseran kesadaran. “Yaitu pergeseran kesadaran dari ‘agamaku [sebagai] satu-satunya kebenaran mutlak’ menjadi ‘[ber]agama atau tidak beragama adalah kekayaan kultural milik kita bersama.
Saat itu dunia akan lebih harmonis. Kultur semakin kaya. Keberagaman didukung kesadaran kolektif’, tulis dia.
Agama for better or for worse juga kian merambah dan semakin terlibat dalam kontestasi di ranah publik—politik identitas yang terus bangkit dan bertahan di sejumlah negara Eropa, di AS di masa Presiden Donald Trump atau dalam Pilgub DKI Jakarta 2017-2018.
Semua perkembangan ini tidak mengisyaratkan manusia menuju kehidupan lebih harmonis; sebaliknya meningkatkan kegaduhan kegaduhan dan konflik menyangkut agama, politik, sosial, budaya dan ekonomi.
Dengan begitu, gelombang demokratisasi, globalisasi, dan informasi instan yang disruptif tak membuat agama kehilangan relevansi.
Agama semakin ekspansif bukan hanya dalam kehidupan politik, tapi juga sosial-budaya, ekonomi, pendidikan, keamanan, media massa, seni, arsitektur dan seterusnya.
Semua fenomena ini jelas menimbulkan dampak tertentu atas kehidupan beragama yang terus kian meningkat akibat disrupsi karena kemajuan sains-teknologi—khususnya teknologi informasi semacam Google.
Keterkaitan agama dengan semua bidang itu tidak selalu membuat kehidupan lebih baik, lebih harmonis dan lebih damai.
Berbagai gejala kontradiksi dan ironi yang menimbulkan kontestasi, konflik, dan bahkan perang karena perbedaan pemahaman dan praksis keagamaan masih bisa terus disaksikan di berbagai penjuru dunia.
Ini terjadi di kalangan umat Kristiani dengan gereja dan denominasi sangat banyak; Islam dengan berbagai mazhab dan aliran berbeda, terutama Sunni dan Syi’ah.
Itu terjadi juga dengan Hindu yang relatif homogen, Budhisme dengan macam sekte dan pecahan agama dan sejumlah agama lain dan spiritualitas tidak berbasis agama utama yang hidup (living major world religions).
Kebangkitan Agama
Kompleksitas perkembangan, fenomena, dan ekspresi keagamaan secara global membuat tidak mungkin atau sulit sekali untuk menjelaskannya secara relatif seragam.
Kompleksitas itu juta tidak bisa dijelaskan secara linier.
Apakah karena perkembangan di dalam dirinya sendiri atau sebab pengaruh bidang kehidupan lain, agama mengalami perubahan sangat cepat pada berbagai segi.
Sebagai contoh, proses demokratisasi dan perubahan politik dan sosial memberikan ruang kebebasan relatif luas bagi ekspresi keagamaan yang sebelumnya terpendam karena restriksi yang diberlakukan rejim penguasa.
Di tengah kian meningkatnya keragaman, perlu semacam ‘penyederhanaan’ konseptual dengan membangun kategorisasi dan tipologisasi yang meski juga mengandung masalah dalam batas tertentu.
Salah satu fenomena dan kategorisasi agama kontemporer paling menonjol adalah revitalisasi dan ‘kebangkitan agama’ (religious revival) yang terlihat dalam peningkatan gairah dan semangat keagamaan.
Fenomena ini muncul pertama kali di AS sejak paro kedua 1980an, yang kemudian menyebar ke berbagai bagian dunia lain yang across the board, mencakup semua agama, khususnya di Asia dan Afrika.
Fenomena ini menunjukkan bahwa bertolak belakang dengan anggapan dan teori klasik tentang perubahan sosial, modernisasi, peningkatan ekonomi, dan pendidikan yang dianggap bakal menyingkirkan agama dari ranah kehidupan, sebaliknya agama bukan hanya bertahan; lebih daripada itu agama mendapatkan momentum baru.
Bahkan terjadi semacam eksplosi keagamaan yang bisa mengambil berbagai bentuk ekspresi sejak yang bersifat rohaniah yang secara kategori termasuk damai, bergairah dalam ritual tapi tetap moderat sampai pada kategori puritanisme, literalisme, ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme.
Fenomena keagamaan kontemporer di sejumlah negara tertentu jelas terkait banyak dengan terbukanya ruang lebih luas dalam gelombang demokratisasi yang dimulai sejak akhir 1980an di Uni Soviet, kemudian Eropa Timur, selanjutnya Indonesia, dan akhirnya Dunia Arab.
Gejala kebangkitan agama (Islam) terlihat di sejumlah bekas republik di Asia Tengah bekas bagian Federasi Soviet; atau di bekas wilayah Yugoslavia yang dilanda ‘ethno-religious cleansing’—pembersihan penganut Katolik Kroasia dan/atau muslim Bosnia oleh gereja ortodoks Serbia.
Karena kombinasi berbagai faktor—termasuk trans-nasionalisme agama yang juga terus meningkat dalam keterbukaan demokrasi—berkembang pula pemahaman dan praktik keagamaan berbeda dengan mainstream agama.
Perbedaan itu dalam kasus tertentu boleh jadi tidak terlalu substantif, tetapi bisa jadi lebih daripada sekadar masalah ‘furu’iyyah’ atau ‘trivial’.
Tetapi dalam kasus lain perbedaan dapat menyangkut hal pokok dan fundamental, yang membuat kelompok tertentu akhirnya dipandang ‘menyempal’ dari agama induknya.
Akibatnya, perbedaan sering berujung pada konflik dan bahkan kekerasan, baik ketika kelompok yang menyempal tersebut bersikap eksklusif dan melakukan truth claim vis-a-vis mainstream. Atau ketika kalangan tertentu di dalam atau atas nama mainstream melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok sempalan.
Dengan begitu, wacana dan gerakan trans-nasional agama di banyak bagian dunia sejak dari Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, sampai Australia mengancam dan mengacaukan warisan dan tradisi agama utama yang telah mapan di masing-masing wilayah.
Wacana dan gerakan trans-nasional yang bergerak secara bebas tidak hanya berupaya merekrut pengaruh dan pengikut secara terbuka, tetapi juga melakukan penetrasi dan infiltrasi ke dalam organisasi dan lembaga agama arus utama; dan juga ke dalam lembaga pendidikan tingkat menengah dan tinggi.
Meski mereka ini tidak selalu berhasil dalam agresi mereka, tetapi tetap saja mereka menimbulkan kegaduhan dan bahkan konlik intra dan antar-agama yang membuat kehidupan beragama tidak rukun dan tidak membahagiakan.
Gejala kebangkitan agama juga terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Untuk mengambil contoh kasus Indonesia, setidaknya dalam 30 tahun terakhir, kelas menengah Indonesia terus bertumbuh berkat kemajuan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut berbagai sumber, kelas menengah Indonesia sekitar separuh penduduk Indonesia; menurut estimasi moderat mungkin antara 75 sampai 100 juta orang.
Terus bertambahnya kelas menengah mendorong kemunculan berbagai bentuk ekspresi keagamaan mulai dari sekadar peningkatan religious attachment—kelengketan pada agama dalam bentuk peningkatan ritual, gaya hidup lebih religius, pendidikan lebih agamis, sampai kepada pengelolaan keuangan dan makanan lebih ketat sesuai syariah atau fikih.
Tetapi, kebangkitan kelas menengah yang memiliki orientasi khusus pada agama, tidak selalu menghasilkan ‘dunia lebih harmonis’ dan ‘kultur semakin kaya’ seperti yang diidealkan Denny JA.
Memang ada kalangan kelas menengah terdidik dan affluent yang semakin toleran, tetapi semakin banyak juga yang berubah orientasi menjadi intoleran dan bermusuhan dengan kaum beriman seagama tapi berbeda paham dan praksis agama, dan juga dengan penganut agama lain.
Terdapat mereka yang melakukan ‘hijrah’, meninggalkan pekerjaan dan kehidupan arus utama; sebaliknya mengalienasikan diri dari lingkungan sosial dan mengadopsi cara dan gaya hidup abad ke-7 Masehi.
Kehidupan beragama semakin ketat membuat kaum beriman cenderung kian tidak bahagia. Mereka tidak bahagia karena kehidupan makin ketat yang kian penuh dengan norma ‘tidak boleh’, ‘haram’, ‘bid’ah’, ‘irreligius’, ‘unAmerican’ dan seterusnya.
Sebaliknya mereka yang beragama secara lapang juga tidak atau kurang bahagia karena sering menjadi sasaran stigmatisasi, kutukan, dan kecaman dari kelompok umat beragama yang menganggap ‘paling religius’, paling benar teologi dan ritualnya.
Akibatnya, banyak di antara mereka kemudian tidak menjalankan agama, menjadi ‘irreligius’ atau ‘ateis’ atau bahkan ‘pindah agama’.
Dalam konteks itu, pemahaman dan praksis agama yang menimbulkan kegaduhan jelas membuat individu dan masyarakat tidak berbahagia.
Secara mafhum mukhalafah, mereka yang tidak mementingkan agama dalam kehidupan justru merasa lebih bahagia; mereka bebas—tidak diganggu keruwetan dan kegaduhan yang ditimbulkan pemahaman dan praksis keagamaan.
Oleh karena itu, jika agama dapat menjadi salah satu sumber kebahagiaan, pemahaman dan praksis keagamaan haruslah menyenangkan; menimbulkan kedamaian dalam secara batin dan lahir.
Semestinya begitulah agama diajarkan, dikhutbahkan, dan dipraktikkan. Jika pemahaman dan praksis agama menimbulkan kerisauan, kegaduhan dan ketidakbahagiaan, pemahaman dan praksis, maka pemahaman dan praksis agama itu perlu diperiksa kembali.
Begitu juga perlu pendidikan ulang bagi fungsionaris agama yang merumuskan dan mengajarkan pemahaman dan praksis agama yang menampilkan agama yang menakutkan.
Itu seperti pemahaman neraka yang membakar, tuhan serba pemarah dan serba menyiksa kaum beriman. Atau juga memprovokasi umat untuk melakukan kekerasan atas nama agama.
Jika agama dapat mendatangkan kebahagiaan, fungsionaris agama mesti menyajikan pemahaman dan praksis agama yang menenangkan, menyejukkan, membahagiakan dan menciptakan harmoni antar manusia.
Walau latar belakang mereka berbeda; tapi umat beragama perlu menjalankan perintah agama dengan ikhlas. Itu bukan karena ancaman dan ketakutan yang disebarkan fungsionaris agama.
Agama dan Politik
Proses dan penguatan demokrasi memberikan ruang kebebasan yang luas pula bagi masyarakat untuk mengekspresikan pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berbeda-beda.
Dalam batas tertentu pemahaman dan pengamalan keagamaan itu bisa muncul menjadi semacam ‘politik identitas.” Ini dapat memunculkan masalah tersendiri ketika masing-masing kelompok terlibat dalam pergumulan dan kontestasi di ruang publik.
Peningkatan religious attachment tidak jarang menjadi objek manipulasi politik oleh para politisi dan partai politik, yang memainkan kartu agama untuk kepentingan politik masing-masing.
Dalam konteks itu, orang bisa menyaksikan manipulasi dan use and abuse agama untuk kepentingan politik.
Fenomena ini bisa dilihat sejak dari India di bawah pemerintahan BJP, partai Hindu fundamentalis, AS di masa pemerintahan Partai Republik, Donald Trump sampai adopsi dan penerapan Perda-perda moral yang sering disebut sebagian kalangan ‘Perda Syariah’ di Indonesia.
Semua fenomena ini hanyalah beberapa contoh terjelas pertemuan kepentingan simbolisme keagamaan tertentu dengan oportunisme politik.
Dalam konteks itu, pada level arus utama masyarakat agama terlihat gejala umum meningkatnya ‘religious attachment’ yang sudah disinggung di atas.
Gejala ini di kalangan muslim—selain yang sudah disebutkan di atas—juga terlihat dalam peningkatan jumlah jamaah haji, umrah dan ziyarah keagamaan, meluasnya penggunaan jilbab di kalangan perempuan muslimah, meningkatnya filantropi Islam.
Selain itu, gejala ini juga bisa terlihat jelas dalam peningkatan kerajinan menjalankan berbagai ibadah, ritual keagamaan dan berbagai aspek ajaran agama lainnya—yang bisa disebut sebagai ‘kesalehan ritual personal’ as opposed to ‘kesalehan sosial komunal’.
Salah satu konsekuensi atau implikasi gejala ini adalah peningkatan usaha berbagai kalangan umat beragama untuk mendirikan rumah ibadah yang pada gilirannya dapat menimbulkan pertikaian dan konflik.
Apalagi ketika rumah ibadah itu secara eksklusif hanya digunakan untuk denominasi, aliran atau mazhab tertentu di dalam agama tertentu.
Kenapa ada kecenderungan negara-negara dengan warga yang menganggap agama penting dalam kehidupannya, justru melakukan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan ajaran agama seperti melakukan korupsi?
Sebaliknya, mengapa warga yang menganggap agama tidak penting juga menghasilkan negara yang bersih dari korupsi seperti dibahas buku Denny JA ini (h 12-20)?
Masalahnya terletak pada keterpisahan (split) antara kesalehan individual dan komunal dalam formal dengan kesalehan sosial.
Tabel yang di halaman 17 dengan jelas menunjukkan tidak ada korelasi antara keyakinan tentang pentingnya agama dalam kehidupan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sebab tidak ada hubungan itulah kemudian membuat praktek korupsi dan pelanggaran hukum lainnya merajalela.
Dengan demikian, religiositas kaum beriman di lima negara yang dikutip Denny tidak terlihat di ranah publik.
Nilai-nilai agama, misalnya tentang hidup yang bersih, sederhana, atau disiplin, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Umat beragama di negara-negara tersebut menunjukkan religiositas hanya ketika melakukan ritual atau ibadah formal; hampir tidak memperlihatkan dan mempraktikkannya dalam kehidupan publik lebih luas.
Tantangan hari ini dan ke depan bagi warga yang yakin bahwa agama penting adalah membangun paradigma, pemahaman, dan praksis keagamaan yang holistik, komprehensif, dan menyeluruh.
Pemahaman dan praksis keimanan tidak diberlakukan atau diterapkan sepotong-sepotong yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara cita ideal agama dengan perilaku umatnya, sehingga agama menjadi tidak fungsional di ranah publik dan negara.
Penutup
Berbagai argumen Denny JA di buku ini menstimulasi kajian lebih lanjut. Perlu dilakukan riset lebih luas dan lebih dalam tentang fenomena keagamaan kontemporer—era Google.
Perlu pemetaan lebih komprehensif dan sekaligus meliputi berbagai bidang kehidupan—tidak terbatas hanya pada bidang keagamaan ‘murni’, tetapi juga ke berbagai ranah kehidupan lain.
Terdapat interdependensi dan interplay, saling memengaruhi antara satu bidang dan ranah kehidupan dengan bidang lain. Pada gilirannya juga memengaruhi dinamika internal keagamaan.
Penelitian yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan akademik-ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara substantif dan metodologis.
Lebih daripada itu, sekaligus juga guna menjelaskan implikasi, konsekuensi dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan kehidupan keagamaan lebih baik di berbagai penjuru dunia.
Agenda penelitian lain terkait dengan ranah-ranah kehidupan tertentu yang menampilkan simbolisme keagamaan seperti politik, ekonomi berbasis agama, pendidikan, sosial-budaya dan seterusnya.
Penelitian dalam ranah-ranah ini bisa pula berfokus pada implikasi dan konsekuensi perkembangan tersebut terhadap kehidupan negara-bangsa dan masyarakat global secara keseluruhan. *
Buku Denny JA yang direview dapat dibaca, diunduh, dicetak dan disebar melalui link
https://www.facebook.com/groups/970024043185698/permalink/1596857733835656/