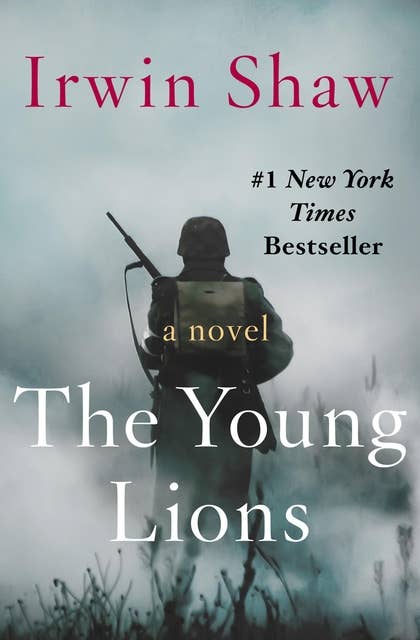Tulisan ini mencoba menyoroti identitas dan asimilasi dalam fiksi Yahudi Amerika pasca-Perang Dunia II dan menyajikan sebuah studi mendalam tentang bagaimana para penulis pada masa itu menegosiasikan posisi mereka di tengah masyarakat Amerika yang sedang berubah. Periode ini menjadi sangat krusial karena menandai transisi generasi kedua imigran Yahudi dari Eropa Timur yang mulai menemukan suara sastra mereka, hingga akhirnya menjadi pusat dari kanon sastra Amerika. Inti dari pergulatan ini bukan sekadar upaya untuk diterima secara sosial, melainkan sebuah dekonstruksi terhadap konsep maskulinitas yang selama ini didominasi oleh nilai-nilai hegemoni kulit putih yang kaku.
Untuk memahami dinamika ini, kita harus melihat konteks sejarah mengenai evolusi konsep “keputihan” atau whiteness di Amerika Serikat. Sejak abad ke-17, kewarganegaraan Amerika secara implisit dikaitkan dengan identitas laki-laki kulit putih. Namun, definisi kulit putih itu sendiri tidaklah statis. Pada awalnya, kelompok imigran dari Irlandia, Eropa Selatan, dan khususnya Yahudi dari Eropa Timur, ditempatkan dalam hierarki ras yang lebih rendah dibandingkan dengan keturunan Anglo-Saxon. Diskriminasi ini bahkan diperkuat oleh ilmu semu eugenika yang populer pada awal abad ke-20.
Perubahan signifikan baru terjadi setelah Undang-Undang Imigrasi tahun 1924 yang membatasi arus masuk imigran baru, yang secara perlahan menggeser fokus masyarakat dari asal-usul etnis menuju integrasi generasi kelahiran Amerika ke dalam kategori “Kaukasia”. Pengalaman Perang Dunia II mempercepat proses ini, di mana retorika anti-Nazi memaksa pemerintah Amerika untuk mempromosikan toleransi beragama dan etnis sebagai simbol demokrasi, yang pada akhirnya memberikan ruang bagi orang Yahudi untuk dianggap sebagai bagian dari kelompok kulit putih.
Namun, pengakuan secara hukum dan administratif tidak serta merta menghapus prasangka sosial. Anti-Semitisme tetap berakar kuat dalam budaya Amerika, sering kali bermanifestasi dalam kecurigaan bahwa orang Yahudi adalah ancaman bagi ekonomi atau pembawa ideologi komunisme. Di sinilah sastra memainkan peran penting untuk membedah kecemasan tersebut. Melalui novel Focus karya Arthur Miller, kita diperlihatkan bagaimana identitas rasial sering kali merupakan konstruksi sosial yang rapuh.
Tokoh Lawrence Newman, seorang pria non-Yahudi yang sangat konformis, tiba-tiba mengalami diskriminasi setelah ia mulai mengenakan kacamata yang membuatnya tampak seperti orang Yahudi. Miller menggunakan narasi ini untuk mengkritik kerapuhan maskulinitas Amerika yang saat itu sangat terobsesi dengan penampilan dan penerimaan kelompok. Newman menemukan kekuatan maskulinnya yang sejati bukan melalui asimilasi buta, melainkan melalui solidaritas dengan mereka yang tertindas, yang direpresentasikan oleh tokoh Finkelstein yang menunjukkan perlawanan fisik yang berani.
Selanjutnya, pengalaman militer sebagai ruang pembuktian kejantanan dieksplorasi dalam novel The Young Lions karya Irwin Shaw. Tokoh Noah Ackerman menjadi representasi dari perjuangan ganda tentara Yahudi: berjuang melawan musuh negara di medan perang, sekaligus berjuang melawan prasangka dari rekan-rekan tentaranya sendiri. Bagi Ackerman, maskulinitas adalah sebuah ujian ketahanan. Ia harus membuktikan bahwa seorang Yahudi bisa menjadi prajurit yang tangguh tanpa kehilangan sisi intelektual dan kemanusiaannya. Tragisnya, kematian Ackerman di akhir cerita seolah menyiratkan bahwa biaya yang harus dibayar untuk integrasi ke dalam cita-cita liberal Amerika sering kali adalah pengorbanan nyawa dan identitas pribadi yang mendalam.
Berbeda dengan nada serius Miller dan Shaw, Saul Bellow dalam The Adventures of Augie March memperkenalkan gaya bahasa yang lebih cair dan penuh energi untuk mengeksplorasi identitas. Melalui Augie March, Bellow menegaskan hak orang Yahudi untuk menjadi “sepenuhnya Amerika” tanpa harus terjebak dalam prototipe maskulinitas yang kaku seperti pahlawan-pahlawan Hemingway yang dingin.
Augie adalah sosok yang menolak untuk dikotakkan. Ia bergerak di antara identitas sebagai “mensch” (orang baik yang bermartabat) dan “schlemiel” (karakter komik yang sering sial namun jujur). Bellow menggunakan karakter saudara Augie, Simon, sebagai peringatan akan bahaya asimilasi yang hanya mengejar kesuksesan material. Simon mencapai kemakmuran namun kehilangan jiwanya, sementara Augie tetap mempertahankan otonomi dirinya meskipun harus hidup dalam ketidakpastian. Hal ini menunjukkan bahwa maskulinitas Yahudi Amerika yang baru adalah tentang kemampuan untuk tetap menjadi manusia yang utuh di tengah tekanan materialisme.
Perspektif yang lebih radikal muncul dalam novel Wasteland karya Jo Sinclair, yang memperluas diskusi identitas hingga ke ranah psikoanalisis dan orientasi seksual. Tokoh Jake Brown mewakili fenomena penyangkalan diri yang ekstrem; ia mengubah namanya dan menjauhkan diri dari keluarganya demi mengejar karier di dunia kulit putih. Namun, tindakan ini justru menyebabkan kehancuran mental yang disebut sebagai “tanah tandus” psikologis.
Menariknya, Sinclair menghubungkan krisis maskulinitas Jake dengan kehadiran adik perempuannya, Debby, seorang lesbian yang mandiri. Jake merasa maskulinitasnya terancam oleh kekuatan Debby, namun melalui proses terapi, ia menyadari bahwa musuh sejatinya bukanlah saudara perempuannya atau identitas Yahudinya, melainkan ketakutan internalnya sendiri terhadap marginalisasi. Sinclair dengan berani menyandingkan alienasi Yahudi dengan marginalisasi kelompok queer dan kulit hitam, menyarankan bahwa asimilasi yang sehat hanya mungkin terjadi melalui penerimaan diri yang total.
Secara keseluruhan, karya-karya ini menunjukkan bahwa perjalanan menjadi “Amerika” bagi komunitas Yahudi bukanlah proses yang searah atau sederhana. Ada ketegangan konstan antara keinginan untuk melebur ke dalam arus utama dan kebutuhan untuk mempertahankan keunikan budaya dan moral. Para penulis ini berhasil menunjukkan bahwa maskulinitas bukan sekadar tentang kekuatan fisik atau dominasi, melainkan tentang keberanian untuk mendefinisikan diri sendiri di hadapan masyarakat yang sering kali menuntut keseragaman.
Dengan demikian, fiksi Yahudi Amerika pada periode ini tidak hanya berbicara tentang satu kelompok etnis, tetapi memberikan refleksi mendalam bagi siapa saja yang berusaha mencari jati diri di tengah tarikan antara tradisi lama dan janji masa depan yang baru. Identitas dan asimilasi, pada akhirnya, adalah tentang menemukan keseimbangan antara menjadi bagian dari sebuah bangsa tanpa harus kehilangan akar yang membentuk kemanusiaan seseorang.