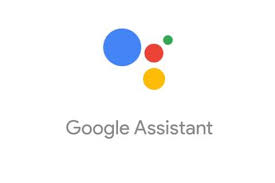Suatu hari di kelas, seorang siswa menyanggah jawaban saya. Dengan nada percaya diri, ia berkata bahwa saya keliru. Saya tersenyum, memintanya menjelaskan. Ia tidak memberi penjelasan, melainkan mengeluarkan ponselnya. Dalam hitungan detik, layar ponselnya menampilkan hasil pencarian Google Lens: jawaban saya memang berbeda dari hasil yang muncul. Ia benar, setidaknya menurut Google.
Saya tak bisa menampik kebenaran digital itu. Namun ada yang mengusik pikiran saya. Siswa itu tidak benar-benar memahami mengapa jawabannya benar; ia hanya menemukan kebenaran yang sudah disediakan mesin. Ia tidak menalar, hanya menyalin. Ia tidak berpikir, hanya memverifikasi. Seolah-olah kecerdasan telah berubah bentuk — dari kemampuan bernalar menjadi kemampuan mengetik pertanyaan dengan tepat di kolom pencarian.
Fenomena ini menjadi potret pendidikan kita hari ini: siswa yang tampak cerdas karena dikelilingi oleh teknologi, tetapi rapuh dalam nalar. Mereka bisa menjawab dengan cepat, tetapi sulit menjelaskan sebab-musabab di balik jawaban itu. Mereka terbiasa klik, bukan berpikir.
Padahal, pendidikan sejatinya adalah proses penemuan diri, bukan sekadar penemuan jawaban. John Dewey pernah mengatakan, “Education is not preparation for life; education is life itself.” Artinya, belajar tidak hanya berlangsung ketika kita mencari kebenaran, tetapi juga ketika kita menghayati proses menuju kebenaran itu. Google, betapapun canggihnya, tidak bisa menggantikan pengalaman berpikir yang reflektif, ragu, dan penuh percobaan itu.
Sebagai guru, saya dihadapkan pada dilema yang tidak ringan. Selama ini, kita dididik untuk menjadi sumber pengetahuan. Namun kini, pengetahuan bertebaran di mana-mana — bahkan lebih cepat diperbarui oleh algoritma daripada oleh buku pelajaran. Maka, tugas guru bukan lagi menjadi ensiklopedia berjalan, melainkan menjadi penafsir, penyaring, dan pengarah. Guru bukan lagi pusat kebenaran, tetapi penjaga akal sehat di tengah banjir informasi.
Ironisnya, banyak guru — termasuk saya — masih sering mengukur keberhasilan siswa dari ketepatan jawaban. Kita lupa, di era mesin pencari, ketepatan bukan lagi tanda kecerdasan, melainkan ketepatan menyalin. Sementara itu, pemahaman, refleksi, dan kemampuan bertanya justru semakin jarang mendapat ruang.
Fenomena “siswa disanggah Google” ini sesungguhnya membuka pertanyaan besar tentang paradigma pendidikan. Apakah tugas sekolah masih untuk “mengajarkan pengetahuan”, atau sudah seharusnya beralih menjadi “membimbing cara berpikir”? Jika pengetahuan kini bisa diakses dengan sekali klik, maka nilai pendidikan bukan lagi apa yang diketahui, melainkan bagaimana cara mengetahui.
Kita hidup di zaman ketika kecepatan mengalahkan kedalaman. Media sosial, video pendek, dan aplikasi pencari membuat kita terbiasa dengan instan. Akibatnya, siswa belajar dalam logika konsumsi informasi, bukan kontemplasi. Mereka “menelan” fakta tanpa sempat mencerna makna. Padahal, berpikir kritis memerlukan waktu, keraguan, dan kesabaran — tiga hal yang sering hilang di era digital.
Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, menulis bahwa pendidikan sejati harus membebaskan manusia dari kesadaran pasif. Ia menolak pendidikan yang hanya memindahkan pengetahuan dari kepala guru ke kepala murid — seperti mengisi celengan kosong. Menurut Freire, murid bukan wadah kosong, melainkan subjek yang perlu diajak berdialog. Dalam konteks hari ini, tantangannya justru lebih pelik: murid tidak hanya menghadapi guru, tetapi juga mesin yang lebih cepat dari guru. Maka, guru harus menciptakan dialog yang melampaui kecepatan — dialog yang menghidupkan kesadaran.
Mungkin, inilah makna baru peran guru: bukan sekadar memberi tahu, melainkan mengajak berpikir; bukan hanya mengajar ilmu, tetapi menumbuhkan kebijaksanaan. Google bisa menjawab apa dan berapa, tapi tidak bisa menjelaskan mengapa dan untuk apa. Itulah wilayah kemanusiaan yang masih menjadi ranah guru.
Pengalaman disanggah siswa tadi menjadi cermin kecil bahwa otoritas guru tengah bergeser. Dulu, guru dihormati karena menguasai pengetahuan. Kini, penghormatan itu lahir dari kemampuan membimbing proses berpikir dan menanamkan makna. Guru bukan lagi menara gading yang menatap dari atas, melainkan teman berpikir yang berjalan bersama siswa.
Di sinilah saya sadar, bahwa menjadi guru di zaman ini berarti juga menjadi pembelajar abadi. Kita tidak mungkin menandingi kecepatan mesin, tetapi kita bisa melampauinya dalam kedalaman refleksi. Mesin bisa menemukan kebenaran faktual, tapi hanya manusia yang bisa menafsirkan kebenaran eksistensial.
Pada akhirnya, saya tidak merasa kalah ketika disanggah oleh Google. Justru di momen itulah saya belajar bahwa otoritas sejati seorang guru tidak lahir dari hafalan, melainkan dari kerendahan hati untuk terus belajar — bahkan dari siswanya sendiri. Sebab mungkin, di tengah derasnya arus teknologi ini, hal paling penting yang harus kita ajarkan bukanlah “bagaimana menjawab”, tetapi “bagaimana memahami”.
Sebab memahami berarti menghidupkan kembali jiwa pendidikan itu sendiri: membangkitkan rasa ingin tahu, mengasah kesadaran, dan menghidupkan dialog antara manusia dan pengetahuan. Dan mungkin, di sanalah letak kebijaksanaan yang tak bisa dipindai oleh Google.