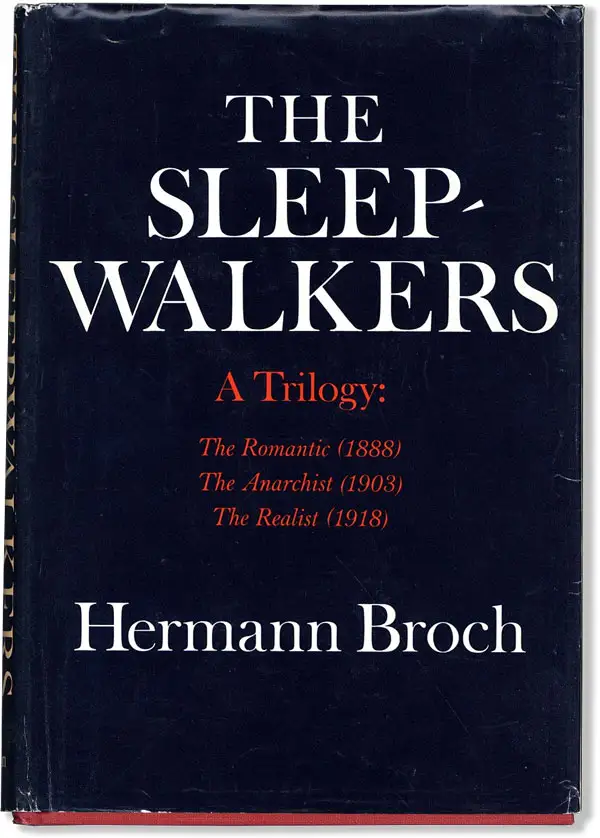The Sleepwalkers (1930) berdiri sebagai monumen modernisme, sebuah karya yang dalam banyak hal dapat dipandang sebagai upaya ambisius para novelis untuk membongkar dan merombak struktur novel Eropa yang kian usang pasca Perang Dunia Pertama. Penulisnya, Broch, sebagaimana Sholokhov, berani menghadapi realitas perang secara gamblang. Ia tak segan menampilkan individu-individu yang bergulat mencari makna, menanggung penderitaan, menghadapi kehancuran, dan berjuang untuk bertahan hidup, alih-alih hanya menggambarkan mereka dari sudut pandang eksternal melalui lensa perang yang disaring, seperti yang dilakukan Joyce dan Svevo.
Senada dengan para modernis lainnya, Broch merasa terpanggil untuk memecah dan merekonstruksi bentuk tradisional novel realis, demi mengkomunikasikan visinya tentang dunia. Disintegrasi bentuk naratif ini, yang juga menjadi ciri khas sebagian besar novelis modern, kini telah menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan. Perang Dunia Pertama, bahkan Perang Dunia Kedua, tak lagi menyimpan makna yang sama seperti dulu. Dan tentu saja, ketidakpercayaan yang riang terhadap rasionalitas, atau bahkan gagasan tentang akhir peradaban dan kesadaran itu sendiri, tidaklah muncul bersamaan dengan metamorfosis Eropa dari serangkaian kerajaan mini-militer yang berperang menjadi sebuah Uni Eropa pasca-kolonial.
The Sleepwalkers dengan cemerlang mengkaji konvergensi tiga generasi dan kelas sosial yang berbeda. Di pusatnya adalah Von Pasenow, seorang aristokrat Prusia pewaris dan prajurit karier yang nasib perkawinan dan sosialnya secara ironis ditentukan pada akhir novel pertama: ayahnya, yang awalnya takut dan menolaknya, akhirnya menjodohkannya dengan putri seorang tetangga kaya. Melalui penyatuan ini, dua perkebunan pun bersatu—sebuah pernikahan yang mengalihkan kebahagiaan lama menjadi bagian dari perhitungan bisnis yang menghasilkan keturunan.
Karakter kedua adalah Esch, dua puluh tahun lebih muda dari Pasenow, seorang akuntan urban yang sedang naik daun di awal abad kedua puluh. Esch digambarkan sebagai sosok yang impulsif dan tidak stabil. Seperti Pasenow, ia bergulat dengan kegelisahan seksual, yang dalam kasusnya merupakan perpaduan kompleks antara ketertarikan dan penolakan terhadap pemilik kantin yang sering ia kunjungi. Ia menemukan dirinya tak sanggup menjauh dari wanita tersebut, namun ironisnya, ia berharap bahwa dalam konteks hubungan seksual, wanita tersebut dapat bersikap pasif.
Secara faktual, The Sleepwalkers adalah galeri modern yang sempurna, menampilkan berbagai nuansa kebosanan mendalam yang seolah dipaksakan oleh kekakuan masyarakat tempat mereka tinggal. Broch sangat mahir dalam menggambarkan bagaimana setiap protagonis dan karakter minor yang lebih kecil secara internal merasakan dan kemudian memproyeksikan sensasi-sensasi ini ke dunia di sekitar mereka. Baik Pasenow maupun Esch menderita dari apa yang disebut “serangan kelebihan beban geometris” terhadap hal-hal kecil, yang pada akhirnya membesar secara tidak proporsional dan terdistorsi. Sebagai contoh, dalam wawancara Pasenow dengan seorang pewawancara prospektif, ekspresi wajahnya seolah memudar menjadi sebuah lanskap kosong, yang terasa menakutkan dan menjijikkan baginya. Kemudian, Esch semakin yakin bahwa mantan bosnya telah melakukan kejahatan dan harus dilaporkan kepada pihak berwenang. Keyakinan ini terus-menerus mengemuka di sebagian besar bagian novel, meskipun bagi pembaca, akar keyakinan Esch ini hanyalah kemarahan dan kebencian akibat pemecatan dirinya.
Mirip dengan karya-karya Kafka dan Robert Musil, hubungan paling krusial para protagonis dalam novel ini sering kali terjalin lebih erat dengan entitas negara daripada dengan sesama individu. Apabila kita membandingkan para novelis Jerman—terutama Kafka dan Musil—dengan, katakanlah, Anthony Trollope, yang sebagian besar karyanya membahas pemerintahan Inggris dalam seri novel Palliser (di mana karakter-karakter utamanya adalah penguasa Inggris), sungguh mencengangkan untuk menyadari bahwa rata-rata warga negara Jerman (atau lebih tepatnya, warga Kekaisaran Austro-Hungaria) mengalami negara sebagai bagian yang sangat nyata dari kehidupan pribadi mereka.
Mereka terdorong untuk memikirkan dan berhubungan dengan negara tanpa kurang atau lebih dari hubungan mereka dengan pasangan atau anak-anak (meskipun harus diakui, figur ibu dan ayah, terutama, seringkali terasa sangat membebani dan menindas dalam narasi). Dalam novel-novel Jerman, pemerintah adalah kehadiran yang tak terhindarkan dalam setiap pikiran; berbeda dengan novel Inggris, di mana bahkan perdana menteri pun memiliki hubungan yang bersifat lebih pribadi dengan sekutu, pejabat fungsional, atau bahkan mediator sosial. Pemerintah, dalam narolongi Trollope, direduksi menjadi sekadar jaringan persahabatan yang memengaruhi sebagian besar jaring-jaring sosial Inggris lainnya.
Volume ketiga The Sleepwalkers mengisahkan penyatuan Esch dan Pasenow, yang kemudian sama-sama tunduk pada Huguenau—sosok yang dua puluh tahun lebih muda dari Esch (dan sekitar tiga puluh tahun saat volume ini dimulai pada tahun 1918). Huguenau, yang berasal dari Alsace dan beragama Katolik, berkomunikasi dalam bahasa Prancis. Ia menjadi kontras yang mencolok dengan para sesepuhnya; ia digambarkan hampir tidak memiliki perasaan seksual sama sekali, dan didorong oleh jiwa komersial yang murni serta kecenderungan tentara bayaran. Huguenau tidak ragu melukai orang lain jika ada kesempatan, sementara Pasenow justru takut menyakiti orang lain demi kebaikan yang lebih besar.
Namun, baik Esch maupun yang lainnya tega melukai sesama hanya demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Ironisnya, Huguenau, yang paling kompeten di antara ketiganya, berhasil meninggalkan dinas militer (memutuskan hubungannya dengan pemerintah dan otoritas moral yang kaku) demi mencari peluang dan dengan kesadaran akan waktu. Setelah tiba di kota Esch, ia memanfaatkan peluang yang sama untuk membaca surat kabar Esch dan mengukuhkan dirinya sebagai warga negara terkemuka.
Namun, meskipun ia telah mengkhianati hubungan dengan otoritas, ia tidak mampu mendapatkan dukungan dari komandan kota (Pasenow) dan berusaha menjalin semacam hubungan ayah-anak dengan Pasenow, yang kini menjadi simbol sisa-sisa kesopanan. Ia tetap menjaga jarak dan berupaya menghindari pria yang lebih muda itu. Setelah Huguenau melakukan pemerkosaan terhadap Frau Esch dan kemudian membunuh Esch, ia melarikan diri kembali ke kampung halamannya, di mana ia berhasil menjadi pengusaha, suami, ayah, dan warga negara yang makmur, tanpa pernah sekalipun merenungkan kejahatan atau pengkhianatannya. Ia adalah personifikasi manusia modern yang amoral, yang membeli murah dan menjual mahal tanpa peduli akan konsekuensi apa pun.
Broch, sebagai seorang novelis, jauh dari kesan bahagia. Ia justru lebih condong pada filsafat ketimbang fiksi murni, bahkan menyela naratifnya dengan esai-esai filosofis yang konon ditulis oleh salah satu karakter minor dalam novel tersebut. Dalam esai-esai ini, ia dengan jelas dan universal menguraikan argumen-argumen yang ingin ditunjukkan oleh karakter-karakternya. Pada suatu titik, ia bahkan merangkai narasi ketiga pria itu dalam format drama, dan sesekali menggunakan puisi untuk menyampaikan ide-ide yang terlalu intens untuk prosa biasa.
Bagian-bagian filosofis dari novel itu, meskipun terkesan tanpa batasan waktu, sesungguhnya sangat relevan dalam konteks novel itu sendiri. Lebih penting lagi, Broch menunjukkan keahlian luar biasa dalam menggambarkan karakter, psikologi, dialog, bahkan alur cerita, meskipun terkadang terasa outdated. Broch adalah seorang stilistis yang tajam, mengingatkan pada Robert Musil, namun tanpa kecerdasan yang kering. Ia justru lebih berani dalam kesediaannya untuk bergulat langsung dengan peristiwa-peristiwa perang yang mengerikan, alih-alih menghindarinya.
Dalam naratif Broch, Pasenow dan Esch bergulat dengan masalah kesehatan mental yang serius. Pasenow tampak menunjukkan gejala obsesif-kompulsif, sementara Esch bergumul dengan hiperaktivitas dan gangguan defisit perhatian, diperparah oleh gangguan oposisional-defian. Huguenau, karakter lain yang dapat dikenali, menunjukkan ciri-ciri antisosial—sebuah gangguan kepribadian yang, bahkan hingga kini, memicu perdebatan apakah itu murni kondisi mental, kegagalan spiritual, atau sekadar bentuk kejahatan. Novel ini seolah bertanya: apakah ini adalah akhir dari peradaban Eropa, ataukah hanya konsekuensi dari meluasnya kondisi mental semacam itu?
Dalam bagian-bagian filosofisnya yang membengkak, Broch menelusuri akar karakter-karakter utamanya hingga ke Reformasi dan bangkitnya individualisme Protestan. Huguenau sendiri dapat dipandang sebagai representasi figur Max Weber, seorang yang sangat piawai dalam dunia bisnis namun memiliki sedikit koneksi manusiawi. Namun, pembaca, tentu saja, memiliki kebebasan untuk tidak sependapat dengan filosofinya, dan dapat menarik hubungan sebab-akibat mereka sendiri. Ini karena Pasenow, Esch, Huguenau, dan tokoh-tokoh minor lainnya hadir dengan begitu nyata sebagai karakter dalam naratif, jauh lebih hidup daripada sekadar personifikasi dari suatu sistem filosofis.