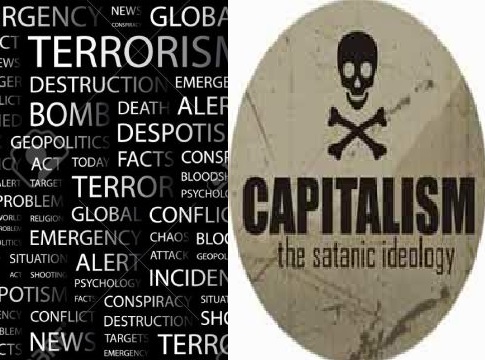Sejarah umat manusia seperti tak pernah sepi dari tragedi-tragedi kekerasan. Ini seakan mengonfirmasikan kekhawatiran para malaikat saat Tuhan menyatakan—terkait penciptaan manusia versi QS al-Baqarah (2) ayat 30—hendak menjadikan khalifah di bumi. Kala itu, para malaikat menyatakan, “Apakah Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?”
Terorisme bisa jadi merupakan ideologi paling tua dalam sejarah hubungan sosial antarmanusia. Ironisnya, ideologi barbar ini masih kerap digunakan hingga kini oleh beberapa pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih ironis lagi, label teroris di era modern tak jarang diarahkan kepada gerakan-gerakan Islam, agama yang baik nama maupun ajarannya berorientasi damai dan untuk menciptakan kedamaian. Tak pelak, labeling ini menimbulkan semacam “paranoia anti-Islam.”
Opini politik dunia cenderung digiring ke arah perang melawan terorisme (Islam). Momentumnya terutama sejak peristiwa perontokan gedung kembar WTC dan Pentagon, 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS), yang merupakan intiklimaks dari rentetan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mengancam AS dan negara-negara Barat pada umumnya.
Sejak saat itu, isu terorisme melambung ke permukaan sebagai musuh global yang harus dihadapi bersama. Al-Qaidah, Jama‘ah Islamiyah, ISIS (Islamic State in Iraq and Syria), dan sejenisnya—dengan stereotipikal Islam—dituding sebagai pihak yang menggerakkan terorisme. Hampir setiap kegiatan terorisme dikaitkan dengan jaringan-jaringan ‘berafiliasi keislaman.’
Celakanya, proyek “paranoia anti-Islam” justru menaikkan seorang Donald Trump ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden AS. Dunia menyaksikan pria dengan latar belakang pengusaha ini sejak kemunculannya sebagai kandidat telah menampilkan diri anti-Islam. Dia mengemukakan gagasan untuk memantau masjid-masjid di AS. Dia juga ingin agar umat Islam diawasi aparat sebagai langkah melawan terorisme.
Proyek “paranoia anti-Islam” makin nyata dengan kebijakan Trump membatasi laju imigran muslim masuk AS serta pernyataannya yang memberikan pengakuan resmi bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel. Tentu saja tindakan Presiden ke-45 negeri Paman Sam ini menuai protes berbagai pihak, tidak saja dari kalangan umat muslim, tetapi juga negara-negara dan mereka yang melihat potensi mara bahaya akibat ketidakadilan sosial yang terus-menerus menghantui masyarakat dunia. Mengingat bahwa jika diselisik lebih dalam, terorisme tumbuh dan berkembang lebih banyak dipicu oleh ketidakadilan sosial.
Hegemoni dan Ketidakadilan Sosial
Terorisme hanyalah satu dari sekian banyak isu global yang diarahkan kepada aksi-aksi berlabel Islam, menyusul isu-isu lainnya yang secara gencar dikampanyekan melalui beragam cara dalam berbagai dimensi kehidupan sosial. Isu ini merupakan kelanjutan atau varian dari isu fundamentalisme yang dilabelkan kepada Islam dan umat muslim.
Gerakan-gerakan seperti tersebut secara nyata ada, dan tak sedikit melibatkan atau mengatasnamakan Islam. Karena itulah, opini mudah diembuskan dengan rumusan bahwa ideologi kekerasan sengaja dibangun oleh sebagian kaum muslim untuk melawan Barat.
Hegemoni Barat terhadap tatanan kehidupan dunia dipandang turut mendorong terciptanya ketidakadilan sosial. Kondisi ini ditengarai menjadi pangkal lahirnya gerakan-gerakan yang berusaha lepas dari hegemoni tersebut.
Suasana ketidakadilan mewarnai hampir semua dimensi kehidupan sosial politik, ekonomi, hukum, budaya, dan bahkan agama. Dunia seakan digiring masuk dalam perangkap ketergantungan. Negara-negara Dunia Ketiga serta rakyat yang hidup di dalamnya seperti sengaja diciptakan bergantung pada negara-negara maju.
Maka tak sedikit dari proyek-proyek “berkedok” bantuan internasional yang alih-alih memberdayakan, justru melemahkan. Kondisi ini mendorong timbulnya aksi-aksi parsial untuk melawan. Aksi-aksi perlawanan ini diangkat ke permukaan untuk kemudian diembuskan sebagai ancaman bagi negara-negara maju.
Noam Chomsky—seorang kritikus sosial asal AS yang gagasan-gagasan politiknya justru terpinggirkan di negara asalnya—mengemukakan dalam bukunya, How the World Works (Bentang, 2016) bahwa sejak awal 1970-an, dunia bergeser ke dalam situasi yang disebut tripolarism atau trilateralism, yakni tiga blok ekonomi utama yang satu sama lain saling bersaing: Blok pertama berbasis yen dengan Jepang sebagai pusat dan bekas koloni-koloninya sebagai periferal. Blok kedua berbasis di Eropa dengan dominasi Jerman. Blok ketiga dominasi AS yang berbasis dolar. Blok-blok kekuatan ekonomi utama ini—maupun blok dengan berbasis Cina-Tiongkok di luar polasirasi versi Chomsky—sepenuhnya merupakan gurita kapitalisme global.
Problem Internal Islam Politik
Setelah kekuasaan Turki Utsmani—yang dipandang sebagai simbol dan benteng terakhir kekuatan integrasi (politik) Islam—jatuh pada 1924, praktis belum ada kekuatan Negara Islam yang berdaya menghadapi hegemoni Barat. Tidak sedikit negara-negara Islam justru tunduk dalam kendali dan cenderung dikuasai Barat, karena ketergantungan secara ekomomi dan politik. Dengan ini, kekuasaan Islam politik seakan tak punya daya.
Ketidakberdayaan Islam politik lebih disebabkan oleh problem internal yang sejak lama mengakar dalam tubuh umat Islam sendiri. Ragam interpretasi menyebabkan gerakan Islam pecah, dan tidak mudah untuk dipertemukan dalam satu titik menuju gerakan yang simultan, sehingga kebangkitan Islam lebih banyak tampil dengan wajahnya yang parsial (partial revivalisme) ketimbang kebangkitan yang bersifat integral (integrated revivalisme).
Interpretasi keagamaan dengan memisahkan wilayah-wilayah sakral dan profan serta urusan privat dan publik menambah kerentanan ikatan dalam beragama. Akibatnya, hubungan antar penganut paham keagamaan yang berbeda menjadi retak. Dikotomi emosional antara Islam Tradisional dan Islam Modern atau Islam Fundamentalis dan Islam Liberal mengindikasikan hal itu. Seakan terjadi perebutan wilayah-wilayah tertentu dalam satu agama dengan klaim kebenaran oleh masing-masing paham.
Ketika gerakan pembaruan bergulir di kalangan umat muslim tak jarang terjadi kontroversi. Perbedaan ekstrim antara penganut salaf (tradisional-fundamental) dan khalaf (modernis-liberal) memperlebar kesenjangan dalam tubuh umat seagama. Berbagai proyek dialog lintas paham seakan tak mampu menjembatani kesenjangan yang terus melebar. Hasil yang diperoleh tak lebih berupa kegiatan tambal sulam, terlebih setelah masuk ke dalam wilayah politik. Politisasi agama yang menempatkan agama sebagai subjek sekaligus objek terbukti melemahkan posisi agama itu sendiri.