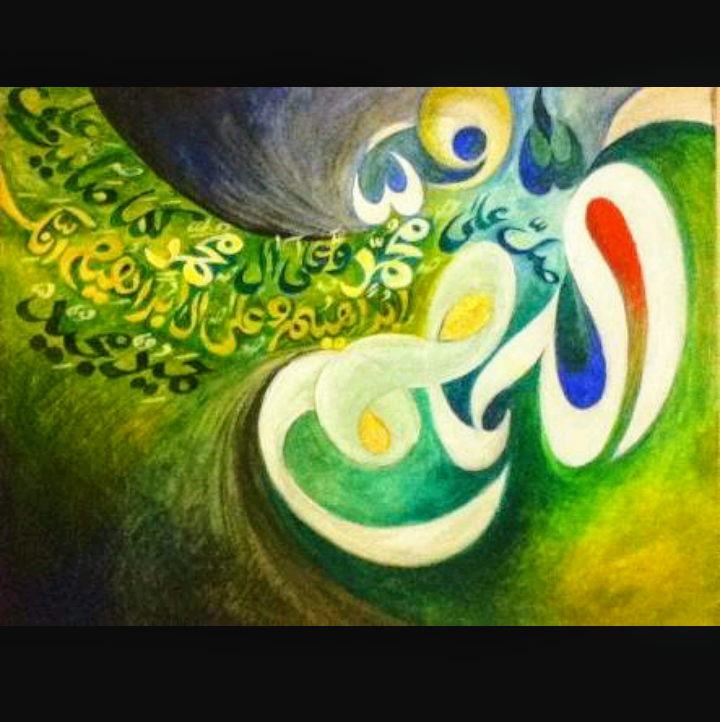Memahami al-Qur’an di samping tidak lepas dari kaidah kebahasaan juga tidak tepas dari konteks kemasyarakatan. Kaidah kebahasaan tentu terkait dengan kesusastraan dan para pengkaji al-Qur’an telah jamak membahasnya. Bagaimana bernasnya diksi yang dipakai al-Qur’an hingga jalinan akhir ayat yang membentuk cadenza sudah dimaklumi khalayak umum. Adapun permasalahan dalam konteks kemasyarakatan saat ini serta bagaimana al-Qur’an dapat dijiwai secara nyata belum lagi banyak dipikirkan. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini historisitas al-Qur’an dapat dipakai sebagai media penerang.
Mengenai konteks historis turunnya al-Qur’an Nasr Hamid Abu Zaid dalam Mafhum al-Nash mencoba mengaitkan antara wahyu dengan komunikasi manusia dan jin sebagai bukti bahwa al-Qur’an tidak dapat terlepas dari kerangka historis bangsa Arab. Menurutnya konsep budaya Arab pra-Islam yang memercayai adanya komunikasi antara manusia dengan makhluk alam lain menjadi dasar epistemologi fenomena kenabian. Penyair ulung dan peramal kerap menyatakan jika masing-masing di antaranya mendapatkan ilham dari jin ketika mengucapkan syair atau ramalan. Tanpa adanya hal ini konsep wahyu akan secara otomatis tertolak. Fenomena turunnya wahyu berangkat dari akar budaya ini, dengan perbedaan jika praktik perdukunan adalah komunikasi manusia –peramal- dengan setan, sementara wahyu dalam konteks malaikat dengan nabi.
Sejalan dengan Abu Zaid mengenai konteks historis turunnya al-Qur’an, Angelika Neuwrith menyatakan jika konsep mukjizat untuk membuktikan kebenaran kenabian tidak lepas dari bagaimana bentuk ayat al-Qur’an itu sendiri. Di mana ayat-ayat dalam surat-surat pendek pada awal turunnya menggunakan diksi yang selayaknya prosa berima atau saj‘ yang merupakan kalimat media yang digunakan oleh peramal Arab kuno ketika meramalkan sesuatu. Ayat al-Qur’an di awal turunnya hampir sama, untuk tidak dikatakan identik, dengan saj‘ yang secara spesisfik adalah kalimat singkat berdiksi ritmis yang ditandai dengan fashila.
Dua pernyataan di atas menandai bahwa adanya penyair dan peramal pada waktu itu menjadi sebab masyarakat Arab pra-Islam tidak kaget ketika konsep wahyu al-Qur’an disampaikan oleh Rasulullah saw. Rangkaian diksi sarat akan nilai sastra yang dilontarkan penyair dan peramal pada waktu itu tersaingi oleh gaya bahasa sastra yang digunakan al-Qur’an yang notabene baru. Dialektika sastra yang terjadi pada waktu itu yakni antara pembacaan syair dan ramalan di tempat-tempat umum dengan pembacaan al-Qur’an secara oral yang menyebar dari mulut ke mulut. Proses dialektika ini memunculkan al-Qur’an sebagai pemenang melebihi syair dan ramalan dari berbagai aspek. Baik dari aspek pemilihan diksi, ritme, logika bahasa, rima hingga nilai subtansial yang dikandungnya.
Pada titik ini keindahan sastrawi al-Qur’an tidak akan nampak jika sebelumnya tidak ada teks bermuatan sastra lain yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Masyarakat yang melek sastra pada waktu itu akan dengan mudah menilai al-Qur’an sebagai teks istimewa bahkan luar biasa. Umar bin al-Khattab sebagai salah satu sosok kompeten dalam kesusastraan pada waktu itu menjadi bukti sejarah betapa kandungan al-Qur’an sangat menginspirasi dan menggugah. Ia masuk Islam sekonyong-konyong ketika membaca teks surat Taha. Hal ini tidak lepas dari perasaan sastrawi yang telah ada dalam dirinya sebelum al-Qur’an sampai kepadanya. Dari sini mulai dapat dimengerti bahwa untuk memahami keindahan makna al-Qur’an diperlukan pembanding berupa teks sastra, yang mana pembanding ini tidak melulu konfrontatif karena terkadang juga dapat menjadi penunjang pemaknaan elaboratif atas teks al-Qur’an itu sendiri.
Konteks historis ini membawa kita dalam sebuah pemahaman jika sastra menjadi prasyarat untuk dapat memahami al-Qur’an lebih dalam. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan signifikansi kesusastraan non-Arab terhadap pemaknaan al-Qur’an, adakah ia memunyai implikasi kongkrit? Jawabannya tentu implikasi ini ada karena sastra –dalam bahasa apapun– dapat menghadirkan rasa kepada setiap pembacanya. Rasa inilah yang menjadikan pemahaman akan al-Qur’an tidak kering makna.
Di Barat hal ini telah dipraktikkan oleh Ian Richard Netton saat menulis artikel Towards a Modern Tafsir of Surat al-Kahf: Structure and Semiotics. Dalam artikel ini Netton mengakaji struktur dan semiotika narasi yang ada dalam surat al-Kahfi, menyandingkannya dengan karya sastra penulis Barat. Artikel ini dengan sangat indah menguak makna kisah-kisah dalam surat tersebut hingga keindahannya adapat dirasakan oleh setiap pembaca karya sastra yang ia cantumkan dalam artikelnya.
Sama dengan halnya dengan karya sastra penulis Barat, karya sastra penulis Indonesia pun bisa memunyai signifikansi untuk memahami al-Qur’an jika keduanya disatukan dalam tema yang seragam. Mari kita buktikan dengan menyandingkan beberapa ayat al-Qur’an dengan beberapa karya sastra Indonesia.
Pernyataan suami Zulaikha kepada istrinya yang diabadikan al-Qur’an bisa jadi selama ini kurang kita perhatikan. Apalagi kita, mufasir sekelas al-Qurtubi pun cenderung lebih suka menerangkan siapa sebenarnya sosok suami Zulaikha daripada perkataannya yang fenomenal kepada istrinya yang nyata diketahui bersalah karena membirahikan Yusuf. Berikut bunyi terjemahan teks surat Yusuf ayat 29:
“Dan istriku mohonlah ampunan atas dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah.”
Masalah tersebut resmi dilupakan, istrinya tidak dijatuhi hukuman. Banyak spekulasi mengapa suaminya tidak menghukumnya, Muhammad Thahir ibn Asyur menilai tindakannya didasari antara sifat kelemahlebutannya atau pertimbangan marwah keluarga. Terlepas dari spekulasi tersebut mari kita sandingkan ayat ini dengan puisi Sapardi Djoko Damono berjudul Aku Ingin Mencintaimu dengan Sederhana berikut;
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana
Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana
Dengan isyarat yang tak sempat diucapkan awan kepada hujan yang membuatnya tiada
Puisi Sapardi di atas dalam kaidah tafsir memang tidak dapat digunakan untuk menafsirkan ayat bersangkutan. Akan tetapi kesan yang ditimbulkan bait tersebut ketika kita telah meresapinya tentu membuat kita berpikir betapa ayat al-Qur’an begitu dramatis, menyentuh hati dan jauh dari kesan kering. Untuk itu wawasan terhadap sastra mutlak diperlukan untuk menggali keindahan intrinsik al-Qur’an.
Usaha untuk membumikan al-Qur’an dapat diawali dengan membuka pemikiran masyarakat agar melek sastra. Ini adalah langkah untuk merekonstruksi konteks historis turunnya al-Qur’an. Pembacaan puisi serta karya sastra lain seperti cerpen maupun ulasan tentang novel di media-media perlu dihidupkan. Jika ini terwujud pemahaman al-Qur-an tinggal menunggu waktu untuk segera membumi.